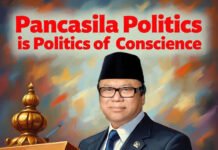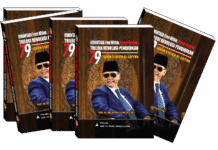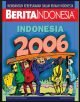Rahasia Intelijen dalam Keterbukaan Demokrasi
Pengawasan Rahasia Intelijen 02

Pengawasan Rahasia Intelijen 02
Intelijen Negara yang berhakikat kerahasiaan bertanggung jawab dalam keterbukaan demokrasi. Hal ini tentu memiliki kearifan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagaimana diamanatkan Sila Keempat Pancasila. Itulah esensi eksistensi Intelijen Negara Republik Indonesia. Intelijen yang sudah memenuhi kaidah intelijen dunia modern dengan kekhasannya sendiri. Intelijen Negara dengan kekhasan nilai etika moral dan filosofinya sendiri (Seyogyanya).
Sebagaimana dikemukakan mantan Kepala BIN Jenderal (Hor) Prof. AM Hendropriyono dalam bukunya Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia bahwa intelijen negara dalam melaksanakan visi, misi dan fungsi intelijen harus sesuai falsafah dan nilai-nilai Pancasila.[1] Budi Gunawan (1 Juni 2017) menyebutnya, nilai dasar, pola hidup atau way of life seluruh insan Indonesia; terutama Intelijen Negara, Intelijen Indonesia, Intelijen Pancasila, sebagaimana diamanatkannya dalam Nilai Dasar Personel Intelijen Negara (Bab II Pasal 4 Peraturan Kepala BIN No.17/2017: Kode Etik Intelijen Negara).
Tema pokok yang ingin disampaikan adalah kerahasiaan intelijen dalam keterbukaan demokrasi. Pemberitaan, pembahasan dan study mengenai intellijen memang sudah zamannya. Berkembangnya penelitian tentang intelijen akhir-akhir ini telah menjadi fenomena akademis. Berawal saat terjadi skandal (Watergate pada tahun 1973, mata-mata CIA pada tahun 1974, peristiwa kontra-Iran pada tahun 1987), walaupun masih relatif sedikit liputan media mengenai kegiatan intelijen, sebab operasi-operasi ini sangat dijaga ketat oleh pemerintah di negara manapun. Lalu, dipicu oleh serangan teroris tanggal 11 September 2001, prediksi yang salah pada tahun 2002 bahwa Irak sedang mengembangkan dan menimbun senjata pemusnah massal (WMD), dan kontroversi yang melibatkan pengumpulan “metadata” besar-besaran terhadap warga negara Amerika oleh Badan Keamanan Nasional (National Security Agency – NSA), hampir tidak ada sepekan berlalu tanpa beberapa laporan intelijen di New York Times dan media terkemuka lainnya. Saat ini, bahkan majalah-majalah sastra ternama di Amerika, Atlantic Monthly dan New Yorker, membahas topik intelijen secara teratur.
Selain itu, berbagai Kelompok Studi Intelijen bermunculan dan kursus tentang intelijen pun telah menjamur di Amerika Serikat, Persemakmuran Inggris, dan Eropa dan lain-lain, membuktikan bahwa topik ini juga menjadi topik akademis di banyak negara di dunia. Jelaslah, sebagaimana kata Loch K. Johnson (2015) dalam Essentials of Strategic Intelligence bahwa studi intelijen sudah menjadi zamannya; dan literatur tentang intelijen telah menjamur selama 40 tahun terakhir.[2]
Buku Essentials of Strategic Intelligence ini menyajikan kajian empiris, perlakuan sejarah, kerangka teori, memoar, studi kasus, analisis hukum, esai komparatif, dan penilaian etika intelijen. Penulisnya juga berasal dari berbagai kalangan akademisi, badan intelijen, think tank, dunia diplomasi, dan dunia hukum; yang mewakili berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, hubungan internasional, hukum, ilmu politik, studi kebijakan publik, dan studi strategis; menjadi sebuah kumpulan penelitian yang mengkaji aspek-aspek kunci dari intelijen modern. Loch K. Johnson dan para kontributor buku ini berharap buku ini akan membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya kegiatan intelijen, serta merangsang para sarjana di seluruh dunia untuk bergabung dalam studi bidang intelijen yang penting ini.
Loch K. Johnson, profesor Urusan Publik dan Internasional di Universitas Georgia dan editor senior jurnal internasional Intelligence and National Security mengatakan, di Amerika Serikat juga mungkin di beberapa negara, badan-badan intelijen kini telah menjadi bagian dari sistem checks and balances. Masyarakat menginginkan dan berhak mendapatkan kebebasan sipil dan pertahanan yang aman terhadap ancaman; oleh karena itu, pencarian terus dilakukan untuk menemukan perpaduan yang tepat antara kebebasan dan keamanan, demokrasi dan efektivitas intelijen.[3]
Dalam kajian Intelijen dan Akuntabilitas, David M.Barrett (2015) profesor ilmu politik di Universitas Villanova dan penulis Kongres dan CIA mengatakan, sebuah negara demokratis di tengah dunia yang berbahaya menghadapi dua dilema yang bisa disebut sebagai “keterbukaan versus kerahasiaan” dan “permainan adil versus trik kotor.” Keterbukaan merupakan inti dari teori dan praktik demokrasi. Jika pemerintah suatu negara tidak terbuka secara substansial mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya, maka warga negara tersebut akan sulit memberikan penilaian yang efektif terhadap pemerintah dalam pemilu berkala. Namun, di dunia yang penuh bahaya ini, pemerintah mana pun harus sangat merahasiakan kemampuan dan rencana militer dan intelijennya.[4]
Sementara itu, banyak warga negara dan pemimpin negara-negara demokratis—tentunya Amerika Serikat—menganggap diri mereka percaya pada fair play. Pidato perpisahan Presiden George Washington yang terkenal menetapkan standar serupa dengan menyerukan pemerintah AS untuk mengikuti “kebajikan yang mulia” dalam berurusan dengan negara lain. Hal ini, menurut prediksinya, pada akhirnya akan membuat negara-negara lain terbiasa melakukan hal yang benar dalam urusan luar negerinya.[5]
Namun, hal ini tidak berarti bahwa kebijakan luar negeri AS secara konsisten baik selama beberapa dekade berikutnya. Satu setengah abad kemudian, sebuah komisi rahasia yang menasihati Presiden Dwight Eisenhower secara eksplisit berpisah dengan George Washington. Dunia telah menjadi sangat berbahaya, karena Uni Soviet yang ekspansionis, komunis, dan bersenjata nuklir, “musuh keras kepala yang tujuan utamanya adalah mendominasi dunia dengan cara apa pun dan biaya apa pun. . . . Jika Amerika Serikat ingin bertahan, konsep ‘fair play’ yang sudah lama ada harus dipertimbangkan kembali.” Amerika Serikat harus “belajar untuk menumbangkan, menyabotase, dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan PSU yang lebih pintar, lebih canggih, dan lebih efektif dari yang digunakan lawan.” Dalam hal ini, “Trik kotor diperlukan!”[6]
Solusi terhadap kedua dilema ini setidaknya tidak sempurna. Namun, hal ini setidaknya dapat dimitigasi oleh pemerintah (Amerika Serikat) dengan membuat beberapa pemimpin yang dipilih secara konstitusional mengetahui dan memberikan arahan terhadap tindakan rahasia, spionase, dan kebijakan-kebijakan lain yang secara moral tidak baik. Yang jelas, presiden—yang mempunyai kekuasaan eksekutif dan panglima tertinggi—harus menjalankan tugas-tugas tersebut. Namun, Konstitusi AS memberi Kongres wewenang untuk membuat undang-undang (dibagi dengan presiden yang memiliki hak veto), yang mencakup hak untuk mengesahkan undang-undang pembelanjaan. Mengingat hal ini, selama masa kepresidenan Washington, Kongres pertama kali menegaskan hak yang tersirat dalam konstitusi untuk memantau dan menyelidiki lembaga-lembaga cabang eksekutif.[7]
Sebelumnya 01 || Bersambung 03
Penulis: Ch. Robin Simanullang, Cuplikan dari Buku Budi Gunawan: Manusia Perang Akal Berkhidmat Negarawan
Footnotes:
[1] Hendropiyono, A.M, 2013. Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia (Editor: Nina Pane). Jakarta: Kompas Media Nusantara, h. 4, 7-8.
[2] Johnson, Loch K. (Ed.), 2015. Essentials of Strategic Intelligence. Santa Barbara, California – Denver, Colorado – Oxford, England: Praeger, p. ix-x.
[3] Johnson, Loch K. (Ed.), 2015. Essentials of Strategic Intelligence, p. xviii.
[4] Barrett, David M., 2015. Congressional Oversight of the CIA in the Early Cold War, 1947-1963. In Johnson, Loch K. (Ed.), 2015. Essentials of Strategic Intelligence. Santa Barbara, California – Denver, Colorado – Oxford, England: Praeger, p. 367.
[5] Barrett, David M., 2015. Congressional Oversight of the CIA, p. 367.
[6] Barrett, David M., 2015. Congressional Oversight of the CIA, p. 367-368.
[7] Barrett, David M., 2015. Congressional Oversight of the CIA, p. 368.