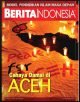[OPINI] – Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) –suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.
Tradisi berbeda pendapat di kalangan umat, bila dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Dengan tradisi perbedaan pendapat, kita menjadi tidak mudah untuk merasa paling benar sendiri. Pada tradisi perbedaan pendapat yang berujung pada dialog, ada sebuah nuansa saling kritik atas kelemahan masing-masing guna memperbaikinya di kemudian hari. Sayangnya, perbedaan pendapat dan penyikapan terhadap fatwa MUI belakangan cenderung sepi dari dialog yang produktif dan kondusif. Bahkan, ada sekelompok orang yang dengan mengatasnamakan kebenaran dan kehendak Tuhan, menyerang kelompok lain yang dianggap menyimpang dengan dalih pelurusan akidah dan ibadah.
Dengan otoritas dan jumlah ulama yang terhimpun di dalamnya, sebetulnya MUI diharapkan menjadi penengah dari berbagai corak pemikiran yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Sayangnya, harapan itu malah menjadi terbalik dengan pembelaan MUI terhadap sekelompok orang dan penghakiman MUI terhadap sebagian lainnya. Bahkan, dengan pengeluaran fatwa yang cenderung terlihat otoriter dan membelenggu kebebasan berpikir yang merupakan pilar demokrasi itu, MUI sama sekali tidak merasa bersalah dan menyesal. Pendefinisian ajaran-ajaran yang dilarang seperti pluralisme, liberalisme, dan liberalisme, tampak menggunakan pengertian sepihak yang sebetulnya sangat berlawanan dengan pengertian sesungguhnya. Mestinya, pendefinisiannya harus melalui pengkajian yang mendalam, serius, dan menggunakan perspektif yang lebih luas.
Pluralisme dalam Islam
Pada dasarnya, pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Justru, dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan. Maka, pendefinisian pluralisme sebagai sebuah relativisme adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab, pluralisme sendiri mengakui adanya tradisi iman dan keberagamaan yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya.
Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) –suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Realitas pluralitas yang bisa mendorong ke arah kerja sama dan keterbukaan itu, secara jelas telah diserukan oleh Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat itu, tercermin bahwa pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.
Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 213 juga disebutkan: “Manusia itu adalah satu umat. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beserta mereka mereka Ia turunkan Kitab-kitab dengan benar, supaya Dia bisa memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”. Dalam ayat itu muncul tiga fakta: kesatuan umat dibawah satu Tuhan; kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi; dan peranan wahyu (Kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat beragama. Ketiganya adalah konsepsi fundamental Alquran tentang pluralisme agama. Di satu sisi, konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai agama, di sisi lain konsepsi itu juga menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama (The Islamic Roots of Democratic Pluralism, 2001).
Menurut Abdulaziz Sachedina (2001), argumen utama pluralisme agama dalam Al-Qur’an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Berkenaan dengan keimanan privat, Alquran bersikap nonintervensionis (misalnya, segala bentuk otoritas manusia tidak boleh menganggu keyakinan batin individu). Sedangkan dengan proyeksi publik keimanan, sikap Alquran didasarkan pada prinsip koeksistensi. Yaitu kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri. Aturan itu bisa berbentuk cara menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Maka, berdasarkan prinsip itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya bisa menjadi cermin sebuah masyarakat yang mengakui, menghormati, dan menjalankan pluralisme keagaman.
Kemerdekaan Beragama
Pada masa lalu, semua agama pasti pernah mengalami penderitaan dan konflik. Hal itu bisa jadi diakibatkan oleh kebijakan yang diskriminatif oleh penguasa atau karena perlakukan agama lain yang lebih mayoritas. Oleh karenanya, hampir semua agama memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak dasar kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan dan kebebasan politik. Dan ketiga hal itu merupakan pilar dari penegakan dan perjuangan demokrasi. Kebebasan individu untuk beragama, hanya bisa diwujudkan dalam sistem yang demokratis. Maka, hak-hak asasi manusia tentang adanya jaminan beribadah secara bebas dan menyebarkan agamanya harus senantiasa dikembangkan. Jangan sampai, sebuah agama atau sekelompok tertentu dalam intern agama memaksa dan menggunakan kekerasan guna menghegemoni dakwah untuk kelompoknya sendiri.
Islam sebagai tradisi moral sangat mengakui fakta akan pluralisme dan kemerdekaan beragama. Dasar pengakuan itu terdiri dua hal: pertama, karena pluralisme merupakan ajakan terhadap penggunaan pikiran manusia. Alquran memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap pilihan rasional dan dorongan individu. Menjadi seorang muslim adalah urusan pilihan rasional dan cara respon individu. Penekanannya di sini bukan hanya karena nilai etika itu rasional dan ilmiah, namun karena layak dan dapat dimengerti oleh semua manusia. Dalam Alquranpun juga dijelaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam beragama, karena beragama merupakan pilihan dan kebebasan individu. Kedua, penerimaan sosial atas nilai Islam sebagai sebuah pemahaman oleh individu dan masyarakat yang berbeda-beda. Maksudnya, basis pluralisme ini senantiasa dikelola oleh perbedaan pendapat yang secara luas diperbolehkan oleh norma-norma sosial. Dialektika sosial akan mengembangkan dan menguatkan definisi yang bisa diterima tentang nilai etika (M. Khalid Masud, The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions, 2002). Maka, tradisi dialog antar agama menjadi penting guna mengembangkan nilai-nilai etika Islam yang sangat menghargai kebebasan beragama.
Berdasarkan hal di atas, maka peranan negara sebagai penjamin kebebasan beragama perlu dipertegas lagi. Negara harus menjamin bahwa kemerdekaan beragama tidak akan melanggar hak-hak orang lain. Negara tidak boleh mendukung satu agama serta satu kelompok paham serta menindas yang lainnya. Fungsi negara adalah menjamin kebebasan menjalankan agama diberikan secara sama kepada semua agama dan pahamnya. Sebab, pada dasarnya ada hubungan yang mutlak antara kebebasan beragama, institusi, dan kebijakan yang dapat menjamin kebebasan itu. Bila salah satunya timpang, maka kehidupan demokrasi dan jaminan kebebasan warganya akan terancam juga.
Akhirnya, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mau menghargai dan melaksanakan prinsip pluralisme keagaman dan kebebasan beragama. Soalnya, kebebasan dan pengakuan akan keberagaman merupakan potensi yang sangat bagus untuk membangkitkan negeri ini dari tirani sekelompok orang dan korupsi yang merajalela. Prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial mesti ditegakkan melampaui sekat-sekat golongan, agama, dan paham keagamaan. Kita semua harus berdoa dan berusaha secara maksimal agar kemelut demokrasi dan gejala otoritarianisme keagamaan ini segera berakhir. Walahu A’lam Bisshawab. (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=883). e-ti
02 | Otoriterisme Pemahaman Keagamaan
Kalau kita kaji secara jeli, teliti, dan mendalam, sebetulnya dalam Islam tidak pernah ada penafsiran tunggal dalam memahami wahyu serta ajaran yang diturunkan oleh Tuhan dan disampaikan oleh Rasul-nya. Bila terjadi perbedaan, ada kalanya yang bisa diselesaikan dengan jalan dialog dan saling melakukan tabayyun, namun ada juga yang berakhir dengan peperangan dan penindasan satu pihak terhadap pihak lainnya. Sejarah telah memberikan cerminan bagaimana perbedaan pandangan antara kaum Syi’ah, Sunni, Khawarij, Murji’ah, dan Mu’tazilah tampil berkontestasi wacana dan pemeluk di dunia ini.
Ada kalanya yang diselesaikan dengan saling membiarkan eksistensi kelompok masing-masing. Ada juga yang secara ekstrem menganggap yang lainnya kafir dan keluar dari Islam, seperti kelompok Khawarij yang dengan yakinnya menganggap kelompok di luar dirinya tidak menegakkan hukum Tuhan dan oleh karenanya wajib dibunuh.
Dari semua perbedaan penafsiran itu, tentu saja jalan kekerasan dan pengkafiran terhadap kelompok lainnya bukanlah solusi yang bermanfaat secara positif bagi eksistensi kelompok maupun ajaran mereka. Hal itu terbukti dari kelompok Khawarij yang tega membunuh Ali bin Abi Thalib serta mencoba membunuh Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Ash meski gagal, ajarannya tidak banyak mendapat simpati dari umat Islam dan justru dianggap sebagai ajaran sempalan yang mengajarkan terorisme dan kekerasan.
Begitu juga dengan ajaran Mu’tazilah yang ketika sedang berkuasa dan menemukan zaman keemasannya, banyak melakukan penganiayaan dan pemaksaan terhadap kelompok yang lain guna menerima paham dan penafsirannya, akhirnya ketika kekuasaan tidak lagi berpihak kepadanya ajaran itu seperti lenyap disapu bumi.
Justru Malapetaka
Pengalaman di atas menunjukkan, sebetulnya hegemoni dan pemaksaan paham sebuah kelompok terhadap kelompok lainnya dengan tindakan kekerasan, pada dasarnya justru membuat malapetaka dan kerugian pada dirinya sendiri. Ketika sebuah paham keagamaan tertentu menjadi dominan, nomor satu, dan merasa paling unggul, biasanya mereka akan kebal terhadap kritik dan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.
Jika fase itu dipertahankan dan dijadikan sebagai acuan utama gerakannya, maka tinggal menunggu saatnya untuk terbenam dan mengalami kebangkrutan.
Meski kelihatannya mudah dikendalikan dan banyak diam serta menurut saja pada ajakan para pemimpin agama, sebetulnya secara sadar dan teliti, umat dan masyarakat meneliti dan menimbang sejauh mana unsur kemaslahatan dan kebaikan sebuah ajaran itu berguna pada kehidupan dan kemajuan peradaban.
Tidak heran jika mereka dapat dengan tiba-tiba memberontak, melawan, dan melakukan pemboikotan pada para pemimpin agama dan kelompok yang banyak menggiring umatnya guna mencapai ambisi pribadinya.
Adanya beberapa fatwa dan pernyataan yang mengatakan beberapa golongan dan kelompok tertentu sesat dan menyesatkan, oleh karenanya wajib diluruskan dan dikembalikan ke ajaran Islam atau membentuk agama baru, sebetulnya itu sudah memasuki wilayah hak Tuhan. Sebab yang bisa menetapkan ajaran itu diterima atau ditolak di sisi-Nya hanyalah Tuhan saja. Sedangkan para makhluknya hanya diberikan kebebasan untuk menafsirkan, memahami, dan menjalankan ajaran agama itu untuk bekal menciptakan kehidupan yang harmoni di muka bumi ini.
Maka yang berhak menghukum apabila sekelompok orang itu sesat dan bisa dihukum dengan tegas, bukanlah manusia atau pimpinan agama. Yang boleh kita lakukan sebagai umat beragama, adalah sebatas melakukan dakwah atau mengajak kepada jalan kebaikan yang diridai Tuhan.
Jika mereka tetap berpegang teguh dan bersikeras dengan keyakinannya, sesuai dengan ajaran dakwah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad, tugas kita adalah mendoakan dan mengajaknya berdialog secara bijaksana dan cerdas (bil hikmah, wa mauidzatil hasanah, wa jadilhum billati hiya ahsan).
Toleransi dan Dialog
Khaled Abou El Fadl pernah menyatakan, ketika sebuah kelompok atau individu sudah menganggap dirinya paling otoritatif dalam menafsirkan ajaran keagamaan, pada dasarnya mereka dengan mudah akan terjerumus pada tindakan yang bersifat otoriter. Sebab batasan antara yang otoritatif dan otoriter sangatlah tipis dan mudah berubah.
Orang yang otoritatif, justru biasanya akan bersikap bijaksana, toleran, dan membuka diri berdialog dengan yang lainnya. Yang otoritatif pun dalam setiap tindakannya akan mengedepankan pengkajian secara mendalam, belajar secara sungguh, serta mendahulukan moralitas daripada nafsu.
Sedangkan orang yang otoriter, dengan segala cara dia akan menunjukkan dirinya dan paham kelompoknyalah yang paling otoritatif dan wajib diikuti oleh yang lainnya (Speaking in God’s Name, 2001).
Kalau kita kaji dari pengalaman dakwah Nabi maupun ajaran Tuhan dalam Alquran, sebetulnya ajaran Islam sangat bertujuan untuk menciptakan rahmatan lil alamin (kebahagiaan dan kedamaian bagi semua).
Hal itupun dipertegas oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa tujuan Islam adalah melindungi lima pokok kehidupan yaitu agama, kehidupan, akal (kebebasan berpikir), keturunan, dan harta benda.
Bila ajaran agama yang kita praktikkan dan kita yakini bertentangan dari kelima hal itu, sesungguhnya identitas keislaman kita patut dipertanyakan. Maka penganiayaan dan penindasan terhadap eksistensi kelompok tertentu baik dalam Islam maupun agama lainnya, sudah seharusnya dihentikan dan diakhiri dengan jalan dialog yang mencerahkan dan membuka wawasan hati serta pikiran yang bertikai.
Kita memang bisa sangat tidak setuju, misalnya dengan tiga ajaran pokok Ahmadiyah yang menimbulkan kontroversi dari dulu hingga sekarang, yaitu: Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai Nabi, penggunaan kitab Tadzkiroh sebagai ajaran utama mereka, serta pemahaman Jihad yang mendukung imperialisme Inggris di negara Islam.
Namun bukan berarti kita tidak boleh hidup toleran dengan mereka dan ketidaksetujuan itu diturunkan dengan tindakan kekerasan atau fatwa yang mengaggap bahwa mereka itu sesat dan menyesatkan.
Mestinya yang kita lakukan adalah mengkaji, meneliti, dan mempelajari aspek-aspek positif adari ajaran mereka guna memajukan peradaban umat.
Misalnya semangat keilmiahan mereka yang tinggi sehingga melahirkan sosok Abdus Salam yang memperoleh Nobel dan semangat filantropi mereka yang tinggi, sebetulnya bisa ditiru dan ditransfer oleh umat Islam lainnya di seantero dunia guna memajukan peradaban Islam.
Selain itu pemerintah dan negara dalam hal ini hendaknya berlaku dan bertindak secara netral dan tidak malah memprovokasi umat Islam guna melakukan penganiayaan terhadap kelompok agama minoritas atau pinggiran.
Negara mestinya berdiri di tengah-tengah menjadi regulator untuk urusan etika dan kehidupan sosial kemasyarakatan, dan tidak bertindak sebagai polisi akidah yang dengan mudah memberi cap pemahaman seseorang sesat dan lurus.
Pengikut ajaran tertentu yang bukan menjadi mainstream, hendaknya diberikan perlindungan yang sama dan setara sebagaimana warga negara lainnya dan tidak perlu mencari suaka ke negara lainnya, sehingga mereka bisa bebas menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana yang dipertegas oleh konstitusi kita yang mengatur kebebasan beragama untuk semua warga negaranya.
Buya Syafii Maarif pernah menyatakan, bahwa fatwa sesat, di luar Islam, dan penghancuran tidak banyak menolong soal kontroversi keagamaan di negeri ini. Sebab, tindakan itu hanya akan melahirkan disharmoni lintas iman, padahal semua agama mengajarkan hidup harmoni sesama manusia. (Suara Merdeka, Jumat, 15 September 2006). e-ti
03 | Membendung’Syahwat’Politik Muhammadiyah
Polemik fatwa resmi Muhammadiyah untuk mendukung Amien, tentu harus diingat kembali. Dukungan itu terbukti banyak menimbulkan riak-riak konflik di internal Muhammadiyah. Selain itu, asumsi awal bahwa dengan keluarnya dukungan resmi menjadikan suara PAN naik dan Amien confidence maju dalam pilpres, akhirnya hanya menjadi impian yang jauh dari kenyataan.
Meskipun PAN hanya menduduki peringkat ke-7 dalam pemilu legislatif, Muhammadiyah secara resmi mempertegas kembali dukungannya pada Amien Rais untuk terus maju sebagai calon presiden. Sebelumnya, pada sidang pleno di Yogyakarta pada 9-10 Februari lalu, Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan pernyataan yang senada. Menurut mereka, dalam hal ini suara PAN adalah modal pertama, sedangkan Muhammadiyah adalah modal utama. Maka, dengan modal utama itu warga Muhammadiyah yang aktif di parpol lain beserta para elemen reformis lainnya, diharapkan memberikan suara pada Amien Rais pada pilpres (pemilihan presiden) Juli nanti.
Di alam demokrasi, dukungan resmi Muhammadiyah itu sah-sah saja, apalagi yang mengeluarkan adalah para “pemilik tertinggi” organisasi itu. Kehendak Amien untuk terus maju dalam pilpres, meski realitas obyektif PAN mengalami penurunan drastis, sah juga dilakukan. Apalagi, Amien Rais merasa bahwa yang akan memilih dirinya lebih besar dari pemilih PAN. Beberapa survei yang ada juga menunjukkan pemilih pada umumnya banyak yang membedakan antara partai dan calon presiden yang akan dipilih.
Namun, dukungan resmi Muhammadiyah terhadap Amien, haruslah diberi catatan. Adalah fakta bahwa warga Muhammadiyah sangat rasional, modern, dan plural. Polemik fatwa resmi Muhammadiyah untuk mendukung Amien, tentu harus diingat kembali. Dukungan itu terbukti banyak menimbulkan riak-riak konflik di internal Muhammadiyah. Hal itu misalnya pada terlihat protes dari warga Muhammadiyah yang juga aktif di PKS, PPP, Golkar, atau PBR yang merasa dianaktirikan secara politik setelah lahirnya keputusan resmi tersebut. Gugatan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) yang menganggap bahwa dukungan resmi itu sebagai bentuk pelanggaran khittah dan runtuhnya peran Muhammadiyah sebagai tenda bangsa, juga patut diperhatikan.
Selain itu, asumsi awal bahwa dengan keluarnya dukungan resmi menjadikan suara PAN naik dan Amien confidence maju dalam pilpres, akhirnya hanya menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Suara PAN malah terbukti ambrol dan kalah dengan pendatang baru seperti Partai Demokrat, bahkan posisinya di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan beberapa contoh itu, dapat diambil pelajaran bahwa meski pengurus Muhammadiyah mengajak secara resmi warganya untuk memilih partai tertentu, mereka tetap memiliki pilihan sendiri yang diyakininya. Kenapa PP. Muhammadiyah kini malah lebih mempertegas dukungannya dan bertindak seolah menjadi “tim sukses” pencapresan Amien Rais?
Keteledoran Pembacaan
Dalam menganalisis persoalan sosial dan politik, banyak orang terjatuh pada kesalahan berpikir. Yakni kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan over-generalisation. Kesalahan berpikir ini (fallacy of dramatic instance) bermula dari penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat umum atau general. Menurut Jalaluluddin Rakhmat (1999), argumen yang overgeneralized ini biasanya agak sulit dipatahkan, karena rujukannya seringkali diambil dari pengalaman pribadi seseorang (individual’s personal exsperince).
Dukungan resmi Muhammadiyah, sangat mungkin akibat keteledoran semacam ini. Pengurus Muhammadiyah meyakini, bahwa karena Amien Rais adalah salah seorang politisi yang masih terbukti bersih, maka ketika mencalonkan diri sebagai presiden pasti akan didukung oleh semua kader Muhammadiyah dan banyak elemen masyarakat yang menginginkan perubahan. Soalnya, dengan sistem organisasi Muhammadiyah yang –menurut Hajriyanto Y. Thohari- sangat sentralistik dan miskin paradigma federasi, keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusatnya selama ini biasanya pasti akan diikuti oleh segenap warganya. Hal itu bisa tampak mulai dari keputusan tentang penetapan jatuhnya hari raya, keputusan tarjih, pedoman organisasi, atau pendirian badan-badan otonom yang menunjang aktivitas organisasi.
Bila Muhammadiyah tetap berasumsi itu, tentu saja kritikan Mohamad Abid al-Jabiri tentang homogenitas metode bepikir umat tentu sangat relevan. Pada umumnya, umat Islam banyak yang masih menyukai model berpikir secara bayani (tekstual). Dalam model berpikir ini, semua hal dipandang secara tekstual, material, dan konkret. Semua akan dilihat sebagai hitam-putih dan otomatis. Karena Amien mantan ketua PP Muhammadiyah dan kader terbaiknya, maka semua orang Muhammadiyah pasti akan mendukungnya. Bila ada yang tidak mendukung, itu pasti terdapat “kelainan” dan bisa jadi mereka adalah “musuh dalam selimut”. Padahal, semestinya sebagai organisasi modern yang anggotanya banyak yang berpendidikan, mestinya mereka harus berani meninggalkan cara berpikir yang terbukti banyak menyebabkan kejumudan dan kemunduran umat ini. Mereka harus berani mulai berpikir secara rasional (burhani) dan imajinatif (irfani).
Maka, Muhammadiyah dan Amien mesti segera berpikir ulang tentang asumsi generalnya itu. Soalnya, saat ini figur alternatif yang diharapkan bisa menjadi pemimpin bangsa dan terbukti bersih bukan hanya dia. Susilo Bambang Yududoyono dan Hidayat Nurwahid adalah figur baru dan bersih yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Selain itu, kepatuhan warga Muhammadiyah dalam soal organisasi dan agama terhadap keputusan resmi para pengurusnya, tentu bisa lain ketika menyangkut persoalan politik.
Kontribusi Bangsa
Memang suara ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah gampang menjadi pusat perhatian dan rebutan banyak pihak. Meminjam istilah KH Mustofa Bisri, seringkali NU dan Muhammadiyah terlampau ge-er (gede rumangso). Jika Muhammadiyah terus terlibat aksi dukung-mendukung dan bahkan lebih mempertegas sikap partisannya, tradisi politik yang kurang baik akan terulang. Maksudnya, jika nantinya ada salah satu atau mantan pucuk pemimpin Muhammadiyah punya keinginan yang sama dengan Amien, pasti akan didukung juga. Pada akhirnya, sangat mungkin orang yang ingin menjadi pengurus Muhammadiyah, hanya menjadikan amanah itu sebagai batu loncatan untuk lebih mempermudah menggapai tangga kekuasaan (baca politik). Warga Muhammadiyah pun, akan terbebani terus-menerus oleh “ambisi” politik para pemimpinnya.
Sejarah membuktikan, hal itu hanya memperboros energi umat. Jika dukungan itu memperoleh hasil, imbalan (reward) yang diberikan pada organisasi lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dinikmati oleh elitenya. Sebaliknya, jika gagal maka hukuman (punishment) secara psikologis dan moral, umumnya akan lebih banyak dibebankan pada warganya. Tanpa dukung mendukung pun, organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, terbukti bisa berkiprah maksimal.
Peran yang paling tepat untuk berkontribusi secara nyata terhadap bangsa adalah menjaga jarak dengan kekuasaan, memperteguh independensi, dan memperkuat civil society. Tradisi civil society yang sudah berjalan di Muhammadiyah lewat jalur pendidikan dan amal usaha, tentu amat sayang bila ditinggalkan begitu saja. Justru, dengan menjadi “oposan” yang baik, mereka akan lebih leluasa untuk bekerjasama dengan siapa saja tanpa kehilangan sikap kritisnya. Toh, tanpa berkuasa pun, Muhammadiyah tidak akan kehabisan cara untuk berkiprah menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa seperti yang selama ini dijalaninya. Politik romantisme dan ketidakpercayaan diri dengan mengorbankan independensi sebuah organisasi dan membebani para anggotanya, sudah selayaknya diakhiri. Wallahu A’lam. (24/05/2004: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=580). e-ti
04 | Ulama dan Godaan Politik Kekuasaan
Fenomena sowan ke kyai, atau kyai yang kembali aktif menjadi tim sukses, menjelang masa-masa pemilihan presiden kembali marak. Bisa jadi, seorang ulama’ akan konsisten menjadi –meminjam istilah Clifford Geertz- perantara dan pialang budaya (cultural broker), dan mungkin saja ia akan masuk jalur politik praktis. Bagaimana seyogyanya ulama’ menghadapi godaan politik itu?
Menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden secara langsung, fenomena para capres yang sowan ke para kyai kembali marak terjadi. Begitu juga dengan para ulama’ atau kyai yang aktif menjadi tim sukses calon presiden. Kedua fenomena itu menunjukkan adanya kesalingtergantungan (interdependensi) antara keduanya. Dan hal itu, mempunyai preseden sejarah yang sudah sangat lama. Sejak zaman penjajahan dan kemerdekaan, kesaling-eratan hubungan antara ulama’ dan politisi-pemerintah marak terjadi.
Dalam ajaran Islam, ulama’ mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan peran yang maha penting dalam kehidupan umat, agama, dan bangsa. Secara garis besar, peran itu berupa tugas pencerahan bagi umat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai para pewaris Nabi (waratsatul anbiya’) (Q.S. al-Jumu’ah: 2). Peran itu biasa disebut dengan ‘amar ma’ruf nahi munkar. Sedang rinciannya adalah tugas untuk: (a) mendidik umat di bidang agama dan lainnya, (b) melakukan kontrol terhadap masyarakat, (c) memecahkan problem yang terjadi di masyarakat, (d) menjadi agen perubahan sosial. Kesemua tugas itu, akan berusaha dijalankan oleh para ulama’ sepanjang hidupnya, meski jalur yang ditempuh berbeda (Masykuri Abdillah, 1999).
Bisa jadi, seorang ulama’ akan konsisten menjadi –meminjam istilah Clifford Geertz- perantara dan pialang budaya (cultural broker), dan mungkin saja ia akan masuk jalur politik praktis. Sebagai seorang pialang budaya, ulama’ berfungsi untuk menghubungkan budaya lokal atau rakyat dengan budaya asing guna lebih memudahkan pemahaman rakyat. Fungsi ini, bisa tampak dari, semisal penjelasan para ulama’ tentang Pancasila yang tidak bertentangan dengan Islam dan perlunya KB (Keluarga Berencana) dalam membantu mewujudkan kesejahteraan keluarga. Sedang ulama’ yang masuk jalur politik praktis, ada juga yang memang berniat menjadikan politik sebagai jalur ibadah dan pengabdian kepada umat. Tokoh semisal Muhamad Natsir, Kasman Singodimedjo, serta Buya Hamka, betul-betul menjadikan politik sebagai jalur untuk mewujudkan aspirasi umat dan menentang segala bentuk penindasan dan kediktatoran. Meski hal itu mengakibatkan kesengsaraan hidup pada diri dan keluarganya.
Pergeseran Peran
Sayangnya, fungsi-fungsi budaya dan politik itu kebanyakan hanya menjadi lipstik yang terlihat cantik di permukaan. Para ulama’ yang berjuang di jalur politik, kebanyakan hanya sibuk mengurusi pengikutnya sendiri dan memenangkan partainya di arena Pemilu. Begitu juga, orang-orang yang menjadi perantara budaya, akhirnya juga banyak yang hanya menjadi corong pembenar kebijakan pemerintah. Fenomena MUI (Majelis Ulama’ Indonesia) di zaman Orde Baru, tampak banyak menjadi “tukang do’a” pada acara-acara resmi negara, imam besar masjid Istiqlal, atau mengumumukan jatuhnya hari raya keagamaan tertentu. Dan pada era Habibie, Gus Dur, dan Megawati pun, fenomena para ulama’ yang membela para patronnya juga tampak sama terjadi. Tentu saja, Buya Hamka harus dicatat sebagai ulama’ yang konsisten dengan perjuangannya dengan bersedia mengundurkan diri dari MUI ketika berseberangan dengan pemerintah.
Ulama’ yang hanya diam ketika terjadi kemungkaran di hadapannya, menurut al-Ghazali digolongkan sebagai ulama al-su’ (ulama dunia). Ulama jenis ini, biasanya bila berbicara atau mengeluarkan fatwa hanya sekedar basa-basi atau pengguguran tugasnya saja, agar dia tetap dianggap kompeten di bidangnya. Jarang sekali, fatwa yang diberikan betul-betul keluar dari hati nurani dan berniat membela rakyat yang tertindas. Terhadap fenomena banjir, penggusuran, perdagangan wanita dan anak kecil, biasanya ulama’ hanya akan diam saja. Namun, terhadap persoalan yang sebetulnya hanya bersifat fiqih oriented yang menekankan pada halal-haramnya sesuatu, mereka akan buka suara sekeras-kerasnya. Labelisasi halal pada produk makanan dan minuman, serta halal haramnya bunga bank dan sah-tidaknya bank konvensional yang terus menerus diteriakkan, adalah salah satu contoh betapa rendahnya sense of belonging mereka terhadap penderitaan rakyat kecil yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan hal itu.
Yang lebih ironis lagi, jika para ulama’ yang semestinya menjadi pialang budaya dan penjaga moral bangsa, banyak yang menjadikan profesinya sebagai lahan untuk mata pencaharian. Maksudnya, penerimaan para ulama’ terhadap para calon presiden yang sowan ke tempatnya, hanya dimaksudkan untuk mengeruk manfaat dan keuntungan bagi dirinya saja. Ia akan menerima siapa saja yang datang, asal memberi sumbangan pada pesantrennya atau memasukkan amplom di kantongnya. Begitu juga, para ulama’ yang kampanye dan menjadi calon legislatif, ketika terpilih akhirnya juga hanya akan melakukan aksi duduk, diam, dan menerima duit. Janji-janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan penegakan ajaran Islam yang dulu digembar-gemborkan, akhirnya dengan begitu mudah akan mereka kompromikan dengan lawan politiknya demi sebuah jabatan atau uang.
Di Iran, peran ulama’ yang masuk kekuasaan dan malah melanggengkan hegemoni kaum konservatif adalah contoh yang layak dijadikan pelajaran. Ketika mereka melakukan revolusi Islam pada tahun 1979, sebetulnya rakyat sangat berharapa akan adanya pemerintahan baru yang lebih demokratis dan memihak rakyat. Akan tetapi, dengan pelembagaan ulama dalam wilayat al-faqih yang bertindak sebagai otoritas utama pemerintah, yang terjadi malah sebaliknya. Para ulama’ ini justru dengan seenaknya memecat orang yang sebetulnya didukung rakyat tapi dianggap tidak memuluskanm aspirasi mereka. Kasus pengusiran Bani Sadr, pengucilan kekuasaan Mohamad Khatami, serta pencoretan calon anggota legislatif dari kalangan reformis, serta pelarangan protes mahasiswa dan pembelengguan kebebasan pers akhir-akhir ini, tampak menunjukkan hegemoni itu. Para ulama’ akhirnya hanya memanfaatkan kharisma dan kedudukannya guna memuluskan ambisi pribadi dan kelompoknya.
Penjaga Moral
Maka, para ulama’ sudah selayaknya konsisten dengan fungsinya sebagai penjaga moral dan alat kontrol terhadap kekuasaan. Tempat para ulama’ adalah di pesantren, madrasah, sekolah, dan pedesaan guna membangun peradaban alternatif. Mereka harus menjadi pembela kaum tertindas dan orang-orang yang selama ini terhinakan, baik oleh struktur kekuasaan atau pemahaman keagamaan yang sempit. Perjuangan lewat jalur kekuasaan yang dilakukan oleh para politisi, sudah semestinya disinerginakan dengan perjuangan budaya dan keadilan sosial yang dilakukan oleh para ulama’. Sebab, tanpa hal itu semua, politik dan Pemilu hanya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan yang tanpa pernah menyentuh kebutuhan mendasar rakyat kecil di pedesaan atau kaum miskin di kota.
Dalam membangun sebuah peradaban ini, menurut KH. Mustofa Bisri, para ulama’ sudah semestinya menjaga jarak dengan kekuasaan. Dengan begitu, mereka akan lebih kuat dari kekuasaan dan tidak akan menghegemoni kekuasaan demi ambisi pribadinya. Mereka tentu akan lebih leluasa membangun nilai dan pranata yang akan dianut oleh masyarakat. Bukan malah sebaliknya, menjadikan masyarakat sebagai pengikut yang dimanfaatkan untuk mendukung calon atau partai yang dianut sesuai subyektifitasnya. Dengan kerja-kerja peradaban ini, maka energi umat akan lebih termanfaatkan untuk urusan jangka panjang. Semisal: perbaikan pendidikan, penyebaran dakwah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemberantasan korupsi, serta kemandirian terhadap kekuatan asing. Determinisme ekonomi dan politik lewat jalur kekuasaan, sudah semestinya diimbangi dengan perubahan budaya dan sosial yang dilakukan oleh para ulama’ dan rakyat.
Sebagai pewaris Nabi dan orang yang tertanam akarnya di masyarakat, para ulama’ dengan semestinya memainkan diri sebagai figur moral, anutan publik, berwatak sosial, serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran ulama sebagai rausyan fikr- meminjam istilah Ali Syariat – akan betul-betul membumi di masyarakat. Intelektual organik semacam itulah, yang akan memberikan pencerahan dan keoptimisan banga ini ke depan. Demokratisasi dan pengentasan krisis tidak akan berhasil dilakukan, jika di kalangan bawah tidak dibangun civil society yang kuat dalam melakukan kerja-kerja peradaban secara konsisten. Wallahu A’lam. (19/04/2004: Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=546). e-ti
05 | Evolusi Pemahaman Keagamaan
Dewasa ini, tafsir-tafsir keberagamaan yang muncul di masyarakat lebih banyak berasal dari satu arah, yaitu tafsir dari lembaga keagamaan. Selain itu, tafsir keagamaan yang ada juga terlalu berorientasi pada pemahaman keagamaan yang bersifat vertikal dan legal-formal. Artinya pemahaman keagamaan yang dipupuk adalah yang berhubungan dengan ibadah ritual, doktriner, dogmatis, dan berhubungan dengan kesadaran langit (ketuhanan).
Dewasa ini, tafsir-tafsir keberagamaan yang muncul di masyarakat lebih banyak berasal dari satu arah, yaitu tafsir dari lembaga keagamaan. Selain itu, tafsir keagamaan yang ada juga terlalu berorientasi pada pemahaman keagamaan yang bersifat vertikal dan legal-formal. Artinya pemahaman keagamaan yang dipupuk adalah yang berhubungan dengan ibadah ritual, doktriner, dogmatis, dan berhubungan dengan kesadaran langit (ketuhanan).
Sementara itu, tafsir-tafsir lain yang dilakukan secara radikal dan kreatif kadangkala sering ditolak kemunculannya dengan berbagai alasan yang dipaksakan. Padahal, sebuah kebenaran tafsir keagamaan tidak serta merta muncul dari satu sisi, namun harus digali dari berbagai segi dan perspektif.
Sebuah tafsir tunggal agama sesungguhnya jauh dari sehat karena akan mengakibatkan terjadinya penyelewengan pada pesan agama yang awalnya bertujuan mulia. Karena, sikap dasar bawaan manusia tidak jauh dari kenaifan, keserakahan, dan nafsu menundukkan lainnya. Hal itu terbukti ketika khalifah Al-Ma’mun pada masa Dinasti Abbasiyah menerapkan mihnah (inkuisisi) yang berisi kewajiban penduduk untuk berpaham teologi Mu’tazilah. Peristiwa lain nampak pada penguasa Taliban tempo hari yang memaksakan penerapan syariat Islam secara radikal pada penduduk Afghanistan. Begitu juga lembaga gereja-gereja Katholik sebelum Konsili Vatikan Kedua yang membekukan pemahaman keagamaan sebagai sesuatu yang eksklusif dengan menyatakan “tidak ada keselamatan di luar gereja”. (Perlu dicatat bahwa setelah Konsili vatikan Kedua, gereja Katholik menjadi sangat inklusif karena mereka mengakui bahwa di luar gereja, yakni dalam epercayaan dan agama selain Katholik, juga terdapat keselamatan).
Evolusi Pengetahuan Agama
Doktrin yang banyak tertanam dalam benak pikiran dan perilaku umat beragama adalah bahwa kebenaran agama bersifat tunggal, pasti, dan tuntas. Mereka menganggap, bahwa agama adalah wilayah yang harus disucikan dari kreatifitas dan kritik manusia. Sebab, agama adalah wilayah milik Tuhan yang terjamin kebenarannya. Orang yang berani mengkritik agama justru dianggap orang yang gila, aneh, jauh dari kebenaran.
Namun, bila kita kembali ke sejarah turunnya agama-agama di dunia, sesungguhnya agama tidak bisa lepas dari unsur kreatifitas manusia. Bila wilayah agama dianggap sebagai wilayah Tuhan semata, lantas kenapa muncul agama-agama baru yang bertugas sebagai pelengkap dan penyempurna agama terdahulu? Seperti agama Islam yang berita turun dan kebenarannya terdapat dalam kitab Injil, dan agama Nasranipun ada dalam kitab Taurat milik agama Yahudi. Artinya, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa Tuhan sangat paham atas kondisi perubahan zaman, alam, serta tingkat pengetahuan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan agama-agama yang -meminjam istilah Frithjof Schuon- di dalamnya terdapat titik temu bersama yang mestinya harus digali dan dimunculkan.
Evolusi agama yang berwujud pada keberagamaan manusia itu, menurut Robert N. Bellah berjalan sesuai dengan tingkat perkembangan kebebasan dan situasi masyarakat yang mengelilinginya. (Beyond Belief, 2001) Fokus utama evolusi keagamaan adalah sistem simbol keagamaan itu sendiri. Maksudnya, arah utama perkembangannya adalah simbolisasi dari yang sederhana menuju simbolisasi yang terdiferensiasi. Evolusi dari agama primitif menuju ke agama historis dan kemudian berkembang menjadi agama modern adalah contoh bagaimana agama berubah dari pengaruh situasi kekuasaan okultis yang bermetaformosis dengan keyakinan yang bersifat rasional.
Berkaitan dengan evolusi keagamaan di atas, Abdul Karim Soroush, seorang pemikir Islam liberal dari Iran yang sering dijuluki sebagai “Luther Islam”, mengajukan teori penyusutan dan pengembangan keagamaan. Dalam cara kerja teori ini, sebuah kebenaran teks keagamaan tidaklah bersifat final. Artinya, meskipun agama adalah sebuah doktrin dari Tuhan yang dijamin kebenarannya, akan tetapi pemahaman agama masih bersifat relatif dan terbuka dari berbagai interpretasi baru. (Reason, Freedom, and Democracy in Islam, 2000) Nilai kebenaran sebuah agama dapat dilihat dari dua hal, yaitu kebenaran teologis dan kebenaran historis. Kebenaran teologis pada dasarnya yang mengetahui hanyalah pencipta agama itu sendiri (baca – Tuhan). Tidak ada satu pihak pun yang berhak merasa paling tahu tentang kebenaran teologis ini. Sedangkan kebenaran historis sebuah agama dapat dilacak dari sejauh mana agama tersebut dapat bermanfaat dan membebaskan umat manusia dari belenggu-belenggu kejahatan. Jadi, antara kebenaran agama dan pemahaman agama haruslah diberikan garis demarkasi yang jelas dan ketat.
Soroush juga menegaskan, bahwa dalam pemahaman keagamaan, mutlak diperlukan adanya evolusi yang bersifat dinamis, kritis, dan progresif. Oleh karena itu, ilmu agama haruslah diposisikan sama dengan ilmu pengetahuan lainnya yang bersifat manusiawi dan bersifat relatif (tidak ada kebenaran tunggal). Pengetahuan agama dan kebutuhan zaman yang baru haruslah dicarikan jawabannya terus menerus dengan ijtihad para agamawan seperti halnya ilmu kemanusiaan lain semisal biologi, fisika, kimia, astronomi, dan sebagainya.
Orang yang menghindari pemikiran evolusi keagamaan dengan dalih menjaga kemurnian agama sesungguhnya secara tidak langsung justru membekukan agama sehingga agama menjadi kehilangan elan vitalnya dan cenderung menjadi kekuatan yang tidak membebaskan bagi pra pemeluknya. Ilmu atau pemahaman keagamaan tidaklah bersifat sempurna dan berlaku sepanjang waktu, sebab ia terikat dengan sistem budaya yang juga senantiasa berubah. Maka, pemahaman keagamaan yang terus berkembang adalah salah satu bentuk usaha reformasi dan kebangkitan keberagamaan.
Membaca dan Memaknai Agama
Sesuai dengan watak evolusi agama yang harus diejawantahkan, maka tradisi kritik dan pemunculan tafsir yang heterogen menjadi suatu kemestian yang wajar dan tak terelakkan. Tradisi ini bertujuan agar peran-peran profetik agama sebagai kekuatan moral dan pembebasan lewat perilaku pemeluknya dapat muncul lagi ke permukaan. Keragaman tafsir juga mempunyai nilai positip sebagai upaya kontekstualisasi teks agama pada problem-problem kemanusiaan masa kini.
Dalam pemunculan keberagaman tafsir keagamaan, metode dekonstruksi yang dicetuskan oleh Jacques Derrida layak dijadikan alternatif paradigma dan cara kerja. Metode yang pada awalnya dipakai dalam bidang sastra dan filsafat ini, bertujuan untuk membongkar, menguak, atau meleburkan setiap jenis struktur yang dipaksakan kebenarannya, sehingga tidak menyisakan ruang untuk bertanya, menggugat, atau mengkritik.
Dalam bidang keagamaan, dekonstruksi terhadap teks ini memungkinkan kita untuk membongkar monopoli tafsir atas otoritas tertentu yang menegaskan mengenai “kebenaran” atas nama Tuhan, negara atau penguasa. Sehingga definisi dan praktek pencarian “kebenaran” menjadi demokratis dan berparadigma antroposentrik. Dalam hal ini, manusia menjadi pusat tafsir yang berusaha untuk menggali kebenaran yang beragam secara obyektif.
Evolusi keagamaan yang menghargai pluralitas itu dengan sendirinya menekankan adanya –meminjam istilah Mohamed Arkoun—historisitas logos dalam pembacaan teks. Maksudnya, dalam pembacaan teks agama mutlak diperhatikan rentang waktu kemunculan, kompleksitas, serta latar belakang ideologi yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, Arkoun mengkritik adanya sebuah pensakralan pengetahuan agama (taqdis al-afkar ad-diniyyah) yang sering terjadi pada umat beragama. (Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah, 1990) Sebab, sebuah pensakralan menjadikan manusia terbelenggu pada kebenaran tunggal dan penerimaan tanpa reserve sebuah penafsiran teks keagamaan. Padahal, kemunculan teks pada masa lalu pasti tidak terlepas dari dimensi politis dan ideologis sang pengarang.
Berkaitan dengan itu, Arkoun menawarkan kita agar jernih dan jeli membedakan pemikiran keagamaan yang ada pada era klasik, skolastik, dan modern. Untuk itu, model pembacaan teks dengan metode hermeneutika yang berusaha menghadirkan teks masa lalu agar bisa terpakai pada zaman sekarang layak dilakukan. Dalam metode ini, latar belakang kemunculan teks, maksud pengarang, struktur bahasa, nilai atau simbol pengetahuan, dan kontekstualisasi adalah sebuah lingkaran yang senantiasa berkelindan. Sehingga, sebuah teks keagamaan tidak serta merta dipakai secara simbolik tanpa mengkaji makna substantif dan moral yang ada di baliknya.
Dengan bahasa dan istilah berbeda, Mohammad Abed Al-Jabiri juga menegaskan, bahwa krititisme dalam pembacaan dan pemaknaan kembali teks keagamaan mutlak dilakukan. Sedangkan metodologi yang ditawarkan adalah metode strukturalis; analisis sejarah, dan kritik ideologi. Metode strukturalis digunakan sebagai pembacaan teks secara literal dan membatasinya dalam melokalisir kebenaran yang bersifat sementara. Sedangkan analisis sejarah adalah mencari pertautan pemikiran sang pengarang teks dengan ruang lingkup sejarah budaya, sosial, politik, serta sosiologisnya. Kritik idelogi mengungkap maksud pengarang dalam penciptaan karya melalui episteme yang dirujuknya. (Post Tradisionalisme Islam, 2000).
Dengan model pembacaan dan pemaknaan agama yang tidak terjebak pada simbol dan homogenitas seperti diatas, maka umat beragama dapat diharapkan menjalankan keberagamaan baru yang humanis dan membebaskan. Penegasan Soroush bahwa “agama terakhir sudah datang, akan tetapi pemahaman agama yang terakhir belum datang” adalah kata kunci untuk memulai keberagamaan baru. Ke depan, umat beragama diharapkan dapat saling hidup bersama dengan menghargai perbedaan, melakukan dialog antar-intra iman, serta giat bekerjasama untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan dan menggalakkan demokratisasi. Wallahu A’lam. (27/10/2002: Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=83). e-ti
06 | Islam dan Tantangan Demokratisasi
Semenjak awal abad ke-21, demokrasi menjadi tema umum yang menarik perhatian banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara bekas Uni Soviet, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia, dan Afrika mempunyai keinginan menyuarakan tentang
perlunya power sharing kekuasaan. Dalam power sharing kekuasaan yang menjadi bagian penting demokrasi itu terdapat aspek partisipasi, representasi, dan perlindungan warga negara. Pada demokrasi, juga meniscayakan adanya
akuntabilitas pemerintahan, aturan hukum, dan keadilan sosial.
Menurut John L Esposito (2003), dalam tatanan demokrasi, para aktivis NGO, partai politik, asosiasi profesional, pendidikan, keuangan, pelayanan kesehatan, organisasi hak asasi wanita dan manusia memungkinkan untuk terlibat. Soalnya, dalam sistem ini, pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Pada banyak negara dan masyarakat Islam, agama menduduki posisi yang signifikan dalam perkembangan tatanan demokrasi ini. Peran agama menjadi penting, apakah ia akan mendukung demokratisasi ataukah justru ia menjadi
penghalang bagi penciptaan sebuah masyarakat yang demokratis. Ditambah lagi, institusi agama juga banyak yang menyediakan pelayan sosial, lembaga pendidikan, sarana kesehatan, yang tentu sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat (Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and the Middle East, 2003). Maka kesesuaian yang jelas dan titik temu pemahaman yang jernih antara Islam dan demokrasi sangat memberikan kontribusi positif pada penciptaan negara dan masyarakat yang demokratis.
Kritik konsep khilafah
Dalam pandangan banyak masyarakat Islam, perdebatan apakah Islam cocok dengan demokrasi atau tidak sudah menjadi polemik lama yang hingga sekarang belum tuntas. Perdebatan ini menjadi penting untuk diangkat terus-menerus,
sebab situasi dalam negara Muslim dan pada umumnya negara di dunia senantiasa berkembang dan berubah. Menurut para pakar hukum Islam, pada era abad lampau, umumnya ada tiga hubungan antara Islam dan pemerintahan yang banyak mengemuka pada masyarakat Muslim.
Pertama, sistem kuno, yaitu sistem negara yang alami, tidak beradab, anarkis, serta bersifat tiranik. Hukum dalam sistem ini adalah sebagaimana hukum rimba, yaitu bagaimana yang kuat memakan atau mengalahkan yang lemah.
Kedua, sistem kerajaan, yaitu adanya seorang raja atau pangeran yang mengatur semua urusan negara. Sistem ini juga banyak menguntungkan hanya pada kelas penguasa dan meminggirkan rakyat jelata, oleh karenanya sangat tiranik dan tidak mempunyai legitimasi. Ketiga, adalah sistem kekhalifahan, yaitu adanya seorang pemimpin yang mendasarkan aturan pemerintahan pada hukum syariah. Karena dianggap sebagai pemerintahan berdasarkan syariah yang mempunyai otoritas dibandingkan manusia, maka sistem ini menjadi kuat dibanding sistem lainnya (Khaled Abou El Fadl, Islam and the Challenge of Democracy, 2003).
Berdasarkan anggapan seperti itu, maka sistem kekhalifahan saat ini juga masih banyak yang menarik perhatian umat Islam. Mereka umumnya kembali menginginkan kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah, kembali muncul pada abad sekarang. Hal ini tampak terlihat dari fenomena Hizbut Tahrir yang banyak mengampanyekan khilafah Islamiyah sebagai solusi atas persoalan bangsa dan dunia. Padahal, pasca-ambruknya kekhalifahan Abbasiyah oleh tentara Mongolia pada tahun 1258 Masehi dan berakhirnya kekuasaan Dinasti Mamluk di Turki yang diganti oleh pemerintahan sekuler Mustafa Kemal Ataturk, sudah banyak masyarakat Muslim yang lebih tertarik pada konsep negara kebangsaan (nation state).
Bila kita telusuri dan pikirkan lebih mendalam, pada dasarnya pada sistem khalifah terhadap persoalan yang mendasar dan problematis. Karena ia mengaku sebagai Khalifatullah war Rasul (wakil Tuhan dan Rasulullah), maka banyak khalifah yang tidak merasa perlu atau penting mempertanggung-jawabkan kekuasaannya. Soalnya, dia menganggap bahwa apa saja yang dikatakan atau diperintahkan, itulah wujud dari hukum Tuhan. Dari sini, otoritanianisme dan absolutisme kekuasaan berawal muncul dan menjadi tradisi yang dipelihara oleh banyak khalifah-khalifah di masa lalu. Padahal, sebagaimana tugas nabi sendiri, pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan dan memberikan bimbingan pada manusia seluruhnya. Selain itu, dalam sistem kekhalifahan, juga tidak ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Adanya kecenderungan romantisme masa lalu itulah maka kesesuaian antara Islam dan demokrasi di masyarakat Islam menjadi persoalan yang rumit. Selain karena anggapan awal bahwa demokrasi adalah ide Barat yang sekuler dan tidak mengakui Tuhan, mereka juga mempertanyakan di mana meletakkan kedaulatan Tuhan di antara kedaulatan rakyat dan aturan negara? Menurut Khaled Abou El Fadl (2003), pada dasarnya demokrasi sangat mendukung kedaulatan Tuhan. Tapi, kedaulatan Tuhan itu sendiri sesungguhnya bisa diketahui lewat kehendak masyarakat atau dengan memenuhi kedaulatan rakyat. Sebab, pada dasarnya yang sering dikatakan sebagai hukum atau kehendak Tuhan oleh sebagian masyarakat itu sesungguhnya adalah penafsiran manusia yang sangat beragam dan tidak terdapat kebenaran tunggal. Oleh karenanya, visi etik Al Qur’an yang mengajarkan tentang penegakan hukum, shuro’, al-‘adalah, dan al-musawah adalah pilar bagi tatanan demokrasi itu sendiri.
Menuju praksis demokrasi
Olivier Roy dalam buku Globalised Islam: The Search for a New Ummah (2004) menyatakan bahwa perdebatan pada istilah atau konsep Islam dan demokrasi pada saat ini bukanlah menjadi persoalan yang terlampau penting. Yang lebih penting adalah persoalan dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembelajaran dan praktik demokrasi. Tentu saja, ini berlaku pada sepanjang waktu, kalangan atas dan bawah, serta dalam keadaan damai atau konflik. Sebab, demokratisasi akan bisa ditegakkan pada masyarakat nyata, jadi bukan pada hal atau visi abstrak yang diinginkan masyarakat.
Pada wilayah ini, maka para aktor demokrasi yang berbeda mesti memberikan pemahaman internal tentang konsep yang selanjutnya ditransformasikan menjadi hal yang praktis dan dipahami masyarakat. Jadi, bukan melulu melakukan permainan retorika istilah atau definisi administratif yang membingungkan rakyat.
Pernyataan Olivier Roy itu memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sebab, bila demokrasi betul-betul bisa dilaksanakan secara prosedural dan substansial, maka partisipasi publik yang luas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk rakyat bisa menjadi kenyataan. Jadi, persoalan pengertian dan cakupan demokrasi memang sebenarnya sangat melindungi hak dan kedaulatan rakyat. Dan semua aturan itu bisa dinegosiasikan lewat cara-cara yang beradab dan terbuka. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah melakukan praksis demokrasi lewat aktor-aktor dan institusi yang bisa mendukungnya.
Para aktor demokrasi itu tidaklah harus berasal dari intelektual progresif yang mempunyai ide-ide bagus sebagai komentator atau ahli politik Barat. Namun, hendaknya mereka berasal dari negara atau masyarakat di mana demokrasi itu akan dikembangkan. Tentu lebih bagus jika mereka juga mempunyai ikatan sosial dan jaringan tradisional yang mengakar pada masyarakat. Dalam istilah yang sekarang banyak dipakai orang, mereka itu adalah kompenen civil society. Civil society ini bisa terdiri dari aktivis NGO dan partai politik yang dikombinasikan dengan masyarakat pers yang bebas, atau juga dengan organisasi keagamaan dan tradisional.
Semua kekuatan itu, sebisa mungkin melakukan jaringan kebersamaan untuk menantang dan melawan semua otoritarianisme dan hegemoni negara atau pasar dunia. Dengan begitu, demokrasi nantinya tidak hanya menjadi ideologi atau wirid yang diucapkan tiap hari, namun sebagai aturan permainan dan alternatif penyaluran politik yang terbaik untuk kedaulatan rakyat. (Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005). e-ti
07 | Tegakkan Tanggung Jawab Sosial Agama
Hari demi hari, fenomena kemiskinan dan kelaparan di kalangan masyarakat ternyata semakin memprihatinkan. Akibat dari telikungan kapitalisme global, keserakahan penguasa, kekurangpedulian para agamawan, mereka yang tidak tersapa oleh kecukupan hidup menjadi pemandangan biasa.
Anehnya, para agamawan kita umumnya tampak tidak ambil pusing. Terbukti, belum ada tanggapan dan sikap tegas para agamawan terhadap privatisasi perusahaan negara dan utang negara. Padahal, yang paling dirugikan dari kebijakan itu pastilah mayoritas masyarakat di bawah yang rata-rata menggantungkan hidupnya dari pertanian, bekerja menjadi buruh dan nelayan tradisional. Mestinya, mereka mau dan mampu melakukan itu daripada mengeluarkan fatwa yang kurang terasakan manfaatnya bagi kehidupan rakyat kecil.
Takdir hingga struktural
Sikap para agamawan kita terhadap kemiskinan, kelaparan, dan problem penindasan lainnya bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, kalangan tradisional. Pada kelompok ini, kemiskinan lebih dilihat sebagai takdir yang harus diterima sebagai bentuk cobaan untuk menguji iman umat manusia kepada Tuhan. Jika mereka mampu melewatinya, diyakini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Melawan kemiskinan bisa diartikan melawan takdir Tuhan, jadi bisa dianggap orang yang tidak bersyukur.
Kedua, kalangan modernis. Menurut mereka, kemiskinan tergantung pada kesadaran setiap umat dalam menyikapinya. Artinya, pemahaman keagamaan sangat menentukan sikap dalam mengatasi kemiskinan. Untuk mengakhiri masalah ini, diperlukan sebuah revolusi kesadaran dan pembaruan penafsiran terhadap ajaran agama. Model ini mendapatkan kritikan dari Paulo Freire yang mencetuskan pendidikan pembebasan. Menurut Freire, hal itu masih berkutat pada kesadaran naif karena yang ingin diubah masih dataran kesadaran individu saja dan kurang menyentuh aspek lain yang menyebabkan problem itu terjadi.
Ketiga, kelompok kritis atau berteologi transformatif dan emansipatoris. Kemiskinan dan penindasan tak hanya dilahirkan oleh penafsiran keagamaan yang kolot saja, tapi lebih karena struktur sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang timpang. Maka, selain mendekonstruksi penafsiran yang otoriter dan ekstremis, juga harus bersikap kritis terhadap fenomena ketimpangan sosial yang dilegitimasi oleh struktur yang menindas. Pada model ini, tampak sudah meningkat dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis. Mereka melihat terjadinya struktur ketimpangan sosial tidak hanya karena kesalahan individu dan pemahaman keagamaannya saja, tetapi ada faktor struktural yang sesungguhnya melatarbelakanginya.
Penegakan keadilan
Dari sejarah, tampak bagaimana kegigihan Nabi Muhammad S>small 2small 0< sebagai seorang pembaru keagamaan sekaligus juga pembela kaum tertindas. Misi profetik Muhammad ketika pertama kali melakukan dakwah adalah merombak struktur sosiologi dan politik masyarakat Mekkah, merevolusi sistem teologinya, dan menghabisi monopoli ekonomi yang terjadi. Tugas membela kaum tertindas memang tidak bisa dipisahkan dari tugas memperbarui model penafsiran dan pemahaman keagamaan.
Dalam tradisi mazhab-mazhab Islam, pada dasarnya doktrin- doktrin tentang keadilan mudah ditemukan. Seperti Syiah, inti ajarannya adalah bagaimana membela orang-orang tertindas dan terpinggirkan. Dalam Sunni, terdapat ajaran Nabi Muhammad bahwa seorang yang beriman secara sebenar-benarnya tidak akan membiarkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar (Omid Safi, Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism, 2003). Maka, perhatian, bantuan, pembelaan, dan pemihakan kita terhadap seluruh umat manusia adalah hal yang mendesak dilakukan. Dalam bahasa Kristiani, “We are all our brothers’ and sister’s keepers now”.
Untuk melawan penindasan, kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan itu, prinsip keadilan sosial harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan terus. Keadilan sosial sering kali hanya dipahami sebagai nilai ideal yang menghiasi sejarah, tetapi jarang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, soal keadilan ini sudah harus inheren dalam diri setiap orang yang beragama. Sebab, keadilan adalah inti dari etika sosial setiap agama. (Kompas, Sabtu, 16 September 2006). e-ti
08 | Gerakan Mahasiswa dan Konstruksi Indonesia Baru
Gelombang aksi gerakan mahasiswa Indonesia akhir-akhir ini sedang mengalami pendulum balik yang rada memprihatinkan. Hal itu tampak dari fenomena demonstrasi yang dilakukan menyambut ST MPR yang baru saja berlalu. Saat itu, dari elemen-elemen mahasiswa yang melakukan aksi, hanya tampak beberapa gelintir organ saja. Dan itu pun, dari presentase kelembagaan, terlihat organisasi yang besar semisal HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan lainnya tidak unjuk gigi memanfaatkan momen tersebut.
Bila kita bandingkan dengan saat pemerintah menaikkan harga BBM, tarif telepon dan listrik awal 2003 lalu, akhir-akhir ini memang terjadi kesenjangan yang luar biasa. Pada peristiwa terdahulu, hampir keseluruhan organ mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang paradoks. Bahkan, banyak elemen mahasiswa yang solid dan bergabung dalam wadah BOKMM (Barisan Oposisi Kaum Muda Mahasiswa) yang di dalamnya Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah menjadi salah satu pelopornya. Saat itu, di Jakarta dan daerah-daerah, hampir setiap pekan demonstrasi marak dilakukan, baik oleh BEM, BOKMM, ataupun organ lainnya.
Terhadap Pemilu 2004 pun, saat ini hampir mayoritas dari gerakan mahasiswa menerimanya. Padahal, dari perangkat undang-undang pemilihan umum dan pemilihan presiden langsung, terdapat kekurangan yang sangat besar dan hanya mengesankan kompromi para politisi di Senayan. Hal itu tampak terlihat dari persyaratan seorang calon presiden yang hanya mengharuskan perolehan 3 % saat pemilu legislatif, diperbolehkannya seorang terdakwa mencalonkan diri, sahnya lulusan SMA sebagai kandidat, serta tidak adanya larangan seorang yang sakit mengajukan diri. Begitu juga di pemilihan legislatif, semisal: aturan-aturan tentang dana kampanye yang tidak jelas, ketidaktegasan sistem yang dipakai, serta gerak KPU dan Panwaslu yang terlihat sangat lamban dan tidak tegas. Dan yang lebih ironis lagi, penulis pernah mendengar bahwa dalam sebuah rapat akbar sebuah organisasi kemahasiswaan, terdapat aspirasi untuk mendirikan partai mahasiswa guna diikutkan dalam Pemilu 2004.
Sikap mahasiswa yang mulai berubah tersebut, mungkin dikarenakan realitas politik di hadapan mereka tidak memungkinkan untuk bergerak. Hal itu bisa dikarenakan kebutuhan untuk mencari posisi aman, ketidakenakan dengan senior, atau rasa frustasi karena kurang adanya dukungan dan simpati masyarakat terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan.
Seharusnya, para mahasiswa tidak larut dalam kekecewaan dan keengganan untuk bergerak demi mengawal proses transisi menuju demokrasi yang sedang berjalan dan ditumpangi oleh para sopir dan penumpang yang tidak bertanggung jawab ini. Untuk menyegarkan aktivitas mereka, gerakan mahasiswa harus mampu mereposisi strategi dan membuat skala prioritas terhadap kebutuhan mendesak apa yang perlu mereka jalankan. Janganlah karena kurang adanya dukungan dan habisnya kesabaran yang revolusioner, mereka menjadi pragmatis dan ikut arus para politisi.
Paradigma Baru
Mahasiswa adalah struktur yang unik dalam tatanan masyarakat, baik dilihat dari sudut politik, ekonomi, maupun sosial. Hal dikarenakan masa ketika menjadi mahasiswa adalah masa transisi sebelum mereka melanjutkan dirinya sebagai seorang profesional, pejuang, politisi, atau pengusaha. Selain itu, keunikannya juga tampak dari kebebasan yang mereka miliki, baik kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, atau melakukan apa pun. Komunitas mahasiswa juga merupakan satu-satunya komunitas yang paling dinamis dalam menangkap dan mengakomodasi sebuah perubahan serta paling harmonis dalam menyuarakan pendapat. Sebab, mahasiswa adalah asosiasi dari kejujuran, integritas dan semangat moral. Dalam diri mahasiswa, juga terdapat kumpulan calon cendekiawan, pahlawan, negarawan, serta profesi lainnya (Gerakan Mahasiswa, Rezim Tirani & Ideologi Reformasi, 2000).
Alangkah sayangnya, jika posisi yang strategis dan unik dari mahasiswa di atas, dibiarkan begitu saja berjalan tanpa ada pemompa semangat dan simpati masyarakat. Yang sering terjadi dan dijadikan ukuran gerakan mahasiswa, memang adalah keunggulannya dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan dan penjatuhan sebuah rezim. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa 1966, 1998, dan 2001 dianggap sukses. Sedangkan gerakan mahasiswa 1974, 1978, dan 2002 dianggap sebagai pecundang dan hanya mengacaukan ketenangan masyarakat. Penilaian seperti itu sangat simplistis dan ukuran sebuah keberhasilan gerakan tidak semudah analisis formal seperti itu.
Sebuah gerakan mahasiswa yang masih mau berpretensi menjadi gerakan moral dan pengawal kebijakan pemerintah demi menuju demokrasi, ukuran kalah atau menang dan kuat atau lemah tidaklah menjadi standar penilaian. Yang lebih penting adalah, bahwa ketika terjadi pertarungan antara isu demokrasi dan dagang sapi, penindasan dan keadilan sosial, kejujuran dan korupsi, maka mahasiswa harus tetap konsisten berdiri di belakang rakyat. Dengan begitu, meskipun tidak berhasil menumbangkan rezim, mereka tetap akan dikenang rakyat sebagai pahlawan hati nurani dan penyambung aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Menurut Craig Calhoun, peristiwa terbunuhnya para mahasiwa yang melakukan demonstrasi di lapangan Tiananmen pada 1988, akhirnya terbukti banyak berpengaruh dalam penumbangan kekuasan Deng Xiaoping.
Sebab, pascaperistiwa tersebut, terjadi pertikaian elite politik di pemerintah dan tubuh Partai Komunis Cina yang menyebabkan pergeseran kekuasaan (Neither Gods Nor Emperors, Students and Struggle for Democracy in China, 1997).
Oleh karena itu, gerakan mahasiswa harus senantiasa bangkit dan bersemangat untuk menyelamatkan bangsanya dari sebuah konspirasi politik nasional ataupun kekuatan kapitalisme global. Berkaitan dengan ini, Sutan Syahrir dalam sebuah konferensi Sosialis Asia di Bombay (India) tahun 1956 pernah meneriakkan sebuah kata-kata yang bagus untuk dikenang dan dipraktikkan. Yaitu: “Para mahasiswa sebagai kelompok pemuda harus bangkit melawan ketidakadilan sosial di negeri-negeri mereka sendiri. Para mahasiswa harus mengoreksi leadership formal di suatu negeri”. Jika mahasiswa mampu melakukan hal itu, maka pengandaian Hariman Siregar bahwa gerakan mahasiswa adalah pilar kelima demokrasi setelah pers, bukanlah sebuah isapan jempol dan harapan semu belaka.
Indonesia Baru
Pengawalan rezim pemerintah yang tentu tidak ada ada yang berjalan secara sempurna itu, memang mutlak dipelopori oleh mahasiswa. Paling tidak, hal itu dikarenakan keharusan mahasiswa sebagai aset masa depan bangsa untuk sadar akan posisi bangsa yang sedang suram dan oleh karenanya membutuhkan sebuah perbaikan. Dan sebuah perbaikan itu, tidak akan dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, jika tidak dikritisi dan dikoreksi setiap saat. Selain itu, sebagai pelopor gerakan yang mengkritisi pemerintah, mahasiswa mempunyai posisi yang signifikan. Maksudnya, dibandingkan elemen masyarakat atau gerakan lain, gerakan mahasiswa relatif masih bersih dan tidak terkontaminasi oleh arus kepentingan pragmatis. Meskipun ada sebagian yang seperti itu, pada umumnya para mahasiswa masih punya hati nurani dan kemauan berpikir secara jernih.
Yang tidak boleh dilupakan oleh gerakan mahasiswa, tentu saja adalah pengambilan simpati rakyat dan agenda transformasi masyarakat. Yang sering terjadi dan menyebabkan kekecewaan masyarakat, bahwa setiap aksi mahasiswa selalu menyebabkan jalan-jalan macet dan ketenangan mereka terusik. Hal itu sebetulnya bisa diatasi dengan mencontoh aksi-aksi yang dilakukan di luar negeri yang berjalan dengan tertib. Aspek kekerasan dan kesemrawutan seyogyanya sebisa mungkin mereka hindari. Dengan begitu, rakyat sedikit demi sedikit akan bersimpati dan sadar akan makna penting perjuangan mahasiswa. Selain itu, advokasi rakyat yang terkena penyerobotan tanah, kekerasan preman, serta arogansi penguasa di daerah-daerah juga penting untuk mereka lakukan. Dengan melakukan itu, gerakan mahasiswa tidak hanya menjadi gerakan elitis yang tidak berbasis di akar rumput. Pendidikan politik rakyat kecil adalah salah satu upaya yang sangat signifikan guna membuka jalan lapang menuju Indonesia Baru yang demokratis.
Harapan konstruksi Indonesia Baru memang layak disematkan pada gerakan mahasiswa yang mempunyai paradigma baru seperti di atas. Sebab, di saat para politisi sibuk berkampanye diri, para tokoh bangsa berlomba-lomba menjadi calon presiden, banyak aparat keamanan menjadi beking judi, para agamawan sibuk berdebat tafsir kebenaran, serta para LSM giat mencari proyek pemberdayaan rakyat, pers dan media massa tidak jarang yang jadi ajang iklan politik, maka gerakan mahasiswa adalah aset bangsa yang patut untuk dijaga.
Terlebih lagi, perjalanan reformasi yang berjalan terseok-seok ini, bisa menyebabkan rakyat frustasi dan rindu akan masa lalu. Jika itu terjadi, ibaratnya kita keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya, dan tercebur lagi ke mulut singa. Tentu saja, masa depan bangsa ini harus diselamatkan dengan kebersihan hati nurani, progresivitas gerakan, dan pemotongan aktor-aktor masa lalu yang ingin berkuasa lagi tapi terbukti culas dan menipu rakyat.
Terakhir, basis intelektualisme pada diri aktivis gerakan mahasiswa, adalah sebuah keharusan yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Dengan intelektualisme ini, maka pengajuan analisis dan konsep alternatif untuk rekonstruksi Indonesia ini akan mudah dilakukan. Selain itu, kejayaan para pejuang dan negarawan Indonesia zaman kemerdekaan yang sanggup menggabungkan kualitas intelektualisme dan aktivisme dapat kembali terulang menjadi kenyataan. Sosok-sosok seperti inilah, yang sebetulnya relatif bisa dipercaya memimpin dan mengatur Indonesia ke depan. Tentu saja, kualitas moral dan spiritual adalah sebuah pencapaian diri yang juga harus diupayakan terus-menerus. Wallahu A’lam. (Sinar Harapan, Senin, 15 September 2003). e-ti
Tokoh Terkait: Ahmad Fuad Fanani, | Kategori: Opini | Tags: Dosen, peneliti, UIN, IUN, HAMKA