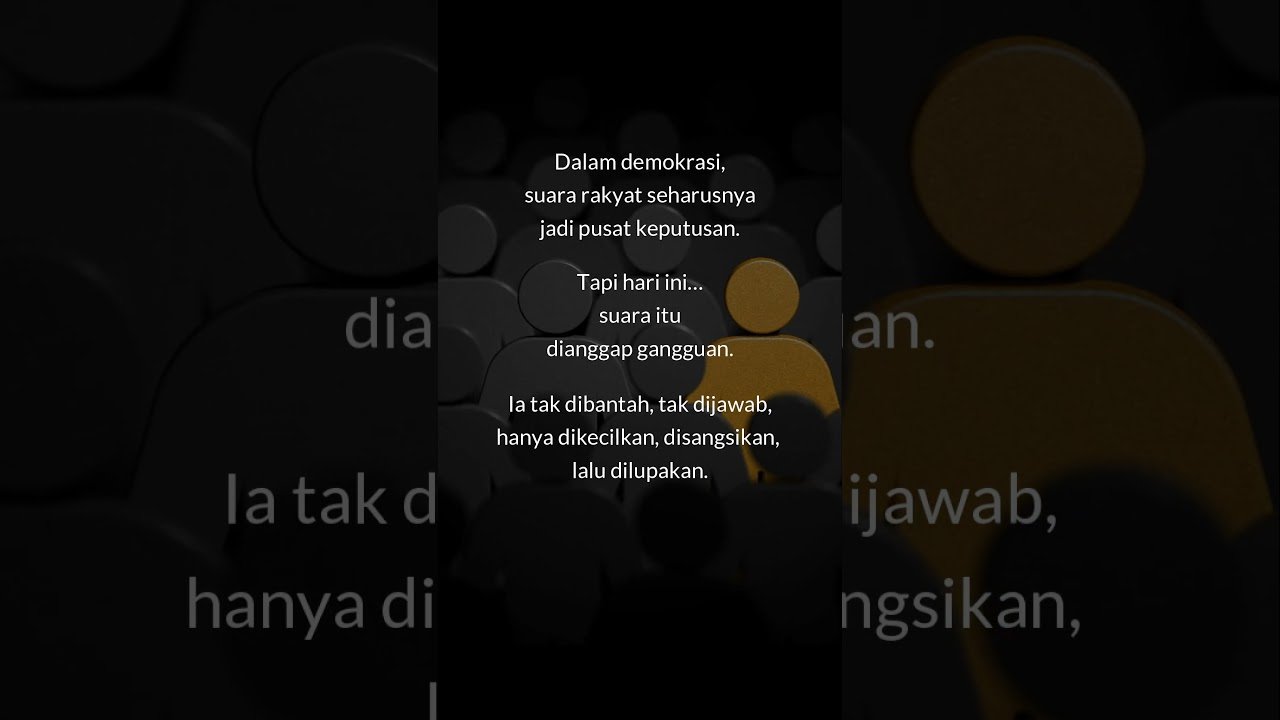Epilog: Yang Tak Didengar
Ketika suara rakyat diperlakukan sebagai gangguan
Dalam demokrasi, suara rakyat semestinya menjadi pusat keputusan. Tapi hari ini, suara itu lebih sering diperlakukan seperti gangguan. Ia tidak dibantah, tidak juga dijawab. Ia dikecilkan, disangsikan, lalu dilupakan.
Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian Lorong Kata yang membedah relasi kekuasaan, kritik, empati publik, dan pengaruh algoritma digital dalam demokrasi Indonesia:
- Kemarahan yang Sah. Menegaskan bahwa protes rakyat bukan gejala anarki, melainkan bentuk akumulasi luka akibat pengabaian.
- Ciri Orang Tolol Sedunia. Membongkar ironi ketika wakil rakyat mencemooh suara publik, dan bagaimana kata bisa jadi sumber delegitimasi.
- Ketika Rakyat Dianggap Bawahan. Melihat lebih jauh: bukan hanya pada insiden, tapi pada logika kekuasaan yang menyuburkan ketimpangan relasi.
- Affan Dilindas, Tanggung Jawab Menguap. Menunjukkan bagaimana tragedi rakyat sering hanya dijawab dengan ucapan duka dan janji bantuan, tanpa tanggung jawab politik yang nyata.
- Cara Halus Membungkam Suara. Mengurai taktik halus kekuasaan membatasi kritik publik, bukan dengan larangan eksplisit, melainkan dengan atmosfer takut.
- Catatan untuk Para Pengecut Digital. Mengungkap bagaimana sensor modern tidak lagi datang dari larangan, tapi dari algoritma yang memilih diam, dan platform yang tunduk bahkan sebelum ditundukkan.
- Epilog: Yang Tak Didengar. Merangkum ironi yang mengikat semuanya: bagaimana suara rakyat, dalam berbagai bentuknya – amarah, kritik, penderitaan, atau ingatan – terus disepelekan, dibungkam, atau dipastikan tak bergema.
Kemarahan yang muncul dari penderitaan disebut ancaman. Tuntutan yang disuarakan secara kolektif dicap sebagai keluhan “sebagian kecil rakyat.” Kata-kata itu diucapkan oleh seorang pejabat tinggi: bukan sekadar salah ucap, tapi salah paham. Dan barangkali, lebih banyak lagi pejabat lain yang tidak mengatakannya, tapi mempercayainya.
Sejak awal republik ini berdiri, suara rakyat selalu punya dua nasib: dijadikan pijakan saat dibutuhkan, atau diabaikan saat sudah tidak berguna. Dari petani yang protes soal tanah, buruh yang menuntut haknya, mahasiswa yang turun ke jalan, hingga masyarakat adat yang melindungi hutan: semuanya pernah dianggap gangguan. Demokrasi Indonesia lahir dari jeritan dan perlawanan, tapi terus-menerus memperlakukan suara rakyat sebagai distraksi.
Lalu kita mulai mengenali pola.
Yang bicara dianggap rusuh.
Yang menuntut dicap segelintir.
Yang mati dijawab dengan bantuan.
Yang bersuara dibungkam dengan algoritma.
Yang protes dikerdilkan menjadi statistik.
Yang mengingatkan dicemooh.
Yang diam… justru dianggap paling bijak.
Suara rakyat tidak sedang dibungkam. Ia sedang dijauhkan dari pendengarnya. Bukan oleh larangan eksplisit, tapi oleh sistem yang membuatnya tampak tak penting. Bukan oleh senjata, tapi oleh normalisasi. Dan ketika suara kehilangan tempat berpijak, maka satu-satunya yang tersisa hanyalah gema yang pelan-pelan memudar.
Di sinilah krisisnya. Ketika suara yang lahir dari luka dianggap berisik. Ketika mereka yang terluka dituduh sensitif. Ketika tangisan publik diubah jadi tontonan, lalu diganti dengan hiburan. Kita menyebutnya netralitas. Tapi sebenarnya, itu cara paling halus untuk berkata: aku tidak peduli.
Maka pertanyaannya kini bukan lagi, siapa yang berani bicara. Tapi: siapa yang masih mau mendengar?
Hari ini, rakyat tak dilarang bicara.
Mereka hanya dipastikan tak didengar.
(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)