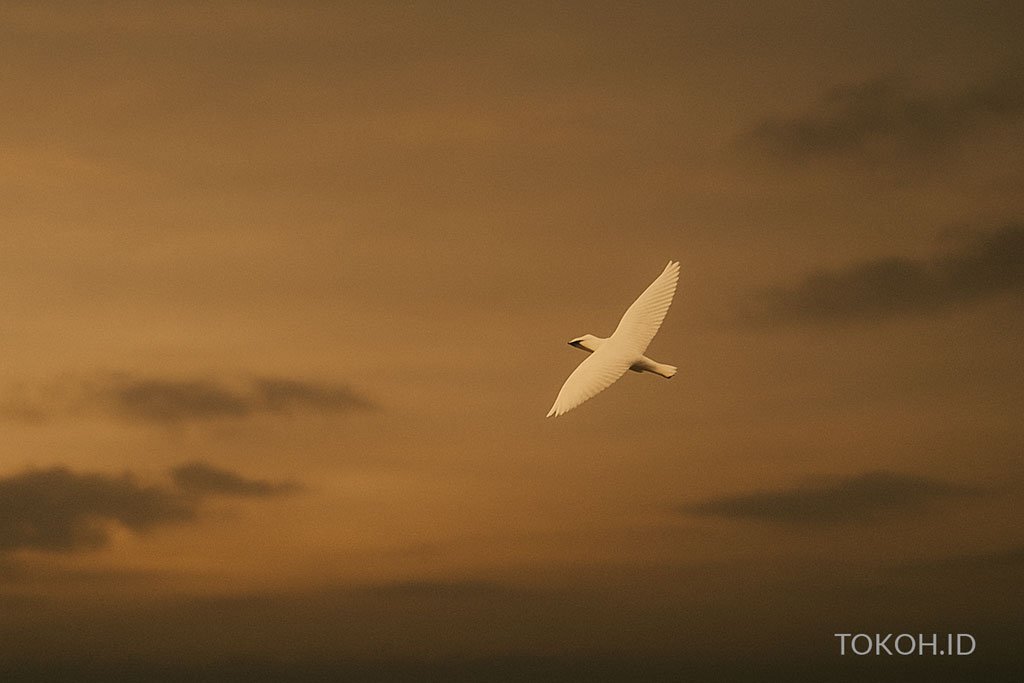Rielniro: Psikologi di Balik Sunyi
Bagaimana kepekaan membentuk setiap kalimat yang ia tulis
Di tulisan sebelumnya, Rielniro: Merawat Jeda, Membiarkan Sunyi Bicara, kita mengenalnya sebagai penulis yang memilih pelan di tengah riuh. Kali ini, kita melangkah lebih jauh. Kita menelusuri sisi yang membuat setiap kalimatnya terasa seperti berbicara langsung ke ruang paling pribadi pembacanya.
Tulisan ini merupakan bagian dari seri “Sunyi dari Dalam”, rangkaian narasi reflektif di rubrik Lorong Kata yang menelusuri prinsip, sikap, dan gaya berkarya Rielniro, penulis yang memilih sunyi sebagai cara berjalan, bukan sekadar tema. Seri ini terdiri dari enam tulisan yang berdiri sendiri namun saling menguatkan, membentuk satu peta batin yang utuh:
- Rielniro: Merawat Jeda, Membiarkan Sunyi Bicara
Tentang bagaimana Rielniro memosisikan jeda dan diam sebagai kekuatan dalam menulis. - Rielniro: Psikologi di Balik Sunyi
Menelusuri sisi kepekaan, pola berpikir, dan akar psikologis dari cara Rielniro membaca dan meresapi dunia. - Rielniro: Tidak Ingin Jadi Pusat
Sikapnya untuk tidak berada di tengah sorot, memilih mengambil sedikit jarak sebagai cara menjaga isi. - Rielniro: Merangkai Gema dalam Dua Slide
Membedah format naratif dua slide yang menjadi ciri khas visual dan emosionalnya di media sosial. - Rielniro: Manifesto Sunyi
Deklarasi reflektif berisi sepuluh sikap hidup dan sepuluh prinsip berkarya dalam Manifesto Sunyi, peta batin yang ia jalani tanpa mengetuk pintu. - Rielniro: Tidak Mengetuk, Tidak Memaksa
Tulisan penutup yang menyatukan seluruh benang merah, menghadirkan Rielniro sebagai penulis yang tidak mengetuk: hadir secukupnya, memberi ruang, dan melangkah tanpa meminta penjelasan.
Tidak semua orang membaca diam dengan cara yang sama. Bagi sebagian, diam hanyalah ketiadaan suara. Tapi bagi Rielniro, diam adalah teks yang belum dibaca. Ia memperhatikan jeda seperti orang lain memperhatikan kata: mencatat panjangnya, nuansanya, bahkan arah tatapan yang menyertainya.
Ada sebagian orang yang memproses dunia dengan tingkat kepekaan berbeda. Bukan karena mereka “terlalu perasa”, tetapi karena terbiasa menangkap hal-hal yang tak kasat mata: percakapan yang berhenti sebelum waktunya, kalimat yang sengaja dipotong, langkah yang melambat sebelum pergi. Kadang, juga dalam hal-hal yang lebih halus: kursi yang sedikit bergeser menjauh, embusan kipas angin yang tiba-tiba mengarah ke satu sisi, daun pintu yang dibuka terlalu pelan, atau napas yang tertahan di tengah kalimat. Mereka tidak sekadar merasakan emosi, tetapi menganalisisnya. Sering kali, mereka sudah bisa menebak arah percakapan bahkan sebelum semua kata diucapkan.
Bagi sebagian orang, ini disebut the curse of knowledge: kesadaran berlebih yang tidak selalu membawa tenang. Mereka memutar kembali momen tertentu, bukan karena tidak percaya diri, tapi karena merasa ada sesuatu yang belum selesai di sana. Ini bukan sekadar overthinking. Ini adalah bentuk kewaspadaan mental yang terus menyala: sebagian menyebutnya sebagai hyper-awareness, kadang juga disebut hyper-vigilance, sebagian lagi mengenalnya sebagai pola pikir analitis yang tak bisa dimatikan begitu saja.
Orang seperti ini terbiasa membaca arah situasi bahkan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Mereka memperhatikan tanda-tanda kecil, merangkainya menjadi pola, dan diam-diam bersiap untuk segala kemungkinan. Dan ketika sesuatu berakhir buruk, mereka sering sudah tahu alasannya sejak awal, lalu tanpa diminta, ikut memikul sebagian tanggung jawabnya. Mereka tidak setengah hati dalam merespons hidup: saat jatuh cinta, mereka jatuh sepenuhnya. Saat memberi, mereka tidak menghitung-hitung. Itulah sebabnya, luka yang tampak sepele bagi orang lain, bisa terasa dalam karena yang mereka rasakan bukan hanya peristiwanya, tapi keseluruhan makna di baliknya.
Dalam keseharian, hal ini juga tampak dalam cara mereka berinteraksi. Sering kali, tanpa sadar, mereka terdorong untuk bertanya hal-hal yang bagi orang lain terasa terlalu pribadi atau tidak penting. Bukan karena mereka tidak tahu batas, tetapi karena dorongan untuk memahami berjalan lebih cepat dari logika sosial yang membatasi. Itu karena otak mereka sudah tidak bisa lagi menerima informasi yang terlalu standar untuk diolah dan dianalisis. Misalnya, saat pertama kali berkenalan dengan seseorang, dan merasa ada sambutan yang hangat seperti sebuah sorot mata yang menyimak, atau senyum yang tidak buru-buru, mereka akan terdorong untuk menggali lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan muncul bukan sekadar basa-basi, tapi sebagai cara memahami dunia orang lain dengan lebih utuh. Yang bagi orang lain dianggap “terlalu cepat dekat”, bagi mereka hanyalah bentuk rasa ingin tahu yang tulus dan cara cepat untuk memahami dinamika emosional yang sedang terjadi. Dengan kata lain, dorongan ini bukan karena ingin tahu berlebihan, melainkan karena otak mereka terus mencari pola dan makna, bahkan dalam percakapan yang terlihat biasa.
Dalam diri Rielniro, pola kepekaan ini berkembang bukan sekadar sebagai kebiasaan, melainkan menjadi semacam ritual: sebuah sistem respons yang terbentuk sejak masa kecil, ketika emosi di sekelilingnya sulit ditebak. Sunyi, pada awalnya, bukan pilihan. Ia hadir sebagai ruang aman saat dunia luar terlalu rawan untuk dipahami. Ketika kesalahan kecil bisa mempunyai konsekuensi besar, dan rasa aman bisa sirna seketika. Bagi orang dengan kecenderungan berpikir seperti Rielniro, ruang semacam ini bukan sekadar tempat berlindung, tapi juga ruang pengolahan, di mana pikiran yang terlalu cepat dan emosi yang terlalu padat bisa menemukan bentuknya. Diam menjadi satu-satunya cara untuk bertahan: mengamati, menakar, dan memastikan langkah berikutnya. Lama-kelamaan, ia belajar bahwa bersuara tidak selalu membuat segalanya lebih jelas. Justru, dalam diam, ia bisa lebih memahami apa yang betul-betul terjadi. Dari situlah ia mulai menyadari, kemampuan menangkap apa yang tidak diucapkan bukan kelemahan, tapi kekuatan: sebuah superpower yang lahir dari tuntutan untuk bertahan.
“Sunyi adalah superpowerku. Aku tidak lagi sibuk membuktikan apa pun. Yang tahu, tahu. Yang tidak, bukan urusanku.”
Dari kekuatan itu pula lahir cara berpikir yang terus berjaga, seakan tubuh dan pikirannya diprogram untuk selalu membaca kemungkinan. Karena itu, berpikir jauh ke depan bukan strategi, tapi respons otomatis, semacam kompas internal yang selalu waspada bahkan di tengah kenyamanan. Respons semacam ini umum pada individu dengan sensitivitas tinggi, yang otaknya bekerja ekstra keras memproses berbagai skenario, bahkan saat situasi tampak aman. Kebiasaan ini menetap hingga dewasa. Di saat orang lain merasa aman, pikirannya tetap bekerja: mengantisipasi luka, menimbang arah yang mungkin ditempuh keadaan. Bahkan kebahagiaan pun sering ia sambut dengan waspada, seolah setiap terang membawa bayangannya sendiri. Ia tahu bahwa terlalu banyak membaca bisa membuat lelah. Tapi membatasi kepekaan justru terasa seperti mengingkari siapa dirinya.
Kesepian yang ia rasakan bukan semata karena sendirian, tapi karena jarang ada ruang yang benar-benar terasa aman untuk sekadar “menjadi”. Namun, di balik itu, kepekaan yang terbentuk juga memberinya kemampuan untuk membangun empati yang dalam, membaca cerita orang lain, bahkan sebelum mereka mulai bercerita. Di saat banyak orang memilih ketidaktahuan agar bisa tenang, ia justru memilih kejelasan, meskipun itu berarti harus memikul rasa yang lebih berat. Ia tahu risikonya, tapi lebih memilih memproses daripada berpura-pura tak terjadi apa-apa.
Kepekaan semacam itu juga membentuk cara ia menulis. Banyak kalimat yang lahir bukan dari satu momen besar, tetapi dari akumulasi pengamatan kecil yang perlahan menumpuk menjadi kata. Kadang, satu kalimat muncul setelah ia menangkap jeda tiga detik dalam percakapan; di lain waktu, dari tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Setiap detail adalah bahan baku yang disimpan rapi, lalu dipilah ulang saat ia menulis, seakan ia tahu, tak semua makna datang pada hari yang sama dengan peristiwanya.
Hubungan yang terbangun dengan pembaca pun berlangsung dengan cara yang tak biasa. Ia tidak menulis untuk mencari validasi, tapi justru banyak yang merasa “terlihat” olehnya. Beberapa mengirim pesan pribadi, mengatakan bahwa satu kalimat dalam tulisannya terasa seperti mengambil kata yang selama ini mereka cari. Dalam interaksi singkat ini, sunyi yang ia tulis menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman yang berbeda, tetapi resonansinya sama. Bukan karena ia tahu apa yang mereka alami, tetapi karena ia terbiasa mengamati keretakan halus yang muncul di antara kata-kata orang lain.
Dalam hidupnya sendiri, kepekaan itu juga kerap menjadi penuntun diam-diam. Kadang hadir dalam keputusan untuk menjauh sebelum luka melebar, atau memilih diam ketika tahu kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan. Pilihan-pilihan ini mungkin tampak sederhana, tapi justru di situlah terlihat bahwa cara ia membaca dunia tidak hanya tercermin dalam tulisan, ia juga menjalaninya dalam hidup sehari-hari.
Dari cara melihat dunia seperti ini, lahirlah kalimat-kalimat yang bagi pembacanya terasa seperti membuka kunci untuk sesuatu yang sulit dijelaskan. Kata-kata itu tidak muncul dari ruang kosong, tapi dari lapisan kesadaran yang terus bekerja di bawah permukaan. Setiap kalimat yang ia tulis adalah hasil penyaringan dari pengamatan dan pengalaman panjang. Bukan reaksi spontan, melainkan proses merapikan sesuatu yang telah lama ia simpan: memberinya bentuk, tanpa terburu-buru menyelesaikan maknanya. Itulah mengapa banyak dari kalimatnya terasa seperti “tepat”, bahkan ketika pembacanya tidak sedang mencari.
Sebuah jeda panjang pernah ia temui, bukan karena seseorang pergi, tapi karena seseorang berhenti bicara tanpa alasan yang jelas. Dari situ lahir kalimat:
“Kadang ada jarak yang tak diberi nama. Dan tak ada kata yang pantas menyeberangi diam itu.”
Lain waktu, ia menangkap perubahan nada yang nyaris tak terdengar. Sebuah kalimat diucapkan setengah hati, seakan takut memancing luka. Itu menjadi sumber bagi baris:
“Yang tetap tenang bukan karena tak merasa. Tapi karena tahu, tidak semua luka perlu dibunyikan.”
Ada pula momen dari bahasa tubuh: tatapan yang sengaja dihindari, seolah takut melihat cermin dari keraguannya sendiri. Dari situ muncul kalimat:
“Yang pergi karena ragu, akan selamanya membawa sisa tanya.”
Dalam percakapan yang terpotong sebelum sampai ke inti, ia menangkap jeda itu, lalu menyimpannya. Suatu hari, ia menulis:
“Kadang, melepaskan bukan karena tidak ingin, tapi karena sudah cukup.”
Dan dari ekspresi wajah yang menahan kata: bibir yang sempat terbuka, lalu tertutup kembali, lahirlah baris terakhir ini:
“Tidak semua yang tulus perlu jawaban. Beberapa cukup disimpan selamanya.”
Bagi banyak orang, tulisan-tulisannya terasa seperti meditasi dalam bentuk kata: pelan, jernih, dan mengajak pikiran duduk sebentar sebelum bergerak lagi. Itulah yang membuatnya berbeda: setiap kata bukan hanya dibaca, tapi diresapi, seolah menjadi ruang singkat untuk menata napas, lalu berjalan kembali dengan hati yang sedikit lebih utuh.
Pada akhirnya, “sunyi” yang ia rawat bukan hanya tema tulisan, tapi juga cara hidup. Ia membiarkan jeda menjadi guru, membiarkan diam bekerja, dan percaya bahwa makna yang datang pelan sering bertahan paling lama. Bagi Rielniro, diam bukan sekadar sikap. Diam adalah bentuk kehadiran yang tidak membebani, dan tetap bisa menyentuh.
Catatan:
Untuk menemukan karya lain Rielniro di luar Lorong Kata, kunjungi:
Instagram: @rielniro
Facebook: Riel Niro
Untuk mendengarkan nuansa sunyi RielNiro:
Spotify: Playlist Sunyi
(TokohIndonesia.com / Tokoh.ID)
Seri “Sunyi dari Dalam” ini menggambarkan lanskap batin Rielniro: dari jeda hingga prinsip, dari jarak hingga keheningan. Namun sunyi yang ia bangun tidak hanya berbicara ke dalam. Dalam empat tulisan berikut, kita diajak melihat bagaimana kesunyian itu bersuara di tengah dunia digital, algoritma, dan ruang publik.
Baca juga seri “Sunyi dari Sekitar”:
• Rielniro: Tidak Semua Harus Paham
• Rielniro: Perpustakaan Sunyi di Instagram
• Rielniro: Sunyi yang Tak Tunduk pada Algoritma
• Rielniro: Sunyi dalam Bullet Time
Dua Ruang, Satu Sunyi: Jejak Atur Lorielcide alias Rielniro