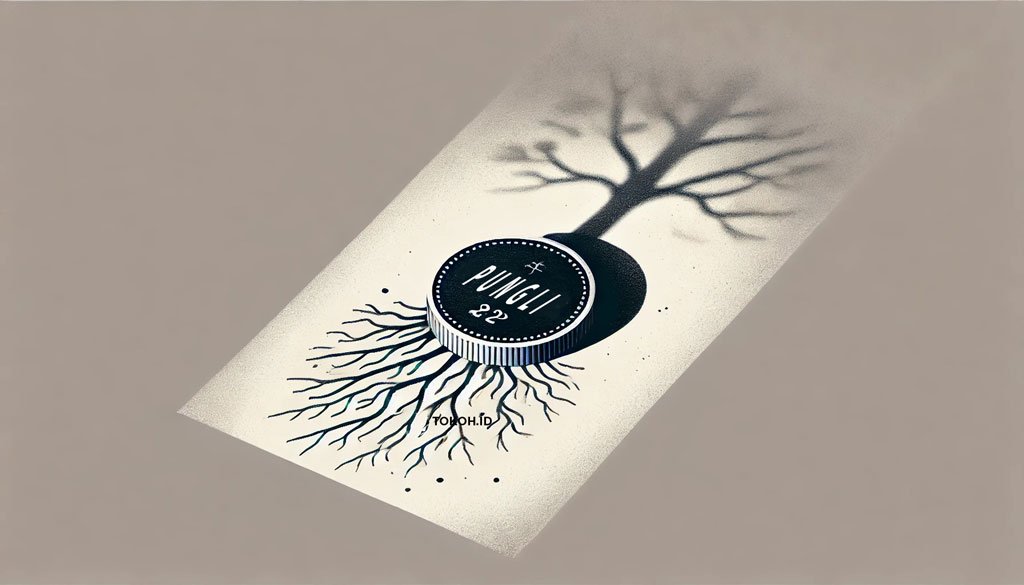Coba Sebutkan: Di Mana Pungli Tidak Ada?
Di negeri yang konon menjunjung tinggi keadilan, pungutan liar (pungli) tumbuh seperti benalu – bukan hanya merayap di ruang kelas, kantor pemerintahan, dan terminal bus, tapi juga sudah menyusup ke jantung lembaga penegak hukum. Pungli bukan lagi kejahatan sembunyi-sembunyi, tapi kenyataan terbuka yang dimaklumi, ditakuti, bahkan diwariskan. Ini bukan cuma soal uang receh, tapi soal kepercayaan rakyat yang terus dikikis oleh sistem yang pura-pura tidak tahu.
Minggu pertama April 2025, publik kembali dikejutkan oleh kasus dugaan pungli yang melibatkan sopir angkot di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Para sopir yang menerima kompensasi dari pemerintah daerah, mengaku diminta menyetor “uang terima kasih” sebesar Rp200 ribu kepada pihak tertentu.
Situasi ini memanas hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung, menyebut praktik tersebut sebagai bentuk premanisme. Dishub Kabupaten Bogor sendiri menegaskan informasi tentang pemotongan dana kompensasi sopir yang sampai ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merupakan hasil miskomunikasi. Meski kemudian diklarifikasi bahwa dana itu “sukarela” dan telah dikembalikan, kasus ini menyisakan ironi klasik: pungli di negeri ini seperti benih yang dilempar di mana saja – selalu tumbuh subur, bahkan di tempat yang paling tak terduga.
Apa yang terjadi di Puncak, Jawa Barat, hanyalah secuil potret dari sebuah penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Pungli telah menjelma menjadi praktik yang nyaris sistemik, menular ke hampir seluruh sektor pelayanan publik. Dari sekolah, birokrasi pemerintahan, tempat wisata, hingga terminal bus, rumah tahanan, bahkan ke dalam institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Mahkamah Agung.
Di sektor pendidikan, praktik ini bersalin rupa menjadi “iuran komite”, “biaya pembangunan”, atau “biaya wisuda” yang nilainya tidak sedikit dan terasa wajib. Banyak orang tua yang tahu itu pungli, tapi juga tahu risikonya jika melawan: anak mereka bisa dikucilkan, dilayani dengan ogah-ogahan, bahkan dipersulit kelulusannya. Ombudsman RI mencatat, setiap tahun pendidikan tetap menjadi sektor dengan laporan pungli terbanyak. Bukankah menyedihkan saat lembaga yang seharusnya menanamkan kejujuran justru menjadi tempat pertama anak-anak belajar, “asal bayar, semua bisa diatur”?
Di sektor birokrasi, praktik pungli tak kalah pelik. Mengurus KTP, akta lahir, surat tanah, bahkan SIM, kerap kali membutuhkan “biaya ekstra”. Bukan karena regulasi, tapi karena sistem yang tidak transparan, lambat, dan penuh celah. Dalam situasi ini, pungli tumbuh subur – diberi ruang oleh ketidaktahuan masyarakat dan dibiarkan oleh aparat yang merasa itu “uang jasa”. Warga yang lelah dan tidak punya waktu lebih akhirnya menyerah. “Daripada bolak-balik, mending bayar saja,” begitu kata yang sering kita ucapkan/dengar. Di titik inilah pungli menemukan ruang hidupnya: di antara keputusasaan dan ketidakpedulian.
Di sektor transportasi, praktik pungli terjadi secara terstruktur di terminal bus kota. Ombudsman menemukan bahwa para sopir dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dari ketentuan, namun karcis yang diberikan tak sesuai. Di Terminal Bekasi Kota, misalnya, pengemudi diduga membayar Rp15.000, tapi hanya menerima karcis senilai Rp2.000. Sisanya? Menguap entah ke mana. Aparat terminal, yang semestinya menjaga ketertiban dan integritas layanan publik, justru menjadi bagian dari lingkaran gelap yang merugikan.
Tempat wisata pun bukan zona aman. Di Raja Ampat, kawasan yang dikenal dunia karena keindahannya, pungli terhadap kapal wisatawan terjadi secara terbuka. Menurut KPK, nilai pungli ini bisa mencapai Rp18 miliar per tahun. Di beberapa pantai Jawa Barat, wisatawan dikenai tarif masuk yang tak resmi dan biaya parkir oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok warga, karang taruna, atau ormas. Mereka hadir seperti bagian dari sistem, padahal tidak ada dasar hukumnya.
Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika pungli sudah merasuk ke dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, mahkamah agung, bahkan Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Kasus yang mengemuka beberapa waktu lalu membongkar fakta bahwa 15 mantan pegawai rutan KPK menerima pungli dalam bentuk “uang fasilitas khusus”. Para tahanan diminta membayar untuk akses ke ponsel, percepatan masa isolasi, atau hanya untuk mendapatkan kemudahan istirahat. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, mereka mengumpulkan sekitar Rp6,3 miliar dari pungli. Ironis. Lembaga yang menjadi simbol antikorupsi malah harus menghadapi korupsi di jantungnya sendiri.
Di kepolisian, pungli muncul dalam bentuk “uang damai” bagi pelanggar lalu lintas agar tak ditilang, atau “uang pelicin” bagi penyidik agar proses hukum dipercepat atau diarahkan. Bahkan dalam proses rekrutmen calon polisi, tak sedikit cerita soal “biaya titipan” agar bisa lolos. Bukti pungli di sektor ini bukan hanya cerita rakyat – sudah sering muncul di laporan Ombudsman dan bahkan OTT Saber Pungli.
Di kejaksaan, pungli bisa terjadi dalam proses tuntutan hukum. Ada cerita tentang “diskon tuntutan” bagi terdakwa yang mau membayar. Ada juga praktik di mana kasus yang semestinya naik ke pengadilan diselesaikan diam-diam dengan uang, lalu menguap begitu saja. Di sisi lain, penegakan terhadap jaksa nakal masih minim, seakan mereka bekerja di ruang kebal kritik.
Di pengadilan, pungli tak hanya soal percepatan sidang. Ia bisa lebih kompleks: pengaturan agenda, pemilihan hakim, bahkan putusan. Suap terhadap panitera atau hakim bukan hal baru. Kita masih ingat bagaimana Komisi Yudisial dan KPK pernah menyasar praktik jual beli perkara yang berlangsung diam-diam namun sistematis.
Dan ketika kita berpikir itu puncaknya, datang kasus Ronald Tannur yang menampar wajah peradilan. Setelah divonis bebas oleh hakim PN Surabaya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, penyelidikan menguak bahwa tiga hakim tersebut menerima suap miliaran rupiah. Lebih parah lagi, kasus ini menyeret nama seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang bertindak sebagai makelar kasus. Ia dijanjikan Rp1 miliar dan berjanji mengatur hakim agung agar putusan kasasi Ronald tetap bebas. Uang tunai dan emas senilai hampir Rp1 triliun ditemukan di rumahnya – bukti bahwa percaloan hukum di Mahkamah Agung bukan hanya skandal, tapi sistem.
Mengapa pungli sulit diberantas? Jawaban sederhananya: karena ia sudah jadi bagian dari sistem. Secara historis, sejak era kolonial, pungutan informal menjadi alat kontrol birokrasi. Setelah kemerdekaan, kebiasaan ini tidak dibersihkan, hanya berganti rupa. Aparatur negara dibayar tidak layak, pengawasan lemah, dan masyarakat kurang paham hak-haknya. Dalam ekosistem seperti ini, pungli bukan hanya terjadi – ia dibutuhkan untuk membuat sistem bergerak.
Secara psikologis, pelaku pungli sering merasa tidak bersalah. Mereka menyebut uang itu “tambahan kecil”, “uang rokok”, atau “imbalan jasa”. Mereka tidak sadar bahwa setiap rupiah yang mereka ambil adalah bagian dari ketidakadilan struktural yang menindas masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang menjadi korban justru merasa tak berdaya. Banyak yang tahu mereka dipungli, tapi lebih memilih diam. Karena melawan berarti menanggung risiko: urusan jadi berbelit, layanan tidak selesai, atau malah disudutkan. Di sinilah pungli hidup – di antara rasa takut dan rasa lelah.
Padahal dari sudut hukum, tidak ada yang bisa membenarkan praktik ini. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), pungli termasuk korupsi dan bisa dikenakan pidana berat. Tapi kita tahu, hanya segelintir kasus yang benar-benar diproses. Sebagian besar menguap, dibungkus kompromi atau “kesepakatan adat”. Penegakan hukum yang tebang pilih hanya memperkuat pesan bahwa hukum bisa dinegosiasi, bahwa kebenaran itu soal siapa yang berkuasa.
Pungli bukan sekadar soal uang kecil. Ia adalah simbol sistem yang rusak dari akar. Ia menciptakan generasi yang percaya bahwa keadilan bisa dibeli, bahwa kejujuran hanya berlaku saat tak ada pilihan. Ia menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi dan membiarkan ketidakadilan tumbuh dalam diam.
Saber Pungli boleh saja digadang-gadang sebagai garda terdepan pemberantasan. Tapi jika tidak menyentuh akar masalah – dari transparansi sistem, perlindungan pelapor, hingga penegakan hukum yang tegas – maka ia hanya jadi slogan.
Pungli tak akan hilang hanya dengan spanduk bertuliskan “tolak gratifikasi”. Ia hanya akan hilang saat negara benar-benar hadir, bukan hanya tampak. Saat aparat tidak hanya dituntut menegakkan hukum, tapi juga memberi teladan. Dan saat rakyat tak lagi dipaksa memilih antara diam atau urusannya tak selesai.
Sampai saat itu datang (entah kapan), jangan salahkan rakyat yang membayar pungli. Salahkan sistem yang membuat mereka merasa tak punya pilihan lain.
Dan jika kita masih menganggap pungli hanya soal “uang kecil”, mungkin kita belum cukup serius mencintai negeri ini. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)