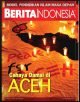[WAWANCARA] Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.
Rorientasi tersebut mencakup dua hal mendasar. Pertama, reorientasi fokus pemba-ngunan, dari basis sumber-daya daratan ke basis sum-berdaya kelautan. Kedua, bahwa tujuan pembangunan kelautan hendaknya tidak semata-mata mengejar per-tumbuhan ekonomi, melain-kan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (social equity), dan terpeliharanya daya du-kung dan kualitas lingkungan pesisir serta lautan secara seimbang (proporsional).
Laut jangan lagi dipersep-sikan sebagai keranjang sampah (tempat pembuangan limbah dari darat) dan ajang ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi se-bagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan diman-faatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahte-raan seluruh umat manusia.
Menteri yang memang ahli dan menyatu dengan bidang kelautan dan perikanan ini berbicara mengenai hal-hal mendasar dan strategis mengenai berbagai masalah pembangunan kelautan dalam dua kali percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia.Com di Jakarta, 29 Desember 2002. Berikut petikannya.
M-TI: Anda menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Apa yang melandasi gagasan ini?
ROKHMIN: Gagasan paradigma pembangunan ini selain mendasarkan pada potensi, peluang, permasa-lahan, kendala, dan kondisi pembangunan kelautan yang ada, juga mempertimbangkan pengaruh lingkungan strate-gis terhadap pembangunan nasional seperti globalisasi dan otonomi daerah.
Letak geografis dan kan-dungan sumber daya kelaut-an yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta km2 atau 3/4 dari total wilayah Indonesia merupakan lautan dan ditaburi sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Kondisi geografis ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Indonesia berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, sebuah kawasan paling dinamis dalam percaturan politik, pertahanan dan keamanan dunia. Alasan di atas sudah cukup menjadi dasar untuk menjadikan pembangunan kelautan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan nasional.
Selain itu, banyak argu-men yang memperkuat mengapa pembangunan berbasis sumber daya kelautan, harus dijadikan arus utama pembangunan nasional, baik secara ekono-mi, politik, sosial dan buda-ya. Pertama, melimpahnya sumber daya kelautan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi.
Kedua, keterkaitan yang kuat (backward and forward lingkage) antara industri berbasis kelautan dengan industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan berarti juga mendo-rong aktivitas ekonomi di sektor lainnya, termasuk usaha transportasi, komuni-kasi, perdagangan, pengolah-an, dan jasa-jasa lainnya.
Ketiga, sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui (renewable resources) sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat bertahan panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif.
Keempat, dari aspek poli-tik, dengan kondisi geopolitis yang ada, maka stabilitas politik dalam negeri dan luar negeri dapat dicapai, jika kita memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan perairan.
Kelima, dari sisi sosial dan budaya, menjadikan pemba-ngunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa merupakan penemuan kembali (reinventing) aspek kehidupan yang pernah dominan dalam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa. Sejarah mencatat bahwa pusat-pusat ekonomi dan peradaban yang pernah ada di wilayah Nusantara, selama berabad-abad telah menjadi-kan sumber daya kelautan sebagai basis pertumbuhannya dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan dalam peradabannya. Pada saat itu, laut telah menjadi media hubungan nasional dan internasional, serta menjadi suatu kawasan penting, baik secara politik, ekonomi dan militer. Bahkan, sampai sekarang masih terlihat sisa-sisa budaya berbasis bahari ini pada beberapa suku di Indonesia.
M-TI: Potensi sumber daya kelautan Indonesia demikian besar. Bagaimana posisi pembangunan berbasis sumber daya kelautan selama ini?
ROKHMIN: Suatu kenyataan pahit yang harus kita akui bahwa selama ini, ternyata pembangunan berbasis sumber daya kelautan diabaikan. Pemba-ngunan berbasis sumber daya kelautan dianggap sebagai sektor pinggiran. Rendahnya kinerja sektor ekonomi berbasis kelautan yang jauh dari potensi yang dimiliki, merupakan harga yang harus dibayar, akibat kelalaian serta ignorant kita sendiri sebagai bangsa.
Namun, sejak reformasi, muncul kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional telah mendapatkan tempat yang lebih baik serta pijakan yang lebih kuat. Ini tercermin dari keputusan politik bangsa sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, yang ditindak-lanjuti dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai institusi utama (leading institution) yang bertanggung jawab memberi arahan, mengeluarkan kebijakan, dan melaksa-nakan program-program di bidang kelautan dan perikan-an. Kondisi ini membuat kita semakin maju beberapa langkah dalam menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa.
M-TI: Munculnya kesadaran dan keputusan politik itu tentu telah mem-buka kondisi yang kondusif untuk menjadikan pem-bangunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa. Lalu bagaimana pembangunan berbasis sumber daya kelautan tersebut dilaksanakan dalam konteks Indonesia baru di tengah arus globalisasi yang semakin deras melanda dunia?
ROKHMIN: Pembangunan ekonomi dunia di masa datang yang penuh tantangan dan persaingan yang ketat, membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumberdaya alam yang penggunaannya akan semakin meningkat. Bahkan tidak mustahil akan mengakibatkan kelangkaan serta persaingan dalam mendapatkannya.
Dengan demikian orientasi pembangunan bangsa Indonesia ke depan yang berbasis pada sumberdaya kelautan merupakan suatu keniscayaan.
Sementara, ada beberapa model pembangunan yang dikembangkan. Namun untuk Indonesia baru di tengah arus globalisasi yang sema-kin deras melanda dunia, model yang kita pilih adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Suatu model pembangunan untuk meme-nuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa menurunkan atau menghancurkan kemampuan generasi men-datang dalam memenuhi kebutuhanya. Pembangunan berkelanjutan ini mengan-dung tiga unsur utama yakni dimensi ekonomi, ekologi dan sosial.
Pertama, pembangunan secara ekonomis dianggap berkelanjutan (an economi-cally sustainable area/ecosystem) jika kawasan tersebut mampu menghasil-kan barang dan jasa (good and services) secara berkesinambungan (on continuing basis), memelihara pemerintahan dari hutang luar negeri pada tingkatan yang terkendali (a manageable level), dan menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrim antarsektor (extreme sectoral imbalances) yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sektor primer, sekunder, atau tersier.
Kedua, pembangunan dikatakan secara ekologis berkelanjutan (an ecologically sustainable arealecosystem), manakala basis (ketersediaan stok) sumber daya alamnya dapat dipelihara secara sta-bil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya dapat diperbaharaui (renewable resources), tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumber daya tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) yang dibarengi dengan upaya pengembangan bahan substitusinya secara memadai. Dalam konteks ini termasuk pula pemeliharaan keanekaragaman hayati (biodiversity), stabilitas sik-lus hidrologi, siklus biogeokimia, dan kondisi iklim.
Ketiga, pembangunan dianggap secara sosial berkelanjutan (a socially sustainable area/ecosystem), apabila kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumah-an, kesehatan, dan pendidik-an) seluruh pendu-duknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil; ada kesetaraan gender (gender equity); terdapat akuntabili-tas dan partisipasi politik.
Dalam konteks pembangu-nan berkelanjutan dalam pe-ngelolaan pembangunan ber-basis sumber daya kelautan, maka secara teknis dapat didefinisikan bahwa “pemba-ngunan kelautan berkelanjut-an (sustainable marine devel-opment) adalah suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkung-an yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manu-sia, terutama stakeholders, sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung (carrying capacity) kawasan pesisir dan laut untuk menyediakannya”.
M-TI: Anda begitu optimis dengan pembangunan berbasis kelautan ini. Sesungguhnya seberapa banyak potensi sumberdaya laut Indonesia ditinjau dari sisi kuantitas maupun diversitasnya?
ROKHMIN: Karakteristik geografis Indonesia serta struktur dan tipologi ekosistemmya yang didominasi oleh lautan telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai mega-biodiversity terbesar di dunia, yang merupakan justifikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia. Fakta ini menun-jukkan bahwa sumberdaya kelautan merupakan kekaya-an alam yang memiliki pelu-ang amat potensial dimanfa-atkan sebagai sumberdaya yang efektif dalam pemba-ngunan bangsa Indonesia.
Berdasarkan jenisnya sumberdaya kelautan dibagi menjadi: (1) Sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources) antara lain ikan dan biota perairan lainnya, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, ekosis-tem pantai dan pulau-pulau kecil; (2) Sumberdaya yang tak dapat pulih (unrenewable resources), antara lain minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya; (3) Energi kelautan, antara lain gelombang, pasang surut, OTEC (Ocean Thennal Energy Conversion), dan angin; (4) Jasa lingkungan, antara lain media transpor-tasi dan komunikasi, penga-turan iklim, keindahan alam, dan penyerapan limbah.
Dengan luas laut 5,8 juta km2, Indonesia sesungguh-nya memiliki sumberdaya perikanan laut yang cukup besar baik dari segi kuanti-tas maupun keragamannya. Berdasarkan perhitungan harga di tingkat produsen tahun 2000 nilai produksi ikan tangkap mencapai Rp. 18,46 triliun. Sedangkan untuk benih ikan laut mencapai Rp 8,07 milyar. Sedangkan untuk budidaya laut yang meliputi ikan, rumput laut, kerang-kerang-an, tiram, teripang, mutiara mencapai produksi senilai Rp 1,36 triliun di tingkat produsen pada tahun 2002.
Sumberdaya laut Indone-sia dengan kekayaan keanekaragaman hayati memiliki potensi untuk pengemangan bioteknologi kelautan. Sumber daya tersebut memiliki kegunaan untuk makanan, minuman, farmasi, dan kosmetika. Dengan pengembangan industri bioteknologi tersebut dapat diharapkan kekayaan hayati yang beraneka ragam itu menjadi produk yang bernilai tinggi. Diperkirakan terdapat 35.000 spesies biota laut memiliki potensi sebagai penghasil obat-obat-an, sementara yang diman-faatkan baru 5.000 spesies.
Potensi wisata bahari Indonesia pun memiliki nilai yang cukup tinggi. Di Indo-nesia terdapat 241 Daerah Tingkat II yang memiliki pesisir.
Dengan demikian Indonesia memiliki lokasi obyek wisata bahari yang cukup besar dibandingkan dengan negara lain. Produk yang bisa dikembangkan antara lain wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga.
Dari sektor pertambang-an, laut Indonesia menyim-pan potensi kekayaan yang cukup besar berupa minyak dan gas bumi. Diperkirakan Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dapat menghasilkan 84,48 milyar barel minyak. Dari sejumlah itu, baru 9,8 milyar barel yang diketahui pasti. Sedangkan sisanya sebesar 74,68 milyar barel berupa kekayaan yang belum dimanfaatkan. (Bersambung) ? ch.robin-yusak-yayat/Majalah Tokoh Indonesia No.7
*** TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
02 | Kontribusi Kelautan Terhadap PDB
M-TI: Seberapa besar potensi dan kontribusi kelautan terhadap PDB?
ROKHMIN: Keberhasilan pembangunan di bidang kelautan sejatinya tidak hanya ditunjukkan dengan mengklaim diri sebagai negara maritim atau diwujud-kan melalui kebanggaan terhadap keunggulan kompa-ratif yang dimiliki saja, tetapi sejauh mana kemampuan kita dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan tersebut dalam mencapai kemakmuran bangsa.
Salah satu ukuran adalah besarnya kontribusi kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Dari tahun ke tahun bidang kelautan memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap PDB. Pada tahun 1995 total PDB yang disumbangkan sektor kelautan mencapai Rp 55,9 triliun atau 12,32 % dari total PDB nasional. Hasil tersebut terus mengalami peningkatan dan pada tahun 1998 menyumbang 20,06 persen dari total PDB atau senilai Rp 189,13 triliun.
Namun demikian, ekspansi ekonomi yang diarahkan pada penciptaan pertumbuhan produksi maksimal yang dicirikan dengan kegiatan eksploitatif telah mewarnai praktek pembangunan bidang kelautan dalam tiga dasawarsa terakhir. Keadaan ini telah mengakibatkan adanya semacam ongkos yang harus ditanggung dalam dimensi jangka panjang.
Dari tujuh sektor kegiatan kelautan yaitu perikanan, pertambangan, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, dan jasa kelautan lainnya, ternyata sektor pertambangan mendominasi kontribusi bagi PDB dengan 35,2 persen pada tahun 1995 dan meningkat menjadi 49,78 persen pada tahun 1998. Sementara sektor perikanan menyumbang 11,56 persen pada tahun 1998 dan menurun menjadi 10,76 % pada tahun 1998.
Namun, sekitar 3,5 tahun sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dewan Maritim Indonesia, beberapa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan secara faktual dapat dirasakan bersama. Misalnya, jika pada tahun l998 total produksi perikanan Indonesia mencapai 4 juta ton yang menempatkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar ketujuh di dunia, maka pada tahun 2002 telah mencapai 5,6 juta ton, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar keenam di dunia (FAO 2002).
Dari total produksi tersebut, sebanyak 5 juta ton untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, sedangkan sisanya 0,6 juta ton untuk ekspor dengan perolehan devisa sekitar US$ 2, l milyar, meningkat US$ 500 juta dibandingkan nilai devisa perikanan tahun l998 yang hanya US$ l,6 juta. Jika sebelum adanya DKP, sektor kelautan dan perikan-an tidak menghasilkan PNBP, maka pada tahun 2002 sektor ini telah menyum-bangkan PNBP hampir Rp 300 inilyar. Tahun 2003 diharapkan menghasilkan Rp 450 milyar, dan tahun 2004 PNBP sektor kelautan dan perikanan insya Allah mencapai Rp 700 milyar.
Sumbangan subsektor perikanan dari produk primer terhadap PDB pada tahun 2001 sebesar 2% (Rp 25 trilyun), maka pada tahun 2002 meningkat menjadi 3% (Rp 47 trilyun). Dan, apabila dihitung dengan produk sekunder (olahannya), maka krontribusinya terhadap PDB pada tahun 2002 hampir l0% (BPS, 2002).
M-TI: Bagaimana perbandingan ekspor-impor perikanan Indonesia?
ROKHMIN: Meskipun Indonesia masih perlu meng-impor beberapa komoditi perikanan, namun secara keseluruhan masih terjadi surplus, dimana ekspor lebih besar dari impor. Dengan demikian sektor perikanan adalah sektor yang tidak membebani neraca keuangan negara. Sebaliknya, malah menjadi andalan untuk menyumbang devisa.
Ekspor hasil perikanan Indonesia jumlahnya terus meningkat. Beberapa komo-diti perikanan Indonesia yang diekspor adalah udang, tuna-cakalang, rumput laut, kerang-kerangan, kepiting, ikan hias, ubur-ubur, dan mutiara.
Sampai saat ini volume dan nilai ekspor Indonesia masih didominasi udang dan tuna-cakalang. Perdagangan ekspor udang terus meningkat dalam kurun waktu 1998-2001 dengan nilai 1,07 milyar dolar AS. Ekspor tuna/cakalang pun meningkat walaupun nilainya tidak sebesar udang yaitu senilai 230 juta dolar AS.
Di sisi lain, meski mampu meningkatkan ekspor, namun pertumbuhan itu masih diikuti kenaikan impor. Volume impor pada periode 1998-2000 rata-rata naik sebesar 25,98 persen dengan kenaikan nilai rata-rata mencapai 1,73 persen.
Faktor lain yang menunjang meningkatnya volume impor adalah maraknya rumah makan asing dan hotel yang memilih ikan impor (jenis ikan yang tidak hidup di perairan Indonesia) dalam memenuhi selera makan konsumen.
M-TI: Produksi perikanan Indonesia kini semakin meningkat. Apakah dengan meningkatnya produksi tersebut meningkat pula konsumi ikan per kapita Indonesia?
ROKHMIN: Jelas! Pening-katan produksi perikanan yang telah dicapai selama ini telah meningkatkan konsum-si ikan per kapita dari 19,98 kg per kapita pada tahun 1998 menjadi 21,78 kg per kapita pada tahun 2001. Konsumsi ikan pada masa mendatang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia.
Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang termasuk ke dalam negara penghasil ikan dunia, Indonesia masih paling rendah mengonsumsi ikan perkapita. Bahkan lebih rendah dibanding dengan Filipina. Sebagai contoh, pada tahun 1990 konsumsi ikan Filipina sudah mencapai 24 kg per kapita per tahun dan Jepang mencapai 110 kg per kapita per tahun.
Peningkatan konsumsi ikan per kapita memiliki korelasi dengan pendapatan per kapita suatu negara. Hal ini disebabkan kemampuan daya beli masyarakat terha-dap suatu produk tergantung pada tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar peluang untuk mengkonsum-si produk pangan berprotein tinggi seperti ikan dan produk hasil laut lainnya.
M-TI: Bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja perikanan?
ROKHMIN: Berdasarkan pola produksinya, tenaga kerja yang terjun ke kegiatan produksi perikanan dibedakan menjadi dua macam, yakni nelayan dan pembudidaya ikan.
Nelayan dikategorikan sebagai tenaga kerja yang melakukan aktivitas produk-sinya dengan cara berburu ikan di laut atau melaut. Umumnya mereka memiliki alat produksi utama seperti kapal, pancing, jaring, bagan, dan lain-lain.
Perkembangan teknik penangkapan modern, terutama semenjak diperke-nalkannya motorisasi (moder-nisasi perikanan) telah mem-bagi formasi sosial nelayan menjadi dua kategori, yakni nelayan tradisional dan nelayan modern.
Berdasarkan teknik dan alat-alat penangkapannya, nelayan tradisional adalah nelayan yang masih memper-tahankan cara penangkapan-nya dengan menggunakan kapal tanpa motor (KTM), tanpa inovasi teknologi, tanpa dukungan modal yang kuat, tanpa kelembagaan usaha yang mapan, cende-rung bersifat subsistem, dan secara geneologi telah menekuni aktivitas tersebut secara turun temurun.
Berbeda halnya dengan nelayan modern, teknik penangkapannya mengadopsi perkembangan teknologi, seperti kapal motor hingga ke teknologi citra satelit misalnya. Dukungan modal dan kelembagaan usahanya mapan, serta ciri-ciri subsistem telah hilang. Usa-ha panangkapannya dituju-kan semata-mata untuk me-raih profit secara maksimal.
Modernisasi perikanan ternyata tidak hanya memilah formasi nelayan atas dasar kepemilikan cara produksi, namun telah memilah pula nelayan atas dasar kepemilikan alat produksi.
Nelayan yang memiliki alat-alat produksi seperti kapal dan modal digolongkan sebagai nelayan pemilik. Berbeda halnya dengan nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan menjual tenaga atau keahliannya untuk menangkap ikan, dikategorikan sebagai nelayan buruh. Klasifikasi nelayan tersebut, atas dasar teknik dan kepemilikan alat produksi itu masih dibedakan berdasarkan kegiatan menjadi nelayan penuh, nelayan sebagai sambilan utama, dan nelayan sebagai sambilan tambahan.
Sampai dengan tahun 2000 jumlah total nelayan Indonesia sekitar 2.486.456 orang atau mengalami kenaikan 3,21 persen dibandingkan tahun 1999 dan dalam kurun waktu 1990-2000 telah mengalami peningkatan sebesar 5 persen per tahun. Nelayan berprofesi penuh pada tahun 2000 berjumlah 1.212.195 orang atau mengalami kenaikan sebesar 3,06 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah tenaga kerja yang menjadi nelayan sambilan utama pun mengalami kenaikan 5,06 persen dibanding tahun sebelumnya atau berjumlah 911.163 orang pada tahun 2000.
Sementara, pembudidaya ikan adalah tenaga kerja perikanan yang menyandar-kan teknik produksinya pada kegiatan budidaya, dan jenis komoditi produksinya adalah jenis-jenis ikan budidaya ekonomis penting, seperti udang, bandeng, ikan mas, gurami, ikan hias atau komoditi lainnya, seperti rumput laut dan lain- lain. Kecenderungan pola sosial atas dasar perbedaan pola dan teknik produksi dan perbedaan kepemilikan alat produksi terjadi pula di kegiatan budidaya perikanan. Aktivitas produksi budidaya dapat digolongkan ke dalam kegiatan budidaya tambak, kolam, karamba, dan sawah.
Perkembangan jumlah pembudidaya ikan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen sejak tahun 1998 walau pernah mengalami penurunan sebe-sar 0,12 persen saat terjadi-nya krisis moneter 1997. Jumlah pembudidaya ikan kolam masih mendominasi jumlah pembudidaya ikan.
Sementara itu, distribusi tenaga kerja perikanan, khususnya nelayan, pada tahun 2000 terlihat tidak merata. Di kawasan barat Indonesia, jumlah nelayan terbesar terdapat di Jawa Timur (386.482 jiwa), Jawa Tengah (192.349 jiwa), Sumatera Utara (177.804 jiwa) dan Riau (123.146 jiwa). Sedangkan di kawasan timur Indonesia daerah yang memiliki jumlah nelayan besar adalah Sulawesi Selatan (146.941 jiwa), Papua (190.178 jiwa), dan Maluku (120.361 jiwa).
Selain itu, hal yang patut dicermati adalah permasalah-an sumberdaya manusia di sektor perikanan khususnya dalam hal rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan nelayan. Berdasarkan perki-raan kualitas pendidikan SDM perikanan bagian terbesar nelayan berpendidi-kan rendah yaitu 70 persen tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tidak sekolah, 19,59 persen tamat sekolah dasar, dan hanya 0,03 persen yang memiliki pendidikan sampai jenjang Diploma 3 dan Sarjana.
M-TI: Jumlah tenaga kerja di sektor perikanan meningkat, apakah juga ada peningkatan pendapatan mereka secara signifikan?
ROKHMIN: Selama ini nelayan dan pembudidaya ikan belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pemanfaatan potensi dan produksi perikanan. Ketergantungan pada iklim dan lingkungan menyebab-kan pendapatan nelayan di setiap daerah menjadi berbeda-beda.
Hasil penelitian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB tahun 1996 mengungkap bahwa pendapatan Rumah Tangga Nelayan di desa pesisir Lombok Bagian Barat berkisar antara Rp 210.540-Rp 643.510 per tahun. Pendapatan nelayan ini diperkirakan menjadi lebih kecil dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia.
Hal ini disebabkan, karena mening-katnya biaya operasional dari sebelumnya, sementara depresiasi nilai rupiah terhadap dollar Amerika tidak dinikmati oleh nelayan kecil, karena pangsa pasar nelayan tradisonal ini masih terfokus dalam negeri. Hal yang berbeda justru dialami pengusaha perikanan yang berorientasi ekspor, dimana nilai produksi perikanan mengalami peningkatan karena adanya depresiasi rupiah terhadap dollar.
Untuk melihat tingkat pendapatan nelayan juga bisa dilakukan dengan melihat proporsi produksi ikan dengan jumlah nelayan per hari. Saat ini kita memiliki potensi lestari 6,26 juta ton, namun produksi nelayan per hari kita jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang potensi perikanannya tidak melebihi potensi perikanan Indonesia. Jika dibandingkan dengan empat negara lainnya, Rusia (140 kg/nelayan/hari), Jepang (75 kg/nelayan/hari), USA (100 kg/nelayan/hari), dan Norwegia (98 kg/nelayan/hari), maka Indonesia memiliki proporsi produksi terhadap nelayan yang paling kecil, yaitu 5,5 kg/ nelayan/hari.
M-TI: Bagaimana dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aspek kelautan?
ROKHMIN:Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kegiatan pengelolaan di bi-dang kelautan, secara kuan-titatif relatif sudah memadai. Selama tiga puluh tahun terakhir, tidak kurang dari tiga puluh produk hukum telah diproduksi untuk mengatur sektor perikanan. Namun, secara substantif, produk hukum tersebut sangat memprihatinkan. Secara kategorik, produk hukum perikanan tersebut memiliki tiga ciri pokok, yakni sentralistik, berbasis pada doktrin open-access, dan anti pluralisme hukum.
Ciri sentralistik dari produk hukum di sektor perikanan menjelma, baik dari sisi materi maupun dari sisi proses produksinya. Dari sisi materi muatannya, produk hukum tersebut mengkonsentrasikan kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan hanya pada pemerintah pusat. Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya sikap merasa ‘tidak memiliki laut’ di kalangan pemerintah dan masyarakat daerah. Akibatnya, di mata pemerin-tah dan masyarakat daerah, laut dipandang sebagai ‘halaman belakang’ dan ‘bak sampah’.
Suatu hal yang tidak kondusif bagi upaya konservasi sumberdaya kelautan. Dari sisi proses produksinya, hukum kelaut-an pada umumnya, diformu-lasi dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) dan Ke-putusan Menteri (Kepmen). Produk hukum yang demiki-an, jelas kurang memiliki akuntabilitas politik.
Selanjutnya, hukum kelautan kita juga dirancang atas dasar doktrin bahwa sumberdaya kelautan meru-pakan sumberdaya open-access sehingga pembatasan keikutsertaan dalam okupasi-nya menjadi sesuatu yang dipantangkan. Laut, ibarat sebuah arena pertarungan bebas, yang tentu saja akan selalu melahirkan pemenang dan pecundang.
Pengalaman menunjukkan bahwa para pengusaha perikanan berkapital besar yang selalu keluar sebagai pemenang. Perlawanan nelayan tradisional yang cenderung sangat radikal, seperti di Bagan Percut Sumatera Utara, merupakan isyarat bahwa tekanan terhadap nelayan tradisional sudah sampai pada titik yang tidak mampu ditolerir.
Konsekuensi logis dari kedua ciri di atas, yakni hukum kelautan yang anti kemajemukan. Hukum adat dan tradisi masyarakat lokal tidak diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, padahal hukum adat tersebut telah terbukti sangat efektif menjaga kelestarian sumber-daya alam. Sasi di Maluku, panglima laut di Aceh, atau tradisi rompong di Sulawesi Selatan merupakan contoh aktual dari hukum adat atau tradisi lokal yang demikian itu.
Sesungguhnya, terdapat pula beberapa produk hu-kum yang memihak kepen-tingan nelayan tradisional, seperti larangan penggunaan pukat harimau. Namun, ketika sampai pada tingkat implementasi, ketentuan tersebut seperti tak bergigi. Lemahnya penegakan hukum masih merupakan salah satu kendala.
Kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memberikan secer-cah harapan. Melalui UU ini, sentralisme kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan dapat dikurangi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang signifikan untuk mengelola laut. Karena itu, yang diperlukan saat ini bukan ‘menghapus’ ketentuan Pasal 3 dan 10 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang membuka peluang desentralisasi, tetapi penjabaran dan penyusunan standar dan prosedur pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan yang diterima secara universal. (Bersambung) ? ch.robin-yusak-yayat/Majalah Tokoh Indonesia No.7
*** TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
03 | Ribuan Pulau Besar dan Kecil
M-TI: Tak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Pulau itu terpisah oleh laut. Masalahnya, pembangunan pulau-pulau kecil tampaknya tidak begitu terdengar. Bagaimana penangan keberadaan pulau-pulau kecil itu?
ROKHMIN: Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, telah menjadikan bangsa ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun frame work pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini mengakibatkan kita hanya mengenal pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua dan Bali, yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama dalam pembangunan. Akibatnya banyak dari kita yang kurang mengenal pulau-pulau kecil atau gugusan pulau-pulau kecil lainnya sehingga kawasan ini menjadi telantar atau tidak terkelola dengan baik.
Konsekuensi logis dari keadaan ini menimbulkan kesenjangan pertumbuhan dan kurangnya sinkronisasi pengembangan antarwilayah. Pada gilirannya, hal ini akan membawa kepada muculnya kerawanan baru terutama pada pulau-pulau di kawasan perbatasan. Contoh paling nyata yang baru saja kita rasakan adalah keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 di Den Haag, Belanda yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan berada dalam kedaulatan Malaysia.
Alasan utama keputusan itu dilandasi oleh adanya tindakan administratif secara nyata oleh pemerintah Inggris pada kedua pulau tersebut sejak tahun 1917. Dengan perkataan lain, dari pengalaman ini dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya perhatian terhadap pemberdayaan pulau-pulau kecil, terutama yang berba-tasan dengan negara asing, maka kedaulatan bangsa Indonesia sesungguhnya dalam ancaman besar.
Oleh sebab itu, sentuhan pembangunan pada pulau-pulau serupa perlu dilakukan meskipun memiliki tingkat keisolasian yang tinggi. Sentuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menarik investasi ke pulau-pulau tersebut, mendeklara-sikan pulau yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai kawasan kon-servasi, melakukan penataan ruang, mendorong nelayan melakukan aktivitas penang-kapan di perairan sekitar pulau, merangsang aktivitas ekonomi masyarakat peng-huni pulau melalui paket-paket tertentu.
Di lain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut masih dihadapkan pada berbagai masalah an-tara lain letaknya yang ter-pencil, terbatasnya sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Di samping itu, di dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan daya dukung pulau mengingat sifatnya yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat, sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. (Bersambung) ? ch.robin-yusak-yayat/Majalah Tokoh Indonesia No.7
*** TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
04 | Ratusan Titik Harta Karun
M-TI: Adakah kekayaan lain di sektor kelautan yang luput dari perhatian masyarakat?
ROKHMIN: Satu hal yang barangkali sering kita lupakan, bahwa laut Indonesia memiliki ratusan titik harta karun. Benda-benda berharga itu berasal dari muatan kapal yang tenggelam. Sebagai salah satu sumberdaya buatan, benda-benda berharga itu mulai menjadi titik perhatian semenjak dikeluarkannya Keppres Nomor 107 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Nasional Pemanfaatan Benda-benda Berharga asal Muatan Kapal Tengelam sebagai pengganti Keppres Nomor 43 tahun 1989. Benda berharga di dasar laut ini menarik minat banyak orang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari unsur sejarah yang dimilikinya.
Dari hasil pemetaan diperkirakan terdapat 463 titik yang potensial terdapat benda berharga dasar laut, yang sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi pelayaran yang menjadi lintasan per-dagangan kerajaan-kerajaan masa lalu. Pemanfaatan dan pengangkatan benda-benda berharga tersebut telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1986 misalnya, telah dilakukan pengangkat-an harta karun yang berasal dari kapal De Geldermalsen yang tenggelam di perairan Kepulauan Riau 235 tahun yang lalu. Dari operasi tersebut ditemukan 150 ribu keping keramik yang berasal dari Dinasti Ming dan 225 keping emas lantakan.
Kemudian juga di perairan Belitung juga pernah dilakukan pengangkatan benda berharga berupa 39.867 keping keramik yang berasal dari Dinasti Tang. Selanjutnya di perairan Tuban juga ditemukan sebanyak 14.800 keping keramik yang diperkirakan berasal dari Dinasti Ming. Nilai lelangnya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
Pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga asal muatan kapal tenggelam ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena selama ini disinyalir terjadi perburuan secara ilegal, sehingga nilai ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi hilang.
M-TI: Sedemikian besar kekayaan laut kita, lantas bagaimana sebaiknya profil pembangunan kelautan ke depan?
ROKHMIN: Profil pembangunan kelautan Indonesia ke depan adalah suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan (on a sustainable basis). Profil pembangunan bidang kelautan dapat dijabarkan ke dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) meningkat-nya kesejahteraan masyara-kat pesisir, (2) meningkatnya peran sektor kelautan seba-gai sumber pertumbuhan ekonomi, (3) peningkatan gizi masyarakat melalui pening-katan konsumsi ikan, (4) pemeliharaan dan peningkat-an daya dukung serta kualitas lingkungannya, dan (5) peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa.
Jika cita-cita pembangun-an kelautan seperti yang kita inginkan di atas dibanding-kan dengan pencapaian (kinerja) pembangunan selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar sektor ini dapat berperan lebih besar dan signifikan guna memperkokoh perekonomian nasional dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur.
Atas dasar potensi pem-bangunan kelautan yang kita miliki, sesungguhnya peran dan kontribusi sektor kelaut-an terhadap pembangunan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan. Namun kenyataannya, walaupun potensi sumberdaya kelautan yang kita miliki cukup besar, ternyata kinerja pembangun-annya masih jauh dari ha-rapan kita bersama.
Dengan perkataan lain, bahwa selama sebelum masa Kabinet Persatuan dan Kabinet Gotong Royong, telah terjadi mis-management (salah urus) pada pembangunan kelautan nasional yang terjadi hampir di seluruh lini (aspek) sistem pembagunan kelautan, sehingga untuk mengatasinya tidak mungkin dapat dilakukan secara sektoral atau parsial saja.
Oleh karena itu, kita perlu membangun kembali pandangan dan cara-cara kita dalam mengelola pembangunan kelautan agar mampu menghantarkan bangsa Indonesia seperti yang kita cita-citakan.
Langkah strategis telah dilakukan dengan pencanangan Gerbang Nina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Teluk Tomini, 11 Oktober 2003 lalu.
M-
Apa alasan dilaksanannya Gerbang Nina Bahari itu?
ROKHMIN: Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) didasari beberapa alasan, antara lain : Pertama, Indonesia memerlukan langkah terobosan (breakthrough) untuk mengatasi krisis ekonomi.
Kedua, sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai penggerak utama (prime mover) untuk keluar dari krisis ekonomi.
Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menciptakan lapangan kerja baru, membangkitkan banyak efek pengganda (multiplier effects), dan menyentuh banyak kepentingan masyarakat kecil (the grass root).
Keempat, sebagai pendatang baru, ‘sektor’ kelautan dan perikanan menghadapi beragam kendala dan permasalahan. Oleh sebab itu, tanpa sebuah “Gerakan Nasional”, maka realisasi (hasil) pembangunan kelautan dan perikanan akan kecil dan lamban.
Kelima, pengalaman keberhasilan Gerakan Nasional pembangunan industri perdesaan (Semaul Undong) di Korea Selatan, pembangunan pertanian tropis di Thailand, dan keberhasilan BIMAS menjadikan Indonesia sebagai negara “Swasembada Beras” (tahun 1984 ).
Keenam, wilayah pesisir dan kelautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, namun kegiatan pariwisata bahari belum dikelola secara optimal. Pembangunan pariwisata bahari di Indonesia diyakini mampu mendorong terbukanya isolasi beberapa daerah yang kurang berkembang.
Ketujuh, Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan, sehingga pengembangan jasa transportasi laut di samping mendukung kegiatan perpindahan dan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah, juga dapat menunjang sektor perdagangan ekonomi. Oleh karenanya pengembangan jasa transpotasi laut berperan secara ekonomi, social budaya, politik dan hankam.
M-TI: Apa misi dan tujuan dan sasaran Gerakan, Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan itu?
ROKHMIN: Misi Gerbang Mina Bahari adalah melaku-kan percepatan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indo-nesia yang maju dan makmur melalui pemanfaatan sumber-daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjut-an, dan berkeadilan.
Sementara tujuannya antara lain: (1) Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pem-budidaya ikan dan masyara-kat pesisir lainnya; (2) Meningkatkan penerimaan devisa negara dan kontribusi terhadap PDB; (3) Menyedia-kan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di dalam negeri; dan (5) Memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.
Keluaran (out put) yang diharapkan melalui Gerbang Mina Bahari ini, akan terjadi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan seca-ra sistematis dan terukur, yang dilakukan oleh seluruh unsur, baik yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perhubungan, maupun lintas sektoral yang didukung oleh seluruh elemen bangsa guna meningkat-kan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Sedangkan sasaran jangka pendek yang ingin dicapai melalui skenario ini, diharap-kan produksi perikanan tahun 2006 mencapai 9,5 juta ton, kontribusi pada PDB nasional sebesar 10 %, devisa dari ekpsor US$ 10 milyar, penyerapan tenaga kerja 7,4 juta orang, dan tingkat konsumsi ikan 30 kg/kapita/tahun.
Sasaran tersebut, antara lain akan dicapai melalui program/proyek unggulan, antara lain: (a) Pengembang-an industri tambak udang terpadu di 7 propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo (kerjasama Pemda dan PT. CPB);
(b) Pengembangan 5 pabrik industri rumput laut di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua; (c) Pengembangan pabrik chitosan (kerang) di Sumate-ra Utara, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan;
(d) Pengembangan industri sosis patin di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sumate-ra Selatan, dan Kalimanta Selatan; (e) Pengembangan industri perikanan tangkap terpadu di Sabang-Aceh, Batam-Riau, Nias-Sumatera Barat, Bangka-Belitung, NTB, Bitung-Sulawesi Utara, dan Gorontalo; (f) Pemberdayaan masya-rakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya di 300 kabupaten dan kota; (g) Pengembangan usaha budidaya kerapu di Bali Barat; dan (h) Penyela-matan kerugian negara US$ 2-4 miliyar dari praktek-praktel ilegal dan pencurian ikan.
Sasaran jangka panjang-nya adalah pembangunan sistem bisnis perikanan terpadu di setiap kabupaten/kota pesisir. Di daerah ter-sebut, akan didirikan pabrik pengolahan ikan sebagai basis industri perikanan. Model tersebut dibangun dengan mengintegrasikan usaha produksi primer (penangkapan dan budidaya) dengan pengolahan/pasca panen serta pemasaran, melalui mekanisme kemitraan antara nelayan/pembudidaya ikan, pengusaha, dan pemerintah.
M-TI: Ditinjau dari aspek proses produksi, tampak jelas terlihat rendahnya produktivitas sektor perikanan. Komentar Anda?
ROKHMIN: Belum optimalnya produksi yang diha-silkan sektor perikanan ter-utama disebabkan rendahnya produktivitas nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Rendahnya produktivitas nelayan disebabkan tiga faktor utama, yaitu pertama, sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisio-nal dengan teknologi penang-kapan yang tradisional pula, sehingga kapasitas tangkapnya rendah.
Hal ini sekaligus mencerminkan rendahnya kualitas sumberdaya manu-sia nelayan dan kemampuan Iptek penangkapan ikan.
Kedua, adanya ketimpang-an tingkat pemanfaatan stok ikan antarkawasan perairan laut. Di satu pihak, terdapat kawasan-kawasan perairan yang mengalami kondisi overfishing, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sula-wesi, dan sebaliknya, masih banyak kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaat-an sumberdaya ikannya belum optimal atau bahkan belum terjamah sama sekali.
Ketiga, telah terjadinya kerusakan lingkungan eko-sistem laut, seperti kerusak-an hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (seagrass beds), yang pada-hal mereka itu merupakan tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (nursery ground). Kerusakan lingkungan laut ini juga disebabkan oleh pencemaran baik yang berasal dari kegiatan manusia di darat maupun di laut.
Sementara itu dalam usaha budidaya perikanan, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, adalah pertama, kemampuan teknologi budidaya (mencakup pemilihan induk, pemijahan, penetasan, pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen pemberian pakan, genetika (breeding), manajemen kesehatan ikan, dan teknik perkolaman) sebagian besar pembudidaya ikan masih rendah.
Kedua, kompetisi peng-gunaan ruang (lahan perair-an) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (pemu-kiman, industri, pertambang-an, dan lainnya) pada umum-nya merugikan usaha budi-daya perikanan. Belum ada Pemerintah Daerah (propinsi atau kabupaten/ kodya) yang menjadikan kawasan budida-ya perikanan sebagai kawas-an khusus/tertentu, yang harus dilindungi dari sege-nap upaya konversi lahan atau pencemaran, didalam penyusunan tata ruangnya.
Ketiga, semakin membu-ruknya kualitas air sumber untuk budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensi-tas pembangunannya, sehu-bungan dengan berkembang-nya kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga (pemukiman dan perkotaan) yang tidak ramah lingkungan atau membuang limbahnya ke alam (perairan) tanpa memperhatikan ambang batas limbah.
Keempat, struktur dan mekanisme diseminasi teknologi yang lemah, sehingga tingkat inovasi teknologi sulit ditingkatkan. Hal ini disebabkan tiadanya tenaga penyuluh perikanan.
Rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan merupakan masalah yang juga harus mendapat perhatian serius. Hal ini terjadi karena kemampuan teknologi pascapanen produk perikanan yang sesuai dengan selera konsumen dan memenuhi standar mutu internasional masih lemah.
Persoalan lainnya adalah lemahnya kemampuan pemasaran produk perikanan. Pemasaran komoditas perikanan Indonesia, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor, sebagian besar masih ditentukan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan harga jual produk perikanan pada umumnya kurang menguntungkan produsen, dalam hal ini nelayan atau pembudidaya.
Dua hal yang melatarbelakangi kelemahan ini adalah pertama, lemahnya market intellegence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera konsumen tentang jenis dan mutu produk. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi produk dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. Nelayan pun masih dihadapkan pada panjangnya rantai pemasaran yang harus dilewati dalam proses pembelian faktor-faktor produksi yang berakibat membengkaknya beban harga yang harus dibayar.
Di samping sektor perikanan, pengembangan obyek wisata bahari pun belum berkembang secara optimal. Padahal, Indonesia adalah negeri dengan keindahan alam pesisir dan laut yang luar biasa. Selain keterbatasan modal, minimnya sarana dan prasarana transportasi, jasa pelayanan, promosi, dan faktor eksternal lainnya membuat potensi itu tidak memiliki nilai ekonomis. (Bersambung) ? ch.robin-yusak-yayat/Majalah Tokoh Indonesia No.7
*** TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
05 | Kapal Asing Pencuri Ikan
M-TI: Di perairan Indonesia sangat banyak kapal asing berkeliaran dan mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Mengapa hal ini terjadi?
ROKHMIN:Keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indo-nesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena hal ini telah diatur dalam ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang menya-takan: negara pantai harus menetapkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE-nya. Apabila negara pantai belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbo-lehkan, maka negara pantai bersangkutan memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya melalui perjanjian dan sesuai ketentuan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat armada perikanan Indonesia masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE Indonesia dan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 tersebut di atas, Indonesia masih memberi kesempatan kapal ikan berbendera Asing (KIA) beroperasi di ZEEI.
Berkaitan dengan kapal asing, umumnya tidak lepas dari isu tentang “pencurian” ikan oleh nelayan dan kapal asing. Hal ini karena adanya dugaan sebagian besar (70 persen) dari sekitar 7.000 (tujuh ribu) kapal perikanan berbendera Indonesia yang telah memperoleh izin dari pusat untuk beroperasi di perairan ZEEI, ternyata masih dimiliki pihak asing, terutama Thailand, Filipina, Taiwan dan RRC.
Kondisi demikian disebabkan masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti: (a) Kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang. (b) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ditangani oleh berbagai instansi, sehingga memerlukan koordinasi. (c) Belum diberdayakannya petugas pengawas sumberdaya ikan (WASDI) dan Pengawas Kapallkan (WASKI) secara optimal.
M-TI: Implementasi dan penegakan hukum (law enforcement) bidang kelautan di Indonesia dinilai masih lemah. Benarkah?
ROKHMIN: Harus diakui implementasi dan penegakan hukum (law enforcement) bidang kelautan di Indonesia masih lemah. Selama ini persoalan penegakan hukum dan peraturan di laut senan-tiasa tumpang tindih dan cenderung menciptakan konflik antar sektor pemba-ngunan, institusi dan aparat pemerintah, serta konflik horizontal antar masyarakat.
Oleh karenanya dibutuh-kan perangkat hukum dan peraturan yang dapat menjamin interaksi antar sektor yang saling menguntungkan dan menciptakan optimal paretto. Terdapatnya perang-kat hukum membutuhkan aparatur penegak hukum yang memiliki komitmen untuk menegakkan peratur-an. Tanpa itu semua, persoalan di laut dan pesisir akan menjadi tumpang tindih dan bermuara pada kerusak-an lingkungan dan kemiskin-an dalam masyarakat.
Peran aparatur penegak hukum, seperti TNI/Polri, kejaksaan, dan pengadilan dalam pembangunan kelautan sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat banyak kasus yang terjadi dalam pembangunan kelautan dilatarbelakangi oleh persoalan hukum. Contoh muktahir dari pentingnya peran hukum dalam pembangunan kelautan adalah kasus pencurian pasir laut dan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.
Kasus penambangan ilegal pasir laut, merupakan contoh kasus dari persoalan tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan. Tumpang tindih peraturan itu membuat kegiatan penambangan mem-bawa berbagai implikasi ne-gatif bagi ekonomi, lingkung-an, sosial, dan politik. Negara dan masyarakat di pesisir dan kepulauan Riau, terutama nelayan yang menyandarkan diri pada kegiatan perikanan hampir selama 22 tahun menderita kerugian.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan sisi kerugian akibat kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali itu. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah menerbit-kan Inpres No.2 Tahun 2002. Garis besar Inpres tersebut menginstruksikan kepada pejabat negara terkait untuk berkoordinasi dalam pengawasan dan pengendalian penambangan pasir.
Inpres ini kemudian diperkuat dengan Keppres No.33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawas-an pengusahaan pasir laut. Dalam keppres itu disebut-kan pula tentang pembentuk-an Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) yang diketuai oleh Menteri kelautan dan Perikanan RI. Tugas dari TP4L ini adalah mengawasi dan pengendali pengusahaan pasir laut.
Dalam mengemban tugas yang diamanatkan, TP4L secara bertahap berhasil meminimalkan praktik ilegal dalam penambangan pasir melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti TNI AL dan polisi. Kapal-kapal yang ditangkap kemudian diseret ke peng-adilan, meski pada tahapan ini, proses peradilan belum optimal memberikan sanksi yang berat bagi kegiatan ilegal ini. Namun kemampuan menyeret pelaku ini merupa-kan langkah yang baik sekali, mengingat hampir 22 tahun kegiatan ilegal ini tidak tersentuh oleh hukum.
Begitu pula halnya dengan masalah praktik penangkap-an ikan secara ilegal, khu-susnya yang beroperasi di perairan ZEEI. Pemerintah telah mengantisipasi praktik tersebut lewat penegakan hukum di wilayah laut. Dalam rangka penegakkan hukum ini dilakukan koordi-nasi dengan pihak aparat hukum seperti kepolisian, dan TNI-AL. Proses tersebut selanjutnya dilakukan dengan menyeret pelaku pencurian ke pengadilan melalui bekerja sama dengan pihak kejaksaan agar tuntutan hukum atas perkara pelanggaran di bidang perikanan dapat diberikan sanksi yang setimpal dan prosesnya cepat.
Tentunya kegiatan pengendalian penangkapan ikan tidak dapat dilakukan oleh aparat pemerintah saja, melainkan juga harus meli-batkan masyarakat. Berkait-an dengan hal itu, DKP telah mengembangkan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang disosiali-sasikan ke beberapa daerah.
Pemasangan alat komunikasi dilakukan di sentra-sentra perikanan seperti Pekalong-an, Pemangkat, Belitung, Kendar yang dihubungkan ke pusat pemantauan DKP. Sehingga informasi pelang-garan terutama oleh kapal penangkap ikan ilegal dapat diketahui dan diteruskan kepada aparat penegak hukum di laut. Pada tahun 2001, telah terpasang 15 set alat komunikasi, serta perangkat sistem komputer database yang dioperasikan secara Wide dan Local Area Net.
Begitu pula sanksi hukum bagi perusak lingkungan terlalu ringan, seperti bagi pengguna bahan-bahan peledak, bahan beracun (cyanida), dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung-jawab, dan seterusnya.
Masih maraknya kegiatan bersifat destruktif, yang tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga nelayan-nelayan modern, dan nelayan-nelayan asing yang banyak melakukan pencurian ikan di perairan nusantara. Fakta ini merupakan bukti lemahnya penegakan hukum.
M-TI: Tumpang tindihnya penanganan masalah ini menandakan lemahnya koordinasi unsur terkait?
ROKHMIN: Memang, permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama antarpelaku pembangunan dan sekaligus pengelola di kawasan tersebut, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antarpelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan laut yang dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak. Lemahnya koordinasi ini diakibatkan oleh belum adanya sistem atau lembaga yang mampu mengkoordinasikan setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan.
Beberapa contoh dapat dilihat seperti terjadi benturan kepentingan antara pemanfaatan sumberdaya kelautan dengan kegiatan konservasi lingkungan, antara pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari dengan pemanfaatan sumberdaya secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Akibatnya, sektor kelautan yang memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkange) dengan sektor-sektor perekonomian lainnya tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu akibat kebijakan sektor-sektor perekonomian tersebut tidak berorientasi atau tidak berkoordinasi dengan sektor kelautan. Sehingga sektor-sektor perekonomian lain yang terkait tersebut juga tidak tumbuh dan berkemban secara optimal dan berkelanjutan.
M-TI: Dengan banyaknya masalah di sektor kelautan, bagaimana masa depan sektor ini?
ROKHMIN: Apabila pola dan praktik pembangunan kelautan tidak segera diper-baiki, maka harapan kita untuk menjadikan bidang kelautan sebagai tulang punggung (prime mover) pembangunan nasional untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan dan sekaligus menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, makmur, mandiri dan berkeadilan akan sia-sia belaka.
Sebaliknya, kita hanya akan mewariskan kepada generasi penerus, sebuah kondisi ekosistem pesisir dan lautan dengan kekayaan alam yang terkuras habis serta menurunnya kemampuan alam dalam mendukung pembangunan (sustainable capacity). Kegagalan kita dalam mempertahankan kapasitas keberlanjutan seperti yang terjadi di sektor sumberdaya alam di darat (hutan dan lahan pertanian) bukan tidak mustahil dapat terulang di bidang kelautan.
Beranjak dari analisis kekuatan, kelemahan, pelu-ang dan ancaman sebagaima-na diuraikan sebelumnya, maka sudah saatnya kita melakukan reorientasi (pembaharuan) paradigma pembangunan Indonesia. Reorientasi tersebut menca-kup dua hal mendasar. Pertama, adalah reorientasi fokus pembangunan, dari basis sumberdaya daratan ke basis sumberdaya kelautan. Ini bukan berarti menge-nyampingkan pembangunan di darat, tetapi berbagai kegiatan pembangunan di darat hendaknya bersifat sinergis dan saling memper-kuat dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan.
Kedua, adalah bahwa tujuan pembangunan kelaut-an hendaknya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (social equity), dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir serta lautan secara seimbang (proporsional). Laut tidak lagi dipersepsikan sebagai keranjang sampah (tempat pembuangan limbah dari darat) dan ajang ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia.
M-TI: Dalam era reformasi, banyak perubahan dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan. Di antaranya paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik mengalami koreksi dengan munculnya lingkungan strategi baru berupa pendekatan pembangunan yang bersifat desentralistik yakni otonomi daerah. Apa saja konsekuensi dari otonomi daerah ini dalam kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan?
ROKHMIN: Perubahan ini membawa konsekuensi berupa pendelegasian kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah. Perubahan yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah (otda) itu, merupakan paradigma baru pengelolaan pemerin-tahan dan dipandang sebagai koreksi atas segala bentuk pemusatan kekuasaan yang telah menggiring rakyat Indonesia ke dalam kesen-jangan sosial ekonomi, baik yang berupa kesenjangan antargolongan, antarsektor ekonomi, maupun antara pusat dan daerah.
Munculnya otda tidak lepas dari tuntutan keadilan dan perbaikan nasib rakyat, khususnya di daerah untuk meningkatkan taraf hidup, penghargaan atas kondisi sosial dan budaya lokal, dan kelestarian lingkungan.
Perubahan itu mempenga-ruhi secara langsung bentuk-bentuk pengelolaan dan pe-manfatan sumberdaya kelautan.
Munculnya UU Nomor 22/ 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, telah menggeser kewe-nangan pengelolaan wilayah laut dari pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini membawa berbagai konse-kuensi dalam pembangunan kelautan yang efisien, adil dan berkelanjutan.
Keadaan yang patut dicermati adalah pasal-pasal yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut di dalam skenario otda. Pada Pasal 10, disebutkan bahwa propinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan propinsi atau sejauh 4 mil laut. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, serta penegakan hukum. Munculnya undang-undang ini membawa konsekuensi-konsekuensi berupa perubahan dalam tata pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.
Pergeseran pengelolaan ini bukan tanpa persoalan kare-na akan berdampak pada masalah yang berkaitan lang-sung dengan institusionalisa-si otda. Persoalan institusio-nal ini dalam konteks wilayah laut di antaranya adalah:
Pertama, belum adanya institusil/lembaga pengelola khusus yang menangani ma-salah pengembangan pesisir dan laut. Implikasinya, tidak tersedianya instrumen hukum wilayah perbatasan antar propinsi (RT/RW, zonasi), yang dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan investasi. Selain itu, belum lengkapnya pedoman bagi instansi di daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam memanfaatkan wilayah laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, keterbatasan SDM (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut. Ini menimbulkan kesulitan da-lam pendayagunaan serta peningkatan perangkat insta-nsi daerah yang ada terha-dap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil laut serta 4 mil laut yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota. Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, pengaturan alur pelayaran; dan lain-Iainnya.
Ketiga, keterbatasan data dan informasi, telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan dan mengelola data dan informasi menjadi rendah.
Keempat, terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayaguna-an teknologi bidang kelautan. Akibatnya, upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terwujud.
Dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dalam batas-batas yang telah ditetapkan, maka sangat jelas manfaat dari sumberdaya kelautan itu akan dirasakan Pemda dan masyarakat setempat. Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemda sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.
M-TI: Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemda untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang dan kekuasaannya?
ROKHMIN: Pertanyaan ini penting mengingat tidak selu-ruh daerah memiliki pemaha-man yang sama tentang pentingnya pengelolaan sumber-daya kelautan secara berkelanjutan.
Isyarat pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini seperti tersirat dalam pasal 10 ayat 1, daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundangan.
Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab disesuaikan dengan kemam-puan daya dukungnya dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyara-kat serta harus memperhati-kan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. ? ch.robin-yusak-yayat/Majalah Tokoh Indonesia No.7
*** TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)