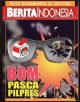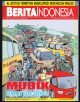Prof. Ahmad Najib Burhani: Lima Tipe Budaya Intoleransi di Indonesia
Ahmad Najib Burhani
Dalam peringatan Hari Toleransi Internasional 2024 di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Prof. Ahmad Najib Burhani dari BRIN memaparkan lima tipe budaya intoleransi yang menghambat keberagaman: tendensi mesianik, false virtue, narasi euphemistik, konstruksi mental konservatif, dan pluralisme terbatas. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk mengubah pola pikir masyarakat, sejalan dengan peran Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan yang menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian.
Penulis: Mangatur L. Paniroy
Unduh: File PDF Presentasi Prof. Ahmad Najib Burhani
Pada Sabtu, 16 November 2024, Pondok Pesantren Al-Zaytun menggelar peringatan Hari Toleransi Internasional untuk pertama kalinya. Acara ini berlangsung di Masjid Rahmatan Lil’alamin, Indramayu, Jawa Barat, dengan tema besar “Melestarikan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Indonesia Raya Abadi.” Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai toleransi yang telah menjadi salah satu pilar utama Al-Zaytun.
Daftar Artikel Terkait Peringatan Hari Toleransi Internasional 2024 di Ma'had Al-Zaytun
- Agama, Kultur (In)Toleransi, dan Dilema Minoritas di Indonesia
- Intelektual Kajian Agama dan Isu Minoritas
- Ahmad Najib Burhani
- Prof. Ahmad Najib Burhani: Lima Tipe Budaya Intoleransi di Indonesia
- Hari Toleransi Internasional: Al-Zaytun Menyala, Negara Membisu
- Peringatan Hari Toleransi Internasional di Kapal Al-Zaytun
Meskipun berlangsung selama 1,5 jam, acara ini terasa sangat padat dan bermakna. Salah satu bagian yang paling berkesan adalah orasi ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Najib Burhani, M.A., M.Sc., Ph.D., seorang peneliti terkemuka dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang dikenal atas kepakarannya dalam bidang ilmu sosial, budaya, dan kajian agama.
Mengawali pidatonya, Prof. Ahmad Najib Burhani membuka dengan penuh penghormatan kepada seluruh hadirin. “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak ibu semuanya, salam sejahtera, syalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu,” sapanya. Dalam suasana penuh kekeluargaan, ia melanjutkan, “Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa bihi nasta’in wa ala muridin ya wadidin, wa ala alihi wa sahabihi ajma’in amma ba’d.”
Ia mengucapkan rasa hormat kepada Syaykh Al-Zaytun, Syaykh Abdussalam Panji Gumilang, Ketua Yayasan Al-Zaytun Ustaz Imam Prawoto, para tokoh agama, akademisi, dan semua peserta yang hadir. Dengan nada hangat, ia mengungkapkan kegembiraannya berada di Al-Zaytun untuk pertama kalinya. “Saya baru pertama ke Al-Zaytun. Tapi sudah merasa seperti di rumah sendiri, di keluarga sendiri,” ujarnya, sambil menyebutkan bahwa beberapa tokoh yang ia temui ternyata memiliki hubungan personal dengannya yakni sebagai alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“Ketemu saya tadi rupanya Syaykh pernah menjadi Ketua IKALUIN, Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang saya adalah Wakil Ketua IKALUIN. Saya juga berbahagia, tadi rupanya Putri dari Syaykh itu adik kelas saya juga di UIN. Terus suaminya juga adik kelas saya juga di UIN. Suaminya di Fakultas Adab. Ini istrinya di Fakultas Ushuluddin, yang sama dengan saya. Jadi ini menjadi semisal forum reuni dengan Alumi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” kata Prof. Ahmad Najib Burhani.
Dalam presentasi selama 27 menit, Ahmad Najib Burhani menyampaikan kajian mendalam dengan meminjam judul dari orasi saat dia dikukuhkan sebagai profesor riset bidang agama dan tradisi keagamaan yaitu “AGAMA, KULTUR (IN)TOLERANSI, DAN DILEMA MINORITAS DI INDONESIA”. Menurutnya, persoalan toleransi tidak hanya bersumber dari regulasi atau struktur kelembagaan, tetapi juga tantangan budaya yang telah lama mengakar di masyarakat. Ia menyebutkan bahwa intoleransi sering kali lahir dari pola pikir yang tidak mendukung keberagaman.
“Jadi, mungkin kita selalu berbicara tentang berbagai peraturan yang terkait dengan toleransi, struktur kelembagaan yang berkaitan dengan toleransi, tentang hubungan antara agama dan sebagainya. Tetapi ada isu yang penting untuk dilihat, yang barangkali perlu untuk terus ditanamkan oleh kita semuanya, yaitu ada problem kultural, ada persoalan kultural yang terkait dengan toleransi yang dikembangkan dalam masyarakat kita,” ungkapnya.
Menurut Prof. Ahmad Najib Burhani, meski Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman, ada pola-pola kultural yang masih menghambat terwujudnya harmoni sejati. Lima tipe budaya intoleransi yang ia paparkan memberikan gambaran jelas tentang akar persoalan yang harus diatasi.

Tendensi Mesianik: Ketika Kekerasan Dianggap Misi Penyelamatan
Salah satu pola intoleransi yang menonjol adalah messianic tendency atau tendensi mesianik. Tendensi ini muncul ketika seseorang atau kelompok merasa dirinya sebagai “juru selamat” yang bertugas membawa pihak lain ke jalan yang dianggap benar. Dalam pola pikir ini, kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan tidak hanya dianggap sah, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kebajikan.
Prof. Ahmad Najib Burhani menjelaskan bahwa tendensi ini sering kali membenarkan tindakan diskriminatif dan kekerasan dengan dalih menyelamatkan orang lain dari “kesesatan.” Sebagai contoh, ia menyebutkan bagaimana pelaku kekerasan terhadap minoritas agama sering kali merasa tindakannya adalah bentuk pengabdian spiritual. Salah satu pelaku bahkan menyatakan, “Kami tidak kapok untuk kebenaran apapun kami siap. Di penjara itu hal biasa, itu uzlah, kalau dibunuh itu syahid bagi kami.”
Tendensi semacam ini, menurut Prof. Ahmad Najib Burhani, lahir dari pola pikir yang disebut Victorian Mindset. Dalam paradigma ini, nilai-nilai budaya atau agama seseorang dianggap superior, sehingga mereka merasa memiliki hak untuk memaksakan pandangannya kepada kelompok lain. “Ketika negara-negara seperti Belanda datang ke Indonesia, atau datang ke Afrika, mereka tidak menyebutnya sebagai penjajahan. Mereka menganggap apa yang dilakukannya itu adalah civilizing, membudayakan, memperadabkan orang-orang di Afrika, di Indonesia, dan sebagainya,” ungkapnya. Pola pikir serupa, katanya, dapat ditemukan dalam isu keberagaman agama di Indonesia, di mana kelompok mayoritas merasa berhak memaksakan keyakinannya kepada minoritas.
“Nah, di dalam agama, seringkali seperti itu. Misalnya, kasus di Jawa Barat, kasus di beberapa tempat yang lain, itu ada kata-kata, We force them to do the true path in order to rescue them, to save them from the punishment of God in the hell. Jadi kadangkala orang yang menyerang, menyerang kelompok Kristen, melawan kelompok yang lain, itu tidak merasa bahwa yang dilakukan itu sebagai sebuah tindakan yang salah, melanggar undang-undang, melanggar prinsip-prinsip dari Islam,” kata Prof. Ahmad Najib Burhani.
Kebajikan yang Salah: Membenarkan Diskriminasi Atas Nama Moral
Intoleransi juga sering kali dibungkus dengan narasi kebajikan yang salah atau false virtue. Dalam pola pikir ini, tindakan intoleran yang sebenarnya melanggar hak asasi manusia justru dianggap sebagai tindakan moral yang benar. Misalnya, kelompok mayoritas mengklaim bahwa mereka melakukan kekerasan untuk menyelamatkan minoritas dari dosa atau hukuman Tuhan.
“Beberapa tindakan intoleran disahkan atas nama kebaikan, padahal sebenarnya mencederai nilai-nilai keberagaman,” jelas Prof. Ahmad. Ia mengutip regulasi seperti PNPS Tahun 1965, yang menyebutkan bahwa keyakinan di luar enam agama resmi dianggap “tidak sehat” dan harus disehatkan. Pandangan ini, menurutnya, menunjukkan bagaimana intoleransi dilegitimasi atas nama moralitas.
False virtue ini tidak hanya memperburuk hubungan antaragama, tetapi juga menciptakan diskriminasi sistemik yang melanggengkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas. “Dengan dalih kebajikan, kelompok minoritas kerap dipaksa menyesuaikan diri dengan pandangan mayoritas, sehingga hak-hak mereka terpinggirkan,” tambahnya.
Narasi Euphemistik: Harmoni yang Membungkam
Fenomena lain yang menjadi penghalang toleransi adalah penggunaan narasi euphemistic atau euphemistic narrative tentang intoleransi. Dalam pola ini, kata-kata positif seperti “harmoni” atau “keamanan” digunakan untuk membungkus tindakan intoleran. Dalam kenyataannya, narasi ini sering kali digunakan untuk membatasi kebebasan kelompok minoritas.
Prof. Ahmad Najib Burhani menjelaskan bahwa narasi euphemistik ini kerap digunakan oleh pihak mayoritas atau bahkan oleh pemerintah untuk membenarkan pembatasan hak-hak minoritas. Ia mengutip kasus di Bogor, di mana perayaan agama minoritas dihentikan dengan alasan menjaga harmoni. Dalam kasus lain, penggusuran kelompok minoritas di Sampang dilakukan dengan dalih menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.
“Alih-alih melindungi kelompok minoritas, pemerintah justru membatasi hak mereka atas nama harmoni,” jelas Prof. Ahmad Najib Burhani. Narasi ini, katanya, menjadi alat untuk menutupi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas. Ia menyebutkan bahwa tindakan seperti ini sering kali dibenarkan dengan alasan seperti: “By stopping or restricting the activities of religious minorities, we can prevent casualties. By compromising their religious freedom, we can create harmony. By displacing Shiite community from Sampang, we can develop harmonious, homogenous Sampang again. By forbidding Ashura Day in Bogor, we can avoid bloodshed and also horizontal conflict.”
Prof. Ahmad Najib Burhani juga mengambil contoh beberapa pepatah bijak lokal yang justru disalahgunakan untuk melakukan tindakan intoleransi. Misalnya, “Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. “Nah itu kadang-kadang diartikan, nah orang agama lain itu tidak boleh mendirikan tempat ibadah yang lebih tinggi daripada kita, jumlah mereka tidak boleh lebih banyak daripada kita, mereka tidak boleh kaya daripada yang mayoritas dan sebagainya. Itu adalah euphemistic narrative tentang intoleransi,” kata Prof. Ahmad Najib Burhani.
Konstruksi Mental Konservatif: Melihat Keberagaman Sebagai Ancaman
Budaya intoleransi juga diperkuat oleh mental construct conservative atau konstruksi mental konservatif. Dalam pola pikir ini, keberadaan kelompok yang berbeda sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mayoritas. Akibatnya, kelompok minoritas sering kali diperlakukan dengan curiga atau bahkan dimusuhi.
Prof. Ahmad Najib Burhani menjelaskan bagaimana simbol-simbol agama tertentu sering kali dipermasalahkan hanya karena dianggap mencederai dominasi mayoritas. “Mental construct conservative itu adalah, misalnya, ini kelompok minoritas itu dianggap menyinggung perasaan daripada mainstream. Mereka kalau umpamanya sedikit-sedikit gitu ya, melakukan keramaian, melakukan festival, dianggap mengganggu lingkungan, dianggap menyampahi masyarakat dan sebagainya,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan kasus di mana keberadaan makam dari agama atau kepercayaan yang berbeda dianggap mengganggu harmoni kawasan pemakaman mayoritas. Bahkan hal-hal yang sepele, seperti bentuk tiang yang menyerupai simbol agama tertentu (salib misalnya), dapat menjadi isu besar di masyarakat.
Pluralisme Terbatas: Ketika Toleransi Bersifat Selektif
Pola intoleransi terakhir yang disoroti oleh Prof. Ahmad Najib Burhani adalah delimited pluralism atau pluralisme terbatas. Dalam pola ini, toleransi hanya diberikan kepada kelompok-kelompok yang dianggap sejalan dengan pandangan mayoritas. Sementara itu, kelompok yang berbeda secara signifikan sering kali ditolak keberadaannya.
Ia menjelaskan bahwa pluralisme di Indonesia sering kali bersifat selektif. Misalnya, ada desa-desa yang disebut sebagai desa toleransi, tetapi toleransi tersebut hanya berlaku untuk kelompok yang “diakui” oleh masyarakat setempat. “Misalnya ada desa yang disebut dengan desa toleransi, tetapi keyakinan tertentu yang berbeda dari kelompok agama yang dominan di situ, tetap tidak diakui di dalam kelompok, di dalam desa tersebut,” jelasnya.
Dalam pandangan Prof. Ahmad Najib Burhani, pluralisme semacam ini adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang seharusnya menjadi fondasi bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa toleransi sejati harus inklusif dan tidak boleh mengesampingkan kelompok mana pun, terlepas dari besar kecilnya jumlah mereka.
Menanam dan Merawat Toleransi
Lima tipe intoleransi yang dipaparkan oleh Prof. Ahmad Najib Burhani menunjukkan bahwa persoalan intoleransi di Indonesia bukan sekadar masalah kebijakan atau hukum, tetapi juga masalah budaya yang telah lama mengakar. Pola pikir seperti tendensi mesianik, kebajikan yang salah, narasi euphemistik, konstruksi mental konservatif, dan pluralisme terbatas harus diubah melalui dialog, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keberagaman.
Prof. Ahmad Najib Burhani mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma dari merasa terancam oleh keberagaman menjadi merayakan keberagaman. Ia menegaskan bahwa kebhinekaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang harus dirayakan. “Kebhinekaan adalah kekayaan. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen, apalagi di era globalisasi ini. Kita harus embrace diversity, bukan menghilangkannya,” tuturnya dengan tegas.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa keberagaman bukan sekadar fakta, tetapi juga fondasi penting dalam pembangunan bangsa. “Jika konflik dibiarkan, maka semua infrastruktur yang kita bangun akan sia-sia,” katanya.
Menutup orasinya, Prof. Ahmad menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat utama untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Ia mengapresiasi Al-Zaytun yang telah menjadikan pendidikan, toleransi, dan perdamaian sebagai tiga pilar utamanya. “Saya juga merasa senang tadi ketika disebutkan bahwa tiga kunci, landasan dan moto daripada Mahad Al-Zaytun, Pesantren Al-Zaytun itu adalah pendidikan, toleransi, dan perdamaian. Bahwa Al-Zaytun adalah pusat pendidikan, pusat pengembangan budaya toleransi, dan juga perdamaian,” ungkapnya.
Peringatan Hari Toleransi Internasional 2024 ini menjadi langkah nyata Al-Zaytun untuk memperjuangkan harmoni di tengah keberagaman. Peluncuran Ensiklopedia Toleransi dan Perdamaian semakin mempertegas peran pesantren ini sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga peduli terhadap perdamaian dunia. Dengan langkah ini, Al-Zaytun menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar wacana, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Raya yang abadi. (atur/TokohIndonesia.com)
Tim Reportase TokohIndonesia.com: Mangatur L. Paniroy (Koordinator), Rukmana, Wiratno
Profil Prof. Ahmad Najib Burhani: Peneliti Unggulan di Bidang Sosial dan Keagamaan
Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A., M.Sc., Ph.D., adalah salah satu tokoh terkemuka di bidang ilmu sosial, budaya, dan kajian agama. Kiprahnya sebagai peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menjadikannya figur yang berpengaruh dalam pengembangan kajian ilmu sosial dan agama di Indonesia.
Prof. Ahmad Najib Burhani lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 27 April 1976. Ia menghabiskan masa kecil dan menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Pada tahun 1999, ia berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan meraih gelar Sarjana Agama.
Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membawanya melanjutkan pendidikan magister di luar negeri. Ia menuntaskan program Master of Arts di bidang Kajian Islam di Universiteit Leiden, Belanda, pada tahun 2004. Tak berhenti di sana, Prof. Ahmad Najib Burhani melanjutkan studi ke University of Manchester, Inggris, dan meraih gelar Master of Science dalam bidang Metode Penelitian Sosial dan Statistika pada tahun 2007.
Pada jenjang doktoral, Prof. Ahmad Najib Burhani melanjutkan studi di University of California, Santa Barbara (UCSB), Amerika Serikat. Ia berhasil meraih gelar Ph.D. pada tahun 2013 dengan disertasi bertajuk “When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia”. Karya ini menjadi salah satu kontribusi besar dalam kajian agama dan diskursus keislaman di Indonesia.
Karier profesional Prof. Ahmad Najib Burhani diawali sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana ia mengajar dari tahun 2004 hingga 2014. Selain itu, ia juga menjadi peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2005.
Pada 27 Agustus 2020, ia dikukuhkan sebagai Profesor Riset di bidang Agama dan Tradisi Keagamaan, sebuah pencapaian yang mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu peneliti terbaik di bidangnya. Setelah LIPI bergabung dengan BRIN, ia diamanahi sebagai Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) sejak 4 Maret 2022.
Dedikasinya di dunia penelitian telah membuahkan berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya: Professor Charles Wendell Memorial Award (2013), Ikon Prestasi Pancasila di bidang Sains dan Inovasi (2020), Peneliti Terbaik LIPI bidang Sosial Humaniora (2020), Muhammadiyah Award (2021).
Keberhasilan Prof. Ahmad Najib Burhani itu mencerminkan dedikasinya terhadap pengembangan ilmu sosial, budaya, dan kajian agama di Indonesia. Ia menjadi salah satu tokoh penting yang terus mendorong kemajuan riset dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional.
Video Tiktok (VT) @tokoh.id
Berikut daftar Video Tiktok (VT) di akun @tokoh.id seputar Peringatan Hari Toleransi Internasional di Al-Zaytun:
- Ternyata Terdidik dan Terpelajar, itu Beda
- Kickoff Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian - AS Panji Gumilang
- Panji Gumilang Berlayar dengan Kapal Buatannya, Kapal Al-Zaytun KM-02 Gunung Pulosari
- Panji Gumilang Menikmati Kapal Buatannya, Kapal KM-02 Gunung Pulosari
- Kapal Al-Zaytun, Ratu Connie Rahakundini Bakrie
- Yang Penting Kita Pancasila - Prof. Ahmad Najib Burhani
- Kapal Kita Bisa Muat 200 Orang - AS Panji Gumilang
- Kenalkan Pancasila, Toleransi Pasti Sampai - AS Panji Gumilang
- Pancasila Harta Karun yang Riil - AS Panji Gumilang
- Detik-detik Kapal Al-Zaytun, KM Gunung Pulosari, Bersandar ke Pelabuhan
- Indonesia Raya 3 Stanza di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Ma'had Al-Zaytun
- Panji Gumilang (78 th) Menaiki Kapal Al-Zaytun yang Dibuatnya
- Gerakan Budaya Toleransi dan Perdamaian - Dr. Haryadi Baskoro, M.A., M.Hum.
- Lima Tipe Budaya Intoleransi - Prof. Ahmad Najib Burhani, peneliti BRIN
- Saya merasa seperti di keluarga sendiri - Prof. Ahmad Najib Burhani, peneliti BRIN
- Santri Al-Zaytun Perajut Toleransi dan Perdamaian
- Kok Bisa Ya, Al-Zaytun Dituduh Seperti Itu? - Ahmad Najib Burhani, Peneliti BRIN
- Merayakan Hari Toleransi Internasional di Atas Kapal Gunung Pulosari (Kapal Al-Zaytun), 16 November 2024
- Al-Zaytun Meluncurkan Ensiklopedia Toleransi dan Perdamaian Digital