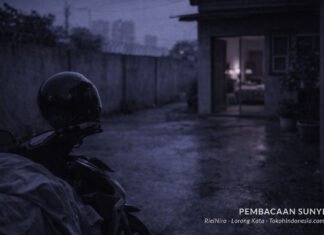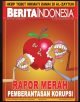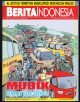Prof. Ki Supriyoko: Ketika Karakter Hilang, Maka Segalanya Hilang
Pelajaran dari Sekolah-Sekolah yang Menanamkan Nilai, Bukan Sekadar Ilmu

“Ketika karakter hilang, maka segalanya hilang.” Kalimat ini bukan sekadar penutup orasi Prof. Dr. Ki Supriyoko, tetapi inti dari seluruh pesannya tentang arah pendidikan Indonesia. Dalam Simposium Hardiknas 2025 di Maβhad Al-Zaytun, ia menyerukan pentingnya kembali ke akar pendidikan: membentuk manusia yang utuh, bukan hanya pintar, tetapi juga kuat secara moral. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter bukan sekadar wacana ideal, tapi sudah hidup dan tumbuh di Al-Zaytun serta sejumlah sekolah lain yang menanamkan nilai melalui keteladanan, kebiasaan baik, dan lingkungan yang mendidik.
Penulis: Atur Lorielcide - TokohIndonesia.com (Tokoh.ID)
Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum yang tidak biasa. Lebih dari 2.000 peserta dari seluruh penjuru tanah air berkumpul di Masjid Rahmatan lil βAlamin, Maβhad Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, dalam simposium tiga hari bertajuk “Membangun Ekosistem Pendidikan yang Tidak Terputus Menyongsong Indonesia Emas 2045.” Di hari penutupan, 2 Mei 2025, Prof.Β Dr.Β Ki Supriyoko, M. Pd., salah satu tokoh pendidikan nasional, menyampaikan pidato yang tidak hanya menyentuh akar filosofis pendidikan nasional, tetapi juga menggugah lewat contoh-contoh nyata yang ia temukan di lapangan.
Ia memulai pidatonya dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada tuan rumah. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Syaykh Panji Gumilang yang telah berkenan mengundang saya,” ucapnya. “Dulu, menjelang masa COVID, saya pernah hadir di sini. Saya masih ingat kenangan unik saat dijemput dari Al-Islah untuk ceramah malam hari. Ketika itu saya memakai sarung, tapi oleh santri diingatkan bahwa di sini tidak diperbolehkan sarung. Saya pun mengganti dengan celana β kenangan itu masih melekat kuat.”
Pengalaman kecil itu, menurutnya, menjadi pengingat tentang pentingnya keterbukaan dan kedisiplinan dalam lingkungan pendidikan. Ia kemudian mengapresiasi bagaimana Maβhad Al-Zaytun membentuk santrinya melalui lingkungan yang tertata, toleran, dan penuh semangat kemandirian. “Saya punya pesantren kecil dengan 700 santri, tapi saya banyak belajar dari Al-Zaytun,” ujarnya.
Prof. Supriyoko kemudian mengenang sosok sentral yang menjadi ikon Hari Pendidikan Nasional β Ki Hadjar Dewantara. Prof. Supriyoko menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional diambil dari tanggal lahir tokoh tersebut, yaitu 2 Mei, sementara 26 April yang merupakan tanggal wafatnya diperingati secara internal di Taman Siswa sebagai Hari Bakti Taman Siswa.
“Ki Hadjar lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sesuai budaya Jawa, pada usia 40 tahun, dia mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara,” jelasnya sambil menunjukkan foto rumah asli tokoh tersebut di Yogyakarta yang kini menjadi Museum Dewantara Kirti Griya. Museum itu, menurutnya, menyimpan benda-benda keseharian Ki Hadjar yang digunakan dalam perjuangan pendidikan: dari tas, kacamata, hingga ruang tamu.
Namun, ada kegelisahan yang dia sampaikan tentang betapa mudahnya bangsa ini lupa terhadap tokohnya sendiri. “Saya sampai membuat patung Ki Hadjar. Banyak yang mengkritik, katanya orang Islam kok membuat patung. Tapi saya jelaskan, ini bukan untuk disembah, tapi supaya anak-anak kita kenal wajahnya,” ucapnya. Ia menambahkan kisah tentang kuis di televisi yang menampilkan foto Ki Hadjar dan ditanggapi siswa SMA dengan jawaban “Bung Tomo.” “Untung dijawab Bung Tomo. Kalau dijawab Ki Supriyoko, saya sudah nggak ada,” candanya.
Masuk ke inti pemikiran Ki Hadjar, Prof. Supriyoko membedah konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, sebagaimana digagas Ki Hadjar Dewantara. “Ki Hadjar menulis, perkembangan seseorang tergantung pada dua hal: dasar dan ajar,” tegasnya. Dasar merujuk pada fitrah, bawaan dari Tuhan; sedangkan ajar merujuk pada lingkungan dan pembiasaan.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dua faktor ini: “Kalau dasar dan lingkungannya positif, hasilnya positif. Tapi kalau salah satu negatif, hasilnya tergantung mana yang dominan. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya sudah jelas.” Ucapan itu menggambarkan prinsip pendidikan sebagai proses individual, bukan pabrik pencetak massal.
Ia memberi contoh realitas: “Di Jogja banyak remaja yang malam-malam membawa celurit, menyakiti orang tanpa sebab. Itu terjadi karena lingkungannya negatif.” Sebaliknya, ia memuji Al-Zaytun sebagai ekosistem yang menciptakan lingkungan positif dan inklusif, bahkan multikultural. “Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha β semua toleran. Tidak masalah.”
Pendidikan, bagi Ki Hadjar, adalah pemerdekaan manusia dari kebodohan dan ketertindasan. Tapi Prof. Supriyoko menunjukkan bahwa misi ini tak cukup jika tidak disertai dengan strategi pendidikan yang menanamkan karakter, bukan hanya keterampilan.
Tapi Al-Zaytun bukan satu-satunya contoh. Prof. Supriyoko memaparkan sekolah-sekolah lain yang menurutnya berhasil membentuk karakter siswa melalui tindakan nyata dan kebiasaan baik.
Salah satunya adalah SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Di sekolah ini, seluruh siswa dan guru saling berjabat tangan setiap pagi. Masuk kelas harus dengan kaki kanan terlebih dahulu β sebuah kebiasaan kecil yang menyiratkan penghayatan terhadap nilai-nilai adab.
Saya pernah membawa jenderal ke sana. Sudah masuk kelas, ditarik oleh siswa kelas lima. Ternyata karena masuknya pakai kaki kiri, disuruh ulangi masuk lagi dengan kaki kanan,” cerita Prof. Supriyoko yang disambut tawa hadirin. Cerita itu menggambarkan betapa nilai diajarkan bukan hanya lewat ceramah, tetapi lewat kebiasaan harian yang disiplin.

Di SMP Taman Jawa, Mojokerto, siswa yang datang dengan sepeda motor tidak boleh masuk begitu saja. Motor harus dituntun, bukan dikendarai. Mengapa? Karena sekolah adalah tempat adab, bukan sekadar area lalu lintas. Di sana, doa bersama dipimpin oleh siswa sendiri setiap hari.
Yang paling mengesankan adalah contoh dari Japanese School di Tangerang Selatan, tempat Prof. Supriyoko melakukan observasi langsung dari pagi hingga sore. Di sekolah tersebut, guru-guru berdiri memberi hormat kepada para siswa saat mereka datang. “Orang Jepang itu kalau menghormati, membungkuk. Makin dalam bungkuknya, makin tinggi hormatnya. Saya sampai takut jatuh waktu meniru,” ucap Prof. Supriyoko.
Lebih menarik lagi, orang tua murid di sekolah Jepang sangat menghormati guru. “Di Indonesia, itu jarang. Tapi di Al-Zaytun, saya lihat itu ada. Orang tua sangat menghargai ustaz-ustazah.”
Di sinilah letak pentingnya “family atmosphere” dalam pendidikan. Bukan nepotisme, tapi suasana kekeluargaan di mana kakak kelas menjadi saudara, guru menjadi orang tua, dan setiap anggota komunitas punya tanggung jawab moral terhadap yang lain.
Karakter Tak Bisa Dibentuk Secara Daring
Dalam era digital yang makin mengagungkan efisiensi dan kecepatan, Prof. Supriyoko menantang satu hal mendasar: apakah karakter bisa dibentuk lewat pendidikan daring? Jawabannya tegas: tidak.
“Saya masuk masjid ini, disambut adik-adik kelas 11. Itu karakter. Tidak bisa diajarkan lewat Zoom. Percaya saya,” ujarnya lantang.
Prof. Supriyoko membandingkan pembelajaran tatap muka dan daring. Meski mengakui keunggulan teknologi dalam hal akses dan efisiensi, ia menekankan bahwa nilai-nilai seperti hormat, keteladanan, dan budi pekerti hanya bisa ditanamkan lewat interaksi langsung.
“Saya punya 700-an mahasiswa S2. Umumnya guru. Mereka suka kuliah daring. Saya bilang boleh, tapi tidak semua daring. Kalau semua daring, karakter kalian mau ditaruh di mana?”
Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi proses pemanusiaan. Di sinilah nilai-nilai luhur, seperti budi pekerti, menemukan tempatnya sebagai inti. “Budi pekerti itu sikap dan perilaku yang baik, sesuai norma sosial,” kata Prof. Supriyoko. “Dan budi pekerti itu sekarang mahal.”
Di kota besar, katanya, makin sedikit siswa yang menghormati guru. Maka karakter bukan hanya dibicarakan, tapi harus dihidupkan.
Memayu Hayuning Sarira, Bangsa, dan Bawana
Salah satu filosofi pendidikan yang mendapat tempat khusus dalam pidato Prof. Supriyoko adalah ajaran Jawa kuno: “memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana”. Artinya, pendidikan harus menghasilkan manusia yang mampu menjaga dirinya sendiri, bermanfaat untuk bangsanya, dan memberi kontribusi bagi dunia.
Di Al-Zaytun, Prof. Supriyoko melihat filosofi ini diterjemahkan secara nyata. Kemandirian diajarkan sejak dini. Santri tidak hanya belajar agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga hidup mandiri, bertani, beternak, dan memahami teknologi.
“Saya ingin ustaz dan ustazah saya datang ke sini belajar langsung. Kalau kita lebih tidak bisa, ya katakan saja. Jangan malu. Yang penting kita mau belajar.”
Pendidikan bukan untuk menciptakan pengangguran intelektual. Ia menyayangkan fakta bahwa lulusan SMK, yang seharusnya siap kerja, justru banyak yang menganggur. “Saya membantu menyusun pendidikan sistem ganda dulu. Tapi ternyata belum maksimal. Di Belanda dan Jerman, anak SMK belum lulus sudah diincar perusahaan. Di sini, masih banyak yang nganggur.”
Trikon dan Tiga Pantangan

Menjelang akhir pidatonya, Prof. Dr. Ki Supriyoko memperkenalkan satu konsep yang sangat penting dalam pendidikan nasional, yakni Trikon: kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas.
“Kontinuitas berarti kita harus melanjutkan budaya positif dari leluhur. Konvergensitas artinya kita terbuka menerima budaya luar β Barat atau Timur β asal positif. Konsentrisitas adalah hasil perpaduannya, budaya baru yang lebih baik,” jelasnya.
Ia mencontohkan bagaimana tradisi pernikahan di Yogyakarta, yang dulunya berlangsung 4 jam dengan sistem sajian berurutan, kini berpadu dengan model standing party dari budaya Barat. “Keduanya boleh digabung, asal tidak meninggalkan nilai-nilai inti.”
Trikon ini adalah kerangka berpikir dalam membangun pendidikan yang berpijak pada akar, tetapi membuka diri terhadap kemajuan zaman. Di sinilah letak pentingnya keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara warisan dan pembaruan nilai.
Lalu, Prof. Supriyoko menyampaikan tiga pantangan yang harus dihindari oleh setiap pendidik, pejabat, dan pemimpin: harta, tahta, dan wanita. “Jangan bermain-main dengan harta. Jangan korupsi. Jabatan tidak usah dibeli. Kalau selingkuh, nama Anda akan terkenal. Tapi terkenal buruk,” ucapnya tegas, disambut gelak tawa dan tepuk tangan peserta.
Namun di balik humor dan ketegasannya, tersimpan pesan yang sangat mendalam. Bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan watak. Bukan hanya mencetak lulusan, tapi menyiapkan manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan tahu arah hidupnya. Pendidikan bisa kehilangan banyak hal, tapi jika kehilangan karakter, maka hilanglah segalanya.
“Kalau kesehatan hilang, separuh hidupmu hilang. Tapi kalau karakter hilang, semuanya hilang,” ucap Prof. Supriyoko menutup pidatonya. Kalimat yang disampaikannya dengan lugas itu menjadi penegasan terakhir dari seluruh rangkaian pemikiran yang ia bangun: bahwa karakter adalah fondasi, dan tanpa itu, pendidikan kehilangan maknanya yang paling mendasar. (Atur/TokohIndonesia.com)