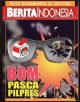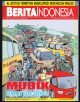Sentuhan Politik Sang Akademisi
Bambang SudibyoHentikan Kerjasama dengan IMF

Isu ekonomi paling hangat saat ini adalah mengenai program penghentian kerja sama RI-IMF. Bambang menyambut gembira keputusan pemerintah untuk merealisasikan penghentian kerja sama dengan IMF. Namun, suatu strategi keluar dari ketergantungan pada IMF yang hanya berperspektif fiskal, moneter, dan psikologi pasar tanpa adanya skenario penataan ulang ekonomi makro Indonesia yang berwawasan nasionalisme dan kemandirian memiliki kans yang kecil untuk berhasil.
Program penghentian kerja sama itu sebenarnya telah lama dipertimbangkannya. Dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Forum tanggal 26 Oktober 2002, Bambang memaparkan pemikirannya dalam sebuah makalah berjudul “Exit Plan dari Ketergantungan pada IMF dan Kemandirian Ekonomi”.
Dalam makalah itu Bambang memaparkan pentingnya kemandirian ekonomi dengan kembali merekatkan kebersamaan di bidang ekonomi, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu jauh, meningkatkan upah tenaga kerja, yang semua itu merupakan tema-tema strategis untuk dijalankan agar setelah lepas dari IMF Indonesia menjadi negara yang mampu mengelola diri sendiri.
Kemampuan mengelola ekonomi sendiri, dikemukakan Bambang, sebenarnya telah dimiliki Indonesia. Buktinya, cadangan devisa meningkat sekitar 3 milyar USD dari 18 milyar USD pada tahun 1999 menjadi 21 milyar USD pada tahun 2002. Sedangkan dana cadangan dari IMF sebesar 11 milyar USD tidak pernah terpakai. Fakta tersebut mendukung konklusi bahwa sebetulnya Indonesia dari perspektif moneter sudah siap keluar dari program IMF.
Bambang menyambut gembira keputusan pemerintah untuk merealisasikan penghentian kerja sama dengan IMF. Maka, mulai 2004 Indonesia akan kembali dapat menentukan program-program ekonominya sendiri tanpa adanya campur tangan lembaga asing.
Namun, suatu strategi keluar dari ketergantungan pada IMF yang hanya berperspektif fiskal, moneter, dan psikologi pasar tanpa adanya skenario penataan ulang ekonomi makro Indonesia yang berwawasan nasionalisme dan kemandirian memiliki kans yang kecil untuk berhasil. Mengapa demikian? Karena struktur makro ekonomi Indonesia yang lemah membuatnya senantiasa rentan untuk tergantung pada kekuatan ekonomi asing.
Maka, Bambang pun menawarkan pendekatan komprehensif terhadap strategi keluar yang mencakup (1) penataan ulang struktur ekonomi makro yang berwawasan nasionalisme ekonomi, (2) strategi fiskal, (3) strategi moneter, dan (4) strategi pengendalian psikologi pasar. Yang dimaksud dengan nasionalisme ekonomi adalah kebersamaan, keberdayaan, dan kemandirian ekonomi.
Catatan istimewa diberikan Bambang bahwa dengan upah tenaga kerja yang rendah hal itu berarti golongan bawah mensubsidi golongan atas. Hal ini harus dihentikan dengan cara peningkatan upah minimum nasional. Dengan demikian, golongan bawah pun akhirnya dapat menikmati hidup layak dan keadilan ekonomi dapat terwujud.
Tentu saja menarik melihat sosok Bambang Sudibyo. Ia mengaitkan antara ekonomi dengan keadilan dan kebijakan. Perhatiannya ini tidak terlepas dari pemahamannya bahwa antara ekonomi dan politik itu saling keterkaitan dan merupakan bidang yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pergulatannya dengan ekonomi makro Indonesia secara nyata terjadi ketika krisis moneter melanda Indonesia. Ia diberikan kepercayaan menjadi Menteri Keuangan. Selama 10 bulan ia menjabat sebagai Menteri Keuangan itu ia mengalami proses pembelajaran yang luar biasa dalam hidup. Ia mengaku bahwa belum pernah sepanjang hidupnya harus mempelajari begitu banyak hal. Secara mendadak terekspose pada berbagai macam hal dan berbagai macam risiko yang tidak pernah terbayangkan. “Betapa proses pembelajaran itu sangat luar biasa, di mana dengan waktu yang sangat singkat saya harus belajar begitu banyak hal.” kenangnya.
Di mata Bambang, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru adalah masa kemajuan dalam perkembangan kemampuan produksi. Orde Baru sangat menekankan bagaimana Indonesia dapat memperbesar kapasitas produksinya. Waktu itu dapat dilihat dengan jelas kecenderungannya.
Akan tetapi, permasalahannya kemudian adalah Orba menjadi relatif abai terhadap pendistribusian hasil produksi. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah pembagian hasil produksi sebagian besar dinikmati sekelompok kecil penduduk saja yang jumlahnya hanya sebesar 18 persen. Akibat dari pengabaian pembagian hasil produksi tersebut menyebabkan lebih dari 80 persen penduduk mempunyai kemampuan beli yang rendah dan terjadilah ketidakseimbangan antara kemampuan produksi dengan daya serap masyarakat untuk komsumsi.
Kenyataan ini meyakinkannya bahwa dengan kemampuan produksi yang besar tidak berarti akan menghasilkan daya serap konsumsi penduduk yang punya daya beli tinggi juga. Jumlah konsumen yang aktif, yang memiliki daya beli kuat jumlahnya hanya kurang dari 20 persen penduduk, bahkan menurut dugaannya hanya sekitar 14 persen. Kelompok masyarakat ini ditengarai sebagai kelas menengah dan elit. Itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki daya serap yang besar.
Sementara yang sekitar 86 persen penduduk adalah mereka yang hidup dalam tingkat perekonomian yang subsistem. Tingkat perekonomian yang mampu memberikan rejeki yang sekadar cukup untuk bertahan hidup. “Inilah yang kemudian membuat ekonomi Indonesia setelah didera krisis, tetap relatif stabil,” katanya seraya menambahkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia telah terbiasa untuk survival. “Hal itu terjadi oleh karena ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh konsumsi.” ujarnya.
Lebih dari 80 persen konsumsi hasil produksi berada pada tingkat subsistem. Konsumsi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk kehidupan, seperti pangan, kesehatan, papan yang tidak bisa ditawar, mau tidak mau, baik ada kerusuhan atau tidak ada kerusuhan, orang harus tetap konsumsi. produksi dan jasa itu yang hingga sekarang yang mempertahankan perekonomian Indonesia.
Di mana pun di dunia ini konsumsi adalah bagian terpenting dalam ekonomi, yang menurut Bambang, banyak orang yang telah menghiraukan hal tersebut. Orang sangat bias terhadap pentingnya investasi, “Memang investasi penting, karena investasi itu akan menciptaan lapangan kerja, tetapi investasi bukan kelanjutan dari konsumsi, itu tidak betul dan tidak akan menguntungkan juga.” ujarnya. Tujuan berinvestasi adalah untuk menjawab daya konsumsi.
Jadi persoalan di Indonesia adalah bagaimana dapat mengembangkan daya serap konsumsi masyarakat terutama kepada kelompok yang lebih 80% itu yang sering disebut rakyat. Hal ini, menurutnya, telah diabaikan sehingga ekonomi Indonesia menjadi kurang lancar, karena ada ketidakseimbangan antara kemampuan kapasitas produksi dengan kemampuan daya serap konsumsi.
Dengan keadaan kesenjangan demikian, tentu terjadi jurang pemisah dan kecemburuan sosial, terjadi beban sosial dan keadaan yang tentu tidak nyaman, tidak ramah, karena adanya kecemburuan sosial masyarakat ekonomi bawah dengan masyarakat menengah ke atas.
Keadaan tersebut yang selalu menjadi kendala proses pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan adanya resiko, gangguan stabilitas ekonomi Indonesia menjadi besar. Jadi ada sumber ketidakstabilan, sebuah ketidakstabilan yang inheren dan berasal dari perekonomian itu sendiri – kebijakan ekonomi tidak adil.
Karena ekonomi yang tidak adil sehingga situasi sosial yang tidak damai penuh kecemburuan berkembang, dan itu menjadi iklim yang tidak bagus untuk keinginan investasi. Akhirnya orang menjadi jera untuk berinvestasi. Ketika orang berinvestasi yang diharapkan return yang dapat mengkompensasi tingkat resiko sosial yang sangat tinggi itu.
Jika keseimbangan antara kapasitas produksi dengan daya serap konsumsi dapat terjadi, sehingga hasil produksi disambut oleh konsumsi dan nilai ekonomi Indonesia dapat bergiling dengan lancar dengan sanksi sosial rendah, maka akan banyak orang yang ingin berinvesatasi, dan dengan konsumsi yang besar akan mengundang juga investasi.
Trilogi Orde Baru
Bambang setuju dengan triloginya orde baru, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan kesatabilan. Permasalahan ekonomi Indonesia pada saat itu, pertumbuhan menjadi tidak maksimal oleh karena ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, ketidakseimbangan itu disebabkan oleh karena tidak meratanya pembagian “kue” produksi, tidak adil yang mempengaruhi resiko sosial dan mengancam kestabilan nasional. Tiga hal tersebut sangat terkait
Sebenarnya yang menyebabkan tidak adilnya pembagian “kue” itu berasal dari tiga hal. Pertama, kecilnya gaji pegawai negeri. Pegawai negeri diberi harga yang sangat murah, termasuk di dalamnya tentara dan polisi. Pelayanan mereka diberi harga yang murah sekali, tidak dapat dibayangkan pegawai mensubsidi majikannya.
Kedua permasalahan upah buruh yang terlalu rendah, mereka juga mensubsidi majikannya. Dan yang ketiga murahnya hasil-hasil produksi tradisional. Seperti pertanian, sektor modern membeli produksi tradisional terlalu murah. Dalam hal ini sektor tradisional mensubsidi sektor tradisional, bahkan mensubsidi ekonomi asing.
Inilah tiga hal yang menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi tidak bergerak dengan cepat, tidak stabil dan tidak aktif. Jadi yang diperlukan adalah penyetelan ulang terhadap tiga harga ini. Tentu hal ini memerlukan waktu yang panjang.
Jika pada waktu masa Orde Baru pemerintah dapat membagikan “kue” secara adil, dengan pertumbuhan ekonomi 5-8 persen per tahun mestinya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi 5-12 persen per tahun. Dan akan lebih stabil karena tidak adanya ledakan-ledakan sosial oleh karena lebih adil. Selain dari pada menyelesaikan tiga harga tadi, juga harus memikirkan bagaimana caranya mengurangi utang dalam negeri yang mengambil alokasi belanja APBN yang sangat besar. Itu terutama terjadi oleh karena usaha rekap bank.
Subsidi
Kemudian persoalan subsidi. Sekarang ini banyak sekali subsidi yang bertentangan dengan Pasal 34 UUD 45. Di sana tidak dikatakan konsumen listrik dan BBM di subsidi oleh negara, tetapi yang disubsidi adalah fakir miskin dan anak-anak telantar. Kalau yang disubsidi adalah pengguna BBM maka yang menerima subsidi adalah mereka yang menggunakan BBM. Siapa sih pengguna BBM? Yaitu para kapitalis yang memiliki pabrik-pabrik besar itu. Mereka itulah yang menerima subsidi, mereka yang memiliki rumah yang besar-besar dengan penggunaan listrik yang besar, merekalah yang paling banyak menerima subsidi. Dengan itu APBN dibebaskan dari subsidi yang tidak adil itu, kemudian dipakai untuk memperbaiki gaji pegawai negeri.
Kemudian bersamaan dengan itu bisa secara bertahap dilakukan proteksi tarif bea masuk terhadap produk-produk sektor tradisional terutama pertanian. Usaha ini tidak membutuhkan dana APBN, yang diperlukan adalah tanda tangan menteri keuangan untuk menaikan bea masuk. Dan tentunya akan berhadapan dengan WTO dan sebagainya. Pro-coment atau advokator utama lembaga WTO adalah negara-negara maju seperti AS, Eropa Barat, Jepang, Australia. Negara-negara ini sampai sekarang tidak mematuhi ketentuan dari WTO. Di mana mereka tidak patuh di produk-produk pertanian.
Jadi untuk apa kita patuh, karena mereka sendiri yang ada sebagai advokator utama WTO, mereka sendiri sangat reluctant untuk patuh terhadap regulasi WTO terutama bidang pertanian. Sehingga menjadi lucu, jika gula dan beras Indonesia hanya diproteksi 25% tarif sedangkan Jepang memproteksi berasnya dengan 400%, Amerika masih memproteksi hasil pertaniannya dengan 184%.
“Lalu kenapa kita tidak berbuat seperti mereka?” tanyanya. Sehingga yang nanti laku di pasar bukan lagi jeruk atau apel dari luar negeri tetapi dari dalam negeri sendiri. Jika harga petanian bagus para petani juga bersemangat menanam. Dan sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggapi ini, karena politik yang betul akan membuahkan kebijakan yang betul. Kebijakan yang betul adalah kebijakan yang memaksimalkan kepentingan umum, kebijakan yang berdasarkan keadilan. Dan keadilan yang paling menjadi konsern orang banyak adalah keadilan ekonomi. Karena apa? Itu menyangkut kepentingan kehidupan mereka sehari-hari.
Setelah gaji pegawai negeri naik dan meningkatnya tarif bea masuk, akan mempengaruhi tingkat agrikat demand. Permintaan agrikat itu akan naik, kemudian revenue atau pendapatan pengusaha naik, sehingga kemudian ada peluangan bagi mereka merestruktur biaya, dengan cara menaikan upah buruh. Jadi proposal kenaikan upah buruh seperti itu tidak samasekali membebani pengusaha. Dan itu akan kembali juga kepada mereka, karena buruh itu adalah juga konsumen terhadap produksi mereka. Jadi berputar sesungguhnya ekonomi itu. Yang menjadi permasalahnya adalah bagaimana roda perputaran menjadi cepat, lancar dan adil.
Ia melihat kebijakan tim ekonomi kita memang plot sejak zaman orde baru itu keliru, ada persepsi yang mengangap komsumsi tidak penting, padahal tulang punggung pergerakan ekonomi itu dikonsumsi, dan investasi itu berada pada tingkat kedua. Investasi akan bergulir dan menjanjikan jika ada konsumsi kuat, yang akan memberikan iklim propektif return yang tinggi untuk investasi dan ada keadilan ekonomi sehingga investasi tidak terancam oleh ledakan-ledakan sosial.
Sekarang banyak orang bicara investasi-investasi, jadi ternyata ada kekeliruan paradigma. Bahwa seolah-olah investasi lebih penting dari konsumsi. Ia tidak percaya itu! “Consumption is primary, investment is secondry”. Yang paling penting adalah bagaimana memperkuat daya beli masyarakat. Dan jalan untuk meningkatkan daya beli itu adalah pemertaan hasil ekonomi (pembagian “kue” yang adil).
Ekonomi Domestik
Kemudian ada sebuah kekeliruan lain yang bahkan sudah melembaga dan itu warisan Orba, yaitu pandangan bahwa mencari rejeki dari negeri orang lebih penting dari pada domestik, seolah-olah rejeki eksport lebih manis dibanding rejeki dalam negeri. Menurutnya itu keliru, itu akan menciptakan Indonesia yang tergantung kepada ekonomi asing. Mestinya adalah bagaimana menggulirkan ekonomi domestik, memperbesar ekonomi domestik dan mempercepat putaran ekonomi domestik, sehingga akan tergantung kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik sendiri.
Sementara penghasilan dari ekspor itu hanya sebuah pelengkap. Bukan berarti menolak ekspor atau tidak melihat ekspor itu tidak penting, tetapi jangan dianggap bahwa dengan demikian sebuah kebijakan yang memperbesar ekspor dengan cara mengorbankan upah buruh. Sebab upah buruh adalah bagian dari konsumsi domestik. Ketika upah buruh ini ditekan berarti memperkecil daya konsumsi domestik, kemudian memperkecil ekonomi domestik. Memang rejeki yang berasal dari luar menjadi lebih besar, tapi rejeki yang dari dalam lebih kecil. “Ketika Indonesia menggantungkan diri kepada ekonomi asing, kita menjadi ekonomi yang rentan.” serunya.
Seharusnya Indonesia memperkuat ekonomi domestik. Jadikan ekonomi Indonesia menjadi magnet ekonomi yang besar dan berputar cepat, sebuah magnet ekonomi yang bermasa besar dan berputar cepat. Karena magnet yang besar daya tariknya juga besar, sehingga orang ingin sekali berinvestasi di Indonesia. Lebih baik investasi asing masuk ke sini untuk memperkuat ekonomi domestik, daripada kita investasi di luar negeri untuk merebut ekspor.
Jadi dengan cara seperti itu kita jadikan ekonomi Indonesia sebuah magnet yang begerak cepat dan besar, sehingga ketika bertransaksi dengan ekonomi asing itu term-nya adalah cenderung menguntungkan kita. Tetapi jika kita dependent terhadap ekonomi asing, term-nya akan berbeda.
Seperti contohnya, peristiwa 11 September di New York, tragedi kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa manusia, sehingga New York menjadi sebuah tempat yang menakutkan dan mengerikan, tetapi tidak ada penurunan rating lembaga-lembaga keuangan di New York, yang terjadi adalah penurunan rating di Indonesia, karena kita magnet ekonomi yang lemah, yang jika terjadi apa-apa ditentukan oleh ekonomi asing.
Mengapa kita bisa berhubungan dengan IMF dan kita sangat tergantung dengan IMF, Itu sebabnya juga karena kita telah abai. Kita mengabaikan pentingnya ekonomi domestik, sehingga kita terjebak. Sekarang bagaimana kita merebut kemandirian kita kembali. Menurutnya, kita bisa saja keluar dari program IMF. Untuk keluar dari IMF berbeda dengan keluar dari program IMF, karena kita anggota IMF. Untuk dapat keluar dari program IMF itu ada dua pertimbangan penting yaitu apakah kita siap dari sisi moneter dan sisi fiskal. Dari sisi fiskal kuncinya adalah besarnya defisit, sepanjang defisit kita besar dan kita membiayai defisit itu dengan utang luar negeri maka kita masih butuh IMF. Kita pergi ke CGI dan kita butuh dukungan atau endorsement dari IMF.
UU Propenas menargetkan defisit sudah nol pada tahun 2004, ketika ia menjabat sebagai menteri keuangan telah mencanangkan kebijakan yang mendukung perkembangan sisi fiskal, yaitu defisit sudah mencapai nol, tax review sudah harus 16%, janjinya kepada DPR waktu itu. Sehingga itu semua diabadikan dalam UU Propenas, dan menjadi amanah undang-undang. Jadi tidak ada alasan jika tahun depan kita masih butuh eksternal financing yang di endorse oleh IMF.
Menurut undang-undang defisit kita sudah harus nol dan utang luar negeri sudah harus turun. Dari sisi moneter yang perlu kita perhatikan adalah cadangan defisa. Cadangan netto defisa kita sekarang US$ 24 miliar, ketika ia menjadi menteri itu masih sekitar US$18 miliar, jadi selama 3 tahun cadangan defisa netto kita sudah menebal US$ 6 miliar. Kalau ditambah dengan dana pinjaman dari IMF, uang pinjaman ini hanya diparkir di Bank Indonesia sebagai tambahan bantalan devisa yang sering disebut second line of defend, itu besarnya sekitar US$ 9 miliar sehingga cadangan devisa bruto kita itu di BI ada US$ 33 miliar.
Kalau kita keluar dari program IMF kita minimal harus mengembalikan sebesar US$ 3,5 miliar. Kalau kita kembalikan cadangan devisa netto kita tetap tidak berubah tetap 24 miliar sedangkan second line of defend-nya akan berkurang menjadi US$ 6.5 miliar ini berarti cadangan devisa bruto kita menjadi US$ 30,5 miliar. Jika dibandingakan pada tahun 2000 ketika ia menjadi menteri dengan cadangan devisa netto sebesar US$ 18 miliar dan cadangan devisa bruto sebesar US$ 27 miliar, jadi sebetulnya baik netto maupun bruto kita dalam dua tahun ini jauh lebih baik. Sesungguhnya tidak masalah untuk kita keluar dari program IMF.
Sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan keluarnya kita dari program IMF akan timbul masalah atau gejolak di pasar, dapat dipastikan ada terjadi. Akan ada orang-orang yang tidak percaya akan kemampuan ekonomi Indonesia untuk berdiri. Tetapi ia yakin itu hanya peristiwa yang temporer yang bisa kita lalui bersama, Karena apa? Kita sudah berkali-kali mengatasi krisis ini, dan daya tahan kita terhadap guncangan itu cukup besar. Itu bisa kita saksikan ketika krisis politik tahun 1998, bagaimana krisis politik itu mem-finalty perekonomian Indonesia, dari pertumbuhan perekonomian pada tahun 1997 sebesar 9% kemudian turun menjadi 6% dan tahun 1998 jatuh di minus 13%, tetapi pada tahun 1999 langsung mulai menjadi 0,30%. Rebound atau daya lentur ekonomi Indonesia itu luar biasa. Jadi ia percaya kita bisa keluar dari program IMF. Walaupun akan ada gejolak, namun akan dapat teratasi.
Ia tidak percaya bahwa ada suatu bangsa lain benar-benar secara tulus ingin membantu kita, semua mereka yang datang ke sini katanya membatu lewat CGI, IMF atau World Bank dan sebagainya itu, mereka mau memenuhi kepentingan mereka sendiri di Indonesia. Jadi yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Sesungguhnya permasalahannya sangat mendasar sekali berhubungan dengan sikap hidup dan sikap bernegara, dan itulah yang disebut Nasionalisme Ekonomi. Bukan berarti kita tidak mau berinteraksi dengan ekonomi asing, bukan, tetapi adalah penting sekali membangun kemandirian, dan kita menumpukan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi itu pada diri sendiri bukan kepada pihak asing.
Tiga Lapis Risiko
Sekarang ini ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang dibungkus oleh tiga lapis resiko yakni risiko sosial, risiko polkam dan risiko global. Lapisan pertama risiko sosial, lapisan sosial itu ada di dalam tubuh ekonomi Indonesia sendiri. Sumber risiko itu adalah 3 harga tadi, inilah yang menciptakan ketidakadilan ekonomi di dalam tubuh ekonomi Indonesia sendiri, dan kita didera dan terbebani oleh resiko itu sejak lama, sejak masa Orba menunjukan keberhasilannya, pada saat itu juga mereka menciptakan resiko sosial yang semakin berat itu yang disebut dengan introphy sosial sesuatu yang menggrogoti diri sendiri.
Sejak tahun 1998 dimana Orba turun, perekonomian Indonesia dibungkus oleh lapisan risiko kedua, yaitu risiko polkam yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah transisi kerangka kebersamaan politik yang tidak kunjung usai. Kerangka kebersamaan politik kita dulu diberi nama kerangka Orba, dan kita semua sudah tidak menyukai kerangka politik yang tidak adil itu. Kemudian kita ingin menggantinya, kita sudah berhasil membongkarnya tetapi kita sampai saat ini belum bisa menggantikannya dengan orde yang betul-betul penganti dari orde baru yang kita sebut reformasi dan kita sedang berada pada masa transisi yang sangat labil.
Selama masa transisi politik ini belum selesai, selama itu pula ekonomi Indonesia akan terbebani oleh risiko polkam. Sepanjang risiko polkam itu menakuti-nakuti pelaku ekonomi, yang kemudian mereka akan menahan konsumsi, mereka menahan investasi. Padahal pergerakan ekonomi dimulai konsumsi dan investasi, dan mereka tahan dan kurangi sehingga memperlambat laju ekonomi, itu sebabnya ekonomi kita hanya tumbuh 3,5%
Lapisan ketiga dari lapisan resiko perekonomian Indonesia adalah dimulai sejak September 2001 yaitu resiko global atau resiko geo-politik dan ekonomi global, terutama hal ini menonjol sejak peristiwa 11 September, di mana resiko global ini terasa sekali, seperti kasus bom Bali, berbeda dengan bom-bom yang lain, bom yang mempuyai nuansa internasional. e-ti | Atur-Yusak
Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2004-2009) / Sentuhan Politik Sang Akademisi | Ensiklopedi | Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Ketua Umum ISEI