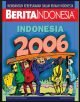Kaya Ide Rektor 20 Tahun
Michael Sastrapratedja
[DIREKTORI] Tak banyak orang jadi rektor selama 20 tahun tanpa henti dengan perguruan tinggi yang berbeda-beda. Tetapi, Prof Dr Michael Sastrapratedja SJ melakukannya. Tahun 1980-1984 sebagai Penjabat Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta; di lembaga yang sama ia diangkat sebagai ketua pada tahun 1984-1988. Tahun 1989-1993 sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, dan tahun 1993-2001 sebagai Rektor Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta.
Koleganya, Ketua STF Driyarkara Dr J Sudarminta SJ, memberi komentar, “Sampai sekarang pun masih bergaya ngrektori.” Romo Sastra-panggilannya-tak membalas sindiran itu. Katanya, “Saya punya banyak pembantu, para wakil rektor yang cekatan mengembangkan ide-ide saya.”
Dari 20 tahun jabatan rektor itu, paling mengesankan justru saat di Jakarta dan Yogyakarta. Membekas di hati koleganya, Sastra terkesan supel, egaliter, serta tak membedakan kedudukan dan jabatan. “Manusia dihargai bukan karena profesi dan kedudukan, tetapi karena kemanusiaannya,” sergahnya.
Banyak yang mencatat, kesukaan tlusab-tlusub, menurut istilah Sudarminta, juga tercermin dalam ide-ide yang menerobos dari Romo Sastra. Misalnya, saat menjabat Rektor STF, dia mengintrodusir program kajian budaya (cultural studies). Lembaga ini menarik, yang kemudian ikut memancing STF Driyarkara keluar dari “kepompong”.
Sekolah filsafat dan teologi di Rawasari itu pun menarik minat banyak orang. Tidak lagi hanya jadi tempat pendidikan calon-calon pastor, tetapi juga kaderisasi tokoh-tokoh masyarakat, terutama Katolik, bahkan mahasiswa dari agama lain.
Dibantu koleganya, seperti Alex Lanur OFM, Frans Magnis-Suseno SJ, Mudji Sutrisno SJ, dan Mardiatmadja SJ, STF semakin banyak peminat, seiring dengan gejala keinginan anak-anak muda “bercas-cis-cus” kosakata filsafat.
Kembali ke Jakarta, di kalangan rekan-rekannya Sastra disindir “pulang kandang”. Tentu dia berharap mengembangkan gagasannya tentang STF Driyarkara menjadi institut. “Dengan institut sekolah ini bisa lebih luas mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat,” kata Romo Sastra, Senin (10/3), di Kampus STF Rawasari, Jakarta.
DIANGKAT sebagai rektor bulan September 1993, dia menangani USD yang baru berganti nama dari IKIP. Kendala utama adalah bagaimana mempersatukan fakultas-fakultas sehingga tidak berkembang sebagai multiversitas, dan membangun kepercayaan-termasuk sumber dana-bahwa USD mempersiapkan pula kebutuhan guru secara lebih profesional.
Apa ide-ide menerobosnya? Dia buka Fakultas Farmasi. Seorang ahli farmasi adalah pendamping dokter. Berkat teknologi, proses pembuatan obat menjadi baku yang mengharuskan ahli farmasi melihat celah lain.
Orientasi fakultas ini adalah klien. Sekarang, kata Romo Sastra, fakultas ini menjaring paling banyak calon. Pernyataan ini sekaligus mengamini pernyataan penggantinya, Rektor USD sekarang, Dr Paul Suparno SJ.
Dia juga memboyong gagasan cultural studies dari STF Driyarkara ke Yogyakarta. Dia kumpulkan sejumlah ahli. Tercatat Arief Budiman, Amin Abdullah, dan Th Sumartana turut menyumbang gagasan pengembangan kajian budaya di USD.
“Ternyata kajian budaya saja tidak cukup. Harus diperluas,” ujarnya. Terciptalah program baru, Kajian Ilmu Religi dan Budaya (religions and cultural studies). Saat ini, lembaga yang diadopsi sebagai program gelar magister itu dipimpin Dr St Sunardi.
Sudah ada tiga angkatan, dan setiap angkatan terdiri dari 15-20 orang. Yang mengajar dan menjadi mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang, agama, dan tingkat pendidikan. Ada biksu, ulama, dan ahli media, seperti Dr Ishadi SK pun mengajar di sana.
Ide kajian agama dan budaya dilatari keinginan agar ilmu-ilmu tidak terkotak-kotak. Sepanjang sejarah, ilmu-ilmu itu tercipta lewat dialog dengan ilmu-ilmu lain. Selain lewat mata kuliah, dialog antarilmu sekaligus berarti antarbudaya itu perlu institusional yang mengintegrasikannya.
Kajian agama dan budaya diharapkan berperan. Karena persoalan agama-agama memang rumit, sewajarnya faktor integrasi itu tidak hanya budaya, tetapi juga agama. Diharapkan, dari program ini dihasilkan sejumlah ahli yang memiliki perangkat ilmiah untuk mengajarkan masalah-masalah humaniora di semua fakultas.
Di tingkat fakultas dikembangkan sarana mengajarkan humaniora di semua mata kuliah. Banyak cara bisa dilakukan. Salah satu di antaranya dengan membaca novel. “Mahasiswa teknik harus baca novel agar punya imajinasi,” katanya, sambil mengingatkan perlunya mahasiswa membaca Saman karya Ayu Utami atau Supernova karangan Dewi Lestari. Mahasiswa MIPA mendapat teori sastra seperti dari B Rahmanto M Hum.
Di USD dia kembangkan program studi kajian bahasa Inggris (English studies) berisi kajian berbagai masalah dalam bahasa Inggris. Ternyata, selain Farmasi dan Psikologi, program ini termasuk yang amat diminati calon mahasiswa. Saat ini lulusan bahasa Inggris di bawah Fakultas Keguruan USD justru lebih “laku” dibanding lulusan Inggris yang kredibel sejak lembaga pendidikan ini bernama IKIP.
Ide-ide yang menerobos dari Romo Sastra dilatari obsesinya tentang kemanusiaan (humanity). Pergulatannya dalam studi humaniora seolah-olah terkristal dalam pidato pengukuhan guru besarnya pada hari Sabtu (8/3). Judul pidatonya, Setelah Limaratus Tahun, Berakhirkah Humanisme? setebal 38 halaman dengan format buku itu, menguraikan perjalanan panjang sejarah filsafat humanisme.
Salah satu yang menarik, Sastra menyampaikan terobosan gagasan soal humanisme baru di bagian akhir pidatonya. Makna humanisme menjadi lebih kentara dan berfungsi justru pada saat diperdebatkan. Humanisme selalu harus dirumuskan kembali sesuai konteks dan perkembangan zaman.
Karena itu, humanisme baru memiliki ciri, hasil dari sebuah dialog antarbudaya sehingga filsafat tidak lagi sebagai pemegang palu norma-norma melainkan penafsir zaman, punya tanggung jawab moral, emansipatorik, sehingga humanisme itu menghargai dan mengembangkan demokratisasi. Semuanya didasari nilai-nilai yang tetap dan harus terus dipegang, yakni penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Humanisme sekarang dan di Indonesia semakin relevan karena ada gejala masyarakat melepaskan faktor moralitas dan hubungan antarmanusia. Tanggung jawab moral diabaikan dengan alasan sesuai prosedur. Seseorang divonis salah, namun tak mau mundur dari jabatan karena tak ada aturan harus mundur. “Tanggung jawab moral diganti prosedur.”
Lahir sebagai Subiyanto di Yogyakarta, 22 Oktober 1943, di urutan ketiga dari 10 saudara keluarga Sastrapratedja, banyak artikel dan buku dia terbitkan; terbaru, Agama dan Tantangan Masa Kini (2002), tentu bukan karya terakhirnya.
Bukan tidak mungkin gagasan-gagasan yang diwujudkan dalam pengembangan tiga universitas, terutama USD, dituangkan dalam uraian yang komprehensif.
Ya, mengapa tidak? Ya, kata doktor ilmu filsafat (politik) lulusan Universitas Gregoriana (1979) ini. St Sularto, Repro Kompas, Sabtu 15 Maret 2003