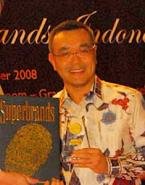Negara Sebagai Arena
Indria Samego
[DIREKTORI] Konsolidasi demokrasi itu ternyata lebih mudah diucapkan ketimbang dipraktekkan. Khususnya untuk Indonesia, bayangan tentang sebuah masa pasca transisi yang menjadikan Indonesia –baik negara maupun rakyatnya– semakin kuat, bukannya kian konkrit melainkan makin kabur. Kendati lembaga dan prosedur demokrasi sudah banyak diciptakan, kekhawatiran tentang akan adanya pembalikan (reversed) atas kecenderungan politik yang terjadi akhir-akhir ini, bukannya tanpa alasan.
Pertama, rakyat memang sudah mendapatkan hak politiknya yang paling mendasar, yakni menentukan siapa yang paling tepat untuk menjadi pemimpin mereka. Dimulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung tahun lalu, dan akan segera menyusul pemilihan kepala daerah. Ini membuktikan bahwa komitmen untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sudah bukan mimpi lagi. Akan tetapi, apa makna dari suara rakyat bagi efektivitas sebuah pemerintahan, nampaknya masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Pada tingkat nasional, barangkali kita secara relatif sudah menyaksikan manfaat dari pemilihan presiden langsung tersebut.
Dengan semakin lemahnya gugatan publik terhadap kepemimpinan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, dapat ditafsirkan bahwa keduanya telah berupaya mentransformasikan mandat rakyat ke dalam kebijakan pemerintah sehari-hari. Walau pun masih pada tataran simbolisme politik, sejauh ini, pemimpin baru Indonesia tersebut, sudah berupaya untuk mendekatkan diri dengan rakyat yang dipimpinnya.
Masalahnya akan lain buat kepala daerah mendatang. Muncul kekhawatiran di sana-sini bahwa yang terpilih kemudian adalah mereka yang sekedar popular dan punya uang. Karena mahalnya pemilihan kepala daerah, maka hanya mereka yang kayalah yang akan terpilih. Konsekuensi selanjutnya, akan lebih banyak berpikir bagaimana mengembalikan modal ketimbang menjalankan fungsi pemerintahan ketika kemenangan itu sudah diraihnya.
Kedua, partai politikpun telah mendapatkan kebebasannya untuk lahir, berkembang serta mencari pendukung. Kehadiran sejumlah partai politik yang mewamai lembaga perwakilan rakyat telah menjadikan sistem multi partai sebagai sebuah keniscayaan terjadinya konsolidasi demokrasi. Yang menjadi masalah, apakah sistem kepartaian kita sudah dapat dijadikan modal bagi upaya-upaya konsolidasi demokrasi selanjutnya.
Mengingat miskin programnya partai, dan kelemahan finansial para fungsionarisnya, dikhawatirkan partai politik dibentuk hanya sekedar untuk batu loncatan para pendirinya (vertical mobility), bukan sebagai alat perjuangan. Kita sering mendengar betapa mahalnya sebuah kongres atau muktamar digelar, tapi hasil konkritnya, selain rekrutmen politik, tidak ada. Ada kecurigaan, kegiatan partai politik hanya terfokus di sana, dan dana dengan sekuat tenaga dicari untuk itu.
Setelah hajat selesai, masing-masing kembali memikirkan kepentingan pribadi, termasuk mengembalikan dana yang telah disumbangkan untuk kegiatan partai di atas. Ini tentu sebuah agenda yang sangat elitis, dan jauh dari kepentingan masyarakat pendukung partai.
Ketiga, belakangan muncul berbagai lembaga yang dianggap mewakili kepentingan civil society. Mulai dari Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsmen, Komisi Hak Azasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum sampai ke Komisi Yudisial, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta Komisi Kepolisian Nasional yang sedang diproses. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang akan menghidupi semua komisi tersebut? Jawabannya pasti adalah negara. Nah, ini ironinya, organisasi yang mestinya mengambil jarak dari negara, ternyata mengandalkan sumber dananya dari negara. Dimana kita bisa berharap banyak terhadap independensi mereka?
Ketiga renungan di atas menggaris-bawahi pikiran kita, bahwa pada akhimya kita kembali mengharapkan dukungan negara dalam merealisasikan keinginan publik, termasuk mewujudkan apa yang disebut sebagai konsolidasi demokrasi. Barangkali karena itulah maka Menteri Dalam Negeri pun menganggap Pilkada bukan sebagai pemilihan umum ansich, melainkan bagian dari proses pembinaan bangsa.
Dalam konteks ini, negara memang sangat berkepentingan untuk memperjuangkannya. Selain menyediakan dana yang diperlukan, secara politis juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kehidupan politik yang kondusif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Perdebatan mengenai boleh tidaknya anggota TNI menjadi calon dalam Pilkada, merupakan salah satu contoh konkrit dari kepedulian pemegang kekuasaan sekarang. Karena khawatir akan munculnya pemimpin daerah yang asal menang dalam pemilihan, maka persyaratan untuk mencalonkan diri pun dikendorkan.
Kecurigaan birkorasi terhadap kekuatan non-birokrasi dalam penyelenggaraan negara kian mencuat, manakala kita mendengar kasus suap Mulyana terhadap personil BPK, dan pembagian dana taktis di kalangan anggota KPU belakangan ini. Semula diharapkan bahwa lembaga yang didukung oleh para tokoh yang non-partisan ini mampu menciptakan citra positif mengenai adanya kekuatan relatif (relative autonomy) di kalangan mereka dalam menghadapi berbagai tekanan dan pengaruh kepentingan.
Ternyata, pertahanan diri mereka jebol juga menghadapi pengaruh uang. Meski secara hukum mesti dibuktikan terlebih dahulu, tapi opini publik sudah diarahkan pada praktek-praktek primitif dalam distribusi rejeki di sana. Lantas apa bedanya mereka dengan birokrat dan politisi korup, yang sering dijadikan sasaran kritikan para akademisi.
Hal yang sama juga muncul di kalangan TNI terhadap kekuatan sipil yang seolah-olah ingin menggantikan posisi tentara dalam politik. Bahwa tentara tidak lagi boleh berpolitik praktis dan memiliki wakilnya di DPR, ini sudah terbukti. Namun seberapa jauh TNI yakin bahwa pihak sipil akan membawa republik ini ke jalan yang benar, dan melindungi semua kepentingan, termasuk TNI di dalamnya, masih menjadi tanda tanya mereka.
Perdebatan mengenai masa depan bisnis TNI, misalnya, salah satunya disebabkan oleh kecurigaan tersebut. Selain karena tidak mudah untuk mendefinisikan secara operasional, serta memilah-milah kriterianya, yang terlebih penting adalah seberapa jauh pihak sipil dapat memberi jaminan bahwa pengalihan tersebut akan berdampak positif baik bagi bangsa maupun TNI. Mengingat begitu buruknya wajah sebagian besar BUMN kita, masuk akal pula bila sampai sekarang persoalan ini belum disentuh secara memuaskan.
Sebenarnya, kunci menuju konsolidasi demokrasi akan lebih mudah dilakukan bila apa yang disebut sebagai civil society sudah benar-benar tumbuh di sini. Mereka sungguh mandiri dan mengambil jarak dari negara di dalam menjalankan perannya. Tidak seperti sekarang, negara dijadikan arena atau bahkan terjad personalisasi negara di dalamnya. Akibatnya, terjadilah bancakan di antara semua aktor politik yang ingin mewamai perubahan negara.
Semuanya menyatakan diri paling berhak. Semuanya tergantung pada negara. Dengan kata lain, selama pembagian kerja dan diferensiasi struktur masih terbatas dan sangat timpang ke negara, rasanya agak sulit buat kita untuk menghela perahu transisi ini. Jangan-jangan, jika salah kayuh, bukan konsolidasi demokrasi yang muncul melainkan kebalikannya, yakni anarki dari masa ke masa. e-ti
***TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
* Disampaikan pada Diskusi bulanan CIDES (Center for Information and Development Studies), Selasa 20 September 2005 mengambil tema “Ekonomi Tumbuh Tetapi Rentan”, menghadirkan tiga orang pembicara yaitu M. Fadhil Hasan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Umar Juoro Ketua Dewan Direktur CIDES, serta Indria Samego Anggota Dewan Direktur CIDES. Berikut ini salinan lengkap makalah yang dibawakan oleh Umar Juoro, yang banyak menyoroti permasalahan ekonomi makro yang sedang aktual berkembang di tanah air.