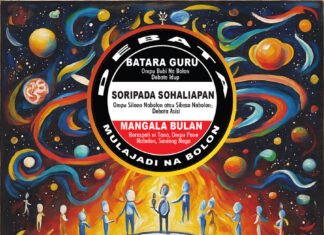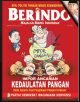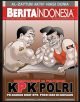Menolak Diam: Perlawanan Sunyi terhadap Civilphobia

Kita hidup di masa ketika keberanian untuk bersuara semakin langka, dan diam perlahan menjadi norma yang diterima.
Ketika suara rakyat dicurigai dan kritik dibingkai sebagai ancaman, diam menjadi pilihan yang dianggap aman. Tapi tidak semua memilih jalan itu. Masih ada suara-suara kecil yang menolak padam – datang dari para jurnalis independen, mahasiswa di jalanan, dan elemen sipil yang terus bersuara meski tak diliput kamera. Perlawanan mereka tidak selalu riuh, tapi justru karena sunyinya itulah ia mencerminkan keberanian yang utuh. Ini bukan tentang suara keras, melainkan tentang kesetiaan pada suara nurani. Ketika civilphobia menjangkiti negara dan sebagian sipil ikut membungkam sesamanya, merekalah yang mengingatkan bahwa demokrasi tak lahir dari kesepakatan untuk diam.
Keberanian mereka berdiri di tengah iklim politik yang kian tidak ramah terhadap kritik. Dewan Perwakilan Rakyat kini tak lagi mewakili kegelisahan rakyat. Mereka membisu saat publik mempertanyakan revisi Undang-Undang TNI yang dibahas di balik pintu tertutup. Mereka menoleh ke arah lain saat demonstrasi damai dibalas dengan tindakan represif. Mereka tak bersuara ketika mahasiswa dibungkam. Sebagian menyebutnya kehati-hatian politis. Tapi publik paham, ini bukan soal strategi. Ini soal keberanian yang hilang – tentang nurani yang memilih diam karena terlalu nyaman berada dekat kekuasaan.
“Satu cahaya kecil bisa mengganggu seluruh gelap yang nyaman.” – TokohIndonesia.com
Dengan 470 dari 580 kursi DPR (atau 8 dari 10 anggota parlemen) dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah, ruang kritik di parlemen nyaris sirna. Demokrasi kehilangan oposisinya. Ruang yang seharusnya menjadi arena penyeimbang kekuasaan berubah menjadi paduan suara yang menyuarakan satu nada: dukung, bukan koreksi. Di tengah dominasi itulah civilphobia tumbuh subur – ketakutan sistemik terhadap suara rakyat sendiri.
Yang menyedihkan, ini bukan hanya soal kekuasaan yang menumpulkan suara kritis. Gejala civilphobia kini juga menjangkiti sebagian kalangan sipil itu sendiri. Mereka yang dulu berdiri sebagai benteng kritik perlahan mulai ikut diam. Bahkan ada yang ikut dalam barisan para buzzer, menyebarkan narasi tandingan terhadap kritik masyarakat. Saat tagar #IndonesiaGelap muncul sebagai bentuk protes, bukan hanya buzzer kekuasaan yang menyerang. Tapi juga sebagian kalangan jurnalis, aktivis, bahkan akademisi yang ikut menyebarkan tagar #IndonesiaTerang – bukan sekadar membantah, tapi menyerang balik mereka yang bersuara.
Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk baru dari pragmatisme sipil? Ataukah sekadar strategi bertahan dalam iklim yang tidak lagi ramah pada perbedaan pendapat?
Bisa jadi, sebagian dari mereka lelah. Merasa kritik tak lagi membawa perubahan. Bisa juga karena tekanan ekonomi, relasi dengan donor, atau perhitungan reputasi. Tapi satu hal pasti: demokrasi tidak tumbuh dari keheningan. Ia hidup dari suara – yang bahkan ketika tak didengar, tetap memilih untuk disuarakan.
Pers, yang dulu menjadi anjing penjaga demokrasi, kini lebih sering tampak sebagai hewan peliharaan kekuasaan. Banyak berita yang terasa seperti perpanjangan lidah pemerintah. Banyak redaksi lebih khawatir soal relasi bisnis daripada soal kebenaran jurnalistik. Sementara jurnalis-jurnalis muda kini dididik untuk hati-hati, bukan untuk kritis. Tapi di tengah kelesuan itu, masih ada media yang bertahan, menolak diam. Dan di antara yang paling bersuara lantang, ada Narasi Newsroom.
Narasi tidak sekadar meliput peristiwa, tapi menjadi bagian dari nalar publik yang resisten terhadap lupa dan kompromi. Saat isu revisi RUU TNI bergulir secara diam-diam, Narasi memberi ruang luas untuk suara masyarakat sipil, menghadirkan laporan investigatif, dan mengangkat wajah-wajah mahasiswa yang terluka bukan hanya oleh gas air mata, tapi juga oleh ketidakpedulian sistem. Mereka memilih tetap bersuara ketika banyak media memilih diam. Mereka menayangkan testimoni, analisis, hingga laporan lapangan – bukan untuk sensasi, tapi untuk menjelaskan bahwa kritik bukan ancaman, melainkan panggilan akal sehat. Tidak sekadar menyampaikan kabar, tapi mempertahankan ruang untuk bertanya agar publik jadi paham.
“Ia berdiri sendiri, bukan karena ingin jadi pahlawan. Tapi karena diam bukan pilihan.” – TokohIndonesia.com
Selain Narasi, beberapa media juga turut menjaga denyut kritik di ruang publik. Tempo, misalnya, secara konsisten mengulas sisi gelap dari proses legislasi dan memberikan panggung pada suara-suara sipil. Kompas dan Media Indonesia juga menyoroti aksi demonstrasi dan mengungkap kekhawatiran masyarakat terhadap kembalinya dwifungsi TNI. CNN Indonesia menyajikan peta lengkap kritik terhadap revisi RUU TNI, memperlihatkan bahwa keberatan publik bukan soal teknis hukum, tapi tentang arah demokrasi yang sedang diambil negara ini.
Dalam lanskap yang seperti ini, kita melihat bahwa civilphobia di Indonesia bukanlah gejala baru. Ia berevolusi dari era ke era. Di masa Orde Baru, ia muncul dalam bentuk paling telanjang: pembredelan, pelarangan, penangkapan. Di era Reformasi, ia tampil lebih elegan: framing media, narasi “ditunggangi”, hingga perundang-undangan yang membatasi ruang kritik. Kini, di era digital, civilphobia menyebar sebagai narasi: bahwa demo dibayar, bahwa protes adalah noise, bahwa kritik adalah hambatan pembangunan, bahwa semua suara yang berbeda pasti punya motif tersembunyi, bahwa ketertiban lebih penting dari kebebasan.
Menurut laporan SAFEnet dan KontraS, sepanjang 2024, terjadi lebih dari 180 pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi – baik terhadap aktivis, jurnalis, maupun mahasiswa. Dalam aksi penolakan RUU TNI pada Maret 2025, lebih dari 80 orang terluka, 161 ditangkap, dan 18 jurnalis menjadi korban kekerasan. Ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan dari negara yang belum selesai berdamai dengan warganya sendiri.
Sejarah sudah mencatat bahwa demokrasi yang membungkam rakyat akan selalu dipaksa untuk mendengar, cepat atau lambat. Ketika parlemen berubah menjadi ruang gema kekuasaan dan menjadi “tukang stempel” kebijakan rezim, ketika media mainstream sibuk menjaga relasi, ketika aktivis mulai mempertimbangkan ketenaran, suara-suara kecil dari lorong kampus dan ruang redaksi independenlah yang justru menjaga agar demokrasi tetap bernapas.
Kini, kita kembali ke pertanyaan mendasar: siapa yang akan membongkar ketakutan civilphobia itu?
Jawabannya tidak datang dari menara kekuasaan. Ia datang dari bawah – dari ruang-ruang kelas, dari berita-berita yang tak tayang di prime time, dari mahasiswa yang tetap turun ke jalan, dari jurnalis yang tetap menulis walau tak populer. Mereka tidak dibayar untuk itu. Mereka hanya percaya, bahwa demokrasi layak untuk diperjuangkan.
Merekalah penjaga demokrasi yang tersisa. Merekalah alasan mengapa kita masih bisa berharap. Dan merekalah yang membuat demokrasi kita, meski goyah, belum sepenuhnya kehilangan rumah. Dan bahwa suara rakyat, meski pelan, tak pernah layak untuk dibungkam. (Atur Lorielcide/TokohIndonesia.com)