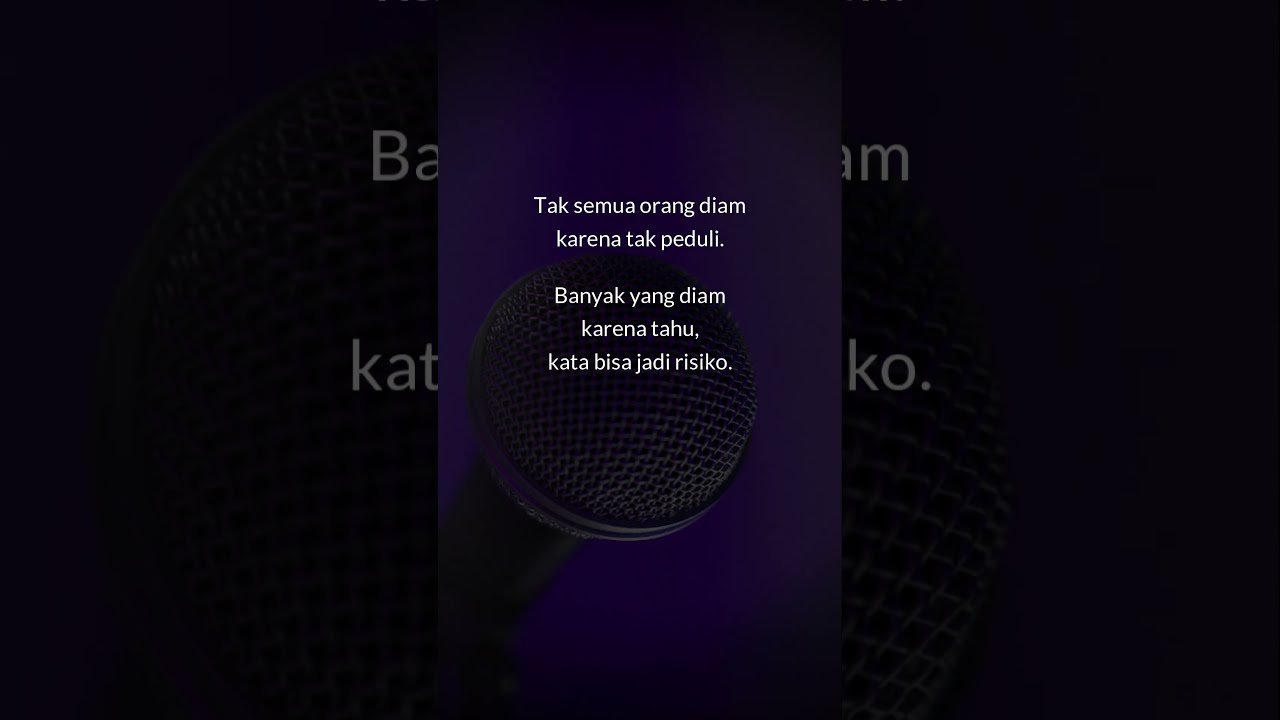Cara Halus Membungkam Suara
Dari penangkapan simbolik hingga hukum yang tumpul ke atas
Tidak semua orang diam karena setuju. Banyak yang diam karena tahu: ucapan bisa menjadi risiko.
Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian Lorong Kata yang membedah relasi kekuasaan, kritik, empati publik, dan pengaruh algoritma digital dalam demokrasi Indonesia:
- Kemarahan yang Sah. Menegaskan bahwa protes rakyat bukan gejala anarki, melainkan bentuk akumulasi luka akibat pengabaian.
- Ciri Orang Tolol Sedunia. Membongkar ironi ketika wakil rakyat mencemooh suara publik, dan bagaimana kata bisa jadi sumber delegitimasi.
- Ketika Rakyat Dianggap Bawahan. Melihat lebih jauh: bukan hanya pada insiden, tapi pada logika kekuasaan yang menyuburkan ketimpangan relasi.
- Affan Dilindas, Tanggung Jawab Menguap. Menunjukkan bagaimana tragedi rakyat sering hanya dijawab dengan ucapan duka dan janji bantuan, tanpa tanggung jawab politik yang nyata.
- Cara Halus Membungkam Suara. Mengurai taktik halus kekuasaan membatasi kritik publik, bukan dengan larangan eksplisit, melainkan dengan atmosfer takut.
- Catatan untuk Para Pengecut Digital. Mengungkap bagaimana sensor modern tidak lagi datang dari larangan, tapi dari algoritma yang memilih diam, dan platform yang tunduk bahkan sebelum ditundukkan.
- Epilog: Yang Tak Didengar. Merangkum ironi yang mengikat semuanya: bagaimana suara rakyat, dalam berbagai bentuknya – amarah, kritik, penderitaan, atau ingatan – terus disepelekan, dibungkam, atau dipastikan tak bergema.
Dalam beberapa pekan terakhir, publik melihat bagaimana seorang influencer bisa ditahan hanya karena siaran langsung, sementara kesalahan pejabat publik sering selesai dengan permintaan maaf. Hukum yang mestinya melindungi justru terasa lebih cepat menekan ke bawah, sekaligus lebih longgar ke atas.
Demokrasi mestinya memberi ruang untuk berbeda, namun yang terasa hari ini justru sebaliknya: ruang itu makin menyempit. Kita masih bisa bicara soal sepak bola, kuliner, atau gosip selebriti tanpa beban. Tapi ketika percakapan menyentuh isu politik, suasana berubah. Suara diturunkan, tatapan saling cek, lalu topik diganti.
Perubahan ini bukan karena publik mendadak apatis, melainkan karena rasa waswas yang makin kuat. Seorang mahasiswa pernah berbisik di sebuah diskusi kecil: “Kami masih mau turun ke jalan, tapi takut nanti ditandai. Lebih aman kalau diam.” Kalimat sederhana itu lebih jujur daripada seribu data: minat tidak hilang, rasa aman yang menyusut.
Tidak ada pasal baru yang terang-terangan melarang. Tidak ada pembredelan terbuka. Tetapi ruang yang dulu leluasa kini dipenuhi kehati-hatian: kalimat disaring sebelum diucapkan, unggahan ditahan sebelum diposting. Ini bukan soal apa yang dilarang, melainkan apa yang pelan-pelan dipelajari publik untuk tidak dilakukan.
Atmosfer seperti ini tidak butuh maklumat. Ia terbentuk dari sinyal yang diulang, contoh yang dipertontonkan, dan reaksi publik yang kian jinak. Jika dicermati, ada setidaknya lima cara halus membungkam suara, bukan lewat larangan, melainkan lewat pembiasaan yang membuat keberanian surut.
-
Penangkapan simbolik, publikasi maksimal
Tak perlu menyasar semua orang. Cukup satu-dua sosok dijadikan contoh dan diberitakan luas. Ketika Delpedro Marhaen ditangkap dengan label “dalang demo”, publik membaca pesan yang sama: siapa pun dapat dicap penghasut. Pola ini tegas terlihat pada kasus Laras Faizati, pemilik akun dengan sekitar empat ribu pengikut, yang dijadikan tersangka karena unggahannya dinilai menghasut membakar Mabes Polri. Begitu pula seorang influencer yang ditetapkan tersangka setelah siaran langsung mengajak pelajar ikut aksi. Otoritas tak perlu menyasar tokoh besar, cukup individu kecil untuk menciptakan efek jera. Pesannya jelas: kalau mereka saja bisa dibawa, apalagi kamu.
-
Tuduhan tanpa wajah
“Dalang”, “aktor asing”, “penyusup”, label yang sering terdengar namun jarang disertai nama dan bukti. Tujuannya bukan memperjelas, melainkan menanamkan ragu: siapa yang dapat dipercaya? Dampaknya, aktivis saling menjaga jarak, diskusi mengeras, dan publik menahan diri bukan karena bersalah, melainkan untuk menghindari terseret framing yang sulit dibantah.
-
Sensor yang tak terlihat, swasensor yang tumbuh
Tidak semua konten harus dibekap. Cukup beberapa contoh keras: akun diturunkan, pembuat konten dipanggil, lalu masyarakat akan belajar menahan diri. Seperti di ruang kelas: satu murid dihukum di depan, yang lain paham untuk tidak mencoba hal serupa. Definisi “konten salah” tidak pernah jelas; justru ketidakjelasan itulah yang membuat orang berhitung.
-
Kekerasan aparat yang dibiarkan, bukan disanksi
Ketika kekerasan terjadi dan tidak ada akuntabilitas, pesannya bukan “hukum tegak”, melainkan “yang kuat aman.” Kasus Affan Kurniawan, warga yang tewas saat kendaraan taktis melintas, disusul ucapan duka dan janji bantuan, tetapi tanpa tanggung jawab politik yang nyata. Ibarat lampu lalu lintas dibiarkan rusak: aturan terasa hanya untuk yang lemah, sementara yang kuat melaju tanpa konsekuensi.
-
Narasi aman untuk yang diam
“Kalau tidak salah, kenapa takut?” terdengar menenangkan, namun di lapangan kalimat itu mengesahkan pilihan untuk bungkam. Perlahan, diam dianggap satu-satunya cara aman; keterlibatan dibaca sebagai masalah; solidaritas rawan dipelintir. Pada titik itu, publik bukan hanya takut pada negara, melainkan juga pada sesamanya. Demokrasi melemah bukan karena dibekukan, melainkan karena keberanian sosial dihabiskan sedikit demi sedikit.
Pola ini bukan baru. Di masa Orde Baru, tidak semua kritik dilarang, tetapi semua orang paham garis tak terlihat: jangan terlalu keras, jangan terlalu menonjol. Reformasi meruntuhkan banyak pagar, namun logika pengendalian tak serta-merta hilang, ia beradaptasi dengan prosedur.
Kecenderungan serupa tampak di tempat lain. India, Turki, Rusia, semuanya masih menyebut diri demokrasi, namun suara yang mengusik cenderung disisihkan melalui jalur hukum dan narasi keamanan. Pemilu tetap ada, parlemen tetap bekerja, tetapi ruang percaya antara warga dan negara menyempit.
Kita berada di persimpangan yang sama. Secara formal, hak berbicara ada; secara faktual, atmosfernya tidak mendukung. Bila warga mulai menghitung risiko sebelum berpendapat, demokrasi kehilangan fungsi utamanya: membuat orang yakin bahwa pendapatnya bukan ancaman.
Ironinya, ketegasan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat biasa cepat dijerat, sementara pejabat publik atau aparat yang keliru sering cukup meminta maaf, kasus bergeser menjadi “klarifikasi”. Seorang influencer bisa ditahan karena siaran langsung, tetapi kekeliruan otoritas kerap selesai di podium konferensi pers. Di sini hukum berubah fungsi: dari pelindung keadilan menjadi alat menekan, sambil melindungi ke atas.
Semua ini: penangkapan contoh, label kosong, sensor samar, impunitas, dan normalisasi diam, adalah cara halus membungkam suara. Tidak dengan larangan, melainkan dengan rasa takut yang diajarkan lewat sinyal berulang. Bila rasa takut lebih berkuasa daripada keberanian berbicara, demokrasi kehilangan artinya.
Demokrasi yang sehat tidak menuntut keseragaman, melainkan ruang untuk berbeda tanpa dihukum. Kita mungkin tidak bisa menghapus risiko, tetapi kita selalu bisa menolak kebiasaan untuk bungkam. Sebab jika publik berhenti bersuara, yang hilang bukan hanya kritik, melainkan juga kemampuan negara untuk memperbaiki diri. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)
Tulisan ini juga hadir dalam format visual 60 detik di Instagram.
Lihat versi reels-nya di akun @rielniro: Cara Halus Membungkam Suara.