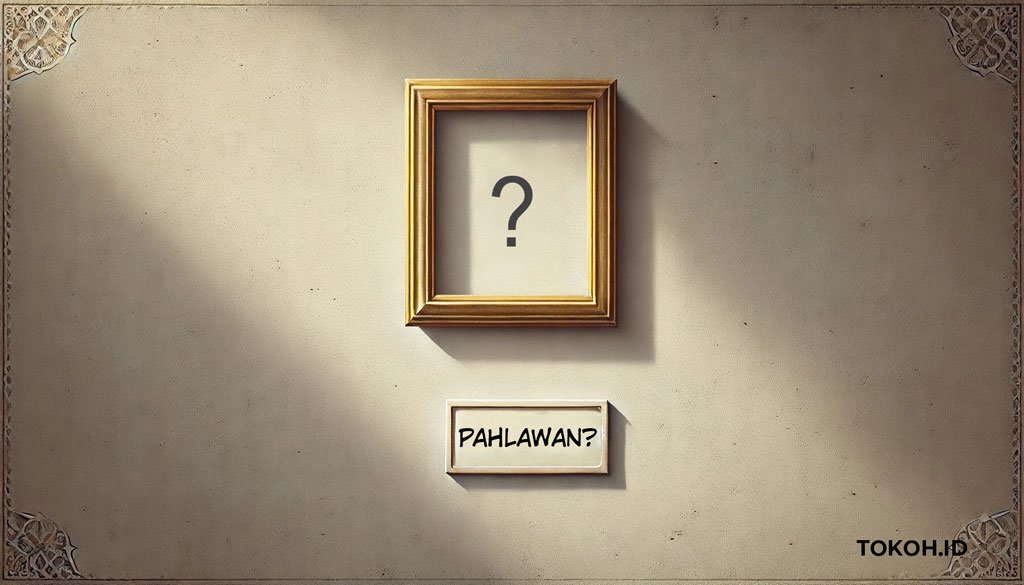Kalau Soeharto Pahlawan, Untuk Apa Dulu Kita Berjuang?
Antara Ingatan, Luka, dan Gelar Kehormatan
Ketika nama Soeharto kembali diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, yang diguncang bukan hanya nalar publik, tapi juga nalar sejarah. Untuk apa ada Reformasi 1998 jika tokoh yang ditumbangkan karena simbol otoritarianisme kini hendak dipuja sebagai teladan bangsa? Sebab tidak semua yang besar layak dikenang dengan kebesaran pula. Ada yang cukup dikenang sebagai pelajaran — agar bangsa ini tahu apa yang tidak boleh diulang.
Dalam sejarah bangsa, ada nama-nama yang menjulang tinggi, mengisi buku pelajaran, disebut dalam pidato kenegaraan, bahkan diabadikan pada nama jalan dan museum. Namun tidak semua nama besar berdiri di atas landasan yang kokoh. Ada tokoh-tokoh yang berdiri di tengah simpang nilai – di antara jasa dan luka, antara pembangunan dan represi, antara kekaguman dan pertanggungjawaban. Soeharto adalah nama yang memaksa bangsa ini untuk memilih cara mengingat: dengan penghormatan, atau dengan kejujuran.
Ia memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Ia menciptakan stabilitas di tengah pusaran konflik. Ia membangun infrastruktur, mengangkat swasembada pangan, dan membawa Indonesia ke panggung internasional. Ia juga dikenal dalam sejarah militer — Serangan Umum 1 Maret dan pembebasan Irian Barat tak bisa dilepaskan dari perannya. Tapi sejarah, sejatinya, bukan hanya tentang keberhasilan yang tampak. Ia juga soal apa yang dikorbankan untuk mencapainya.
Karena itu, ketika nama Soeharto kembali diajukan sebagai calon Pahlawan Nasional, muncul keraguan, kekhawatiran, dan pertanyaan. Ini bukan pertama kalinya nama itu diusulkan. Sejak 2010, Soeharto sudah berkali-kali diajukan oleh berbagai pihak, mulai dari kelompok masyarakat di Jawa Tengah hingga Partai Golkar yang mengusungnya dalam Munaslub 2016. Presiden Prabowo Subianto, menantu Soeharto, sudah menyuarakan dukungan pada saat kampanye pilpres 2014 dan 2019. Setelah ia terpilih menjadi Presiden pada 2024, tekanan politik untuk memuliakan nama Soeharto kembali menguat. Puncaknya terjadi pada 23 September 2024, ketika MPR mencabut nama Soeharto dari Tap MPR No. 11/1998 tentang pemberantasan KKN. Langkah itu membuka jalan simbolik: nama Soeharto tidak lagi menjadi beban sejarah, tetapi justru mulai ditulis ulang sebagai potensi kehormatan.
Bulan Maret 2025, Kementerian Sosial menerima pengusulan resmi dari Bambang Sadono Center di Jawa Tengah. Nama Soeharto masuk dalam daftar sepuluh tokoh yang dibahas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Dukungan pun mengalir, mulai dari Partai Golkar, beberapa pejabat negara, hingga lingkaran istana. Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan, “Bangsa ini harus belajar menghormati para pemimpinnya. Jangan hanya melihat kekurangannya.” Ia menegaskan bahwa Soeharto berjasa besar dan layak diberi tempat di hati bangsa.
Tapi benarkah sekadar jasa cukup untuk mendapat gelar pahlawan? Dan lebih penting lagi: untuk apa ada Reformasi 1998 jika akhirnya tokoh yang digulingkan karena simbol kekuasaan yang represif dan koruptif kini hendak dijadikan pahlawan nasional?
Jika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan, bagaimana kita akan menjelaskan pada anak-anak sekolah tentang makna dari demonstrasi besar-besaran, tuntutan reformasi, dan korban yang berguguran pada 1998? Akan ada disonansi moral yang tak terhindarkan dalam pendidikan karakter bangsa. Mereka akan bertanya, apakah memperjuangkan kebenaran itu penting, jika pada akhirnya sejarah mengganjar yang ditolak dengan penghormatan tertinggi?
Sebab Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian pemimpin. Ia adalah letupan nurani nasional. Ia adalah gugatan rakyat terhadap kekuasaan yang mengakar terlalu lama dan terlalu dalam. Soeharto dijatuhkan bukan karena semata-mata krisis ekonomi, tapi karena akumulasi represi, pelanggaran HAM, dan praktik korupsi yang membudaya. Komnas HAM mencatat 12 pelanggaran HAM berat terjadi di masa Soeharto. Pembantaian pasca-1965 yang menewaskan ratusan ribu orang. Operasi Petrus di awal 1980-an. Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, penghilangan aktivis 1997–1998. Kekerasan di Timor Timur. Dan tentu, kerusuhan Mei 1998 yang memakan korban jiwa dan melukai kepercayaan warga Tionghoa.
Tak hanya itu, Soeharto sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi tujuh yayasan oleh Kejaksaan Agung tahun 2000. Negara memenangkan gugatan terhadap Yayasan Supersemar dan memerintahkan pengembalian dana ratusan miliar rupiah. Namun hingga kini, tidak semua dana kembali, dan proses hukum berhenti karena alasan kesehatan.
Apakah fakta-fakta ini cukup diabaikan hanya karena kita ingin menghargai jasa? Gelar Pahlawan Nasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2009, bukan hanya soal kontribusi. Ia mensyaratkan integritas moral, keteladanan, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Maka pertanyaan bukan hanya soal kelayakan, tetapi juga soal kejujuran kita dalam membaca sejarah.
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya membuka luka lama, tetapi juga membingungkan arah moral bangsa. Jika tokoh yang ditolak oleh rakyat dijadikan simbol kehormatan, maka reformasi kehilangan makna. Ia menjadi catatan kaki, bukan tonggak sejarah. Maka tak heran jika penolakan datang dari banyak pihak. KontraS, IKOHI, GEMAS, dan SETARA Institute menyuarakan keberatan.
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyebut usulan ini sebagai bentuk pemutihan sejarah. “Ini pelecehan terhadap korban,” kata mereka. SETARA Institute menilai pemberian gelar ini bisa menjadi preseden impunitas — seolah-olah kesalahan besar bisa dihapus hanya dengan membandingkannya dengan prestasi. IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) menyatakan bahwa langkah ini menyakitkan bagi keluarga korban yang sampai hari ini belum tahu ke mana anak mereka dibawa. Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut langkah ini sebagai pengabaian terhadap prinsip moral yang terkandung dalam Undang-Undang Gelar Kehormatan. “Syarat moral dan keteladanan jelas tak terpenuhi,” ujarnya. JJ Rizal lebih tegas lagi: jika Soeharto diberi gelar, itu artinya sejarah bisa diputar balik jika politik berkuasa.
Di sisi lain, suara pro terus bergema. Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa setiap pemimpin layak dihargai. Presiden melalui jubirnya, Prasetyo Hadi, mendorong publik untuk memandang jasa. Sejarawan Agus Suwignyo menyarankan agar jika pun gelar diberikan, sebaiknya dalam kerangka jasa militer yang lebih terbatas.
Bangsa ini sedang diuji bukan soal siapa yang pantas dikenang, tapi soal bagaimana kita mengenangnya. Kita bisa saja menghargai jasa tanpa mengabaikan luka. Kita bisa memberi tempat pada tokoh besar tanpa menyebutnya pahlawan. Tapi gelar Pahlawan Nasional bukan tempat kompromi sejarah. Ia bukan tentang kebesaran kekuasaan, tetapi tentang keteladanan nilai.
Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka satu pertanyaan harus dijawab dengan jujur: apa gunanya Reformasi 1998? Apa gunanya mahasiswa turun ke jalan, air mata tumpah, darah tergenang, jika akhirnya simbol kekuasaan yang dilawan kini disucikan dengan gelar tertinggi?
Barangkali, lebih dari apa pun, yang harus kita pertanyakan adalah: apakah kita bangsa yang belajar dari luka, atau bangsa yang pandai mengemas luka menjadi piagam?
Gelar pahlawan bukan soal seberapa besar pengaruh yang ditinggalkan, apalagi seberapa lama seseorang memegang kekuasaan. Ia adalah tentang keberanian moral — tentang siapa yang mampu berdiri di sisi nilai, bahkan ketika itu berarti melawan arus kekuasaan.
Maka sebelum kita tetapkan nama, sebelum piagam kehormatan itu dicetak dan ditabalkan, mari kita tanya pada diri sendiri: sudahkah kita menyembuhkan ingatan? Sudahkah kita memberi ruang kepada suara mereka yang hilang, mereka yang tak pernah sempat kembali, mereka yang tak pernah diminta maaf?
Ada nama-nama yang besar dalam sejarah, tapi tidak semua harus ditinggikan dengan kebesaran pula. Beberapa cukup dikenang sebagai pelajaran — agar bangsa ini tahu apa yang tidak boleh diulang. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)
INFORMASI TAMBAHAN
🏅 Syarat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional (UU No. 20 Tahun 2009)
Berikut adalah tabel berisi syarat-syarat pemberian gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, khususnya yang relevan untuk menilai kelayakan seorang tokoh:
| No. | 📌 Kriteria | 📖 Penjelasan |
| 1 | Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia | Hanya tokoh yang sudah wafat yang bisa diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. |
| 2 | Telah berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara | Jasa harus bersifat nasional dan berdampak besar terhadap kehidupan bangsa dalam berbagai bidang. |
| 3 | Memiliki integritas moral dan keteladanan | Tokoh harus menjadi panutan publik dalam sikap hidup, perilaku, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. |
| 4 | Tidak pernah melakukan perbuatan tercela | Termasuk tidak terlibat korupsi, pelanggaran hukum, atau pelanggaran HAM. |
| 5 | Tidak pernah mengkhianati negara | Termasuk tidak terlibat dalam upaya memecah-belah, pemberontakan, atau subversi terhadap NKRI. |
| 6 | Pernah berjuang dan mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara | Dedikasi tersebut bisa dalam bentuk perjuangan kemerdekaan, pembangunan, pendidikan, dan sebagainya. |
| 7 | Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berat oleh pengadilan | Termasuk tidak pernah terbukti secara hukum melakukan tindakan kriminal besar. |
| 8 | Diusulkan oleh pemerintah daerah atau lembaga resmi, dan diseleksi oleh TP2GP | Proses formal melalui rekomendasi daerah, dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). |
| 9 | Keputusan akhir berada di tangan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) | Presiden menetapkan pemberian gelar setelah rekomendasi dari Menteri Sosial dan Dewan Gelar. |
🗂️ Tabel Fakta-Fakta Pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Berikut adalah tabel fakta-fakta utama terkait proses pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, mulai dari awal wacana hingga dinamika politik dan administratif terkini:
| 📅 Tahun/Peristiwa | 📝 Fakta Kunci |
| 2010 | Usulan pertama kali muncul dari kelompok masyarakat di Jawa Tengah. |
| 2014 & 2019 | Prabowo Subianto menyatakan dukungan dalam kampanye pilpres untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. |
| 2016 | Partai Golkar secara resmi mendukung usulan ini dalam Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa). |
| 23 September 2024 | MPR mencabut nama Soeharto dari Tap MPR No. 11/1998 tentang Pemberantasan KKN, membuka jalan politik usulan ini. |
| Oktober 2024 | Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI; dorongan pengusulan Soeharto semakin menguat. |
| Maret 2025 | Nama Soeharto termasuk dalam 10 calon Pahlawan Nasional yang dibahas oleh Kementerian Sosial dan TP2GP. |
| Pengusul Resmi 2025 | Bambang Sadono Center dari Jawa Tengah mengajukan usulan; awalnya terkendala syarat tanda tangan ahli waris. |
| Dukungan Politik | Didukung oleh Partai Golkar, tokoh-tokoh pemerintahan, dan sebagian birokrat. |
| Sikap Pemerintah | Presiden melalui Jubir Prasetyo Hadi menyatakan semua presiden layak dihormati, termasuk Soeharto. |
| Sikap Kemensos | Menyatakan bahwa pengusulan dilakukan normatif, dan semua pihak termasuk pengkritik akan didengar. |
| Reaksi Penolakan | Penolakan muncul dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), SETARA Institute, GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto), akademisi dan ribuan penandatangan petisi publik. |
⚖️Tabel Pro dan Kontra Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Berikut adalah tabel perbandingan pandangan pro dan kontra mengenai pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dirangkum dari berbagai pernyataan tokoh, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil berdasarkan dokumen resmi:
| Aspek | ✅ Pihak yang Mendukung (Pro) | ❌ Pihak yang Menolak (Kontra) |
| Alasan Utama | Soeharto dianggap berjasa besar dalam pembangunan nasional, stabilitas, dan perjuangan kemerdekaan | Soeharto dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, korupsi, dan represi panjang terhadap rakyat |
| Tokoh/Institusi Pendukung | Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto, Bambang Sadono Center, Kemensos, sejarawan tertentu (Agus Suwignyo) | KontraS, IKOHI, SETARA Institute, GEMAS, sejarawan (Asvi Warman Adam, JJ Rizal) |
| Argumentasi Historis | Soeharto berperan dalam Serangan Umum 1 Maret, Operasi Trikora, pembangunan Orde Baru | Sejarah mencatat 12 pelanggaran HAM berat era Orde Baru, pembungkaman pers, dan penghilangan paksa |
| Pandangan atas Reformasi | Reformasi dianggap sebagai transisi, bukan penghakiman personal terhadap Soeharto | Reformasi adalah penolakan moral dan politik terhadap sistem yang dipersonifikasi oleh Soeharto |
| Status Hukum | Belum pernah divonis bersalah di pengadilan, kasus hukum dihentikan karena alasan kesehatan | Ditersangkakan dalam kasus korupsi yayasan, negara menang gugatan perdata, dana belum seluruhnya dikembalikan |
| Dampak Sosial Politik | Diharapkan bisa menjadi bentuk rekonsiliasi dan penghormatan terhadap jasa pemimpin nasional | Bisa memicu luka baru bagi korban, mencederai prinsip keadilan dan integritas sejarah |
| Saran Akademik | Pemberian gelar bisa dibatasi pada kategori tertentu, misalnya jasa militer | Gelar pahlawan harus mencerminkan nilai moral dan keteladanan, tidak bisa diberikan kepada tokoh dengan rekam buruk |
| Respons Publik | Didukung sebagian kelompok loyalis Orde Baru dan beberapa daerah | Petisi penolakan ditandatangani ribuan orang, kritik luas dari masyarakat sipil dan korban |
Pusat Data Tokoh Indonesia, 25 April 2025