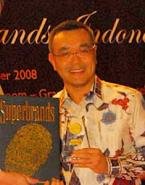Ketidakadilan Menjadikannya Kuat
Dimyati Hartono
[ENSIKLOPEDI] Pengalaman pahit karena diperlakukan tidak adil tidak menjadikannya patah semangat. Pengalaman itu justru menjadikan mantan ketua DPP PDI ini semakin kuat dan gigih memperjuangkan apa yang dianggapnya benar. Sosok Brotoseno, sebuah karakter dalam pewayangan yang berani karena benar dan tidak takut akan rintangan, dan sosok Soekarno yang ia kagumi sebagai bapak bangsa, sudah menjadi pengobar semangat dalam hidupnya selama puluhan tahun.
Prof.Dr. Muhammad Dimyati, SH, lahir 3 Maret 1932 di Malang Jawa Timur. Ia dibesarkan dalam keluarga petani yang juga berdagang kecil-kecilan di Desa Sumber Manjing Wetan, Malang, kira-kira 40 km dari kota Malang. Pada waktu itu, desanya masih dijajah oleh Belanda.
Dalam wawancara dengan TokohIndonesia DotCom di kantornya di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, 3 November 2003, Dimyati menguraikan bahwa mulai dari masa kanak-kanak hingga remaja ia mengalami berbagai perlakuan tidak adil akibat budaya dan kebijakan politik penjajah setempat. Pada saat itu, di dekat ‘Hinderland’ dari desanya itu terdapat perkebunan Belanda yang disebut ‘Ondernaming’ sehingga lingkungannya sangat dipengaruhi kehidupan penjajahan Belanda.
Di desa itu, di sekolah ‘Ongko Loro’ (angka dua), ia bersekolah. Sekolah dasar ini hanya sampai kelas 3. Namun, belakangan menjelang Belanda jatuh, dikembangkan menjadi ‘Verschol School’ (sekolah sambungan) yaitu untuk kelas 4 dan 5. Sedangkan kelas 6, Dimyati harus ke kota Malang karena di desa itu belum ada.
Ketika baru sekolah, Anak dari Marsidin Restohartono ini sudah merasakan adanya diskriminasi oleh penjajah. Misalnya, dalam hal tempat duduk. Dimyati bersama teman akrabnya Cung sama-sama masuk sekolah, kemudian mereka duduk di bangku terdepan. Hari pertama, gurunya menanyakan mereka, “Cung! Bapakmu jadi apa?”, “Bapak saya kerja di ‘Governemen’ Pak”, jawab Cung. Tiba giliran Dimyati, gurunya bertanya, “Dimyati! Bapakmu jadi apa?”, “Bapak saya petani dan dagang, Pak”, jawabnya. Mendengar jawabannya, guru itu menyuruh Dimyati agar mundur duduk di belakang dan tidak duduk di depan bersama temannya yang anak pegawai governemen tersebut.
Kejadian itu membuat Dimyati bertanya-tanya dalam hatinya. Ia tidak diperbolehkan duduk di depan dengan temannya itu, tetapi diperbolehkan bermain bersama di luar kelas. Sepulang sekolah, Dimyati bercerita dan bertanya kepada bapaknya tentang perlakukan yang diterimanya di sekolah. “Begitulah keadaannya,” jawab ayahnya singkat agak kesal. Waktu itu, beliau belum menjelaskan apa alasannya. Bapaknya termasuk orang ‘pergerakan’. Jadi beliau mengerti perasaan anaknya, semangat nasionalismenya yang tinggi tersinggung.
Di ‘Onderneming’ itu, rumah-rumah tinggal Belanda mempunyai halaman yang luas, disana ada ‘tennis ban’ atau ‘tennis korg’. Kalau Sabtu-Minggu, Dimyati jalan-jalan sekalian lihat permainan itu. Yang main disitu anak-anak Belanda yang pada jaman itu kalau laki-laki disebut ‘Sinyo’, dan perempuan disebut ‘Noni. Sebagai anak-anak, dia sebenarnya hanya mau menonton saja, tetapi ternyata tidak boleh, ia dihalau oleh polisi perkebunan.
Di sebelah kanan rumahnya β sedikit agak jauh — disana ada rumah ‘Asisten Wedana’. Semua orang yang naik kuda, bila lewat di depan rumah itu harus turun dari kudanya, kemudian berjalan menuntun kudanya, kalau sudah lewat baru boleh naik lagi. Itulah sebagian dari diskriminasi yang pernah ia alami dan saksikan dalam kehidupannya, yang kemudian baru disadarinya setelah besar yaitu ketika Indonesia sudah merdeka.
Dalam bidang pendidikan, sebelumnya orang tuanya sudah menyadari bahwa kalau di desa Sumber Manjing tersebut ia tidak bakalan boleh sekolah lebih tinggi dari SD karena untuk bisa sekolah yang lebih tinggi βsedikit di atas SD β syaratnya harus diakui sebagai anak pegawai ‘Governemen’, diakui sebagai anak Belanda, atau yang dipersamakan.
Sedangkan ia tidak punya syarat itu. “Karena itu kemungkinan untuk bisa meningkatkan taraf hidup itu tidak ada. Namun kemudian Indonesia memperoleh kemerdekaan, saya akhirnya bisa sekolah SMP dan SMA”, kata pria yang menamatkan sekolahnya di SMP Turen, Malang dan SMA Malang ini. Dari situ barulah dia mengerti arti kemerdekaan itu. “Barangkali kalau tidak merdeka saya cuma jadi petani di desa saja, tidak lebih dari itu” lanjutnya. Dia bisa menyelesaikan pendidikan SMP-SMA dan Peruruan Tinggi, itu antara lain dimotivasi oleh keinginannya untuk mengangkat derajat dan martabat keluarganya.
Dua Tokoh Idola
Sebagaimana pada umumnya orang Jawa kalau belajar wayang selalu memilih salah satu tokoh menjadi idolanya. Maka ketika dia mempelajari tokoh-tokoh di pewayangan, ‘Brotoseno’ atau nama lainnya ‘Workudoro’ menjadi tokoh yang diidolakannya.
Dia mengidolakan Brotoseno, karena Brotoseno secara fisik digambarkan dalam pewayangan itu tinggi besar, suara besar, sifatnya lurus, berani karena benar, tidak takut akan rintangan dan semboyannya adalah ‘Rawe-rawe rantas, malang-malang buntung’ artinya ada tali temali yang menghalang, putus, atau kalau ada halangan melintang, sisihkan. Brotoseno juga digambarkan jadi ‘Agul-aguling Pendowo’ (jagonya keluarga Pendowo), setia kepada negara, setia kepada kebenaran, dan berani membela kebenaran, juga sangat hormat pada orang tua.
“Dalam hati saya, semua ciri-ciri tersebut cocok dengan saya, maka saya pegang itu terus. Sehingga apa saja, saya beri lambang Brotoseno,” katanya.
“Sekarang ini, karena anak muda tidak mengenal tokoh sehingga mereka memilih orang-orang yang ada. Padahal begitu diidolakan, di tengah jalan idolanya korupsi. Dulu karena idola itu pada wayang, berarti idola itu kan tidak pernah ada, jadi dia tidak pernah cela, namun yang kita lihat itu atau kita kenal di wayang itu adalah karakternya,” katanya membedakan tokoh idola orang-orang muda sekarang dengan mereka dulu.
Saat Indonesia baru merdeka, pidato Bung Karno selalu menggetarkan semangatnya, yang kemudian menjadi ‘Nation Character Building” selama berpuluh-puluh tahun. Di pikirannya, di matanya, di hatinya, kemerdekaan itu identik dengan Soekarno karena dia mengetahui demikian besarnya peranan Soekarno dalam kemerdekaan bangsa ini. Ketika dia mulai belajar di SMA, pidato Soekarno selalu didengarnya, begitu pula di perguruan tinggi.
Kekagumannya kepada Bung Karno terlihat dari foto-foto Bung Karno, dalam ukuran besar maupun kecil yang terbingkai indah dan dipajang di setiap ruangan kantornya. Dan bukan hanya itu, sebagian dari pidato-pidato dari ‘Bapak Negara’ tersebut dibingkainya dan dipajang juga. “Kok ada manusia yang dikaruniai Tuhan kharisma yang demikian besar, yang dedikasinya kepada bangsa dan negara begitu tinggi,” pujinya kagum pada sosok Bung Karno.
Tapi setelah belajar sampai sarjana, melalui apa yang dibacanya sendiri, diapun kemudian tahu bahwa Bung Karno sendiripun sebenarnya tidak menghendaki untuk ‘dikultus individukan’. Sehingga dia merasa bahwa sebagian dari pengikut Soekarno-lah yang tidak benar. Sedangkan dia sendiri ingin menjadi pengikut yang kritis, yang mempelajari ajaran Bung Karno itu secara kritis. Sehingga dalam menerapkannyapun sesuai dengan kondisi. Menurut pengakuannya, itulah akhirnya yang membuat nasionalismenya kental.
Dalam kesehariannya, dia selalu berusaha mencontoh perilaku dan tindakan kedua tokoh tersebut. Di ruangan kantor, rumah bahkan di mobilnya juga di penuhi dengan foto, assesoris dan segala macam yang berhubungan dengan kedua tokoh yang menjadi idolanya tersebut.
Didikan Orang Tua
Di samping kekagumannya kepada tokoh tersebut, dalam pembentukan watak dan sifatnya, diakuinya peranan Bapak dan Ibunya sebagai pekerja-pekerja keras juga sangat mempengaruhinya. Bapak Ibunya yang dagang kecil di rumah, dan punya kios di pasar depan rumahnya, pagi-pagi sekali sudah harus ke pasar, kemudian pulang jam 12 siang, masak, habis makan berangkat lagi ke kebun. Dengan begitu, secara tidak langsung dia tercetak menjadi pekerja keras. “Dalam prinsip saya kalau yang namanya kerja musti keras, kalau tidak itu bukan bekerja, tapi main-main” katanya dengan tegas.
Bapaknya yang sangat mencintai kebudayaan Jawa, khususnya ‘wayang’ itu, juga mempengaruhi pembentukan kepribadiannya.”Kalau waktu tidur, Ibu di samping saya dan Bapak di samping saya yang lain. Sebelum saya tidur, Bapak selalu cerita tentang wayang” katanya mengenang. Waktu itu orang kita sudah ada yang meniru-niru ‘Barat’ dimana anaknya dibacakan buku cerita. Namun saya, tanpa buku sudah diceritakan oleh Bapak saya tentang apa itu ‘Pendowo’, apa itu ‘Kurowo’, semua itu dijelaskan,” katanya.
Berkat pengalamannya itu, kecintaannya terhadap wayang semakin besar. Sampai sekarangpun hal itu terlihat dari ruangan-ruangannya yang dipenuhi dengan gambar dan assesoris wayang, begitu juga di mobilnya, dikatakannya bahwa dia selalu bawa kaset wayang satu set, berganti-ganti didengarkannya terutama kalau macet.
Pewayangan merupakan pengajaran tentang kehidupan. “Bukan hanya mengenai cerita tentang ‘Bharatayuda’, ‘Mahabarata’ tetapi juga diketemukan kebudayaan, pelajaran tentang kebatinan, tentang ketuhanan, filosofi kehidupan semua kental sekali ada di situ,” katanya menjelaskan. “Indahnya pertunjukan wayang itu, memberi peluang bagi semua umur untuk bisa menyerap sesuai kapasitas masing-masing. Jadi kalau anak-anak, senang pada boneka-bonekanya, sedikit lebih besar lagi, senang pada perangnya yang heroik. Dan kalau sudah lebih dewasa dan tua senang pada dialog-dialognya yang berisi petuah, filosofi, ajaran kehidupan,” katanya lebih lanjut.
Melalui kisah pewayangan yang diceritakan Bapak dan Ibunya, suami dari Siti Soelastri ini menyerap filosofi-filosofi seperti kejujuran, harga diri, rasa hormat kepada orang tua, bahkan juga termasuk kecintaan kepada negara dan bangsa.
Oleh Bapaknya, ditanamkan kepadanya bahwa manusia itu harus berpegangan pada, “drajat gumantung ono tekad, nek tekadmu gede derajatmu duwur, nek tekadmu cilik derajatmu ndek,” katanya menirukan ucapan Bapaknya. Artinya, derajat itu tergantung dari tekad, kalau tekadmu besar derajatmu tinggi, kalau tekadmu kecil derajatmu rendah. Falsafah itu dia pegang sehingga membentuk wataknya pantang menyerah dalam memperjuangkan apa yang dianggapnya benar.
Sarjana Hukum dan peraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya ini masih ingat ketika pertama kali hendak melamar di Kejaksaan Agung setelah menyelesaikan kuliah strata satunya. Waktu itu ia terasa sedang bermimpi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Dikatakannya bahwa perjalanannya sebelumnya hanya ke Sumber Manjing β Malang dan paling jauh Surabaya. Maka ketika berangkat ke Jakarta naik kereta api, dia diberi bekal (petuah) oleh orang tuanya yang intinya mengatakan bahwa dia tidak usah takut, pada siapapun tidak usah takut.”Podo manung sani, podo mangane sego,” katanya meniru ucapan Bapaknya yang artinya, sama manusianya sama makannya nasi.
Sedangkan dalam mengejar ilmu, orang tuanya selalu menganjurkan ‘nek wong lio engelmu iku kasat’ artinya, ilmu itu terlihat oleh mata. ‘Nek wong lio biso, kenopo ono ora iso’ artinya, kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa.
Pembebasan Irian Barat
Begitulah akhirnya, selesai sarjana, ayah dari Eko Djuliardhie Dimyati (Koi) ini bekerja sebagai jaksa, yang pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain sampai ke Irian Barat.
Dalam rangka pembebasan Irian Barat, waktu itu dicari sukarelawan-sukarelawan. Ribuan orang mendaftar. Dia termasuk sukarelawan saat itu, lalu dipersiapkan dalam satu wadah yang di lingkungan kejaksaan itu disebut Komponen Sipil dan dia sendiri dipilih jadi komandan. Komponen sipil ini dilatih militer, kemudian dipersiapkan untuk di-drop. Dia sendiri dilatih oleh militer di Rinif Malang.
Tapi waktu mereka masih menunggu dikirim dimana segala perlengkapan sudah disiapkan, lahir New York Accord – Perjanjian New York. Akhirnya dia tidak jadi dikirim sebagai sukarelawan. Kemudian dipilihlah di antara mereka siapa yang bisa berbahasa Inggris. Karena dia bisa bahasa Inggris, lalu diapun mendaftar, dan akhirnya dikirim ke Irian Jaya. Ditempatkan di Perwakilan RI. Di sana dalam bagian Social Affairs.
Kemudian dalam rangka transfer of authority dari PBB ke Indonesia, dia dipilih menjadi Kepala Perwakilan RI di Merauke. Tanggal 1 Mei 1963, dia menerima penyerahan Irian Barat bagian Selatan di Merauke dari UNTEA. Jadi nama dan tandatangannyalah dari pihak Indonesia yang masuk ke PBB.
Perlakuan Tidak Adil
Setelah normal, dia kembali ditempatkan di Kejaksaan di Jawa Timur dan kemudian dipindahkan ke Jakarta. Saat itu, dibenaknya masih penuh dengan Heroisme. Namun tiba-tiba meledak peristiwa G 30/S PKI. Saat itu dia mengaku mengalami suatu ‘goncangan mental’ sebagai seorang pengagum Soekarno. Dan bangsa ini semuanya mengetahui betapa besar peranan Bung Karno dalam membebaskan dan memimpin bangsa ini. “Di awal-awal dijatuhkannya Soekarno, diungkaplah segala yang jelek-jelek tentang Soekarno. Disebutlah bahwa dia PKI agung, korupsi agung, seksmania, suka kawin. Semua hal-hal yang jelek dikeluarkan di koran-koran dengan gambar-gambar yang entah bagaimana. Di dalam hati, saya berontak, tapi bukan berontak kepada bangsa saya,” katanya.
Dalam hatinya, “Kok begini bangsa ini memperlakukan pemimpin bangsanya sendiri. Yang dulunya dipuja, dikagumi tapi kini kok dimaki seperti orang yang tidak ada harganya”. Sehingga timbul konflik dalam batinnya. Namun itu juga yang menyebabkan sikap tegasnya makin timbul.
Dia ingat Jaksa Agung saat itu adalah Letnan Jenderal Sugiharto. Ketika semua anggota kejaksaan diberikan formulir isian yang menanyakan apakah setuju atau tidak setuju kalau Soekarno itu di ‘Mahmilub’-kan, Dimyati menjawab, “Sebagai jaksa saya tunduk pada atasan”. Maksudnya, kalau itu diperintahkan dia tidak setuju, dia pilih keluar sebagai jaksa. Kemudian formulirnya dia kembalikan, tapi datang lagi formulir yang sama. Hal ini terjadi sampai tiga kali. Dan terakhir dengan perintah harus dijawab yang tegas, setuju atau tidak setuju, namun jawabannya tetap sama. Sehingga besok lusanya dia diberitahu, bahwa dia boleh tidak masuk. Istilah waktu itu namanya ‘DRS’ (di rumah saja). Oleh karena itu, ketika dia keluar seperti dari PDI-P beberapa waktu lalu, hal itu bukan pertama kali. Kalau sudah prinsip, itupun dilakukannya.
Mengambil Gelar Doktor
Sejak itu untuk beberapa tahun, dia mengalami perlakuan yang tidak baik pada jaman orde baru, dimana masuk kantor boleh, tidak masuk kantor juga boleh. Selama tahun-tahun itu tanda tangannya hanya berlaku untuk ‘bon teh’ saja. “Tapi bagi saya itu tidak jadi masalah,” katanya.
Pada saat itu dia diingatkan oleh temannya seorang senior wartawan, namanya Mas Darmawan Condronegoro. “Mbok daripada kamu begitu, kamu ambil Doktor saja,” kata temannya. “Loh memangnya bisa?” jawabnya. Terus temannya berjanji akan dicarikan bahan-bahannya. Dia tergugah. “Saya pikir, why not,” katanya mantap.
Salah satu pertimbangannya mengapa mengambil Doktor adalah di masa depan, Indonesia membutuhkan orang pandai. Dalam pikirannya kalau begini-begini tidak mungkin bisa berperan. Maka himbauan teman wartawannya tersebut dia terima. Mulailah dia belajar. Dan atas biaya sendiri dia melakukan riset ke Jepang, Amerika, Belanda, dan Inggris sampai selesai. Dia memilih bidang Hukum Laut Internasional, karena dilihatnya negara ini negara kepulauan maka dibutuhkan ahli-ahli untuk menanganinya. Jadi sejak tahun 1967 sampai 1975 sekitar delapan tahun, dia mengaku tidak punya kedudukan apa-apa. Tahun 1975, dia kemudian diangkat kembali.
Ketika sudah mendapat gelar Doktor, dia merasakan pengaruhnya cukup besar yakni dimana wawasannya menjadi makin luas. Selama di kejaksaan sebelumnya, dia mengaku bahwa yang mengemuka pada sikap mentalnya adalah penonjolan kekuasaan, tetapi setelah peristiwa yang dialaminya dengan segala penderitaanya, barulah dia sadar bahwa, ternyata kekuasaan itu tidak langgeng.
Begitulah kariernya, setelah bekerja di kehakiman dia berkesempatan menjadi Kakanwil Kehakiman di Sumatera Utara. Di sanalah dia berkenalan dengan Pak Susilo Sudarman (Alm), waktu itu beliau sebagai Pangkowilhan. Maka ketika beliau menjadi Menparpostel, dia diminta oleh beliau melalui Menteri Kehakiman untuk diberi tempat sebagai Kepala Biro Hukum di sana dengan tugas menyelesaikan dua buah UU yaitu UU Pariwisata dan UU Telekomunikasi, yang dua-duanya selesai. Sesudah itu dia menjadi guru besar. Atur Lorielcide Paniroy – Marjuka
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)