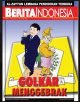Pembela Buruh Migran
Anis Hidayah
[DIREKTORI] Membela hak pekerja Indonesia di luar negeri atau TKI menjadi pekerjaan Anis Hidayah. Untuk tugas itu, ia kerap harus menomor duakan keluarganya, bahkan kehidupannya sendiri. Ia adalah Direktur Eksekutif Migrant Care.
Kantor yang terletak di jalan Jalan Pulo Asem, Rawamangun, Jakarta Timur itu kerap didatangi para jurnalis baik lokal maupun asing. Di kantor itu pula, sehari-hari Anis Hidayah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Migrant Care, sebuah LSM yang didirikannya bersama para aktivis peduli kaum pekerja Tanah Air di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah buruh migran. Migrant Care merupakan salah satu LSM yang berada di garda depan memperjuangkan nasib buruh migran. Mereka banyak melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang menimpa TKW.
Menurut Anis, LSM yang berdiri sejak tahun 2004 itu dirintis dengan dana pinjaman dari sejumlah aktivis buruh yang waktu itu sejumlah Rp 30 juta. Dana tersebut digunakan untuk sewa kantor di kawasan Cipinang dan mengurus legalitas lembaganya itu.
“Saya nekat meminjam uang. Toh, ini juga untuk kepentingan orang banyak,” ujar wanita yang pernah nyantri di Denanyar Jombang itu. Perjalanan lembaga anyar tersebut tidak mulus-mulus saja. Karena advokasi bagi aktivis buruh migran itu kerap menyinggung banyak pihak, kantor Anis pun kerap diteror. Namun, langkahnya tidak surut. Perlahan, gaung Migrant Care mulai terdengar. Lembaga donor yang mempunyai perhatian dengan sepak terjang para aktivis pun mulai berdatangan.
Perempuan kelahiran Bojonegoro, 7 November 1976 itu telah memulai kiprahnya sebagai aktivis semenjak masih berstatus mahasiswa. Kala itu Anis tergabung dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Anis kerap berdiskusi dengan LSM yang fokus pada masalah buruh migran. Selain itu, ia juga aktif di SD Inpres dan LSM lokal di kota Jember.
Di saat yang sama, ia baru menyadari bahwa tempat tinggalnya merupakan salah satu basis buruh migran di Indonesia. “Saya lahir di situ, tapi saya baru sadar di depan, kanan, kiri dan belakang rumah saya itu semuanya TKI.
Dari sekelumit pengalamannya itu Anis semakin timbul kesadaran dalam dirinya bahwa penipuan dan penganiayaan terhadap pra TKI di luar negeri dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Hal itu semakin mendorong Anis dan rekan-rekan aktivis lainnya untuk membela mereka yang tertindas. Mereka kemudian mendirikan Solidaritas Perempuan Jawa Timur di tahun 1998. Melalui wadah itu para mantan buruh migran dan aktivis mahasiswa aktif memberikan advokasi terhadap kasus penganiayaan dan pemerkosaan.
“Saya pernah bertemu dengan TKW yang mengalami perkosaan di Arab Saudi. Dia dipulangkan. Namun, kasusnya tidak diurus. Tak ada yang peduli. Kasus ini kemudian saya angkat dalam skripsi,” ujar istri Teguh Prawiro itu. Namanya mulai mencuat di tahun 1999. Wanita berperawakan mungil itu kerap tampil saat melancarkan advokasi untuk buruh migran.
Tahun 2001 Anis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Gajah Mada (UGM) Program Pascasarjana Hukum Internasional UGM. Ketika dalam proses menulis tesisnya, Anis hijrah ke ibukota dan bergabung dengan sebuah LSM. Saat itu Anis kembali di hadapkan pada kenyataan miris, banyaknya TKI yang diperlakukan semena-mena. Namun rencana untuk memperdalam kasus justru berubah di tengah jalan. “Saya enggak tahan melihat kondisi yang ada maka saya tunda kuliah,” jelasnya.
Setelah mantap menjadi pejuang buruh migran, di tahun 2004 Anis dan empat kawannya, Wahyu Susilo, Mulyadi, Alex Ong, dan Yohanes Budi Wibawa, mendirikan Migrant Care. Karena minimnya dana, untuk berkantor pun mereka harus menumpang. Namun keadaan itu tak menyurutkan semangat mereka dalam membantu sesamanya.
Kiprahnya semakin menonjol saat dirinya mengadvokasi rencana pemerintah Malaysia yang mengumumkan deportasi besar-besaran kepada kaum buruh migran dari negeri jiran itu di tahun 2004 serta mencuatnya kasus Nirmala Bonat, seorang TKW yang terancam hukuman mati di Singapura. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, Anis bahkan terpaksa meminta sumbangan untuk membeli tiket dan fiskal agar dapat berangkat ke Negeri Jiran tersebut. Baginya, kasus Nirmala seharusnya tak hanya menjadi sebuah shock therapy tapi jadi sebuah pembelajaran bagi pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk memperbaiki kebijakan.
Namun, hal itu tak terjadi. Padahal pemerintah mengesahkan undang-undang tentang TKI pada September 2004, empat bulan sesudah kasus Nirmala Bonat yang terjadi. TKI dianggap sebuah barang yang bisa dijual tanpa dibekali perlindungan hukum yang jelas. “UU TKI sudah lima tahun dan terbukti gagal karena masih banyak kasus pelanggaran terhadap buruh migran,” tuturnya.
“Saya hanya membantu agar para buruh migran mendapatkan keadilan,” ucap berdarah Jawa itu.
Pekerjaannya sebagai aktivis yang tak mengenal waktu, mau tak mau memaksa Anis untuk merelakan 24 jam waktunya dalam seminggu untuk mengurusi masalah yang dialami para buruh migran. Tak jarang ia bahkan harus menghabiskan waktunya hingga berhari-hari lamanya di negeri orang.
Seperti saat ia berada di Malaysia untuk mendampingi para TKW bermasalah. Di negara serumpun itu, Anis menyaksikan penderitaan para TKW bernasib malang itu. KBRI yang menjadi harapan mereka satu-satunya, juga tidak memiliki tempat layak untuk menampung para pahlawan devisa itu.
Mereka hanya ditempatkan di empat kamar kecil. Isinya puluhan orang. “Kondisinya menyedihkan,” ujar wanita bergelar sarjana hukum itu. Mereka yang tidak kebagian tempat harus rela tidur di teras atau berbagai tempat dengan mobil-mobil yang parkir di kantor itu. “Saat rombongan pemerintah mengunjungi kehidupan buruh migran di KBRI Malaysia, saya nyelonong masuk. Saya menyaksikan kenyataan memprihatinkan itu,” jelas ibu satu anak itu.
Menurut Anis, para TKI yang diberikan julukan sebagai pahlawan devisa belum mendapat perlakuan yang sesuai dengan apa yang telah mereka sumbang untuk tanah kelahirannya. Puluhan trilyun yang masuk ke kas negara seakan tak ada artinya saat hak asasi mereka sebagai manusia tak dihargai. Perlakuan keji mulai dari penyiksaan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan kerap menghantui mereka. Namun pemerintah sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hanya bisa bersikap reaktif. Seperti kasus yang sudah-sudah, semuanya tak jelas penyelesaiannya. Tak heran jika kasus yang mengoyak rasa kemanusiaan itu terus menerus terulang. Pemerintah seakan tak memiliki human rights sensitivity.
Setiap tahunnya ribuan TKI pulang ke Tanah Air dalam keadaan tak bernyawa. Mereka yang nasibnya masih sedikit lebih beruntung harus menanggung malu karena memiliki anak dari hasil perkosaan. Belum lagi para TKI yang mengalami cacat fisik akibat mengalami penganiayaan hebat dari para majikan mereka. Menurut Anis sebenarnya kasus-kasus tersebut tak perlu terjadi jika pemerintah dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI.
Tapi pemerintah tidak juga menunjukkan tajinya, dan ujung-ujungnya hanya bisa mengkambinghitamkan para penyalur nakal yang nekad memberangkatkan TKI tanpa dibekali kemampuan berbahasa asing yang baik. Padahal menurut Anis, seterampil apapun buruh migran, kalau dia bekerja di satu negara yang tidak ada regulasi tentang perlindungan pekerja, mereka tidak punya akses, logistik terbatas, itu menjadikan mereka rentan.
Padahal pemerintahlah seharusnya pihak yang paling bertanggung jawab. Karena para TKI itu tak harus jauh-jauh mencari nafkah hingga ke luar negeri andai saja pemerintah dapat menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.
“Kalau boleh berkata jujur, yang diuntungkan dari pengiriman TKI adalah pemerintah dan penyalur. Sementara TKI hanya begitu-begitu saja. Itu bisa dilihat dari kehidupan mereka. Sepulang bekerja dari luar negeri, mereka tetap miskin,” ujar Anis. Bukan hanya itu, menurut Anis, pemerintah kurang berterima kasih atas sumbangan devisi yang diberikan TKI.
Dalam hal penanganan kasus TKI, Anis tak juga dapat menyembunyikan rasa kecewanya pada kinerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY di mata Anis, paling lemah dalam diplomasi perlindungan TKI jika dibandingkan dengan para pemimpin lainnya. Dalam catatan Anis, ia membandingkan dengan diplomasi yang dilakukan mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid ketika seorang TKI, Siti Zainab, pada 2007 divonis hukuman mati di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya. Lewat diplomasinya, Presiden RI ke-4 tersebut mampu menunda dilangsungkannya hukuman mati atas TKI asal Madura tersebut. Gus Dur langsung menghubungi Raja Fahd di Arab sehingga ditunda vonis hukuman matinya,” jelas Anis.
Dalam kasus lain, Anis juga memuji diplomasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah negara lain ketika tenaga kerja mereka mengalami masalah di negara penempatan. Salah satu kasus yang ia contohkan yaitu ketika ada buruh asal Srilanka yang divonis hukuman mati di Arab Saudi, Presiden Sri Lanka langsung menelpon Raja Fahd untuk meminta penundaan hukuman mati. Anis menegaskan, langkah konkret kepala negara yang seperti itu yang perlu dicontoh. Bukannya malah berikan HP untuk TKI. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menguasai masalah. Yang seharusnya diberikan adalah perlindungan hukum. Bukan telepon seluler,” kata Anis.
Di samping itu, menurut Anis, kultur menempatkan perempuan secara tidak adil. Budaya patriarki dan perbudakan yang masih kental di Arab Saudi, misalnya membuat TKI dianggap sebagai budak yang bekerja tiap hari dengan waktu tidur 2 jam saja.
Kesibukan bungsu dari tiga bersaudara ini sebagai seorang aktivis tak jarang mengundang protes sang suami dan anak semata wayangnya. “Kadang suami protes. Membela TKI di luar negeri, tapi “dua TKI” di rumah sendiri ditelantarkan,” ujar Anis menceritakan keluhan suami dan anaknya. Meski demikian, suami dan keluarganya secara prinsip tetap mendukung perjuangan Anis selagi itu dapat bermanfaat bagi orang banyak. Ia bersyukur karena dalam mendidik anak, ia bisa berbagi tanggungjawab dengan suami tercinta. Anis juga mengungkapkan, meski suami kadang protes, tapi ia sangat paham profesi istrinya. Kalau pun sudah terlampau sibuk, sang suami hanya mengingatkan agar Anis meluangkan waktu untuk keluarga.
Selain dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap sesamanya, Anis juga merupakan pribadi yang sederhana. Meskipun punya mobil, namun ia jarang menggunakannya. Kendaraan pribadi itu lebih sering diparkir di rumahnya yang luasnya seukuran tipe 45. Mobil itu, kata dia, bukan hasil dari keringatnya sebagai aktivis Migrant Care. Mobil itu hasil pembelian ibunya di Bojonegoro. “Saya punya mobil, tapi dibelikan ibu yang kebetulan PNS,” ujar ibu satu anak tersebut.
Untuk beraktivitas ke mana pun, Anis hanya menggunakan mobil operasional yang disediakan lembaga yang dia pimpin. Anis menyatakan bahwa gajinya dari membela buruh migran tidak seberapa. Bagi dia, yang penting, aktivitas itu bermanfaat untuk orang banyak. “Saya tidak terlalu mikir orientasi ekonomi. Saya juga tidak tahu kelak tua seperti apa,” ujarnya. Dia juga mengatakan tidak menabung secara khusus untuk persiapan hari tua.
Sedangkan untuk berangkat dan pulang dari tempat kerja ke rumahnya di Depok, Jawa Barat, Anis lebih sering menggunakan kendaraan umum. “Kadang naik bus kota atau kereta api,” ungkapnya.
Jika aktivitas di kantornya rampung larut malam, Anis harus rela merogoh kantong lebih dalam untuk naik taksi. “Tapi, kalau malas (pulang), ya saya tidur di kantor. Sudah biasa begini,” akunya. Di kantornya memang tidak ada tempat tidur khusus untuk sang direktur. Karena itu, Anis harus memanfaatkan ruang kerja di kantor tersebut. Artinya, ruang kerja ya ruang tidur. Esok paginya, dia harus beraktivitas lagi hingga malam.
Sebenarnya, Anis kerap mendapatkan tambahan honor dari menjadi pembicara di berbagai seminar. Sesekali waktu dia juga diminta mengisi kuliah umum di berbagai kampus. Namun, tidak semua uang yang didapat bisa masuk kantong. Kebijakan Migrant Care mengharuskannya memasukkan beberapa persen honor itu untuk kas lembaga.
Gaji para aktivis lain di Migrant Care juga tidak besar. “Bisa untuk makan sudah cukup.” ucapnya. e-ti | muli, red