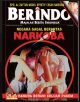Ketika Guru Mulai Dianggap Beban Angka
Di balik pertanyaan Sri Mulyani: Haruskah semua ditanggung negara?

Guru dan dosen bukan sekadar pekerja pendidikan. Mereka adalah penopang masa depan bangsa. Namun di tengah rendahnya kesejahteraan yang mereka terima, muncul pertanyaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani: “Haruskah semuanya ditanggung keuangan negara?” Kalimat yang sederhana, tapi cukup untuk membuat kita bertanya: apa arti pendidikan di mata negara?
“Haruskah semuanya ditanggung keuangan negara?”
Kalimat itu meluncur dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di sebuah forum di Institut Teknologi Bandung. Topiknya serius: rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Nada ucapannya mengundang tafsir. Bagi sebagian orang, itu ajakan mencari jalan keluar bersama. Bagi yang lain, itu terdengar seperti langkah mundur dari tanggung jawab.
Sulit untuk tidak bereaksi. Di tengah gencarnya tuntutan tunjangan, di tengah berita bahwa gaji guru kita termasuk yang terendah di Asia Tenggara, pertanyaan seperti itu menimbulkan kesan bahwa negara sedang menimbang ulang perannya pada hal yang mestinya paling mendasar.
Pendidikan di negeri ini tidak berdiri sendiri. Ia hidup dari gotong royong yang sudah lama berlangsung. Di sekolah negeri, ada iuran per kelas yang merupakan inisiatif dari para wali murid untuk menutupi biaya-biaya kegiatan di sekolah. Di kampus, UKT yang naik perlahan tapi pasti. Di desa-desa, guru honorer kerap mengandalkan insentif dari kas lokal atau sumbangan warga. Bahkan untuk hal remeh seperti memperbaiki papan tulis, mengganti atap bocor, masyarakat sering bergerak lebih cepat daripada birokrasi.
Maka, ketika negara bertanya tentang partisipasi masyarakat, wajar jika publik menjawab balik: partisipasi yang seperti apa lagi? Sebab beban itu sudah lama mereka pikul. Kadang dengan rela, kadang karena terpaksa.
Partisipasi bisa berarti dukungan moral, keterlibatan mengawasi mutu pendidikan, atau gotong royong dalam kegiatan sekolah. Itu sehat. Tapi jika partisipasi dimaknai sebagai mengalihkan beban keuangan negara ke masyarakat, batasnya harus jelas. Terutama dalam hal yang menyangkut gaji pendidik, karena itu adalah tanggung jawab sistem, bukan belas kasihan warga.
Bisa jadi, Sri Mulyani berbicara dari ruang penuh angka, ruang yang setiap harinya mempertemukan tabel penerimaan dengan daftar belanja yang tak ada habisnya. Tapi di luar ruang itu, ada dunia yang berbeda: kelas dengan kursi reyot, guru yang pulang pergi 20 kilometer dengan motor butut, dosen yang mengajar sambil mengejar riset tanpa kepastian insentif.
Dan di titik inilah, kita melihat ironi yang lebih besar: negara kerap lebih sigap pada program-program yang memberi sorotan cepat ketimbang pada sektor yang hasilnya baru terasa setelah satu generasi. Pendidikan tidak pernah menjadi bintang panggung politik. Ia tak bisa dipamerkan dalam hitungan bulan. Justru itu sebabnya ia membutuhkan komitmen jangka panjang, sesuatu yang kerap kalah dalam logika popularitas.
Contohnya bisa kita lihat pada program Makan Bergizi Gratis, yang dijalankan dengan janji menyehatkan generasi penerus, dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dibingkai sebagai penggerak kemandirian ekonomi desa. Secara prinsip, keduanya tidak keliru. Namun jika alokasi besar diberikan pada program seperti ini sementara gaji guru honorer tetap jauh dari layak, dan tunjangan dosen masih tersendat, maka prioritas kebijakan patut dipertanyakan.
Pendidikan tidak memberi sorotan instan. Tidak ada upacara peresmian yang gemerlap, tidak ada foto-foto yang bisa langsung dipublikasikan untuk menuai pujian. Yang ada hanyalah ruang kelas yang setiap hari dijaga oleh orang-orang yang jarang masuk berita. Dan mungkin karena itulah, pendidikan kerap kalah dalam persaingan memperebutkan perhatian anggaran.
Guru dan dosen tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin cukup untuk hidup layak, agar bisa mengajar tanpa dihantui kekhawatiran soal biaya listrik atau cicilan rumah. Dan itu bukanlah “bantuan”, melainkan kewajiban negara.
Negara memang tidak mungkin mengurus semua hal. Tapi ada hal-hal yang tak boleh dilepaskan, dan pendidikan adalah salah satunya. Menjaga kesejahteraan pendidik berarti menjaga masa depan. Mengabaikannya berarti membiarkan fondasi bangsa retak perlahan.
Publik paham anggaran itu terbatas. Yang mereka minta hanyalah jaminan bahwa keterbatasan itu tidak digunakan sebagai alasan untuk menghindar. Dan bahwa di tengah semua program dan proyek, negara masih ingat siapa yang seharusnya berdiri di barisan prioritas.
Akhirnya, ini bukan sekadar soal “mampu” atau tidak mampu menanggung. Ini soal kemauan. Apakah negara benar-benar menempatkan pendidikan di jantung kebijakannya, atau hanya di pinggir pidato?
Jika jawabannya yang kedua, maka kita sedang membayar mahal untuk masa depan yang rapuh. Dan ketika itu terjadi, pertanyaan yang patut kita ajukan bukan lagi “haruskah semuanya ditanggung negara?”, melainkan: apakah negara ini masih mau menanggung masa depannya sendiri? (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)