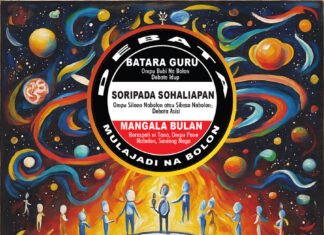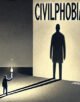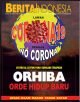Sang Pejuang Cilik Berjiwa Mandiri
Probosutedjo
[ENSIKLOPEDI] DUA | Sejak kecil, Probosutedjo sudah memiliki semangat kejuangan dan kemandirian. Setiap pagi naik sepeda dan berjalan kaki (jika sepedanya rusak) menyusuri rel menuju sekolahnya yang berjarak tiga sampai 10 km. Kemudian pada usia remaja sudah ikut bergerilya, sebagai pejuang termuda, pejuang cilik, melawan penjajah Belanda. Kemudian, tepat dalam usia 21 tahun, 1 Mei 1951, bertekad mandiri merantau ke Medan.
Probosutedjo lahir 1 Mei 1930 di Desa Kemusuk, kurang lebih 10 kilometer arah barat kota Yogyakarta, dari sebuah keluarga yang cukup terpandang akar garis keturunan dan kejuangannya. Ayahnya, bernama Purnomo. Ibunya, bernama Rr Sukirah. Dari darah Sang Ayah, dia mewarisi jiwa pejuang. Sedangkan dari garis darah Sang Ibu, dia mempunyai trah dengan Keraton Yogyakarta.
Sang Ayah, bernama kecil Purnomo, berganti nama setelah menikah, menjadi R Atmoprawiro, sebagaimana kebiasaan masyarakat desa Kemusuk dan Jawa pada umumnya. Nama setelah menikah itu adalah gabungan dari nama orang tua sendiri dan nama dari mertua. Atmo diambil dari nama mertua, yaitu Atmosudiro. Sedangkan Prawiro diambil dari nama ayahnya, Prawirodiryo.
Sedangkan Sang Ibu, Soekirah, adalah keturunan Demang Wongso Menggolo, pendiri desa Kemusuk. Demang Wongso Menggolo memiliki dua orang anak, yaitu Dronolawe (ikut memberontak melawan Belanda) serta anak perempuan bernama Wongsowijoyo, menikah dengan Djomenggolo yang kemudian menjadi demang di Kemusuk Utara.
Kemudian, Cicit Wongsowijoyo, setelah menjadi demang, menikah dengan salah seorang keturunan Hamengku Buwono VII dari salah seorang selirnya. Pernikahan itu melahirkan Notosudiro, bergelar Raden Ngabei Notosudiro. Notosudiro mempunyai putra tunggal bernama Sukiman. Setelah menikah dengan Suminem, Sukiman berganti nama menjadi Atmosudiro, dengan panggilan kehormatan Raden Ngabehi Atmosudiro.
Dari pernikahan ini, Raden Ngabehi Atmosudiro dikaruniai sembilan orang putra-putri, yaitu Dasuki (Mangkusudiro), Soekirah (ibunda Probosutedjo), Soepilah (Sastroharjo), Soepardi (Notosuparto), Soekarno (Uayengsudiro), Soemadi, Soetimah (Warsosudiro), Soedarmadi (Prawiro Sudarmadi), dan Soekinah (Dipodiwarno).
Probo memutuskan untuk berangkat merantau, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-21, 1 Mei 1951. Dia menjual sepeda pemberian kakaknya untuk menambahi uang simpanannya yang tidak cukup sebagai bekal hidup. Tujuannya ke kota Medan.
Jadi, Probosutedjo yang bernama kecil Suprobo adalah cucu Raden Ngabehi Atmosudiro. Dia merupakan anak keempat dari tujuh orang putra-putri bersaudara, buah kasih pernikahan R. Atmoprawiro dengan Rr. Sukirah yaitu Sukiyem, Sutjipto, Basirah, Suprobo (Probosutedjo), Suminah, Suwito dan Noek Boesinah.
Keluarga ini berada di lingkungan Desa Kemusuk yang amat subur. Karena kesuburannya itu, pemerintah kolonial Belanda membuka perkebunan tebu dan membangun Pabrik Gula di Rewulu, sebelah utara desa itu.
Kakek Probosutedjo, Raden Ngabehi Atmosudiro, yang pada waktu itu dipercaya sebagai sindhoer (di atas mandor besar) di Pabrik Gula Rewulu, memberi kesempatan yang luas bagi sanak-saudara dan penduduk sekitar menjadi pegawai di perkebunan tebu dan pabrik gula itu. Termasuk ayah Probosutedjo, Atmoprawiro, yang kemudian menjabat mandor kepala di perkebunan tebu itu.
Sebagai mandor kepala, kehidupan ekonomi keluarga ini tergolong berkecukupan untuk ukuran desa Kemusuk kala itu. Keluarga ini menjadi cukup terpandang dan menjadi tempat orang mengadukan keluh-kesahnya.
Dalam kondisi kehidupan ekonomi yang berkecukupan dan suasana Desa Kemusuk yang subur dengan rerimbunan daun dan gemericik air yang jernih, itu Probo dididik berhati teduh, berakal budi jernih dan bertutur kata santun. Dia diasuh dengan kasih sayang dengan berbagai dinamikanya untuk belajar menghayati dan mensyukuri nilai-nilai kehidupan, sebagai bekal meniti jalan kehidupan masa depan.
Saat Probo masih berusia belia 10 tahun, pada tahun 1941, sudah memperoleh kepercayaan dari ayahnya, yang mandor kepala di perkebunan tebu, untuk menukarkan uang sebesar lima gulden menjadi pecahan senilai 500 sen setiap hari Sabtu. Nilai satu gulden setara 100 sen. Uang itu untuk membayar gaji para buruh setiap akhir pekan. Masing-masing buruh, rata-rata memperoleh gaji delapan hingga 10 sen per minggu, setelah dipotong uang makan. Gaji buruh masih rendah sekali ketika itu, sangat jarang yang menerima gaji di atas 15 sen.
Probo mendapat tugas khusus menukarkan uang gulden ke Koperasi Atmo, jaraknya 500 meter dari rumah. Uang lima gulden, setelah menjadi recehan berbetuk sen, benggol atau bribil beratnya cukup lumayan sebab bahannya terbuat dari tembaga, harus dibawa dalam kantongan. Sang Ayah, begitu jelinya, sudah melihat bakat dan kemampuan Probo sehingga dipercaya untuk menukarkan uang.
Probo menikmati masa kecil yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Memiliki banyak sahabat sepermainan. Di antaranya, permainan petak umpet dan bernyanyi di bawah sinar temaran bulan kala malam tiba. Kala itu, Probo lebih senang bermain dengan teman-teman yang sudah dewasa, dibanding dengan teman sebayanya.
Ditambah lagi kehangatan kasih sayang kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Sang Ibu, meskipun selalu sibuk membuat kue-kue kecil untuk dijual kepada pegawai perkebunan gula, selalu memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya.
Sang Ibu, Rr Soekirah, yang dikenal dengan sebutan R Nganten Atmoprawiro, juga mengasuh anak-anaknya dengan belajar tirakat dan kemandirian. Sang Ibu mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang dan pengorbanan atas kesenangan duniawi yang diwujudkan dalam berbagai laku spiritual atau olah batin.
Sifat dan sikap kebersahajaan, nrima ing pandum dan welas asih, selalu diasuhkan Sang Ibu kepada anak-anaknya. Sang Ibu yang selalu murah senyum, banyak memberikan petuah berharga, yang menjadi kekayaan batin serta membentuk pribadi anak-anaknya. Seperti gemi, nastiti lan ngati-hati, yaitu hemat, tekun, dan selalu bersikap hati-hati (waspada). Juga pepatah open dan kopen, yaitu sikap merawat serta memelihara segala sesuatu.
Suatu hari, Sang Ibu marah melihat orang yang tidak menghabiskan makanan yang telah diambilnya, sehingga terbuang. Dalam keyakinan Sang Ibu, orang yang menyia-nyiakan nasi (makanan) akan mendapat kutukan dari Dewi Sri berupa paceklik panjang yang mengakibatkan kekurangan pangan dan terjadinya pagebluk.
Ketika itu, belum ada sekolah di Kemusuk. Masalah pendidikan belum menjadi kebutuhan utama masyarakat. Namun, oleh Sang Ibu, pendidikan sudah merupakan kebutuhan dan keharusan bagi anak-anaknya. Maka Probo kecil harus bersekolah di Desa Pedes, sekitar tiga kilometer dari rumahnya. Setiap hari, dia harus berjalan kaki pulang-pergi dari rumahnya ke sekolah.
Pada zaman Jepang, 1942-1945. Probo masih duduk di Sekolah Dasar. Saat itu banyak diajarkan nyanyian perjuangan melawan sekutu Inggris dan Amerika dan juga lagu-lagu perjuangan Jepang dan disiplin yang sangat mengesankan. Tiap pagi menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yakni Kimigayo. Usai itu siswa diajak menghadap ke arah utara untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Siswa kemudian diajak menghadap lagi ke Kepala Sekolah, Leo Yadira, yang sudah siap berpidato memberikan pengarahan dan petunjuk mengenai budi pekerti. Kemudian sebelum masuk kelas, harus berolahraga (taisooo) dengan diiringi lagu olahraga.
Pada malam hari, Probo yang pada zaman Jepang (sekitar 1943) baru berusia 13 tahun, setiap sore hari diminta ayahnya mengajar pemberantasan buta huruf anak-anak remaja, teman-teman seumuran kakaknya. Walau masih siswa kelas lima Sekolah Rakyat (SR), probo berani saja dan mampu mengajar pemberantasan buta huruf itu. Di samping mengajar membaca dan menulis, Probo juga mengajarkan nyanyian-nyanyian Jepang yang dipelajari di sekolah. Banyak nyanyian Jepang yang masih diingatnya hingga sekarang, seperti Miyoto, Kainoto dan Kainosoru.
Probo kecil menekuni sekolahnya. Dia pun melanjut ke SMP di Yogyakarta, yang berarti harus berjalan kaki lebih jauh lagi, sekitar 2 x 10 kilometer pulang-pergi. Perjalanan jauh yang melelahkan selama bertahun-tahun itu, tidak membuat semangat belajarnya surut. Bahkan sebaliknya, didorong dukungan ayah-ibunya, semangat belajarnya makin tinggi.
Agar tidak terlambat, dia harus berangkat subuh pukul 04.00 dan pulang malam hari. Sering kali dalam perjalanan pulang, Probo melihat bintang Kemukus atau bintang berekor. Kesempatan melihat bintang Kemukus, bagi orang Jawa, dipandang sebagai pertanda bahwa terhadap yang bersangkutan akan terjadi sesuatu yang besar.
Setelah lulus SMP, dia melanjut ke Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), juga di Yogyakarta. Pada saat itu, Probo sangat merasa senang dan bangga. Pasalnya, dia tidak harus berjalan kaki lagi menuju sekolah. Sebab kakaknya, Soeharto, yang telah menjadi tentara dan berpangkat Letnan Kolonel (Letkol), memberinya sepeda. Suatu hal yang masih langka dimiliki anak-anak di desanya kala itu.
Probo menekuni sekolahnya. Sang Ibu memberinya dorongan untuk berprestasi. Dia memang merasa paling dekat dengan Sang Ibu. Dalam kenangannya, Sang Ibu tidak pernah merasa lelah mengasuh, mendidik dan menabung sedikit demi sedikit untuk biaya sekolah anak-anaknya.
Sang Ibu juga selalu menjenguk Soeharto, kakak Probo, yang ikut bibinya di Wuryantoro, Wonogiri. Kala menjenguk Soeharto, Sang Ibu selalu membawakan oleh-oleh serta uang simpanannya untuk jajan.
Sang Ibu sering melakukan tirakat, loro lopo dan gedhe prihatine. Pada saat Soeharto masih dalam kandungan, misalnya, Sang Ibu melakukan puasa ngebleng yang nyaris merenggut nyawanya. Semua itu dilakukan Sang Ibu sebagai permohonan kepada Tuhan agar diberi kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan anak-cucu serta keturunannya. Juga sebagai ekspresi rasa syukur sepanjang hidup kepada Allah atas karunia drajat, semat dan pangkat.
Sikap Sang Ibu ini telah menanamkan prinsip dan makna kehidupan bagi anak-anaknya bahwa hidup tidak hanya ditimbang dari dunia fisik melainkan juga harus ditimbang dari kehidupan rohani. Sikap rohani itu harus diamalkan dalam tutur kata, serta harmoni dengan lingkungan, baik dengan keluarga maupun tetangga dengan harus saling menghormati satu sama lain.
Begitu pula keteladanan Sang Ayah yang mampu mengayomi dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sang Ayah menanamkan nilai-nilai kejuangan kepada anak-anaknya. Semua masalah selalu dihadapi dan diatasi, dalam kondisi sesulit apa pun semasa penjajahan Belanda sampai Indonesia Merdeka.
Perpaduan pribadi kejuangan Sang Ayah dan kasih kerohanian Sang Ibu yang sedemikian rupa membuat suasana rumah tangga mereka sangat rukun dan tenteram. Suasana itu membuat Probo dan saudara-saudaranya mereguk kebahagiaan semasa kecil. Bahkan suasana keluarga tenteram itu telah membentuk sikap dan perilaku mereka dalam mengarungi mahligai kehidupan kemudian hari.
Pejuang Cilik
Proses pengasuhan orang tua, telah membentuk pribadi Probo memiliki nilai-nilai kerohanian dan kejuangan yang tinggi. Pada usia 16 tahun, Probo sudah ikut bergerilya. Dia seorang pejuang cilik, termuda, dalam pasukan gerilya yang dikenal dengan nama pasukan Tedjo Eko (komandannya Tedjo Eko).
Walaupun kemudian, pasukan ini terpaksa ditinggalkannya, karena banyak melakukan penjarahan terhadap warga kota. Probo yang memiliki semangat kejuangan yang tulus demi bangsanya mengambil sikap meninggalkan pasukan ini.
Pada 1946, saat Probo ikut bergerilya, Sang Ibunda tercinta meninggal karena penyakit kanker kandungan yang dideritanya. Kala itu, seorang saudaranya menemui Probo yang sedang bergerilya dan memberitahu meninggalnya Sang Ibu. Betapa terperanjatnya Probo mendengar berita itu.
Lalu, Probo berusaha mencari Soeharto yang pada waktu itu sedang melakukan perlawanan gerilya terhadap penjajah Belanda di Semarang. Namun, dia tidak berhasil menemukan Soeharto. Dengan sangat kecewa, Probo pulang ke desa Kemusuk untuk melihat wajah Sang Ibu terakhir kali.
Kakaknya, Soeharto, bersama teman-temannya bekas PETA dan Heiho, pada 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang nantinya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Yogyakarta. Ketika pembentukan BKR itu, Soeharto dipercaya sebagai Kepala Penerangan. Kemudian, setelah Proklamasi, ketika pembersihan markas Jepang di Kota Baru, Soeharto menjadi pemimpin pasukan sebagai Komandan Batalion X dengan pangkat Mayor.
Ketika Belanda melakukan tindakan pendudukan kembali, tahun 1949, Probo yang sudah remaja merasa tidak senang. Ketidaksenangan itu dilampiaskannya dengan mengganggu penjajah itu. Biasanya pada sore hari tatkala banyak orang sudah beristirahat, Probo malah menggunakan kesempatan itu menghalau sapi yang sedang berkubang di tengah sawah hingga berlari kencang ke arah asrama Belanda. Padahal sore hari, biasanya Belanda sedang mandi-mandi di sungai.
Begitu melihat aksi Probo menghalau sapi ke arah asrama, Belanda itu sangat marah. Probo dikejar-kejar diteriaki sebagai londo, bahkan memberondongnya dengan tembakan senjata. Jika sudah demikian, Probo segera terjun ke lembah agar terhindar dari tembakan. Tetapi, suatu ketika, dua sahabatnya menjadi korban. Yang satu perutnya terkena tembakan sampai ususnya keluar, satu lagi kakinya terkena peluru.
Probo punya banyak cara mengganggu sekaligus menunjukkan ketidaksenangan terhadap pendudukan Belanda, terlebih setelah Ayahnya meninggal dunia Januari 1949 akibat ditembak serdadu Belanda.
Bersama kakak perempuannya, Probo sering berangkat dari desa Kemusuk menuju kota Yogyakarta, mengunjungi Bu Harto yang ditinggal pergi oleh Pak Harto bergerilya. Dari desa Probo biasanya membawa oleh-oleh beras atau kelapa.
Ketika kembali ke desa, Probo suka berjalan menyusup sembunyi-sembunyi supaya jangan sampai ketahuan Belanda. Belanda suka sekali melakukan patroli. Setiap pemuda yang ketahuan melintasi jalan-jalan dihabisi.
Pasalnya, Desan Kemusuk dikenal Belanda sebagai kampung kelahiran Pak Harto. Di sana setiap Jumat Belanda mengadakan pembersihan seisi sudut kampung habis diobrak-abrik.
Pada 1949, Probosutedjo ikut gerilya lagi. Dia bergabung dengan pasukan KODM (Komandan Onder Distrik Militer, setingkat Koramil sekarang). Komandannya bernama Asikin, masih satu kampung dengannya. Dalam pasukan itu, Probo memang berusia paling muda namun memiliki semangat juang paling tinggi. Ia berani menyusup-nyusup ke mana-mana.
Ketika itu Soeharto sudah menjabat Komandan Resimen 22 dengan pangkat Letnan Kolonel. Seoharto berjuang melawan Belanda di Semarang, kemudian menjadi Komandan Wehrkreise III memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang dikenal dengan peristiwa 6 jam di Yogyakarta yang pada waktu itu telah menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Belanda memburu Soeharto sampai ke desa Kemusuk, tapi tidak menemukannya. Sampai pasukan Belanda merasa putus asa dan marah.
Suatu ketika seorang kepala keamanan kampung ditangkap, dipaksa menunjukkan lokasi persembunyian keluarga Pak Harto termasuk Probo. Siang hari persis jam tiga pada 8 Januari 1949 hari Jumat Kliwon, Belanda mengadakan pembersihan di desa Kernusuk.
Setiap laki-laki, terutama pemuda yang ditemukan Belanda, ditembak mati. Pada pembersihan hari pertama 23 orang pemuda ditembak mati. Kemudian sesudah Serangan Umum 1 Maret 1949, korban yang ditembak Belanda berjumlah 126 orang, termasuk 62 orang anggota Brimob.
Kala itu, Probosutedjo berada di desa Kemusuk. Di tenga berondongan peluru tentara Belanda, dia pulang ke rumah untuk mengambil senjata sekalian menemui ayahnya. Namun, Sang Ayah kemudian menyuruhnya segera menyelamatkan diri bersama adiknya Soewito. Seraya menggandeng adiknya, Probo memanggul senjata yang tadinya disimpan di kamar. Tentara Belanda mengejar dan menembaki ke arah Probo dan adiknya.
Probo sambil membawa Sang Adik, terus saja berlari ke arah selatan, sesekali berbelok ke rumah-rumah penduduk menghilangkan jejak, lalu dari utara menyeberang rel menuju selatan. Setelah melewati gundukan tanah rel kereta api, keduanya terlepas dari kejaran tentara Belanda. Probo dan Adik selamat.Namun Sang Ayah dan ratusan pemuda desa menjadi korban rentetan tembakan peluru tentara Belanda.
Menjelang magrib, Probo menyelinap dengan sangat hati-hati berusaha pulang ke rumah. Firasatnya menuntun untuk pulang. Sekitar pukul setengah tujuh malam, dia tiba di rumah.Dan ternyata dia menemukan Sang Ayah telah gugur. Dia pun menghela nafas, bersyukur masih bisa melihat wajah Sang Ayah untuk terakhir kalinya.
Di situlah Probo baru tersadar bahwa hari itulah pertemuan yang terakhir kali dengan Sang Ayah dalam keadaan masih sama-sama hidup.Mula-mula Probo tidak sadar sudah kehilangan orang terkasih. Ia hanya merasa tambah panas hati terhadap Belanda.
Waktu pulang dan tiba di rumah Probo tersadar, sebab menyaksikan seorang kakak dan adek perempuan terkecilnya usia empat tahun, disertai seorang pengasuh, menangis sesunggukan saling berpelukan. Dalam isakan tangis, Probo diberitahu kalau Ayah mereka sudah meninggal dunia ditembak Belanda.
Karena situasi darurat, jenazah Sang Ayah pun segera dimakamkan di pemakaman keluarga Wongso Menggolo, di daerah Gedong. Tidak sempat disandingkan dengan makam Sang Ibu di pemakaman Gunung Pule, pemakaman keluarga pendiri desa Kemusuk, Wongso Menggolo, terletak persis di pegunungan. Tanahnya terdiri batu-batuan. Dalam kondisi darurat terasa tak mungkin menggali kuburan berbatuan dalam waktu singkat. Jasad jenazah Sang Ayah saja tak sempat lagi dibungkus kain kafan. Hanya bungkusan seadanya yang melilit.
Probo bersama saudaranya menjadi yatim-piatu. Sang Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia, tahun 1946, akibat terkena penyakit kanker kandungan. Saat ayahnya meninggal, Probo baru berusia 18 tahun. Namun, dia tidak mau larut dalam kesedihan. Dia meneguhkan hati dengan tekad meneruskan cita-cita kedua orang tuanya sebagai pejuang.
Probosutedjo selalu mengenang ayahnya sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan desa Kemusuk, tanah kelahirannya, dari penjajah Belanda. Dan, sejarah membuktikan bahwa kelak salah seorang putra desa Kemusuk menjadi seorang pejuang, Jenderal Besar, dan pernah menjadi pemimpin bangsa dan negara selama 32 tahun.
Ikut Sang Kakak
Sebelum ibunya meninggal, Probosutedjo diajak kakaknya Mayor Soeharto tinggal bersama di Yogyakarta. Kala itu, Mayor Soeharto masih bujangan dan tinggal di rumah yang cukup besar di Jalan Merbabu No. 2A Yogyakarta.
Mereka hanya tinggal berdua di rumah itu. Di sinilah pertama kalinya Probo tinggal di rumah yang sudah ada listrik dan lantainya dilapisi karpet. Probo terpesona dan sangat senang tinggal bersama kakaknya. Soeharto membimbingnya untuk selalu menjaga kebersihan dan bertanggung jawab. Tanpa disuruh pun, Probo setiap pagi bertanggung jawab membersihkan rumah, mengambil air dan mengisi bak serta menyetrika pakaian. Pada waktu itu air ledeng tidak bisa sampai ke dalam rumah.
Kedua kakak-beradik ini sangat bahagia tinggal di rumah besar itu. Namun rumah itu terasa lengang dengan beberapa kamar yang masih kosong. Untuk mengatasi kesepiannya, Probo senang bergaul dengan beberapa tukang batu yang kebetulan bekerja di rumah itu, di antaranya bernama Pak Merto. Pak Merto, sering mengobrol dengannya hingga malam, bercerita tentang agama dan wayang. Cerita Pak Merto itu sering membuat Probosutedjo tertidur.
Sampai suatu ketika, Amir Murtono, mencari rumah datang bertamu. Kepada Probo, Amir Murtono menyatakan hasratnya untuk tinggal di salah satu kamar yang belum terpakai di rumah itu. Probo menyambutnya dengan senang hati, karena dia memang memerlukan teman.
Kenangan bahagia lainnya saat tinggal bersama kakaknya adalah menunggang kuda. Seringkali Soeharto menyuruhnya mengembalikan kuda tunggangannya ke Markas Batalion X. Probosutedjo yang kala itu baru berusia 15 tahun sangat merasa gagah dan bangga menunggang kuda meskipun hanya sebatas jarak dari rumah ke Markas Batalion X.
Rasa bangga dan gagah juga memenuhi kenangan Probo, tatkala bersama Soeharto, sering pulang ke desa Kemusuk memakai mobil dinas sedan Chevrolet. Apalagi jika warga desa Kemusuk melihatnya, rasa bangganya bertambah besar. Namun, nasehat Sang Ibu tetap membimbingnya untuk rendah hati.
Kemudian, 1947, Soeharto menikah dengan RA Siti Hartinah (Ibu Tien). Jika sebelum menikah Soeharto selalu membawa jatah makan ke rumah, lalu sesudah menikah tidak boleh lagi. Karena ada peraturan bahwa tentara yang sudah kawin tidak boleh mengambil jatah makanan untuk di rumah.
Sehingga Ibu Tien selalu menyediakan kebutuhan makan sehari-hari. Probo yang tetap tinggal bersama kakaknya meski sudah berkeluarga, merasa berbahagia dan tetap membantu seperti sediakala.
Kebiasaan Probo di Desa Kemusuk suka bercocok tanam, diterapkannya dengan menanam berbagai jenis sayuran, antara lain bayam dan terong, di rumah yang pekarangannya cukup luas dan kurang terpelihara.
Berjiwa Mandiri
Tak lama sesudah Belanda mundur dari kota Yogyakarta, Probosutedjo dipercayakan menangani Koperasi Kas Desa. Koperasi yang merupakan lumbung desa itu berfungsi mengumpulkan padi dari berbagai desa. Saat ditanganinya, roda kehidupan desa semakin membaik. Jumlah padi yang dikumpulkan semakin banyak, mencapai ratusan ton. Dia pun mendapat gaji yang cukup lumayan.
Namun, kesibukannya mengurusi Kas Desa membuat semangat dan waktu belajarnya menjadi berkurang. Sehingga dia tidak sempat lagi melanjutkan sekolah. Saat itu, dia sudah kelas dua SMEA. Apalagi ketika itu, meski sudah bekerja di Koperasi Lumbung Desa, Probo masih belum merasa puas. Dia ingin mandiri dan merantau ke Sumatera karena tidak ingin membebani kakaknya, Soeharto. Akhirnya, Probo memutuskan keluar dari sekolah.
Keputusan ingin hidup mandiri, itu semakin menggelora tatkala ada kesalahpahaman dengan Ibu Tien. Bermula saat Probo mengizinkan Sudwikatmono mengambil tanaman bayam yang ditanaminya. Sore harinya, Ibu Tien ingin memetik bayam, yang ternyata sudah habis. Probosutedjo terkena getahnya, dia dimarahi Ibu Tien. Ketika itu, perasaan Probosutedjo sangat nelongso.
Probo memutuskan untuk berangkat merantau, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-21, 1 Mei 1951. Dia menjual sepeda pemberian kakaknya untuk menambahi uang simpanannya yang tidak cukup sebagai bekal hidup. Tujuannya ke kota Medan. Menuju Medan, dia singgah di Jakarta menginap di Merdeka Selatan, tempat tinggal Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Kebetulan Kepala Bagian Rumah Tangganya bernama Hendro Budjono kenal baik dengan kakaknya. Hendro Budjono yang tidak berkeluarga seperti terkejut mendengar keinginan Probosutedjo mencari pekerjaan ke Sumatera. Namun Hendro tak bisa menghalangi, hanya bisa menggeleng-kan kepala. Karena tekad Probosutedjo sudah bulat untuk meretas jalan hari depannya yang lebih baik secara mandiri. Penulis: Ch. Robin Simanullang – ht-mlp | Bio TokohIndonesia.com |
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA