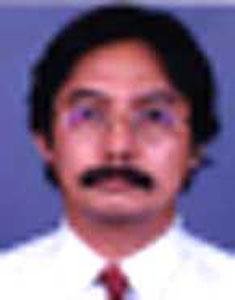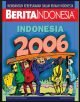Prabowo, Civilphobia, dan Naluri State-Centered
Stabilitas Jadi Tujuan, Kritik Dianggap Gangguan

Pernyataan Prabowo soal demonstrasi mengisyaratkan cara pandang yang dibayangi civilphobia dan naluri state-centered – di mana stabilitas dijunjung sebagai tujuan utama, sementara kritik cenderung dilihat sebagai suara yang mesti dikendalikan, bukan dijadikan sandaran refleksi kekuasaan.
“Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif dong!” – Prabowo Subianto, April 2025
Pernyataan itu keluar dalam forum terbuka, saat Presiden Prabowo menjawab pertanyaan seputar kondisi sosial-politik terkini, termasuk gelombang demonstrasi yang sempat mengisi ruang-ruang publik. Bukan kalimat yang mengejutkan, tapi mencengangkan – karena datang dari pemimpin tertinggi negara yang sedang menghadapi kegelisahan sipil.
Dalam wawancara terbuka dengan tujuh jurnalis senior pada Minggu, 6 April 2025, Prabowo melanjutkan:
“Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. It’s public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih.”
Alih-alih menyambut kritik publik sebagai tanda vitalitas demokrasi, Prabowo memilih narasi penuh kecurigaan: bahwa demo bisa dibayar, bisa ditunggangi, dan bisa didanai pihak asing. Maka pertanyaannya kini mengemuka: apakah Prabowo sedang memperlihatkan gejala civilphobia – ketakutan berlebihan terhadap masyarakat sipil yang bersuara?
Civilphobia bukanlah istilah yang umum digunakan di ruang publik Indonesia, namun ia sangat terasa. Ini bukan sekadar ketidaksukaan terhadap protes, tapi persepsi mendalam bahwa masyarakat sipil tidak sepenuhnya otonom, bahwa mereka mudah diarahkan oleh kekuatan luar, bahwa ekspresi mereka tidak selalu tulus.
Gejala ini kentara dalam pernyataan Prabowo berikutnya:
“Kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat.”
Dan juga:
“Enggak usah merusak. Enggak usah merusak pagar. Enggak usah merusak stasiun base, terminal base. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat.”
Pernyataan terakhir sebenarnya valid. Tidak ada yang membenarkan demonstrasi yang berujung pada perusakan fasilitas publik. Tapi yang lebih menggelisahkan adalah pola pikir dasarnya: bahwa demonstrasi cenderung diasosiasikan dengan gangguan. Dan lebih dari itu, dicurigai sebagai agenda yang dibayar.
Mereka yang mengikuti perjalanan Prabowo sejak lama tentu paham, bahwa latar belakang militernya membentuk cara berpikir yang sangat state-centered – negara sebagai pusat stabilitas, dan setiap potensi gangguan harus dicegah bahkan sebelum tumbuh. Dalam kerangka seperti ini, masyarakat sipil yang protes bukan sekadar pengkritik, tetapi pengganggu ketertiban nasional.
Dan ini bukan semata soal ideologi. Ini adalah warisan psikologis dari medan operasi militer: saat musuh bisa menyamar sebagai rakyat, dan kecurigaan adalah alat bertahan hidup. Lalu pola itu terbawa saat Prabowo kini menjabat sebagai presiden. Ia ingin mendengar, tapi tetap menaruh curiga. Ia menghormati hak, tapi membatasi makna.
Wawancara bersama tujuh jurnalis senior pun menunjukkan karakter itu dengan jelas. Ketika Najwa Shihab menanyakan soal proses legislasi yang tertutup, Prabowo mengaku bahwa RUU memang belum dibuka. Tapi ia tidak menjanjikan perubahan. Saat Uni Lubis menanyakan logika prioritas legislasi, Prabowo menjawab panjang, normatif, dan berputar-putar. Ia mendengar – tapi tak selalu siap dikoreksi.
Dalam wawancara itu, publik melihat seorang Prabowo yang lebih tenang, lebih naratif, dan bahkan menyentuh secara emosional. Ia bicara tentang telur rebus untuk anak-anak miskin, tentang ibu-ibu yang masak untuk sekolah, tentang Danantara dan swasembada pangan. Tapi pada saat berbicara soal masyarakat sipil yang berdemo, ia seperti berubah menjadi figur yang curiga dan normatif. Di sinilah kekontrasan itu muncul: antara empati sosial dan kendali terhadap suara politik.
Fenomena civilphobia dan state-centered mindset bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat cerminan pola yang sama dalam banyak pemimpin dunia. Di Rusia, Vladimir Putin dengan tegas membubarkan LSM dan menuding oposisi sebagai antek asing – ekspresi klasik civilphobia. Di Tiongkok, Xi Jinping menempatkan partai dan negara sebagai otoritas tunggal atas kebenaran, dengan menekan kebebasan akademik dan sipil. Di Turki, Recep Tayyip Erdoğan menyebut demonstran sebagai pengkhianat negara pasca-Gezi Park, dan menangkapi ribuan akademisi serta jurnalis yang kritis.
Di Indonesia sendiri, warisan state-centered paling kentara berasal dari era Orde Baru Soeharto. Saat itu, protes diidentifikasi sebagai gangguan terhadap pembangunan. Media dibredel, demonstrasi dibungkam, dan masyarakat sipil hanya diberi ruang jika tunduk pada narasi negara. Bahkan dalam era reformasi, bayang-bayang itu belum sepenuhnya hilang. Susilo Bambang Yudhoyono, meski lebih demokratis, beberapa kali menunjukkan gestur civilphobic ringan – yakni kepekaan berlebih terhadap kritik publik. Ia kerap mengeluhkan kritik yang dianggap terlalu keras atau ‘tidak adil’, dan cenderung merespons kritik dengan perasaan pribadi alih-alih kebijakan struktural.
Kini, Prabowo berada di titik yang sama: sebuah titik persimpangan sejarah. Ia bisa memilih jalan lama – yang memusatkan kekuasaan, menaruh curiga pada partisipasi, dan menjaga stabilitas dengan cara mengeraskan ruang publik. Atau ia bisa menciptakan jalan baru – yang berani mendengar, memberi ruang koreksi, dan memahami bahwa kekuasaan sejati bukan diukur dari seberapa tenang jalanan, tapi seberapa terbuka pendengaran seorang presiden.
Dalam sistem demokrasi, protes publik bukan aib. Ia adalah detak jantung republik yang hidup. Maka ketika suara-suara sipil bergema di jalanan, tugas seorang presiden bukan bertanya siapa yang membayar, tapi mendengar apa yang disuarakan. Seorang presiden boleh mencurigai informasi. Tapi tidak boleh mencurigai niat rakyatnya sendiri tanpa dasar.
Kalimat seperti “apa demo itu murni atau dibayar” memang terbuka untuk tafsir, tapi dalam konteks kekuasaan, itu bisa menjustifikasi represi. Dan di negeri dengan sejarah panjang pembungkaman, sinyal seperti ini berbahaya. Presiden seharusnya berkata: “Saya mendengar suara rakyat. Kita akan pastikan semua kanal partisipasi terbuka. Tapi mari kita jaga agar demonstrasi tetap damai dan bermartabat.”
Kalimat itu sederhana, tapi penuh kejelasan. Tidak menghakimi. Tidak menuduh. Dan tidak merendahkan integritas masyarakat sipil.
Tidak ada demokrasi yang sempurna. Tidak semua demonstrasi murni. Tapi justru karena itu, negara harus hadir dengan komitmen untuk membedakan mana kritik, mana provokasi; mana suara tulus, mana agenda tersembunyi. Dan membedakan itu perlu kedewasaan, bukan kecurigaan refleksif.
Prabowo mungkin belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Tapi ia punya kesempatan. Menjadi presiden bukan hanya soal memimpin ekonomi dan pertahanan – tapi soal mendengarkan, bahkan saat suara itu datang dari jalanan yang bising. Karena suara dari jalanan, bagaimanapun riuhnya, tetap lebih jujur daripada ruang rapat yang sunyi tapi penuh bisik kompromi.
Pada akhirnya, pemimpin dengan civilphobia cenderung menyayangi rakyat, tapi mencurigai suara mereka. Pemimpin dengan pandangan state-centered cenderung melihat bahwa stabilitas lebih penting daripada partisipasi. Keduanya bisa lahir dari trauma sejarah, dari pendidikan militeristik, atau dari budaya politik yang tidak memberi ruang negosiasi. Tapi demokrasi yang matang hanya bisa lahir jika pemimpin berani mempercayai rakyatnya – bukan sekadar mengaturnya. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)