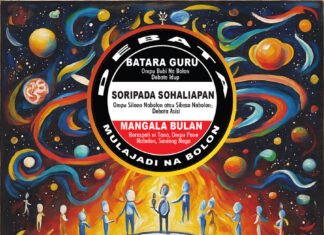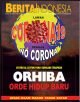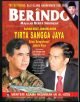Sosok Sederhana Gagasan Besar
Maswadi Rauf
[DIREKTORI] Prof Dr Maswadi Rauf MA, guru besar ilmu politik yang sederhana tapi penuh dengan gagasan besar dan berani. Pria kelahiran Teluk Kuantan, Riau, 15 Februari 1946 ini, melempar gagasan tentang perlunya partisipasi politik masyarakat untuk menciptakan negeri ini menjadi lebih baik.
Sosok dan Pemikiran Maswadi, Impian Akselerasi Aktualisasi Pancasila
Ruang kerjanya di Gedung B Lantai II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tidak besar, hanya tiga meter persegi. Isinya sederhana, cuma dua meja dan satu set komputer. Tetapi, di sana banyak buku dan tempat dia membimbing para kandidat doktor politik.
Ruangan itu seakan mencerminkan sang empunya. Prof Dr Maswadi Rauf MA, guru besar ilmu politik yang sederhana tapi penuh dengan gagasan besar dan berani.
Sejak 25 tahun lalu, ketika negeri ini masih dipimpin rezim otoriter Orde Baru, pria kelahiran Teluk Kuantan, Riau, 15 Februari 1946 ini, sudah melempar gagasan tentang perlunya partisipasi politik masyarakat untuk menciptakan negeri ini menjadi lebih baik.
Masyarakat Indonesia perlu “partisipasi persuasif” agar mereka bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik. Demikian kata Maswadi saat itu seperti dikutip harian ini, 22 Juni 1981.
Gagasan Maswadi secara tidak langsung banyak mendorong percepatan demokratisasi di negeri ini. Tahun 1997 ketika muncul keinginan menunda pemilu, dia termasuk yang mendorong agar pemilu terlaksana. Menurut dia, mungkin ada orang menganggap pemilu tidak demokratis, tetapi lebih tidak demokratis lagi kalau pemilu ditunda.
DPR dan MPR pun banyak disempritnya kalau keluar garis. Pada 1990-an, Maswadi sudah mengkritik sikap para legislator yang tak berani bersikap berbeda dengan eksekutif, kurang kritis, dan kurang aktif mengajukan usul ke pemerintah. Sebaliknya, dia juga menunjuk sikap seorang menteri dan stafnya yang menganggap enteng saran dan pandangan anggota Dewan.
Maswadi juga termasuk yang paling awal mempertanyakan kelayakan MPR, yang pada tahun 1990-an sebanyak 57,5 persen anggota MPR tidak dipilih langsung oleh rakyat. “Alangkah baiknya apabila hanya sebagian kecil saja dari anggota MPR yang diangkat,” kata Maswadi dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap pada FISIP UI, 1 November 1997.
Kini, setelah bangsa ini memasuki era reformasi, gagasan-gagasan itu sudah banyak yang menjadi kenyataan. Namun, banyak juga yang belum tapi sudah terekam menjadi cita-cita banyak orang. Maswadi pun masih aktif menyampaikan gagasan besarnya, termasuk tentang Pancasila, seperti disampaikan dalam perbincangan dengan Kompas, beberapa hari lalu.
Menurut Maswadi, sejak awal bangsa Indonesia sudah bertekad mengambil Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan konsensus nasional. Pada masa-masa awal, Pancasila dianggap sebagai alternatif jawaban bagi dua ideologi besar, liberalisme dan komunisme. Bangsa Indonesia kini pun tetap menganggap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi final. Tidak ada yang ingin mengganti dengan yang lain. Berikut cuplikan perbincangan dengan Maswadi.
Mengapa Pancasila dibicarakan lagi sekarang ini?
Saya pikir ada dua penyebab. Pertama, dulu itu kita sibuk dengan hal-hal yang lebih konkret sehingga Pancasila untuk sementara dilupakan, tapi bukan untuk dihilangkan. Bagaimanapun, bangsa Indonesia tetap memerlukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai konsensus nasional yang merupakan basis bagi terwujudnya negara.
Alasan kedua, Pancasila tidak lagi banyak disebut karena Pancasila yang ditafsirkan Soekarno dan Soeharto dianggap bukan perwujudan sesungguhnya. Soekarno dengan demokratisasi terpimpin, sedangkan Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Keduanya itu hanya penafsiran.
Saat ini ideologi pun telah dirasakan menjadi kebutuhan sebagai basis konsensus nasional. Kalau tidak ada konsensus, kita akan menghadapi masalah mendasar dalam hidup bernegara.
Kita membuang Orde Baru, tapi tidak membuang Pancasila. Kita masih beranggapan Pancasila diperlukan dan baik, tapi belum mengetahui isinya. Artinya, kita harus mencari bentuk konkret dari Pancasila.
Pancasila sering dikatakan berasal dari bumi Indonesia. Tetapi, Soekarno dan Soeharto tidak pernah menunjukkan hal itu. Keduanya justru tidak ingin memperjelas Pancasila karena dengan kaburnya Pancasila, mempermudah penafsiran sesuai keinginan masing-masing.
Harusnya nilai-nilai ideal Pancasila dikonkretkan menjadi pedoman untuk bertindak sehari-hari dalam hidup bermasyarakat dan diterjemahkan dalam konsep dan struktur.
Liberalisme dan komunisme itu jelas. Liberalisme, misalnya, menginginkan kebebasan, yang diwujudkan dalam partai politik, pemilu, kebebasan berserikat berkumpul dan berpikir, serta ada kontrol rakyat terhadap eksekutif. Nilai-nilai liberalisme tidak hanya disimpan, tetapi diimplementasikan dalam sistem politik. Komunisme juga jelas, tak menghendaki kebebasan karena dianggap berbahaya. Karena itu, menjadikan negara sebagai satu-satunya penentu.
Bagaimana mengembangkan nilai Pancasila?
Pancasila mesti diwacanakan oleh publik. Tiap orang dapat memberi masukan dan pikirannya. Ideologi tidak mungkin berasal dari atas seperti yang dilakukan Soekarno dan Soeharto. Ideologi mesti dibiarkan berkembang dalam masyarakat. Nantinya akan terjadi seleksi alamiah mana yang dijadikan nilai-nilai bangsa. Ini memang akan memakan proses lama, karena kita tidak punya seorang Karl Marx. Soekarno hanya filsuf yang masih bicara umum. Nilai-nilai yang diajarkan Marx juga telah dijabarkan oleh Lenin. Nilai-nilai yang diajarkan Soekarno tidak ada yang menjabarkannya. Soeharto juga bukan filsuf. Tokoh-tokoh Orde Baru tidak ada yang mampu menjabarkan nilai Pancasila sehingga menjadi mandek.
Soekarno dan Soeharto telah membuat Pancasila mandek lalu ditafsirkan sendiri. Masih beruntung, bangsa ini tidak menghujat Pancasila. Kita menghujat Soekarno, tapi Pancasila tetap dipertahankan oleh Soeharto. Kita menghujat Orde Baru, Pancasila juga tetap dipertahankan. Saat MPR mengamandemen UUD 45, Pancasila tetap dipertahankan walau ada keinginan diabadikan.
Kalau mau mendapat contoh, bagaimana wacana publik mampu menghasilkan ideologi itu adalah liberalisme. Kalau kita melihat bagaimana berbagai ide para filsuf itu saling berinteraksi sama lain dan berinteraksi dengan masyarakat, liberalisme juga contohnya. Itu membuat liberalisme berkembang menjadi ideologi yang matang. Sementara itu, komunisme lebih banyak dibentuk dari atas, dan cenderung dipaksakan, akhirnya menjadi tidak berakar dan tidak awet.
Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebuah ide yang bagus, tapi belum bunyi dan belum bisa diaplikasikan menjadi lebih konkret dan bisa dijadikan pedoman berpolitik.
Sistem pemerintahan apa itu saya juga belum tahu. Tetapi, harus lain dari sistem parlementer, juga presidensial. Kalaupun ada kesamaan, harus ada warnanya. Ini pekerjaan besar. Tanggung jawab terletak pada intelektual dan yang peduli mengenai kehidupan bernegara.
Yang menentukan adalah proses pergulatan nilai-nilai itu di dalam masyarakat. Di Barat, datangnya kedaulatan rakyat juga tidak tiba-tiba. Liberalisme seperti mozaik yang disusun dari lempengan-lempengan kecil. Pancasila juga harus seperti itu, tapi tidak mungkin harus menunggu 200-300 tahun. Karena itu, harus ada akselerasi kristalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat.
Bagaimana agar perdebatan tidak membahayakan?
Kita perlu kembali memperteguhkan tekad bahwa kita menginginkan Pancasila sebagai ideologi. Kalau tidak ada tekad itu, maka akan membuka pertarungan antar-ideologi. Di Barat tidak ada pertanyaan ideologi. Malaysia juga sudah menganut liberalisme, tidak ada lagi debat. Kalaupun ada, kualitasnya lebih rendah, bukan mengganti ideologi, tapi memperdebatkan implementasi.
Perdebatan ideologi pernah dialami bangsa Indonesia pada 1950-an, antara Pancasila, Islam, dan komunisme. Pertarungan ini sangat abstrak dan di belakangnya ada fanatisme dan ini berbahaya. Jadi persoalan kita ke depan adalah membicarakan apa isi Pancasila. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, nilai Pancasila itu harus berbeda dari dua ideologi besar itu atau ideologi lain. Kedua, harus lebih baik dari liberalisme karena komunisme sudah hancur.
Bagaimana dengan peran pemerintah dan partai politik?
Pemerintah perlu membentuk tim-tim pengkaji, tapi membebaskan mereka untuk menyampaikan pemikiran. Pemerintah pun memfasilitasi untuk memublikasikannya. Pemerintah harus bisa menstimulasi, tapi tidak bisa mengambil alih karena hal itu yang menjadi kegagalan BP7. Dulu BP7 sibuk dengan ideologi terbuka, tapi dia sendiri tidak pernah membuka debat dan berbagai kemungkinan alternatif. Pemerintah hanya bisa membantu akademisi untuk mengkaji.
Parpol pun bisa ikut berwacana, bahkan bisa memberi warna tersendiri. Yang harus dihilangkan adalah keinginan parpol untuk menang sendiri dan tak siap menerima kekalahan. Saat ini parpol belum bergerak ke sana. Parpol belum sama sekali membicarakan ideologi. Masih nol besar.
Setelah jatuhnya Orde Baru, wacana Pancasila masih nol besar karena masih banyak yang alergi dan takut. Ekonomi Pancasila yang sempat dilontarkan Prof Dr Mubyarto (almarhum) juga sempat dihujat habis-habisan.
Dengan mengembangkan wacana, maka akan banyak orang tertarik dan memberikan sumbangan. Yang penting penguasa jangan melarang orang membicarakan Pancasila dan mengambil alih kebenaran Pancasila.
Porsi intelektual
Dalam kondisi ekonomi yang terpuruk seperti ini, menurut Maswadi, rakyat belum bisa diharapkan terlalu banyak membicarakan Pancasila. Kalau dipaksakan, orang malah banyak akan antipati. “Nanti setelah keadaan ekonomi membaik. Baru kita buka peluang diskusi,” ucapnya.
Menurut Maswadi, yang penting ada jaminan bahwa Pancasila itu tetap ada. Soal penjabaran “Mungkin sekarang baru porsinya intelektual. Banyak gagasan saya baca, tapi belum ada satu pun yang menyinggung tentang substansi,” ucapnya.
Kapan gagasan besar Maswadi sendiri soal substansi Pancasila akan keluar, dia sendiri belum bisa menentukannya. Dia hanya menjawab dengan rendah hati, “Terus terang belum dapat…. Sebegitu sulitnya. Sebab itu harus lebih baik dari ideologi lain dan original.” Kita tunggu saja. (Sutta Dharmasaputra, Kompas 10 Juni 2006). TI