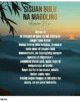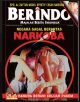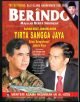Meniti Karir dari Lapangan, Tawarkan Agropolitan
Soenarno
[ENSIKLOPEDI] Ia seorang menteri yang meniti karir dari lapangan. Insinyur sipil (UGM) yang ‘ahli air’ (IHE Delft, Netherland), ini menjalani hidup ‘laksana air mengalir’. Lebih 22 tahun, secara terus-menerus, bertugas di lapangan (proyek). Ia berhasil memimpin beberapa proyek besar dengan berbagai kesulitan teknis dan sosialnya. Karir pria Solo yang santun, rendah hati dan relijius, ini mencapai puncak, jadi Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil), pada era reformasi. Ia pun menggugah: “Kenapa kita tidak kembali saja kepada nature bangsa ini sebagai bangsa agraris?” Untuk itu, ia pun menawarkan konsep agropolitan, jangan metropolitan.
Penulis disertasi ‘Dampak Pembangunan Irigasi pada Sikap Petani’, ini sangat konsern atas konsep agropolitan yang diyakininya sangat pas bagi Indonesia sebagai negara agraris, untuk mencegah urbanisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan.”Konsep yang kita tawarkan adalah mari membangun agropolitan, jangan metropolitan,” kata doktor (S3) program Civil Engineering, Columbia Pacific University, San Rafael, California, USA (1982) dan program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Malang (1985), ini dalam percakapan dengan watawan Tokoh Indonesia di ruang kerjanya, Kamis 27 Februari 2003.
Konsep agropolitan ini ditawarkannya dalam rangka memberdayakan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistim agrobisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat serta pemanfaatan sumber daya alam secara holistik di pedesaan. Konsep ini sangat diyakininya mampu untuk mengurangi kemiskinan struktural, mendukung ketahanan pangan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang luas dan merata. Sebuah konsep dengan sasaran akhir tercapainya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan lainnya, dengan memperhatikan hak, asal-usul dan adat-istiadat desa melalui pembangunan yang holistic dan berkelanjutan.
Pria kelahiran Solo 19 Mei 1942 yang akrab disapa Mas Narno, ini menjelaskan, dengan agropolitan kita membangun desa-desa yang menjadi pusat-pusat produksi pertanian yang beraneka-macam. Dan sekaligus membangun industri-indutri kecil yang mengolah hasil-hasil pertanian desa itu. Sehingga ada nilai tambah kepada masyarakat setempat. Dengan demikian penduduk tidak lagi terus mengalir ke kota-kota.
“Jadi sebaiknya basis kita ke depan adalah agropolitan. Kita harus mencegah urbanisasi dengan mengembangkan desa. Infrastruktur desa diperkuat. Kemudian produksi di pedesaan diperkuat dengan memberikan berbagai insentif. Konsep ini sangat tepat bagi Indonesia sebagai negara agraris,” kata penerima Piagam Penghargaan dalam Pengembangan Reformasi Sistem Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (1998) ini.
Konsep ini, boleh dibilang, sebagai reformasi yang mengoreksi kebijakan percepatan pengembangan industri metropolitan selama ini. Yang ketika krisis terjadi, menjadi terhenti karena 10 persen dari pergerakan industri berasal dari luar negeri dan sangat menentukan. Maka, ia menggugah: “Kenapa kita tidak kembali saja kepada nature bangsa ini sebagai bangsa agraris?”
Konsep ini sudah ia tawarkan kepada beberapa menteri terkait, seperti, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Nnegeri. Sementara, di departemennya, sudah dicoba diterapkan di beberapa daerah pada tahun 2003 ini. Ia berharap, ke depan semua provinsi memiliki model-model argopolitan yang meluas. Walaupun disadari proses ini akan berjalan panjang dan dapat terjadi friksi dengan keinginan-keinginan untuk terus mengembangkan industri (metropolitan). Padahal, sebaiknya yang dikembangkan adalah industri yang berbasis pertanian.
Selain itu, prasarana dan sarana transportasi juga merupakan bagian penting untuk keberhasilan konsep agropolitan ini. Ia yakin dengan terbangunnya prasarana dan sarana transportasi hingga ke desa-desa, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih merata.
Ketua Dewan Penyantun Universitas Diponegoro, ini menyadari kondisi prasarana dan sarana transportasi, khususnya jalan, masih jauh dari kebutuhan, terutama di luar Jawa. Maka, ia heran kenapa para mahasiswa di daerah ikut-ikutan demo mengenai kenaikan tarif tol di Jakarta. Padahal, kenaikan tarif tol di Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membangun prasarana jalan di daerah lainnya.
Sehingga, menurutnya, kebijakan adil adalah mendorong APBN untuk dialihkan ke daerah dan pelosok terpencil. Tetapi masyarakat mengartikan jika ada kenaikan tarif sepertinya rakyat yang disengsarakan. Rakyat yang mana? Jalan tol hanya ada di Jakarta dan kota-kota besar saja. Memang tarif tol jangan sampai meyusahkan rakyat kecil seperti menaikan tarif bis. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai mobil lima, tarif tol dinaikan harus diterima.
Sehingga dengan begitu, APBN dapat bergeser ke daerah dan pulau-pulau terpencil. “Saya kalau melihat kondisi daerah-daerah pedalaman, jadi kasihan. Kalau kita tidak melihat visinya ke arah itu, nanti bobotnya ke Jawa terus. Padahal daerah-daerah di luar Jawa telah banyak memberikan subsidi bagi Jawa,” kata Dosen Luar Biasa Fakultas Teknik Universitas Negeri Brawijaya Malang ini.
Pembangunan prasarana jalan ini, menjadi salah satu fokus kebijakan departemen yang dipimpinnya, di samping masalah pemukiman (perumahan) dan masalah sumber daya air. Ketiga masalah ini menjadi fokus perhatiannya, yang merupakan bagian dari empat tugas pokok departemennya (Kabinet Gotong-Royong) yakni penciptaan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa, pemulihan ekonomi, pemberantasan KKN dan penegakan hukum.
Ketiga fokus perhatiannya langsung menyentuh kepentingan hidup masyarakat banyak. Ia memang seorang figur yang sangat peduli kepada wong cilik. Masa kecil hingga remajanya, tampaknya sangat mempengaruhi kepribadian dan kepeduliannya kepada masyarakat kurang mampu.
Ketika ia masih berusia 6 tahun, ayahnya yang bekerja sebagai inspektur di BPM (sekarang Pertamina), meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Ia tidak begitu banyak mengenal sosok ayahnya. Ia bersama 6 saudaranya diasuh oleh ibunya yang bekerja sebagai guru agama di wilayah Solo. Hidup keluarga ini hanya pas-pasan. Figur Sang Ibu sangat dominan membentuk pribadinya. Sejak kecil, ibunya telah menanamkan landasan keagamaan kepadanya dan saudara-saudaranya.
Ia dibekali pendidikan agama yang cukup panjang. Bahkan selain bersekolah di sekolah umum, ia juga bersekolah di sekolah Madrasah untuk belajar bahasa Arab, sejarah Islam dan sebagainya. Sampai lulus SMA, ia bersekolah di Solo. Semasa SMA ia sudah ikut mengajar membantu ibunya di beberapa sekolah yang sebagian tingkat SLTP, untuk membantu menopang ekonomi keluarganya.
Setelah lulus SMA, ia kuliah di UGM. Namun ia tetap mengajar di beberapa sekolah di Solo. Tidak lagi hanya di tingkat SLTP dan SLTA, bahkan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Ia sendiri merasa mempuyai bakat mengajar. Sehingga sampai sekarang pun ia masih menyempatkan waktu mengajar di Universitas Muhammadiyah Solo sebagai dosen tetap. Juga senang dan sering memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi. Serta sering menjadi pembicara di berbagai seminar di dalam negeri dan luar negeri. “Saya ingin masih bisa terus mentransfer ilmu dan pengetahuan saya kepada generasi-generasi berikutnya,” ujarnya.
Kehidupan keberagamaan yang taat, berperilaku sopan dan santun telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupannya sejak kecil. Bekal itulah yang tetap melekat padanya selama ini. Serta mempengaruhinya untuk meneruskan kepada kerabat dan mahasiswa-mahasiswanya untuk memiliki hal-hal yang sifatnya baik. Seperti budi pekerti, harus bersifat jujur, adil terhadap sesama. Itu ajaran yang tetap ia pegang dan diteruskan kepada para mahasiswa maupun kerabatnya.
Ia orang yang biasa menjalani hidup ini apa adanya. Filosofi hidupnya, ‘seperti air mengalir’. Filosofi ini tidak hanya slogan. Secara nyata, ia memang orang yang menjalani hidup ini laksana air mengalir. “Air mengalir tetapi tidak mempuyai daya rusak, jangan sampailah. Air sebagai sumber kehidupan, tapi kalau diganggu dapat meledak-ledak juga,” katanya sambil tertawa.
Karena terbiasa hidup ‘seperti air mengalir’ di tengah kesibukannya sebagai Menkimpraswil pun, setiap hari pulang ke rumah antara jam 9 sampai jam 10 malam, ia kelihatan seperti tak kenal lelah. Penampilannya jauh lebih muda dari usianya yang sudah 61 tahun. Ia pun masih bisa makan apa saja. Belum ada pantangan karena faktor kesehatan. Olahraganya hanya jalan kaki dan pernapasan.
Saat ini ia sudah menjadi seorang kakek atas tiga orang cucu. Setiap ada kesempatan isterahat di rumah, ia bercengkerama bersama cucunya. Ia kini memang tinggal di rumah hanya bersama isteri, Soepanti Prodjodiwirjo, dan cucunya. “Jika dengan cucu, rasanya mengingatkan kembali masa kecil,” ujarnya mengungkap kehidupan kesehariannya di rumah.
Ia juga berusaha mengasuhkan ketaatan beragama dan sopan-santun kepada anak-cucunya sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini. Menurutnya, orang tua sekarang harus mempunyai kemampuan dalam menjelaskan secara logika hal-hal apa sajakah sebetulnya yang diminta agar anak-cucu mempuyai sopan santun dalam berbahasa, berkomunikasi dan dalam bekerja.
Kehidupan apa adanya laksana air mengalir, ia jalani juga ketika masih kuliah di UGM. Ia tidak indekos. Tidak bisa seperti anak kuliah lainnya yang mampu indekos. Setiap hari ia harus naik kereta api dari Solo ke Jokja. Harus berangkat dari rumah sejak subuh. Kadang-kadang ia tidak pulang, menginap di rumah teman di Jokja. Waktu itu belum ada sistem absen. Jadi ia bisa (sering) tak masuk kelas, namun selalu mengikuti ujian. Ia banyak menggunakan waktu untuk bekerja, mengajar. Namun, ia selalu berupaya menggunakan kesempatan belajar di luar kelas.
Ia menyadari dirinya berasal dari keluarga yang tidak cukup mampu. Walaupun ayahnya pernah menjabat sebagai kepala perminyakan Jawa-Madura. Tapi mereka tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Hidup mereka tergantung kepada pencaharian ibu sebagai guru saja. Sehingga setelah lulus dari UGM (Universitas Gajah Mada), ia berusaha segera mencari pekerjaan untuk membantu ibu. Pekerjaan apapun yang ada waktu itu ia terima.
Pekerjaan pertamanya, di luar mengajar, adalah di proyek Brantas Jawa Timur, Nopember 1967. Ia bekerja di sana selama 17 tahun. Beberapa bulan setelah bekerja ia menikah dengan Soepanti Prodjodiwirjo, 23 Maret 1968 dan dikarunia empat orang putra-putri masing-masing Diah Ayu Kusumadewi, Zaafri Ananto Husodo, Ratna Ayu Puspitasari dan Rino Ardhian Nugroho, yang semuanya lahir di sana.
Ia merintis karir mulai dari pekerja harian sampai menjadi pimpinan proyek di tempat itu. Sebagai pekerja harian, statusnya belum PNS, ia digaji dari proyek itu sendiri. Baru setelah 4 tahun, ia diangkat menjadi pegawai negeri. Ia pun bersyukur karena pengabdiaannya selama empat tahun tersebut tetap menjadi pertimbangan dalam proses pengangkatan menjadi PNS.
Tahun 1970-1972 diangkat menjadi Kabag PLTA Proyek Karang Kates, unit kerja Proyek Brantas Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Ia pertama kali, menjadi pemimpin proyek bendungan Selorejo (Poyek Brantas), Karangkates, 20 km sebelah selatan kota Malang. Sebuah proyek bendungan cukup besar dengan ketinggian 100 meter yang masih jarang saat itu. Proyek itu dibiayai oleh papasan perang. Waktu itu ada tiga proyek yang dibangun dari biaya papasan perang yang dikerjakan secara paralel, yaitu Karang Kates dan Kali Kanto di Jawa, serta Meriam Kanan di Kalimantan.
Dari situ, ia ditugaskan memimpin proyek, dari satu proyek ke proyek lain. Di antaranya Pemimpin Proyek Bendungan Karang Kates (1975-77), Karang Kates (1977-79), Brantas Hilir (1979-80), Proyek Induk P.W.S.Kali Brantas (merangkap) Jawa Timur (1985), Proyek Induk P.W.S.Citanduy Jawa Barat (1985-88) dan Proyek Induk PWS Jratunseluna, Jawa Tengah (1988-91), yang lebih dikenal dengan proyek waduk (bendungan irigasi) Kedungombo. Sebuah proyek yang mengundang sikap pro dan kontra secara sosial, yang hingga sekarang masih memunculkan persoalan.
Sebagai salah seorang pimpinan di lingkungan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas, ia berperan pada berbagai pembangunan prasarana dan sarana pengairan antara lain pembangunan Bendungan Serba Guna Karang Kates, Bendungan Serba Guna Selorejo serta prasarana dan sarana pengairan lainnya seperti Cek Dam, Sabo Dam.
Demikian juga ketika menjabat sebagai Pimpinan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Citanduy, ia berhasil memimpin pengembangan daerah irigasi baru di wilayah sungai Citanduy. Sebuah sungai yang berada di bagian Selatan Jawa dan terkait antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi pertanian dan penanggulangan banjir di Jawa Barat bagian tenggara.
Setelah tiga tahun di proyek Citanduy, ia ditugaskan memimpin Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratun Seluna, dimana terdapat aliran 5 sungai, yang salah satu proyek besarnya adalah waduk Kedungombo. Ia ditugaskan di sana ketika proyek tersebut sudah berjalan pada tahap pembebasan tanah dan mengalami kesulitan dalam proses pembangunannya dari segi teknis dan segi sosialnya. Proyek ini, antara lain bermanfaat untuk irigasi, pengendalian banjir, pembangkit tenaga listrik dan sumber air baku untuk berbagai kepentingan industri dalam upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya.
Dalam proses pembangunan Waduk Kedungombo, itu ia ditantang untuk menyelesaikan banyak masalah baik teknis maupun sosial yang krusial. Ia melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ada beberapa kelompok masyarakat yang berbeda pendapat dan kepentingan. Contohlnya, ada sekelompok masyarakat yang cenderung dekat lingkungan Kraton Solo, yang berpendapat dan berkepentingan berbeda dengan kelompok yang dekat dengan Semarang. Ia berupaya memfasilitasi dengan baik kelompok yang berbeda-beda itu. Walaupun diakui, belum dapat menampung seluruh aspirasi semua kelompok masyarakat.
Sehingga, menurut penulis berbagai karya ilmiah, ini proyek waduk Kedungombo ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita semua. Ia secara pribadi sampai saat ini memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di sana. “Bahkan sering mereka datang ke sini. Ya, sekedar silaturami saja. Kadang-kadang saya juga berkunjung ke kampung dan rumah mereka. Karena saya dan mereka tidak ada persoalan. Yang ada hanya persoalan yang mereka yakini tekanan-tekanan tertentu dari penguasa,” katanya betapa ia bisa bersosialisasi dan menyelami kepentingan masyarakat setempat.
Kemudian, dari sana (Kedungombo), setelah mengalami proses bekerja sangat panjang di lapangan, setelah ia berusia lebih 50 tahun, akhirnya ia ditarik ke pusat, menjadi Kepala Pusat Data dan Pemetaan (1991-93). Inilah saatnya ia dipromosikan ke dalam jabatan struktural di tingkat eselon dua. Sebelumnya, sebagai kepala proyek, ia tidak memiliki jabatan struktural, hanya jabatan fungsional.
Saat menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Pemetaan, ia kembali belajar dalam menekuni bidang tersebut. Sebuah pekerjaan yang bervariasi untuk mengepalai sebuah unit yang mengelola data dan pemetaaan yang memang sangat penting dalam setiap proses proyek pembangunan PU waktu itu. Sebab PU tanpa data dan peta, tidak bisa berbuat apa-apa.
Sebagai Kapus Data, ia merintis pengembangan sistim informasi yang menyeluruh di lingkungan DPU. Yang diwujudkan dengan dukungan nyata pengembangan sistim jaringan on line pada masing-masing instansi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal di lingkungan DPU.
Begitu pula saat menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan DPU (1993-98), ia menghadapi permasalahan pembangunan yang sangat berorientasi sektoral. Sehingga ia berupaya memaksimalkan hasil pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum (PSPU) melalui pendekatan pengembangan wilayah dan sinkronisasi program menggunakan piranti Analytical Hierarchical Process (AHP).
Dalam pengembangan piranti lunak sinkronisasi program dengan AHP itu berbagai program antarsektor di lingkungan DPU dan pembangunan sektor-sektor lain di luar DPU disinkronkan, baik terhadap lokasi, fungsi, waktu maupun besaran program dan dana. Sehingga pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif.
Kemudian, ia dipercaya menjabat Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, Direktorat Jenderal Pengairan (1998). Saat itu, ia melakukan evaluasi penggunaan pinjaman luar negeri dari aspek cost, waktu dan manfaat. Sehingga dapat memperkecil kerugian negara karena inefisiensi dan inefektifitas terhadap sasaran.
Setelah itu, sempat menjadi Staf Ahli Menteri PU Bidang Kelembagaan (1998-99), sebelum diangkat menjadi Direktur Jenderal Pengembangan Perdesaan, Departemen Kimbangwil, pada awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Selaku Dirjen Pengembangan Perdesaan, ia berupaya mencari konsep dan langkah tepat untuk mempercepat pembangunan perdesaan secara holistik dan berkelanjutan, yang kemudian disebutnya sebagai konsep agropolitan.
Selain itu, saat menjabat Dirjen Pengembangan Perdesaan, itu ia juga telah mengubah suatu konsep organisasi mandiri pengoperasian dan pemeliharaan bendungan dengan membentuk Perum Jasa Tirta I. Perum Jasa Tirta I ini mengelola sumber daya air dari Bendungan Karang Kates secara lebih mandiri tanpa mengurangi aspek daya-guna untuk kepentingan masyarakat banyak. Sehingga proyek tidak lagi dibebani biaya operasi dan pemeliharaan. Kemudian, dalam perjalanan waktu, tahun 2002, telah dibentuk pula Perum Jasa Tirta II Bengawan Solo dengan maksud serupa.
Selanjutnya, bersamaan berubahnya Depkimbangwil menjadi Depkimpraswil, ia diangkat menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Mei 2001). Pada kesempatan ini, ia bertindak sebagai inisiator untuk reformasi peraturan kepengairan yang semula menekankan pada kebijakan pemerintah pusat (top-down) menjadi peraturan yang melibatkan swasta dan masyarakat (bottom-up) sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Undang-Undang Kepengairan. Selain itu, hasil pemikirannya telah banyak pula dituangkan dalam Rancangan Keputusan Presiden yang merupakan dasar pembentukan pengelolaan sungai, secara korporatisasi untuk wilayah sungai Jeneberang, Serayu-Bogowonto, Way Seputih-Way Sekampung.
Kemudian, pada pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri (Kabinet Gotong-Royong), ia mencapai karir puncak, diangkat menjadi Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (09-08-2001-2004). Suatu jabatan yang yang tak pernah dikejar-kejarnya. Ketika itu, ia sendiri mengaku tidak menduga akan diangkat menjadi menteri. “Karena saya tahu masih banyak orang lain yang kenal dekat dengan beliau, seperti Ibu Erna Witoelar yang juga sangat menguasai bidang ini,” katanya.
Walaupun memang saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, ia sudah mengenal Megawati sebagai ketua umum PDI-P. Ketika itu, ada sebuah program yang terkait dengan Departemen PU yang berhubungan dengan air. Selanjutnya, ketika Megawati menjabat wapres, dan ia sebagi Dirjen, beberapa kali bertemu dalam rapat-rapat kabinet dan kunjungan pembangunan di kawasan timur seperti Lombok, Sumbawa.
Namun demikian, ia merasa kaget juga ketika Presiden Megawati meneleponnya pada hari Rabu malam, sekitar pukul 20.00 WIB. “Mas, bisa bantu saya dalam bidang yang selama ini digeluti?” sapa Presiden Megawati. Ia sejenak merasa kaget. Ketika ditelepon itu, ia sendiri tidak tahu pada departemen apa akan ditunjuk. Waktu itu, apakah di Meneg PU atau di Menkimpraswil atau yang lainnya. “Tapi waktu itu, saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan beliau dan saya berjanji untuk membantu dengan baik.”
Ia sendiri, ketika itu, sedang mempersiapkan pernikahan anak keduanya yang akan dilaksanakan di Solo. Isterinya sudah duluan berada di Solo. Maka, ia pun tidak serta-merta memberitahu kepada isterinya. Besok paginya ia berangkat ke Solo. Di sana baru diberitahu kepada isteri tentang telepon Ibu Mega itu.
Banyak orang menilai, pengangkatannya sebagai Menkimpraswil itu sangat tepat. Kompetensinya di bidang ini tidak diragukan. Ia kaya pengalaman tentang bidang Kimpraswil (dulu pekerjaan umum) ini. Karena ia orang yang meniti karir lama di lapangan dan punya latarbelakang pendidikan yang sesuai untuk bidang itu. Belum lagi, selama perjalanan karirnya, ia pun telah menerima berbagai penghargaan sebagai bukti (piagam) pengabdiannya.
Di antaranya, Piagam Penghargaan PELITA II (1980), Satyalancana Pembangunan (1982), Piagam Penghargaan, atas peran sertanya dalam rangka Penanggulangan Jembatan Comal (1989), Piagam Satyakarya 20 Tahun (1989), Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (1991), Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (1995), Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (1997), Piagam Penghargaan dalam Pengembangan Reformasi Sistem Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (1998) dan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2000).
Ia juga seorang putera bangsa yang aktip di beberapa organisasi, terutama organisasi profesi. Ia kini menjabat Ketua Umum Komite Nasional Indonesia – International Commission on Irrigation and Drainage (KNI-ICID) sejak tahun 2000. Juga sebagai Majelis Penilai Komisi Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB) dari 1998 â sekarang. Di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga duduk sebagai Majelis Penilai Insinyur Profesional dari 1996 â sekarang. Anggota International Commission On Large Dam (ICOLD-Indonesia) dan anggota International Association on Hydraulic Research (IAHR), serta anggota American Society of Civil Engineer (ASCE)
Selama menjabat Menkimpraswil, selain bertekad ingin mewujudkan konsep agropolitan, ia juga melakukan beberapa hal yang cukup menonjol dan responsif atas kebutuhan reformasi. Salah satu di antaranya adalah peninjauan kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 272-AlKPTS/1996 – Nomor: 434/KMK. 016/1996 tentang Pengoperasian Terpadu Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (Tomang-Cawang- Tanjung Prick-Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit-Grogol- Tomang) serta Penetapan Angka Perbandingan Pembagian Pendapatan Tol.
Peninjauan kembali ini menghasilkan dicabutnya SKB tersebut pada tanggal 8 Mei 2002. SKB ini dianggap oleh publik sebagai salah satu simbol perilaku KKN di era Orde Baru. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, adil dan kompetitif, terutama di bidang jalan tol.
Selain itu, ia juga menerbitkan Instruksi Nomor : 02/IN/M/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang-Jasa melalui Media Internet di Lingkungan Depkimpraswil. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa dengan menyampaikan informasi paket-paket pengadaan dan pelaksanaan pelelangannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 melalui media internet.
Disamping itu sedang dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur (hardware dan software), sumber daya manusia, dan berbagai perangkat hukum yang diperlukan untuk menuju pelaksanaan e-procurement (pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara interaktif dengan dukungan internet) secara penuh.
Hal tersebut dilakukan mengingat pentingnya transparansi sebagai salah satu ciri atau karakteristik dari terciptanya good governance, sekaligus sebagai wujud instropeksi bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan simpul kegiatan di lingkungan Depkimpraswil yang sangat rawan terhadap penyimpangan dan kebocoran.
Dengan langkah-langkah tersebut, secara bertahap tapi pasti, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Depkimpraswil diharapkan berjalan semakin bersih dan bebas dari KKN. Sehingga akan dapat meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, kesetaraan, penegakan hukum, keadilan, dan lain sebagainya.
Pelaksanaan e-procurement ini disambut positif oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Majalah Dwimingguan Warta Ekonomi yang telah melakukan penilaian terhadap tidak kurang dari 400 situs pemerintah. Penilaian ini menobatkan Depkimpraswil sebagai lembaga pemerintah pengaplikasi E-Government terbaik pertama untuk kategori departemen. Penganugerahan award tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2002 yang dihadiri oleh Presiden.
Ia juga salah satu sosok yang membidani lahirnya Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), khususnya KAPET DAS KAKAB Kalimantan Tengah dan KAPET Bukari di Sulawesi Tenggara, yang menjadi tanggung jawab DPU pada waktu itu. Selaku Ketua Tim Badan Pengembangan KAPET, ia sangat menyadari bahwa salah satu kendala utama dalam pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sehingga pendekatan KAPET dinilai menjadi salah satu entry point yang patut digunakan.
Di bawah kepemimpinannya, di lingkungan Depkimpraswil, perhatian terhadap KAPET dan Kawasan Timur Indonesia ini dapat dilihat dari mulai berimbangnya alokasi anggaran yang disediakan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Kini, setiap tahun anggaran baru, di Depkimpraswil telah berkembang wacana untuk mengkaji kebutuhan dukungan prasarana dan sarana di wilayah KAPET untuk dipertimbangkan pembiayaannya.
Bersama Menteri Koordinator Perekonomian, ia telah meletakkan dasar- dasar pengembangan Institusi Badan Pengelola KAPET dengan time frame bantuan anggaran APBN yang jelas dan evaluasi kinerja KAPET yang dibahas sampai ke dalam Forum Sidang Kabinet Terbatas. Sehingga treatment terhadap KAPET dapat dilakukan secara lebih spesifik.
Ia juga memfasilitasi kunjungan rombongan duta besar dan dunia usaha ke wilayah KAPET untuk melihat secara langsung potensi dan peluang investasi yang dapat dikembangkan. Sekaligus memberikan dorongan kepada Badan Pengelola KAPET untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah, mempertajam peluang investasi yang ada serta peningkatan upaya-upaya promosi. Sehingga dapat menjadi fasilitator yang handal dalam membuka kesempatan pengembangan ekonomi di daerah.
Penerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan (1982), ini juga sangat concerned (terpanggil) dalam penegakan hukum, tentunya dalam rangka mewujudkan good governance. Terutama terhadap berbagai kasus penyimpangan yang terjadi selama ini. Namun tetap berpegang pada rasa kemanusiaan. Sehingga agar penegakan hukum benar-benar dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang aspiratif, maka ia sangat konsisten mendorong penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak up to date lagi.
Sehubungan dengan itu, ia sangat aktif memberi berbagai arahan substantif terhadap penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti penyusunan dan pembahasan RUU tentang Bangunan Gedung, Sumber Daya Air, Jalan dan lain-lain. TI