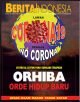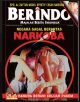[OPINI] – Oleh Dr. Paul Budi Kleden SVD | Agama menjadi bingkai pemikiran mengenai dunia dan menawarkan nilai dalam menyikapi permasalahan sosial. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebangkitan ini merupakan satu bentuk resureksi agama, atau lebih merupakan sebuah restorasi?
Dalam diskursus filosofis runtuhnya dua menara kembar di New York, agama menjadi tema yang mendapat perhatian yang semakin sentral. Tokoh seperti Juergen Habermas yang menyebut diri sebagai religioes unmusikalisch (tidak berbakat agama) pun mesti mengakui bahwa agama tidak dapat ditampik begitu saja dari kehidupan manusia ( post) modern.
Kubur-kubur yang digali para proklamator kematian agama ternyata tetap kosong. Resistensi agama terhadap berbagai upaya penghancurannya tidak dapat disebut sekadar sebagai sebuah kebertahanan. Yang kita hadapi dewasa ini bukanlah semata kenyataan bahwa agama-agama bertahan hidup.
Lebih dari itu, agama-agama juga mengalami kebangkitan. Berdampingan dengan ekstremitas sekelompok warga dunia yang tidak hanya bersikap indifferent terhadap agama, tetapi juga secara tajam merumuskan gagasan dalam ateisme radikal,dewasa ini dijumpai dalam semua kelompok agama gejala kebangkitan agama.
Orang yang beragama secara resurektif tidak terutama membanggakan diri karena jumlah penganut yang banyak atau kemeriahan peribadatan. Tanpa mengurangi makna dari jumlah penganut dan ibadat, yang menjadi komitmen orang beriman yang resurektif adalah pemanfaatan peluang yang diberikan oleh jumlah yang besar dan impuls dari kegiatan ritual untuk perjuangan mengangkat martabat kemanusiaan dan melindungi alam dari penghancuran.
Bukan Sekadar Restorasi
Restorasi adalah pemulihan. Yang menjadi rujukan restorasi adalah kejayaan masa lalu. Pemulihan berarti rekonsiliasi dengan suasana awali. Yang hilang hendak direbut, yang tercemar dikuduskan kembali. Di dalam penghayatan keagamaan, restorasi dapat tampak dalam dua bentuk.
Pertama, agama terfiksasi pada dosa dan pelanggaran. Karena terobsesi pada pemulihan kemurnian ajaran dan perilaku, agama seperti ini cenderung mengarahkan perhatiannya pada pencarian dan pencegahan kesalahan.
Penghayatan keagamaan dalam lingkungan seperti ini berarti ketepatan mengulangi ajaran,ketelitian menjalankan ritual, dan kepatuhan melaksanakan perintah. Penyimpangan dalam penyebutan nama Tuhan atau kreasi baru dalam ibadat dapat berakibat fatal.
Seorang teolog Jerman JB Metz menyebut pola beragama restoratif seperti sebagai satu bentuk Suendenabsolutismus. Agama mengabsolutkan dosa seolah keprihatinan utama Tuhan adalah kesalahan manusia. Dosa manusia dinilai sebagai penodaan terhadap kekudusan Tuhan.
Karena memandang diri sebagai pelindung Tuhan dari segala kemungkinan pencemaran, agama restoratif selalu berada dalam bahaya menjadi pembela Tuhan dan polisi moral. Bahaya restorasi dapat ditemukan dalam semua agama. Kemurnian ajaran dan kepastian ritus menjadi segala-galanya.
Agama-agama menanamkan mentalitas melalui pengajaran bahwa hal yang paling utama adalah kelurusan dalam mengulangi doktrin. Masalah kehidupan konkret yang terus berubah dan menuntut tanggapan aktual diabaikan.
Kedua, agama restoratif cenderung membela diri dan menutup kesalahan sendiri. Ketidaktercermaran Tuhan sering ditafsirkan sebagai kebebasan agama dari segala bentuk kelemahan. Obsesi pada ketidakbercelaan ini menjadi sebab orang menyangkal berbagai pelanggaran yang pernah terjadi di dalam dan atas nama agama.
Agama yang terpusat pada kemurnian diri mudah menjadi agama yang absolut. Karena mata diarahkan pada kesalahan pihak lain dan daya dikerahkan untuk menutupi kesalahan sendiri, penghayatan keagamaan seperti ini mudah terjebak dalam sikap merendahkan agamaagama lain.
Menjadi Agama Resurektif
Berbeda dengan restorasi adalah resureksi. Agama yang dihayati dalam semangat resurektif menjadi sumber inspirasi untuk memperjuangkan perubahan kualitas hidup manusia dan alam. Orang yang menghidupi agama seperti ini memiliki kepekaan terhadap penderitaan, merasa tergerak olehnya, dan berjuang untuk mengatasinya.
Dalam bahasa JB Metz, agama seperti ini menghayati Leidsempfindlichkeit atau keterbukaan terhadap penderitaan dan kesediaan untuk menanggapinya. Orang yang beriman dalam pola seperti ini sadar bahwa agama adalah sebuah panggilan untuk membela manusia, khususnya mereka yang dipaksa menderita secara tidak adil.
Dia tidak sekadar berjuang menegakkan ajaran agama dan menjaga kemurnian ritus, tetapi juga terutama menegakkan manusia yang bungkuk karena tertindih tekanan ekonomi, paksaan sosial, dan kamuflase politik serta memurnikan keluhuran martabat manusia.
Orang yang beragama secara resurektif tidak terutama membanggakan diri karena jumlah penganut yang banyak atau kemeriahan peribadatan. Tanpa mengurangi makna dari jumlah penganut dan ibadat, yang menjadi komitmen orang beriman yang resurektif adalah pemanfaatan peluang yang diberikan oleh jumlah yang besar dan impuls dari kegiatan ritual untuk perjuangan mengangkat martabat kemanusiaan dan melindungi alam dari penghancuran.
Doa yang dilantunkan kepada Tuhan dibarengi usaha nyata ke arah peningkatan mutu kehidupan manusia dan keutuhan lingkungan. Tuhan tidak hanya dimuliakan melalui kekhusyukan ibadat, tetapi juga melalui usaha nyata untuk menegakkan kebenaran dan membela keadilan.
Keterlibatan dalam pergumulan kemanusiaan ini hanya dimungkinkan oleh harapan pada Tuhan yang berkuasa membangkitkan yang mati. Kuasa membangkitkan hanya ada pada Tuhan, bukan pada agama.Agama resurektif menyadari perbedaan radikal antara Tuhan dan manusia serta institusi manusiawi mana pun,termasuk agama.
Kesadaran ini membuat agama resurektif lebih terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan agama-agama dan pandangan hidup lain. Dialog inter-religius ini dapat disebut sebagai inter-hope-dialogue, dialog antar, dan mengenai harapan. Agama resurektif menjadi penyulut harapan dan bukan horor yang menakutkan dan memangkas semangat hidup. Opini TokohIndonesia.com | rbh
Penulis Dr. Paul Budi Kleden, SVD, Dosen STFK Ledalero Maumere, Flores, NTT.