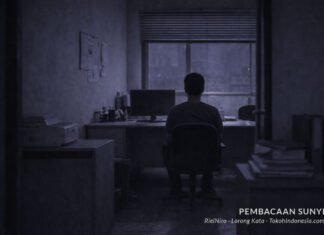Intelijen, Policymakers dan Pengawasan
Fungsi, Tugas dan Pengawasan BIN
Budi Gunawan Budi Gunawan Jejak Polisi Pembaharu Paradigma Think Win/Win: Budi Gunawan Berkhidmat Pusaran Aliran Air
Penulis: Ch. Robin Simanullang, Wartawan TokohIndonesia.com ||
Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, selama lebih sewindu, terbilang berhasil mengoptimalisasi fungsi dan tugas BIN dengan memasok berbagai produk yang actionable intelligence kepada Presiden Joko Widodo (Policymakers, user tunggal) dalam mengambil berbagai kebijakan penting, di antaranya, terkait keputusan hebat dan berani pemindahan Ibu Kota Negara. Baik juga ketika diperhadapkan pada tantangan netralitas, integritas dan loyalitas intelijen untuk ‘Berbicara Kebenaran kepada Pembuat Kebijakan’ yang belum tentu selalu sesuai pandangan dan kehendak politik penguasa (user), tetapi Intelijen mesti selalu bermafaat bagi pembuat kebijakan. Lalu, bagaimana pengawasannya? Bukankah pengendalian dari policymakers (eksekutif) dan pengawasan legislatif maupun publik atas intelijen adalah berpotensi politisasi?
Kepala Badan Inteijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan mengatakan, tugas intelijen semakin penuh tantangan. Peran dan fungsi intelijen saat ini dan ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks. “Tantangan itu berjalan sangat cepat sehingga harus terus-menerus dicermati dan diantisipasi oleh segenap jajaran intelijen negara,” kata Budi Gunawan dalam upacara hari jadi BIN ke-71 di Jakarta, Rabu (24/5/2017).[1]
Budi Gunawan mengatakan, dinamika situasi global dan regional, seperti ancaman terorisme, radikalisme, fundamentalisme, proxy war dan cyber war, semakin terlihat. Selain itu, persaingan dalam penguasaan sumber energi dan pangan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi nasional.
Prof BG menegaskan, BIN berkomitmen untuk terus membenahi dan menguatkan kelembagaan organisasi, kemampuan SDM maupun modernisasi peralatan teknologi intelijen untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut. Dalam hal ini, BIN juga bertekad untuk terus memberikan dharma bhakti pengabdian tanpa batas dengan segenap jiwa raga untuk setia, loyal, solid, dan semangat. Tujuannya untuk mewujudkan BIN yang semakin profesional, obyektif, dan berintegritas dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Dia berkomitmen, BIN akan semakin meningkatkan kinerjanya.
Perayaan HUT tersebut mengangkat tema Darma Bakti Pengabdian dan Jiwa Ragaku untuk Setia, Loyal, Solid, dan Semangat Guna Mewujudkan BIN yang Semakin Profesional, Obyektif, dan Berintegritas. Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan mengatakan, perayaan HUT BIN dimaknai sebagai suatu momentum untuk melihat kembali sejarah masa lalu melalui pengabdian BIN kepada bangsa dan negara. “Melakukan refleksi dan evaluasi perjalanan BIN serta mempersiapkan diri dengan proyeksi ke depan dalam rangka peningkatan peran dan kemampuan BIN (Intelijen Negara) sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional,” kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/2017).[2]
Apakah kepentingan nasional merupakan pedoman yang cukup bagi integritas, loyalitas dan netralitas, serta etika dan moralitas intelijen? Mark M. Lowenthal (2012) dalam Intelligence: From Secrets to Policy mengatakan, di satu sisi, itu adalah satu-satunya panduan. Menurutnya, jika aktivitas intelijen tidak dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang sah, maka aktivitas tersebut tidak ada artinya, atau itu operasi jahat yang paling berbahaya. Di sisi lain, pemerintah yang sah—bahkan yang menganut cita-cita dan prinsip demokrasi—terkadang bisa mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang dipertanyakan secara moral dan etika.[3]
Robert Jervis (2007) dalam Intelligence, Civil-Intelligence Relations and Democracy mengatakan, Intelijen dan badan intelijen sama-sama diperlukan bagi demokrasi dan sekaligus merupakan ancaman bagi demokrasi. Intelijen itu perlu dan berbahaya. Badan intelijen sangat penting dan merepotkan. Intelijen itu penting karena untuk berkembang, atau bahkan untuk bertahan hidup, negara harus memahami lingkungannya dan menilai musuh-musuh yang ada dan yang potensial. Tanpa intelijen yang baik, suatu negara akan bertindak secara membabi buta atau membiarkan ancaman semakin besar tanpa melakukan tindakan penanggulangan.[4]
Menurut Robert Jervis, adalah hal yang basi untuk mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa pengetahuan diperlukan agar kekuatan dapat digunakan dengan baik. Meskipun kita masih bisa memperdebatkan kontribusi intelijen terhadap kebijakan dan sejauh mana intelijen mampu melawan atau memenangkan perang, namun sulit dipercaya bahwa peran intelijen bisa diabaikan. Para pemimpin tentu saja menghargai intelijen; Winston Churchill menyebut pemecah kode sebagai “ayam” karena mereka membawakannya telur emas.
Di sisi lain, layanan intelijen juga bisa merepotkan, bahkan jika mengesampingkannya ketika mereka tidak memadai, bisa menimbulkan masalah. Robert Jervis mengatakan, jika pengetahuan (informasi) berkontribusi kepada kekuasaan, maka mereka yang mempunyai pengetahuan adalah orang yang kuat (powerful), itulah sebabnya badan intelijen yang tidak diatur dengan baik dapat mengancam para pemimpin dan warga negara. Hal ini terutama berlaku ketika lingkungan dan musuh yang perlu dipahami bersifat internal dan eksternal. Berdasarkan sifatnya, sebagian besar informasi intelijen bersifat rahasia dan banyak prosedur pengumpulan intelijen harus dirahasiakan dari pengetahuan publik. Hal ini juga membuat layanan tersebut berbahaya bagi demokrasi dan sulit dikendalikan. Pengawasan tidaklah mudah: beberapa pemimpin sipil tidak ingin mengetahui metode tidak menyenangkan apa yang digunakan atas nama mereka, sementara banyak badan intelijen menolak membagikan informasi ini, baik karena alasan keamanan yang sah atau karena keinginan untuk mempertahankan otonomi.[5]
Fakta bahwa badan intelijen mempunyai kemampuan menjaga kerahasiaan membuat mereka berguna untuk komunikasi “saluran belakang” secara internasional dan domestik. Namun hal ini juga berarti bahwa para pemimpin negara mungkin tidak yakin akan kegunaan lain dari informasi yang diberikan oleh organisasi intelijen, sehingga mereka mungkin kurang percaya pada badan intelijen tersebut. Ketidakpercayaan seperti itu kemudian dapat mempengaruhi para pemimpin tersebut untuk mengembangkan organisasi-organisasi yang lebih rahasia, dan seringkali informal, untuk bekerja di belakang badan intelijen yang sudah mapan, seperti yang dicatat oleh Doug Porch, yang sering terjadi di Prancis dan hal ini memang benar adanya, juga di Amerika pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon.[6]
Lalu, bagaimana pengawasannya? Apakah pengendalian dari pejabat politik (eksekutif) dan pengawasan dari anggota DPR (legislatif), bahkan pengawasan pers dan publik, berpotensi politisasi? Menurut Robert Jervis, pengawasan dan kontrol sipil berarti politik, dengan segala dampak baik dan buruknya. Politik juga dapat mempersulit intelijen dengan cara yang kurang jelas. Mereka (politisi sipil) yang mempunyai tanggung jawab pengawasan intelijen dapat memilih untuk mengungkapkan rahasia demi memajukan agenda substantif atau karir politik mereka. Robert Jervis memberi contoh, di tengah perjuangannya (yang gagal) untuk mempertahankan kursi Senatnya pada tahun 1979, Frank Church memilih untuk mengumumkan bahwa intelijen AS telah “menemukan” brigade tempur Soviet di Kuba, dan memicu badai diplomatik yang secara serius membuat kemunduran hubungan Uni Soviet-Amerika.[7]
Pengambil kebijakan (pemimpin politik) seringkali juga dipandang mempolitisasi Intelijen karena Intelijen harus berfungsi dan berperan mendukung kebijakan mereka. Dalam konteks ini, ‘mempolitisasi’ fungsi dan peran Intelijen sampai batas tertentu bisa dipandang sesuatu yang sulit ‘terhindarkan’ walaupun tak mesti sampai menjadi suatu ‘keniscayaan’.
Sebagaimana juga dikemukakan, Dr.Hans Born dan Dr. Loch K. Johnson dalam Balancing Operational Efficiency and Democratic Legitimacy (2003), ada yang berpendapat bahwa intelijen selalu dipolitisasi sampai batas tertentu, karena intelijen seharusnya mendukung keputusan dan prioritas kebijakan para pemimpin politik. Menurut mereka, memang benar, pengumpulan dan analisis informasi pada dasarnya dimaksudkan untuk digunakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Jika tidak, intelijen tidak akan relevan lagi dengan kepemimpinan politik. Namun, sebagai suatu kecenderungan umum, politisasi yang berlebihan terhadap badan intelijen mungkin sebagian disebabkan oleh demokratisasi pengawasan intelijen yang terjadi saat ini. Semakin besarnya peran parlemen dan komite pengawasnya dalam meninjau kegiatan intelijen, serta penghapusan seluruh kerahasiaan yang selama ini menyelimuti badan-badan intelijen, mungkin telah mengakibatkan peningkatan tekanan politik dan publik terhadap badan-badan intelijen tersebut.[8]
Menurut Hans Born dan Loch K. Johnson, pemerintahan yang terpilih secara demokratis tidak bisa lagi menolak memberikan komentar mengenai isu-isu intelijen; Pemerintah kini semakin terpaksa menggunakan strategi media yang rumit untuk memenangkan parlemen dan media demi kepentingan mereka, termasuk penggunaan “spin doctor” yang terkenal kejam. Bahayanya adalah politisasi intelijen akan meningkatkan sinisme, ketidakpercayaan, dan paranoia masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap badan intelijen dan sistem politik. Pertanyaannya adalah apakah politisasi intelijen disebabkan oleh proses demokratisasi dan perluasan pengawasan di dunia rahasia ini, atau fakta bahwa para pemimpin politik selalu mempolitisasi intelijen tetapi tindakan tersebut baru sekarang terlihat karena demokratisasi pengawasan intelijen yang terjadi saat ini.[9]
Dalam konteks Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Hakikat Intelijen Negara adalah merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Yang dimaksud dengan “lini pertama” adalah terdepan dalam sistem keamanan nasional dengan menyajikan Intelijen secara cepat, tepat, dan akurat dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugan Intelijen Negara tersebut, dilakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yang kita jabarkan menjadi enam mekanisme pengawasan Intelijen Negara, khususnya BIN, yakni: Pengawasan Internal mencakup: 1. Pengawasan Eksekutif, dan 2. Pengawasan Internal BIN. Pengawasan Eksternal mencakup: 3. Pengawasan DPR; 4. Pengawasan Lembaga Negara BPK; 5. Pengawasan Yudikatif; dan, 6. Pengawasan Masyarakat, Pers, LSM dan Civil Society.
Dalam penjelasan umum UU tentang eksistensi Intelijen Negara dijelaskan: “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.
Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.
Upaya mewujudkan tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.
Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.
Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (cyber war), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang takterbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah.
Perlu diwaspadai bahwa ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional tak sebanding) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.
Upaya untuk melakukan penilaian terhadap ancaman tersebut dapat terwujud dengan baik apabila Intelijen Negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun aktual. Guna mewujudkan hal tersebut, Personel Intelijen harus mempunyai sikap dan tindakan yang profesional, objektif, dan netral. Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan Personel Intelijen yang independen dan imparsial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.[10]
Itulah hakekat keberadaan Intelijen Negara yang diamanatkan dalam UU 17/2011 sebagai landasan etik dan moral serta payung hukum penyelenggaraan Intelijen Negara yang merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Budi Gunawan menyebutnya manusia perang pikiran yang harus mampu menerjemahkan security minded secara ilmiah dan mendalam, sehingga tindakan yang dilakukannya down to the earth atau membumi dalam mengamankan ibu pertiwi dari segala macam ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Insan intelijen sebagai prajurit perang pikiran yang berpikir ilmiah dengan ragam ilmu pengetahuan yang variatif agar segala tindakannya memiliki dasar kuat sehingga pengambilan keputusan tidak salah, terutama dalam mengatakan kebenaran kepada pengambil kebijakan, dalam kesetiaan tinggi mendukung kebijakan pemerintah yang sah, demi keamanan nasional dan kepentingan bangsa dan negara.[11]
Artikel Terkait:
- Perlukah Intelijen dalam Demokrasi?
- Paradoks Intelijen dalam Demokrasi
- Akuntabilitas Intelijen Selaras Demokrasi
Footnotes:
[1] Republika.co.id, 25/05/2017. Tugas Intelijen Semakin Berat. https://news.republika.co.id/berita/oqh06r313/tugas-intelijen-semakin-berat
[2] SINDOnews.com, 24/05/2017. Budi Gunawan: Tantangan Intelijen Semakin Berat dan Kompleks: https://nasional.sindonews.com/berita/1207811/14/budi-gunawan-tantangan-intelijen-semakin-berat-dan-kompleks
[3] Lowenthal, Mark M., 2012. Intelligence: From Secrets to Policy. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE/CQ Press, p. 310.
[4] Jervis, Robert, 2007. Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy; in Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness. Austin: University of Texas Press, p. vii.
[5] Jervis, Robert, 2007. Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy, p. vii-viii.
[6] Jervis, Robert, 2007. Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy, p. viii.
[7] Jervis, Robert, 2007. Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy, p. xii-xiii.
[8] Born, Hans, and Loch K. Johnson, 2003. Balancing Operational Efficiency and Democratic Legitimacy. In Born, Hans; Loch K. Johnson and Ian Leigh (Ed.); Who’s Watching the Spies: Establishing Intelligence Service Accountability. Washington: Potomac Books, p. 228.
[9] Born, Hans, and Loch K. Johnson, 2003. Balancing Operational Efficiency, p. 228.
[10] Undang-Undang RI No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Penjelasan.
[11] Gunawan, Budi, dan Barito Mulyo Ratmono, 2022. Membentuk Manusia Perang Pikiran. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, h. 139-140.