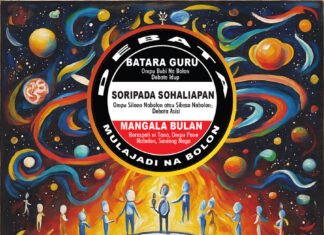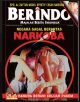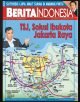Mendorong ‘Narsisisme’ Cagar Budaya
Eddy Supangkat
[WIKI-TOKOH] Eddy Supangkat galau. Begitu banyak bangunan cagar budaya di kota kelahirannya, Salatiga, Jawa Tengah, berganti bangunan modern yang seragam. Padahal, keindahan arsitektur bangunan kuno itu yang membuat semasa kolonial Belanda, Salatiga dijuluki “de schoonste stad van midden Java”, kota terindah di Jawa Tengah.
Suatu pagi pada pertengahan Januari 2010, Eddy Supangkat berjalan-jalan di Jalan Diponegoro, Salatiga. Langkahnya terhenti. Pemerhati cagar budaya dan penulis buku itu terpaku melihat seng mengelilingi pagar bekas Markas Kodim 0714 Salatiga, bangunan cagar budaya berusia sekitar 100 tahun, yang beberapa waktu sebelumnya diwacanakan bakal dijadikan pusat perbelanjaan modern.
Ia melihat beberapa pekerja sibuk memereteli atap bangunan yang pada masa penjajahan Belanda difungsikan sebagai hotel. Eddy lantas masuk ke dalam kawasan seluas 6.000 meter tersebut. Ia hanya bisa geleng-geleng kepala. Sang pemilik yang mendapat dukungan dari Wali Kota Salatiga John Manoppo, tanpa izin dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, nekat meruntuhkan peninggalan budaya itu meski polemik mulai berkembang di masyarakat.
Eddy hanya warga biasa yang mencintai sejarah kota. Ia tak punya organisasi. Namun, Eddy nekat menghubungi beberapa warga Salatiga di luar kota. Kecaman mencuat lewat situs jejaring sosial Facebook. Beberapa hari kemudian, Eddy bersama Nick T Wiratmoko dan Widya PS dari Lembaga Percik Salatiga dan Yakub Adi Krisanto dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana berkumpul di Kampung Percik.
Mereka menyepakati pembentukan Forum Peduli Benda Cagar Budaya (Forped BCB) Salatiga. Eddy diminta menjadi koordinator. Mereka ini yang menggalang aksi turun ke jalan, menuntut moratorium pembongkaran bekas Markas Kodim Salatiga. Aksi itu hanya dilakukan belasan orang, tetapi solid.
Wali kota Salatiga ngotot bahwa bangunan itu bukan cagar budaya. Forped BCB terus mengulang aksi. Belakangan, muncul teguran dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng yang memperingatkan Wali Kota agar “utak-atik” bangunan itu dihentikan dan pemilik meminta izin ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Tak lama kemudian, muncul hasil penelitian BP3 Jateng yang menyatakan eks Markas Kodim itu merupakan cagar budaya klasifikasi satu yang harus dikonservasi. Bangunan hotel itu dinilai sebagai penanda Salatiga sebagai kota pada zaman kolonial. BP3 Jateng juga mendesak bangunan yang sudah dipereteli atap dan kusennya, serta dijebol sebagian temboknya, itu direkonstruksi. Sesuatu yang sampai kini belum juga dipenuhi meski tak lagi ada penghancuran lanjutan.
Mendapat teror
Eddy mengaku, pengalaman baru terjun ke jalan itu memberi kesan bagus dan buruk. Baiknya, dia bersama rekan-rekannya di Forped bisa mencegah kehancuran (lagi) cagar budaya. Namun, buruknya, ia kerap diteror melalui telepon, misalnya mempertanyakan motivasinya atau ajakan bertemu. Bahkan, ada komentar bahwa aksi tersebut bertujuan agar bukunya, Salatiga, Sketsa Kota Lama dan Salatiga, Kota Seribu Nuansa, yang berkisah soal keindahan bangunan cagar budaya di Salatiga, laris.
“Enggak benar itu. Buku saya paling hanya ada beberapa ratus eksemplar. Kekhawatiran kami, kalau penghancuran BCB itu terus dibiarkan, Kota Salatiga akan kehilangan identitasnya,” ujar Eddy.
Hal ini bukan tanpa dasar. Menurut Eddy, setidaknya sudah lebih dari 70 bangunan cagar budaya di Salatiga lenyap. Misalnya, rumah dinas Wedana Salatiga yang kini menjadi kantor samsat dan ruko Salatiga. Tugu Beatrix menjadi lapangan parkir Mal Tamansari, beberapa rumah pribadi masa kolonial Belanda berubah menjadi pompa bensin. Selain itu, Hotel Berg en Dal yang menjadi pasar loak serta Tweede Europesche Lagere School yang kini jadi Pasar Blauran.
Namun, yang paling menggemaskan Eddy ialah hancurnya gazebo Gedung Pakuwon. Bangunan bekas kediaman Bupati Salatiga yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari Kantor Wali Kota Salatiga itu bertahun-tahun dibiarkan telantar. Belakangan, gazebo bangunan tersebut lenyap.
Padahal, Pakuwon tak hanya penting bagi Salatiga, tapi juga bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di gazebo Pakuwon, pada 17 Maret 1757, ditandatangani perjanjian Salatiga yang monumental. Lewat perjanjian itu, sebagian wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta diserahkan kepada Raden Mas Said. Ia kemudian diangkat menjadi Pangeran Adipati dengan gelar Mangkunegara.
Kegelisahan terhadap kehancuran cagar budaya itu yang akhirnya mendorong Eddy mengabadikan Salatiga tempo doeloe dalam bentuk buku, semisal Salatiga, Kota Seribu Nuansa (2001), Salatiga, Sketsa Kota Lama (2007), dan Galeria Salatiga (2010). Buku-buku itu menampilkan foto-foto Salatiga masa lalu beserta sedikit narasi sejarah. Namun, Eddy berkali-kali mengingatkan bahwa dia bukan sejarawan dan buku itu hanya buku memori, bukan buku sejarah.
Buku terakhir disusunnya setelah pembongkaran eks Markas Kodim. Ada semangat Eddy untuk mendokumentasikan benda cagar budaya sebelum kian banyak yang hancur. Karena itu, buku terakhir yang diterbitkan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda itu lebih kaya foto-foto lawas dan kini. Buku itu dicetak 800 eksemplar saja. Separuh dibagikan ke sekolah-sekolah di Salatiga. Separuh lainnya barulah dikomersialkan. Ia ingin mengajak anak-anak lebih “narsis” mengenal warisan budaya masa lalu.
“Kalau dilihat, orang Salatiga itu memang agak ‘narsis’ dengan kotanya. Bisa jadi ini karena kota kami kecil. Kenapa tidak ‘narsis’ itu untuk cagar budaya,” ujarnya.
Soal “narsis” orang Salatiga, kata Eddy, bisa dilihat dari percakapan jika orang Salatiga perantauan berkumpul. Mereka bisa dengan fasih membahas orang gila “legendaris”. Misalnya Min Kebo di Taman Sari atau Maryuni di Pasar Baru. Maryuni dikenal karena ia suka menggoda laki-laki yang ditemuinya. Konon, ia jadi gila karena laki-laki. e-ti
Sumber: Kompas, Selasa, 12 Oktober 2010 | Penulis: Antony Lee