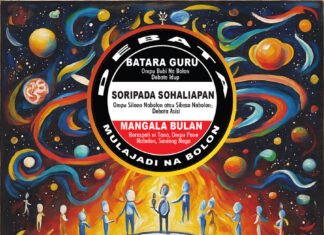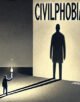Arsitek Pembentukan KPK
Romli Atmasasmita
[ENSIKLOPEDI] Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM adalah arsitek pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dialah yang mengarsiteki dan memimpin tim mulai dari persiapan, pembentukan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilanjutkan dengan persiapan dan pembentukan KPK. Romli berperan strategis selaku Ketua Tim Perumus RUU KPK dan Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang pertama.1]
Tidak berlebihan apa yang telah dikemukakan pakar hukum dan advokat senior Dr. Frans Hendra Winarta2] bahwa semua orang tahu Prof. Romli adalah arsitek pembentukan KPK. Pernyataan ini dikemukakan mengingat betapa besar peranan Romli dalam proses, mulai dari penyusunan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembahasan di DPR hingga disahkan menjadi UU; serta penyusunan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi hingga disahkan menjadi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sampai seleksi calon pimpinan KPK yang pertama.
Prof. Romli sendiri tidak pernah menyebut diri sebagai pelopor UU Antikorupsi maupun arsitek pembentukan KPK. Dia selalu menyebutnya sebagai hasil kerja keras tim atas dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak pemerintah (terutama atasannya, Menteri Kehakiman) dan mitra kerja DPR, terutama political will dan dorongan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika itu. Namun, melihat perannya sebagai Ketua Tim yang didukung kapasitasnya sebagai pakar hukum yang mumpuni, tidak berlebihan pula bila banyak pihak menyebutnya sebagai pelopor UU Antikorupsi dan arsitek pembentukan KPK.
Memang, Romli menyebut bahwa cetusan pembentukan KPK bukan berasal dari dirinya atau pemerintah, melainkan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ketika itu diwakili oleh Muh. Zen Badjeber. Romli sebagai wakil pemerintah menerima usulan tersebut dan didukung fraksi-fraksi lain. Menurut Romli, ini fakta yang selama ini tidak diketahui masyarakat luas.
Ketika itu, dalam pembahasan RUU Antikorupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999), Fraksi PPP mengajukan usul pembentukan KPK itu sebagai ‘kompensasi’ diterimanya usulan pemerintah tentang pasal pembuktian terbalik. Romli yang mewakili pemerintah menanggapi serius sekaligus menerima usulan tersebut dan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain.
Kemudian, Menteri Kehakiman Muladi ketika itu menyetujui pula dimasukkan ketentuan tersebut sebagai perintah UU untuk membentuk KPK dalam waktu satu tahun setelah UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan. Romli pun dengan cekatan merespon dengan mulai menyusun draft RUU KPK.
Kemudian, terjadi perubahan kepemimpinan nasional dari Presiden BJ Habibie ke Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Terjadi pula pergantian Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Perundang-undangan) dari Muladi (16 Maret 1998-20 Oktober 1999), diganti oleh Yusril Ihza Mahendra.
Menteri Yusril Ihza Mahendra melanjutkan proses untuk memenuhi perintah pembentukan KPK sebagaimana ditetapkan Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Di bawah koordinasi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Izha Mahendra terbentuk tim persiapan untuk mempersiapkan organisasi dari KPK. Tim itu dipimpin oleh Romli Atmasasmita. Seingat Romli, tim persiapan pembentukan organisasi KPK ini mendapat dukungan bantuan dana dari Bank Pembangunan Asia (ADB), sebesar 1 juta dollar untuk keperluan melakukan studi banding ke beberapa negara, termasuk ke Australia, Malaysia, Hongkong dan Amerika Serikat. Waktu itu, Tim Persiapan ini juga disupervisi oleh mantan Komisioner, De Speville; dari Komisi Anti Korupsi Hongkong.
Tim pimpinan Romli ini terus bekerja, kendati waktu itu terjadi beberapa kali pergantian Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Yusril diganti oleh Baharuddin Lopa, kemudian diganti oleh Marsilam Simanjuntak, dan diganti lagi oleh Mahfud MD, dalam kurun waktu 23 Oktober 1999 sampai 9 Agustus 2001. Sampai akhirnya Gus Dur digantikan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Yusril kembali menjabat Menteri Kehakiman dan HAM. Hingga UU KPK baru diselesaikan pada era pemerintahan Megawati.
Setelah Romli dan anggota tim yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, praktisi dan akademisi, melakukan studi banding,3] Romli melihat banyak perbedaan di beberapa negara. Kalau di Hongkong, mereka melakukan langkah-langkah penyidikan tetapi penuntutan diserahkan kepada penuntut umum. Demikian pula pemberantasan korupsi di Malaysia, Singapura dan di tempat lain.
Setelah persiapan-persiapan itu rampung, tim tersebut menyusun Rancangan Undang-undang tentang KPK. Pada draft awal pembentukan KPK itu, tim berpikir bahwa era reformasi menuntut segala perubahan-perubahan yang sifatnya total, terhadap kondisi penegakan hukum, sosial ekonomi, sebagai akibat dari warisan Pemerintahan Orde Baru yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sangat penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian ketika itu, sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.
Oleh karena itu, dalam draft awal KPK, seluruh tugas wewenang Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani perkara korupsi dilepaskan dan dilimpahkan, bahkan dimonopoli oleh KPK. Jadi dalam draft awal ini, diusulkan agar KPK memonopoli fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Polri dan Kejaksaan tidak lagi melaksanakan fungsi tersebut. Draft RUU KPK dengan model ini diteruskan ke DPR oleh pemerintah, sekalipun di dalam tim penyusun terjadi perbedaan sengit soal fungsi tersebut karena aspirasi rakyat ketika itu tidak ada kepercayaan terhadap Polri dan kejaksaan untuk menangani korupsi.
Draft awal ini menimbulkan persoalan awal pula dalam diskusi dengan DPR dan mendapatkan reaksi keras dari Kejaksaan dan Kepolisian. Wakil kejaksaan selalu mempersoalkan kegunaan keberadaan lembaga baru (KPK) dalam sistem peradilan pidana (SPP) dengan merujuk kepada KUHAP (UU nomor 8 Tahun 1981). Begitu pula wakil Kepolisian mempersoalkan bahwa dalam KUHAP hanya mengakui Polri dan Jaksa. Kepolisian dan Kejaksaan berpandangan bahwa pembentukan KPK bertentangan dengan KUHAP.
Romli yang mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR tersebut berdalih, perintah pembentukan KPK dengan UU telah menjadi ketentuan UU nomor 31 Tahun 1999 khusus Pasal 43. Jika tidak dilaksanakan oleh pemerintah maka pemerintah telah melanggar UU alias ada alasan dilakukan “impeachment” terhadap presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, hal mana dia dan tim penyusun merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berkehendak untuk membentuk KPK.
Akibat kuatnya lobi-lobi pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam pembahasan di DPR, maka draft tersebut hampir menemui jalan buntu. Hal yang paling keras dipersoalkan adalah perihal wewenang monopoli KPK dalam pemberantasan korupsi dan pemberlakuan surut wewenang KPK. Perdebatan wakil pemerintah (yang diwakili Romli) dengan beberapa anggota DPR terjadi begitu ketat sehingga dari pihak DPR ketika itu ada yang telah mengeluarkan pernyataan keras, jika pihak pemerintah bersikeras mempertahankan prinsip monopolistik tersebut, RUU ini akan ditolak DPR.
Akibat kuatnya lobi-lobi pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam pembahasan di DPR, maka draft tersebut hampir menemui jalan buntu. Hal yang paling keras dipersoalkan adalah perihal wewenang monopoli KPK dalam pemberantasan korupsi dan pemberlakuan surut wewenang KPK. Perdebatan wakil pemerintah (yang diwakili Romli) dengan beberapa anggota DPR terjadi begitu ketat sehingga dari pihak DPR ketika itu ada yang telah mengeluarkan pernyataan keras, jika pihak pemerintah bersikeras mempertahankan prinsip monopolistik tersebut, RUU ini akan ditolak DPR.
Sehingga, Romli sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan itu mengambil cara lain. Memang, secara historis sejak kita merdeka hanya ada dua institusi yang bergerak dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karena itu, kemudian pemerintah berpendapat menghargai eksistensi dua lembaga tersebut secara historis walaupun masih ada kelemahan-kelemahan tetapi perlu kita perkuat dengan lembaga yang disebut dengan KPK.
Romli selaku wakil pemerintah dan sekaligus ketua tim penyusun berpikir keras untuk menemukan solusi dari kebuntuan tersebut. Seketika itu, Prof. Romli teringat akan prinsip komplementaritas dalam Statuta ICC (1998) dalam hal pelanggaran HAM berat. Prinsip ini menegaskan bahwa kompetensi ICC dalam hal terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara adalah sebagai sarana yang bersifat “ultimum remedium.” Artinya, jika negara yang bersangkutan tidak mau dan tidak mampu melaksanakan peradilan atas pelanggaran HAM berat tersebut, maka ICC akan mengambil-alih persidangan perkara tersebut.
Berangkat dari prinsip komplementaritas itu, maka Romli memasukkan ketentuan KPK wajib koordinasi dan melakukan supervisi (dalam Pasal 6 huruf a dan b), namun jika Polri dan kejaksaan tidak mau atau tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya karena sesuatu hal maka KPK akan mengambil-alih (take over) perkara tersebut. Fungsi KPK inilah yang Romli sebut, “trigger mechanism”, sebagaimana fungsi ICC dalam peradilan pelanggaran HAM Berat. Istilah “take over”, itu Romli peroleh dari konsep akuisisi dalam hukum perusahaan.
Ketika konsep rumusan ketentuan baru yang didasarkan pada prinsip komplementaritas itu diajukan ke komisi III DPR RI, maka terjadilah kompromi dan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan. Diterimanya konsep baru fungsi, tugas dan wewenang KPK dalam hubungan dengan Polri dan kejaksaan merupakan langkah strategis “mundur selangkah untuk maju dua langkah”4]. Hal mana, dengan diterimanya rumusan baru itu maka tujuan awal “memonopoli” penyelidikan, penyidikan dan penuntuan, sesungguhnya telah tercapai. Sebab Romli pun menyiasati komplementaritas itu dengan memberi perkuatan wewenang luar biasa (extraordinary measures) kepada KPK yang tidak dimiliki Polri dan Kejaksaan.
Apalagi, kendati instansi Kepolisian dan Kejaksaan masih dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, akan tetapi jika kedua institusi itu tidak mau dan tidak mampu, maka KPK memiliki kewajiban untuk mengambil-alih.
Kemudian, berlanjut perdebatan alot dalam penyusunan UU KPK sekitar hubungan KPK dengan Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana agar ada koordinasi dan sinkronisasi tugas dan wewenang sehingga dicegah tumpang tindih.
Sehingga muncullah pada Pasal 6, perihal tugas KPK: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Lalu dengan fungsi supervisi (b) itu, setiap langkah Polisi dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, diwajibkan memberitahukan kepada KPK, dan sebaliknya KPK diwajibkan mengawasi langkah-langkah itu. Jadi ada dua hal, dalam rangka pengawasan, yakni: 1) KPK bisa menilai apakah yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan itu berjalan atau tidak, efektif atau tidak; 2) sebaliknya Kepolisian dan Kejaksaan harus jujur dan berterus-terang bahwa yang dia sedang tangani tidak bisa dilanjutkan karena berbagai hal, intervensi dan sebagainya. Dalam hal itulah KPK dapat melakukan pengambil-alihan sehingga muncullah Pasal 8, dan Pasal 9, alasan-alasan pengambil-alihan begitu banyak, disusun sedemikian rupa dan disetujui waktu itu oleh DPR. Dalam proses pengambil-alihan ini, muncul konsep “unwillling dan unable” dari Statuta ICC, yang kemudian diatur dalam Pasal 9 tentang alasan-alasan pengambil-alihan dalam rangka supervisi.
Bahkan Pasal 50 sudah menegaskan bagaimana koordinasi antara ketiga institusi ini dalam menangani pemberantasan korupsi. Di situ sudah disepakati jika Polisi memulai penyidikan atau Kejaksaan mereka wajib memberitahu kepada KPK. Tetapi jika KPK memulai, mereka harus berhenti melakukan penyidikan, tidak boleh dilakukan.
Romli mengungkapkan semua itu sudah disepakati, jadi tidak mungkin ada tumpang tindih. “Persoalannya, selama KPK jilid satu hingga jilid tiga, saya amati, fungsi satu-satunya yang lemah dalam pemberantasan korupsi dalam hubungan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan adalah fungsi koordinasi dan supervisi. Sangat lemah, bahkan tidak berjalan efektif. Seharusnya itu berjalan efektif. Kalau itu berjalan efektif maka tidak ada cerita lagi mengenai kasus, misalnya, mengapa Gayus tidak diambil-alih. Itu seharusnya secara otomatis. Kalau mengikuti rule yang ada, itu seharusnya berjalan dan tidak ada alasan KPK mengatakan belum mampu, belum mau. Atau tidak ada alasan bahwa Kepolisian tidak akan menyerahkan, itu tidak ada. Karena dalam Undang-undang KPK jelas, wajib, kalau KPK meminta,” jelas Romli Atmasasmita5].
Ketika itu, Romli berharap sekalipun Polri dan Kejaksaan masih memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tetapi tanpa wewenang luar biasa akan sulit menghadapi perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif dan judikatif. Hambatan kelancaran tugas dan wewenang penyidik Polri dan kejaksaan tersebut sudah tentu dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan KPK, hal mana KPK akan dapat mengambil-alih.
Harapan ini dalam praktiknya kemudian setelah 7 (tujuh) tahun pembentukan KPK, tidak menjadi kenyataan karena hambatan psikologis KPK untuk melakukan “take over” dan keengganan Polri dan kejaksaan untuk diambil-alih perkaranya. Apalagi di dalam tubuh KPK, ada wakil Polri dan kejaksaan yang menduduki jabatan deputi penindakan dan deputi penuntutan yang dijabat oleh wakil kedua instansi tersebut.
Persoalannya, apakah Pimpinan KPK paham terhadap Undang-undang yang dia harus jalankan? Prof. Romli dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR (23 November 2010) itu bertanya. Kelihatannya tidak paham, terutama yang filosofi dan misi dari Undang-undang KPK itu sendiri.
Romli menjelaskan, filosofi Undang-undang KPK sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks sistem peradilan pidana, dia berada di luar sistem peradilan pidana, dia berada di luar Undang-undang Dasar 1945, tetapi karena dia dibentuk oleh Undang-undang, disepakati, maka dia menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, yang memiliki sifat-sifat yang extraordinary, wewenang yang sangat luas tetapi dengan pengawasan secara melekat yang ketat, antara lain KPK tidak boleh menghentikan penyidikan.
“Hal itu bukan sesuatu yang gampang, karena pada waktu itu, kita membuat, tidak boleh ada wewenangnya SP3 karena KPK itu sudah diberi wewenang yang sangat luas melebihi kedua institusi itu, apakah dalam penyidikan, penyelidikan, penyadapan, membuka rahasia bank, dia tidak terpengaruh oleh status seseorang yang dijadikan tersangka, tidak perlu ijin Presiden, tidak perlu ijin pengadilan untuk menyadap. Jadi wajar kalau dia diberi rambu-rambu yang memperketat, dan memperkuat bahwa dia tidak menyalahgunakan wewenang, tidak boleh SP3. Itu salah satu dan bahkan ancaman hukumannya berat sekali di dalam Undang-undang KPK. Karena kita tahu SP3 itu selama ini, entah sampai saat sekarang, sering menjadi bagian dari trading, itu yang kita khawatirkan,” jelas Romli.
Kemudian, untuk memperkuat itu semua, maka Pimpinan KPK yang lima itu harus dipilih melalui suatu proses seleksi yang transparan dan independen, tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Lalu, untuk mencegah intervensi terhadap Pimpinan KPK yang lima itu, pada saat penyusunan UU KPK, terdapat dua pendapat bahwa (1) Ketua boleh memilih Hak Veto, satu lagi bahwa (2) Ketua tidak memiliki Hak Veto, hanya sifatnya koordinator semata-mata. Pilihan jatuh pada yang kedua.
Rambu penting lainnya menurut Romli adalah integritas pimpinan KPK yang harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya, antara lain ditetapkan jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka diberhentikan sementara dan jika menjadi terdakwa, diberhentikan secara tetap. Ketentuan dalam UU KPK ini menurut Romli memang disengaja berbeda (bukan diskriminatif) dari PNS pada umumnya. Oleh karena itu, kelalaian sekecil apapun, tidak ada toleransi sama sekali (zero tolerance) bagi pimpinan KPK; mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain. Romli kecewa dengan putusan MK RI tentang kasus Bibit-Chandra terhadap ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK, dan pembentukan komite etik untuk Chandra Hamzah; seharusnya Chandra diminta mundur saja karena pelanggaran kode etik KPK dan potensial pelanggaran Pasal 29 UU KPK. Romli sambil mengeluarkan kekecewaannya juga melihat belum ada pemahaman di kalangan KPK dan MK RI mengenai filosofi, visi dan misi pembentukan UU KPK termasuk juga di kalangan LSM.
Sehubungan dengan itu, dalam pembahasan, ada dua azas dalam kepemimpinan KPK: (1) azas yang disebut kolektivitas, kolegialitas; dan (2) azas independen. Oleh karena itulah, kelima Pimpinan KPK harus diseleksi dan dipilih secara transparan dengan fit and proper test di DPR, setelah sebelumnya oleh Panitia Seleksi. Mereka harus dapat mengambil keputusan bersama-sama, jadi tidak boleh sendiri-sendiri. Dengan kata-kata bersama-sama sehingga akan dicegahlah apapun intervensi yang dilakukan terhadap kelima Pimpinan KPK. Dengan penguatan seperti itu, Romli berharap waktu itu, Undang-undang KPK bisa dilakukan dengan baik.
Maka dalam penjelasan umum UU KPK secara khusus dijelaskan bahwa dalam proses pembentukan KPK, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola KPK. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada KPK.
Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota KPK, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPR, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Prof. Romli menjelaskan, kalau kita lihat dari penjelasan umum saja, memang KPK itu fungsinya sebagai trigger mechanism, mendorong kedua institusi (Kepolisian dan Kejaksaan) bisa bekerja lebih efektif, akan meningkatkan kinerja dengan lebih baik. Dengan fungsi trigger mechanism maka hubungan koordinasi sinkronisasi kita harapkan akan lebih baik. Bahkan ketika itu, Romli sangat yakin koordinasi itu akan berlangsung efektif, karena unsur pemerintah diwakili oleh Kepolisian dan Kejaksaan ada di sana.
Hanya, ketika itu Romli tidak memprediksi adanya hambatan psikologis, hubungan kerjasama KPK dengan dua institusi tersebut serta stigma masyarakat luas terhadap dua institusi tersebut. Stigma tersebut akhirnya mengakibatkan kontraproduktif, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara ketiga institusi di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi.
Romli memberi gambaran betapa jor-joran dukungan dan tekanan masyarakat luas, termasuk LSM, mendorong KPK sebagai ujung tombak dari pemberantasan korupsi. Sehingga KPK lupa kepada fungsi koordinasi dan supervisi, fungsi sebagai trigger mechanism, untuk mendorong Kepolisian dan Kejaksaan bisa bekerja lebih efektif dan meningkatkan kinerja dengan lebih baik.
KPK merasa didorong bukan sebagai fungsi trigger mechanism, tetapi harus sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Apalagi ujung tombak itu kemudian didukung oleh pihak asing dengan bantuan-bantuan dana yang begitu besar, yang tidak terkontrol oleh kita semua, tidak terawasi. Sedangkan sisi lain, kedua institusi itu (Kepolisian dan Kejaksaan) memperoleh tekanan stigma negatif, sehingga termasuk pihak yang ‘dirugikan’.
Semua ini, menurut Romli, merupakan masalah psikologis yang menimbulkan persoalan. Di sisi lain, Pemerintah juga tidak fair dalam memperlakukan ketiga institusi tersebut. Romli memberi contoh, kalau KPK diberi kemungkinan outsourcing untuk rekrutmen pegawai, Kejaksaan dan Kepolisian tidak. Begitu pula dalam hal anggaran, KPK diberi keleluasaan biaya perkara, penanganan besar sekali, tetapi dua institusi itu tidak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang menimbulkan kontraproduktif dalam hubungan koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian terhadap KPK; hal ini juga menjadi hambatan KPK untuk melaksanakan supervisi secara konsisten sesuai dengan UU KPK. Romli melihat, hal ini yang terjadi sekarang. Bagaimana dua institusi itu resisten terhadap koordinasi dan supervisi KPK.
Selain itu, pada draft awal UU Antikorupsi, Romli menghendaki ada dua komisi yang harus dibentuk. Yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tetapi DPR menolak. Mereka tidak ingin membikin dua Komisi. Maka disatukan dalam KPK. Padahal Romli sudah merancang, selain Komisi yang menindak yakni KPK, ada Komisi yang mencegah korupsi yakni KPKPN. Tetapi DPR menolak Komisi yang mencegah korupsi. Komisinya dimasukkan ke dalam KPK.
Penggabungan tersebut menimbulkan persoalan. Tugas KPK menjadi lebih berat. Tadinya Romli berpikir, KPK perlu didukung oleh KPKPN. Karena informasi dari KPKPN disalurkan ke KPK untuk ditindak lebih lanjut. KPK-lah yang menindak perbuatan korupsi.
Sekarang, terlihat dampaknya. Di satu sisi tugas KPK jadi berat sekali. Tetapi di sisi lain, pencegahan korupsi terlunta-lunta. KPK banyak menindak, tidak mencegah. Laporan-laporan harta kekayaan para penyelenggara negara yang dikirim ke KPK tidak tertangani. Akhirnya terjadi makelar kasus (Markus) seperti yang dilakukan Gayus Tambunan.
Lantas yang terus dilakukan Romli adalah menjelaskan lewat tulisan di surat-suratkabar kenapa KPKPN disatukan dengan KPK. Dia ingin masyarakat mengetahui dan mengerti duduk soalnya. Seharusnya ada dua komisi dengan tugas yang terpisah, satunya dan lainnya menindak, tetapi digabung oleh DPR. Sekarang baru disadari bahwa penggabungan kedua tugas tersebut di tangan KPK menjadi pekerjaan yang sangat berat. Bayangkan berapa juta pegawai negeri yang harus disuruh melapor harta kekayaan mereka sekali setiap 2 tahun.
Romli menyayangkan upaya pencegahan korupsi yang tertatih-tatih.6]. Keadaan ini merangsang munculnya para makelar kasus dan mafia hukum. “Ini kesalahan strategi, karena terburu-buru mengambil keputusan. KPKPN dimatikan supaya harta kekayaan penyelenggara negara tidak diusik-usik. Itu maksudnya,” kata Romli.
Mereka (para anggota DPR) berhasil, tapi bisulnya pecah sekarang. Sebenarnya mereka hanya menunda permasalahan. Romli menginginkan supaya semuanya tuntas, “Sayangnya, masih banyak orang yang mau kaya dengan jalan pintas, tetapi menimbulkan banyak masalah.” Pekerjaan KPK sekarang, kalau ada pejabat yang diduga kuat melakukan tindak korupsi, baru dibuka. Meskipun ada kecurigaan, kalau tidak ketahuan tidak dibuka-buka.
Untuk mengisi formulir laporan harta kekayaan memang bikin mumet (pusing tujuh keliling). Soalnya, jumlahnya ratusan orang dan harus mengisi beberapa lembar formulir disertai bukti-bukti dan kwitansi. Belum lagi klarifikasi ke lapangan. “Coba kalau DPR tidak berpikiran minus,” kata Romli, “maka tidak akan ada Gayus dan Bahasyim.” Pasalnya, mereka sendiri (anggota-anggota DPR) harus melaporkan harta kekayaan mereka dan harus diklarifikasi. Sekarang muncul lagi keinginan untuk mengintensifkan pelaporan kekayaan penyelenggara negara dan pembuktian terbalik. Namun keinginan tersebut dikhawatirkan mengarah kepada pelanggaran HAM.
Hikmahnya, Romli bersyukur karena kebetulan diberi tugas yang berat, menyusun rancangan undang-undang yang strategis. Alhamdulilah, amanah tersebut dapat diselesaikannya dengan baik. Dia juga bersyukur karena Allah Swt memberinya nikmat kesehatan.
Footnote:
1] Anggota Pansel KPK Jilid I (Tahun 2001) adalah: Dr. Adnan Buyung Nasution, Dr.Todung Mulya Lubis, Basrief Arief SH MH; Mugihardjo (alm); Prof.Dr.Indriyanto Senoadji; Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, Prof.Dr.Andi Hamzah; Prof.Dr.Harkristuti Harkrisnowo; Dr.Komaruddin Hidayat; Drs.Ansahari Ritonga MH; Irjen Pol.Sukamto; dan Abdul Wahid SH MH (sekretaris).
2] Dr. Frans Hendra Winarta, Wawancara Tim Penulis.
3] Anggota tim studi banding: Taufiequrachman Ruki (eks Ketua KPK Jilid I); Hamid Chalid (LSM); Teten Masduki (ICW); Prof Sahetapy (UNAIR); BPKP; Chaeruman Harahap (Kejaksaan).
4] Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Wawancara, Rabu, 8 September 2010.
5] Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR-RI (Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan) dengan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Penyampaian masukan terhadap seleksi Calon Pengganti Pimpinan KPK termasuk yang berkaitan dengan masa jabatan Calon Pengganti Pimpinan KPK terpilih, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa, 23 November 2010.
6] Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Wawancara, Rabu, 8 September 2010, Op.Cit.
Penulis: Ch. Robin Simanullang | Cuplikan dari Buku Jalan Keadilan di Tengah Kezaliman, yang segera diterbitkan Pustaka Tokoh Indonesia | Bio TokohIndonesia.com