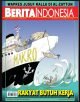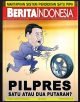Sekolah dan ‘Melting Pot’ di SMT
Urip Santoso
[ENSIKLOPEDI] BIO 03 | Urip kecil pertama kali mengecap pendidikan di sekolah Muhammadiyah di Tegal. Saat itu, orang tuanya yang sering pindah tempat tugas menitipnya tinggal bersama bibinya, adik perempuan ayahnya, yang waktu itu aktif sebagai anggota Muhammadiyah dan sering kongres ke Batavia.
Di sekolah Muhammadiyah itu, Urip hanya menyelesaikan kelas satu. Lalu dia pindah ke Batavia, kumpul sama orang tuanya. Di Batavia, dia masuk sekolah dasar Katholik di Jl. Sumbawa. Namanya Idenburg School. Namun, di sekolah ini, dia tidak sampai tamat.
Dia menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah zending Protestan HJS (Javaaansche Hollandsch School) di Magelang. Ketika di HJS, Urip sangat terkesan met de bijbel atas seorang gurunya bernama Meneer Dwijo, tinggalnya di Blabak. Dia terkesan karena guru tersebut kalau datang ke sekolah, selalu pakai delman bersama anak-anaknya yang juga sekolah di situ.
Kemudian, dia melanjut ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)[1] di Yogyakarta. Ketika itu, ayahnya masih sering pindah sebagai pegawai negeri. Kemudian pindah ke MULO Protestan. Namun kemudian dia pindah lagi ke MULO di Medan dan di sana tamat tahun 1941.
Setelah tamat MULO, dia sendiri pindah ke Batavia untuk melanjut ke Algeme(e)ne Middelbare School – AMS[2]. Sementara, orang tuanya masih di Medan, jadi di Batavia dia indekost. Baru belajar selama empat bulan di AMS, Jepang masuk setelah mengalahkan Belanda, Maret 1942. Lalu Jepang menutup semua sekolah Belanda. Semua siswa di seluruh Indonesia terpaksa behenti sekolah, tentu tak terkecuali Urip.
Kisah di SMT Jakarta
Indonesia memasuki babak (zaman) baru di bawah pendudukan Jepang (1942-1945), yang menjadi babak (zaman) kedua bagi Urip Santoso. Urip sebagai seorang remaja yang sudah mulai matang, sangat merasakan kekejaman penjajahan Jepang. Antara lain, dia terpaksa berhenti sekolah karena semua sekolah zaman Belanda ditutup. Beruntung, kemudian, pada September 1942, Jepang membuka kembali sekolah-sekolah dengan nama baru dan tidak lagi menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tetapi mengharuskan belajar bahasa Jepang dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
Di antara sekolah yang baru dibuka adalah Sekolah Menengah Tinggi (SMT) di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. SMT yang pertama dibuka adalah SMT Jakarta, bertempat di bekas Canisius College Menteng 40. Yang diterima menjadi siswa di SMT ini adalah bekas murid AMS (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat yang belum tamat atau bagian pertama perguruan tinggi dari berbagai daerah nusantara.
SMT Jakarta dengan nama Jepang Jakaruto no Kotto Chu Gakko sempat menerima beberapa angkatan siswa. Tahun 1942, terdiri dari tiga angkatan, yakni Angkatan 42/III (kelas 3), Angkatan 42/II (kelas 2) dan Angkatan 42/I (kelas 1). Urip Santoso masuk dalam Angkatan 42/I B. Rosihan Anwar dan Koentjoroningrat[3] adalah kakak kelasnya Angkatan 42/III A. Ketiga angkatan ini memperoleh ijazah dalam bahasa dan tulisan Jepang. Yakni Katakana untuk nama kotanya, Hiragama dan Kanji untuk keterangan ijazahnya, hanya nama murid dan kepala sekolah yang ditulis dalam huruf Latin.
Selanjutnya Angkatan Keempat diterima pada tahun 1943, Angkatan Kelima tahun 1944 dan Angkatan Keenam tahun 1945. Angkatan Keempat (1943) telah menerima ijazah SMT dalam bahasa Indonesia dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merdeka. Angkatan ini yang terakhir kali menerima ijazah dengan nama SMT. Sebab Angkatan Kelima dan Keenam (1944 dan 1945), kendati ketika masuk masih bernama SMT (Kotto Chu Gakko), tetapi ketika ujian akhir (1947 dan 1948) telah mendapat ijazah dengan nama SMA (Sekolah Menengah Atas).
Ada banyak hal menarik yang dialami para siswa dan guru SMT (1942-1945) ini yang telah dirangkum dalam buku berjudul ‘Jembatan Antar Generasi’ diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, 1997. Urip Santoso menjadi salah satu Tim Redaksinya bersama Eddy Djoemardi Djoekardi, Soebardi Soeria Atmadja, Agus Subroto, Moh. Su’ud, Abd. Wahab Nyakman, Moh. Soetrisno dan Mochtar Thayeb.
Dalam prakata buku itu disebutkan ada beberapa kebahagiaan (kenangan) para mantan murid SMT Djakarta (1942-1945) itu. Kebahagiaan pertama, karena mereka merupakan sebagian manusia Indonesia tiga zaman. Yakni zaman penjajahan belanda, zaman penjajahan Jepang dan zaman Merdeka[4].
Kebahagiaan kedua, mereka yang kala itu sebagai remaja yang sudah matang mendapat kesempatan mengikuti seluruh proses sampai lahirnya Pancasila oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.
Melalui buku ini mereka ingin membagi pengalaman kepada generasi penerus, tanpa pretensi ingin menggurui. Sebab setiap tahapan zaman mempunyai tata nilainya sendiri. Mereka hanya berharap agar generasi penerus dapat mengambil hikmahnya saja, demi tetap tegaknya persatuan bangsa dan kesatuan negara berdasarkan UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Itulah sebabnya mereka memberi judul buku tersebut: Jembatan Antar Generasi: Pengalaman Murid SMT Djakarta 1942-1945.
Buku ini juga mencatat beberapa keunikan SMT, sebagai cikal bakal SMA (SMU), yang dirasa perlu dibagi sebagai bagian sejarah kependidikan Indonesia. Keunikan Pertama, bahwa muridnya terdiri dari berbagai jurusan setingkat sekolah lanjutan atas, disatukan dalam satu wadah yang merupakan suatu melting pot[5]. Sebab, selain terdiri dari berbagai jurusan juga berasal dari berbagai lingkungan sosial dan daerah asal yang berbeda.
Urip Santoso mengenang bahwa waktu itu memang terjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa dibayangkan, ketika Jepang kala itu mulai membuka sekolah itu, September 1942, ditampung siswa dari berbagai penjuru nusantara dengan aneka budaya dan bahasanya. Ada Jawa, Sunda, Batak, Padang, Manado, dan lain-lain, semua kumpul di situ.
Keunikan Kedua, adalah penggunaan bahasa Indonesia. Sebab barulah di SMT tersebut mereka pertama kali belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Sebab sebelumnya di sekolah-sekolah Hindia Belanda mereka selalu belajar dengan pengantar bahasa Belanda.
Pada bulan pertama, para siswa kalau tidak pakai Bahasa Belanda, ya bahasa daerah masing-masing. Urip sendiri masih ngomong bahasa Belanda, apalagi Rosihan Anwar yang mengambil jurusan barat. Tapi dalam waktu 3-7 bulan, everybody sudah menggunakan bahasa Indonesia, karena gurunya yang orang Indonesia juga, wajib mengajar dengan pengantar bahasa Indonesia. Di situ terjadi suatu keajaiban metafora, melting pot, yang oleh karena situasi dan nasionalismenya tumbuh sedemikian rupa. Hal ini makin terasa di tahun kedua, di tengah kekejaman penjajahan Jepang.
Bukan hanya muridnya yang merasakan betapa menariknya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahkan terlebih lagi para gurunya. Sebagaimana diungkapkan Amin Singgih, MO (mantan guru Bahasa Indonesia SMT Djakarta) bahwa sebelumnya semua guru menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, termasuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan sepanjang pengalaman, mereka tidak pernah memperoleh bahasa Indonesia sebagai pelajaran yang sungguh-sungguh. Lalu di SMT, tiba-tiba diharuskan menggunakan bahasa Indonesia.[6]
Selain Amin Singgih yang mengukir kenangannya dalam buku Djembatan Antar Generasi tersebut, juga Prof. Dr. Ir. Herman Johannes[7] (Guru Ilmu Pasti dan Ilmu Pesawat), S Soerjotjondro (Guru Ilmu Ekonomi dan tata Negara), dan Wahjoedi (Guru Ilmu Alam). Sedangkan dari 801 siswa SMT Djakarta 1942-1945, ada 32 orang yang mengukir kenangannya, di antaranya Edwin L Tobing, Harjati Soebadio[8], Koentjoroningrat, Miriam Budiardjo[9], Rosihan Anwar dan Soebagio Wiriodharmoro[10]. Bio TokohIndonesia.com | crs
Footnote:
[1] MULO, singkatan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (bahasa Belanda), berarti “Pendidikan Dasar Lebih Luas”. Suatu jenjang pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia yang setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sekolah ini menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 30-an, sekolah-sekolah MULO sudah ada hampir di setiap ibu kota kabupaten di Jawa dan di beberapa kabupaten di luar Jawa.
[2] AMS, singkatan dari Algeme(e)ne Middelbare School (bahasa Belanda) suatu jenjang pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia, setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda. Tahun 1930-an, AMS hanya ada di beberapa kota, seperti di Medan, Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta), Surabaya, Malang, Makassar, serta ada beberapa AMS Swasta.
[3] Prof Dr Koentjaraningrat (1923-1999), Bapak Antropologi Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 15 Juni 1923 dan meninggal di Jakarta, 23 Maret 1999. Pak Koen, panggilan akrabnya, seorang ilmuwan yang berjasa meletakkan dasar-dasar perkembangan ilmu antropologi di Indonesia. Sehingga ia diberi kehormatan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Hampir sepanjang hidupnya disumbangkan untuk pengembangan ilmu antropologi, dan apsek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesukubangsaan di Indonesia. (www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/k/koentjaraningrat/)
[4] Zaman Merdeka (Catatan): Urip menjalani hidupnya mulai dari zaman perjuangan kemerdekaan (1945-149) dimana dia ikut berjuang dengan pangkat kapten dan sempat dipenjara selama tiga tahun. Berlanjut pada zaman pemerintahan (demokrasi) parlementer (1950-1955, zaman demokrasi terpimpin (1955-1966). Lalu berkiprah di zaman Orde Baru (1966-1998), hingga sampai ke zaman Reformasi (1998-sekarang).
[5] The melting pot adalah sebuah ‘wadah’ metafora masyarakat yang heterogen menjadi lebih terasa homogen, dimana unsur-unsur yang berbeda “melebur bersama” menjadi satu kesatuan yang harmonis dengan kebudayaan umum. Istilah ini pertama kali populer digunakan untuk menggambarkan asimilasi imigran ke Amerika Serikat, yang bermetafora tahun 1780-an. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah tahun 1970, keinginan untuk asimilasi model melting pot mulai ditantang oleh para pendukung multikulturalisme, yang menyatakan bahwa perbedaan budaya dalam masyarakat yang (sangat) berharga dan harus dilestarikan. Lalu muncul metafora alternatif dari ‘mangkuk salad’ campuran aneka budaya yang berbeda dalam satu mangkuk, menyatu dalam perbedaan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Melting_pot)
[6] Amin Singgih MO, Mengenang SMT, Jembatan Antar Generasi, Pengalaman Murid SMT Djakarta 1942-1945, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm.104.
[7] Prof. Dr. Ir. Herman Johannes, lahir di Rote, NTT, 28 Mei 1912 dan meninggal di Yogyakarta, 17 Oktober 1992. Namanya sering juga ditulis Herman Yohannes atau Herman Yohanes. Dia adalah cendekiawan, politikus, ilmuwan Indonesia, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Pahlawan Nasional Indonesia. mantan guru SMT Jakarta ini pernah menjabat Rektor UGM (1961-1966), Koordinator Perguruan Tinggi (1966-1979), anggota Dewan Pertimbangan Agung RI (1968-1978), dan Menteri Pekerjaan Umum (1950-1951). (www.tokohindonesia.com/herman-johannes/)
[8] Prof. Dr. Haryati Soebadio (1928-2007), lahir di Jakarta, 24 Juni 1928 dan meninggal di Jakarta, 30 April 2007, pada umur 78 tahun. Alumni SMT Jakarta ini menjabat Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan V (pemerintahan Presiden Soeharto). Alumni Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini pernah juga menjabat Dekan Fakultas Sastra dan Dirjen Kebudayaan P&K. (www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/haryati-soebadio/)
[9] Prof Miriam Budiardjo (1923-2007), Guru Besar Para Pakar Politik. Guru besar ilmu politik yang ikut mendirikan FISIP UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), adalah alumni SMT Jakarta. Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ini lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1923 dan meninggal dunia dalam usia 83 tahun, Senin 8 Januari 2007 di Jakarta, akibat menderita komplikasi pernapasan dan gagal ginjal. (www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/miriam-budiardjo/)
[10] Soebagio Wiriodharmoro (1914-2010). Letkol Cin (Purn) Soebagio Wiriodharmoro lahir tahun 1914 dan meninggal pada usia 96 tahun hari Sabtu (24/7/2010) pukul 07.45 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Ayah dari Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro S.IP, MM ini terakhir menjabatan Kepala Logistik Direktorat Intendan. Dia pernah menerima Tanda Kehormatan Negara Bintang Gerilya. (Pusat Data Tokoh Indonesia