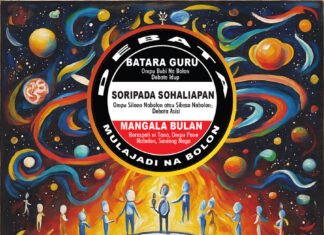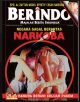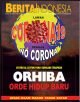Sastrawan Pemberontak
Radhar Panca Dahana
[DIREKTORI] Sastrawan, esais, kritikus sastra, jurnalis, dan seniman teater merupakan sederet profesi yang digeluti pria kelahiran Jakarta, 26 Maret 1965 ini. Penyakit gagal ginjal kronis yang dideritanya tidak menghentikannya untuk terus berkarya dan tampil beda. Atas prestasinya, dosen Sosiologi FISIP-UI dan master Sosiologi dari EHESS, Prancis, ini malah dihadiahi penghargaan Paramadina Award (2005), Medali Frix de le Francophonie (2007), dan Kuntowijoyo Award (2009).
Radhar Panca Dahana, demikian sosok pria berdarah Jawa nan bersahaja ini dikenal. Namanya merupakan akronim dari nama kedua orang tuanya, Radsomo dan Suharti. Selain dirinya, enam saudara kandungnya juga mempunyai nama depan Radhar.
Kehidupan masa kecilnya terbilang sangat keras. Sang ayah bahkan pernah difitnah sebagai antek komunis. Ayahnya pula yang mendidiknya dengan penuh kedisiplinan bahkan cenderung otoriter. Dalam publikasinya, Radhar menceritakan bagaimana sejak kecil ia dan saudara-saudaranya sudah diajari berhitung angka hingga jutaan, pulang ke rumah harus tepat waktu, dan rajin belajar. Jika melanggar aturan, hukuman berupa sabetan rotan harus siap-siap mereka terima. Selain itu, seluruh anak lelaki dikuncung dan digunduli dengan disisakan sedikit rambut di ujung kepalanya. Namun dari semua saudaranya, hanya Radhar Panca Dahana yang kerap membangkang dan mendapat hukuman yang sangat keras.
Soal minat dan bakat pun, Radhar merasakan ketidakcocokkan dengan orangtuanya yang menginginkannya menjadi seorang pelukis sementara ia amat menyukai teater dan menulis. Saking seringnya mendapat hukuman fisik, Radhar jadi tak betah di rumah. Puncaknya sekitar akhir tahun 1970, ia sering minggat dari rumahnya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk mencari tempat yang membuatnya nyaman dan merasa diterima. Kawasan Bulungan menjadi pilihan tempat pelariannya, tempat yang di kemudian hari turut andil membentuk pribadinya seperti saat ini.
Sifat pemberontaknya tak hanya ia tunjukkan di lingkungan keluarga, namun berlanjut juga di bangku sekolah. Sejak SD, Radhar dijauhi teman-temannya karena tabiatnya yang terkesan ingin “menguasai” lebih banyak area publik. Di bangku SMA pun sifat itu terus berlanjut, ia menolak sistem sekolah, bahkan pernah bertengkar dengan gurunya.
Meski tergolong sulit diatur, putra kelima dari tujuh bersaudara ini telah menemukan potensinya sebagai penulis berbakat sejak kanak-kanak tepatnya di usia 10 tahun. Ketika anak-anak sebayanya tengah asyik bermain, Radhar kecil yang saat itu masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar justru sudah mampu menghasilkan sebuah cerita pendek (cerpen). Cerpen berjudul “Tamu Tak Diundang” yang dikarangnya di usia 10 tahun itu bahkan dimuat di harian Kompas. Pada akhir tahun 70-an, Radhar melirik dunia jurnalistik dan mulai merintis karirnya sebagai reporter saat Arswendo Atmowiloto membuat Koma (Koran Remaja). Kemudian pada 1977, ia bekerja sebagai redaktur tamu majalah remaja, Kawanku. Saat itu, Radhar mendapat kepercayaan untuk membantu menyeleksi naskah cerpen dan puisi yang masuk.
Memasuki masa SMP, ia semakin giat menulis cerpen, puisi, hingga membuat ilustrasi. Beberapa karyanya dimuat di majalah Zaman, yang waktu itu redakturnya adalah Danarto. Radhar menyamarkan jati dirinya dengan nama Reza Morta Vileni sebagai penata artistik. Nama samaran itu diilhami oleh nama teman sekolahnya, Rezania, yang piawai berdeklamasi. Sedangkan nama Radhar dicantumkan sebagai reporter.
Pada periode ini, Radhar amat produktif mengarang cerpen remaja. Terlebih ketika itu di Jakarta tengah menjamur berbagai majalah kumpulan cerpen, seperti Pesona dan Anita, yang kerap memuat karya-karya Radhar. Cerpen karya Radhar Panca Dahana kala itu juga mengisi majalah remaja seperti Gadis, Nona, dan Hai, bahkan majalah dewasa, yakni Keluarga, Pertiwi, dan Kartini.
Karirnya sebagai jurnalis pemula semakin berkembang ketika ia diterima bekerja di harian Kompas. Valens Doy, seorang wartawan senior berpengaruh, menempatkannya sebagai pembantu reporter atau reporter lepas. Radhar kemudian diminta menulis berbagai macam rubrik, mulai dari olahraga, kebudayaan, pendidikan, berita kota tentang kriminalitas, hingga masalah hukum. Kemampuan itu didapatnya dari kebiasaannya yang sejak kecil sudah gemar membaca.
Akan tetapi, pekerjaannya sebagai jurnalis terhenti saat orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk bekerja. Dengan berat hati, Radhar pun kembali ke bangku sekolah. Untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA saja, Radhar sampai menghabiskan waktu enam tahun lantaran ia kerap berpindah-pindah sekolah, yakni di SMA 11, SMA 46 Jakarta, dan sebuah SMA di Bogor. Menurutnya, hal itu adalah buah dari kekecewaannya karena tidak diizinkan bekerja oleh orang tuanya.
Saat duduk di bangku SMA pun, Radhar kerap bertengkar dengan guru lantaran menolak sistem sekolah. Sikap kerasnya itu boleh jadi akibat pengaruh buku bertema berat yang sering dibaca kemudian ditelannya bulat-bulat tanpa mencernanya. Seperti pemahaman Ivan Illic tentang formalisme pendidikan dalam buku berjudul Bebas dari Sekolah serta buku berjudul Pendidikan Kaum yang Tertindas buah karya Paulo Freire.
Karirnya sebagai jurnalis pemula semakin berkembang ketika ia diterima bekerja di harian Kompas. Valens Doy, seorang wartawan senior berpengaruh, menempatkannya sebagai pembantu reporter atau reporter lepas. Radhar kemudian diminta menulis berbagai macam rubrik, mulai dari olahraga, kebudayaan, pendidikan, berita kota tentang kriminalitas, hingga masalah hukum. Kemampuan itu didapatnya dari kebiasaannya yang sejak kecil sudah gemar membaca.
Ketika itu pula, Radhar mulai merambah dunia teater. Sebenarnya, teater bukanlah hal yang baru bagi Radhar sebab ia telah naik panggung teater ketika berumur 14 tahun. Saat itu ia memerankan tokoh perempuan bernama Rebecca dalam drama Jack dan Penyerahan. Di Bogor, Radhar kembali meneruskan hobinya lamanya itu dan bergabung dengan Bengkel Teater Rendra. Namun, keberadaannya di Bengkel Teater Rendra tak bertahan lama. Karena berselisih mengenai manajemen grup dengan si empunya sanggar, Radhar akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Selain Rendra, Radhar saat itu juga dekat dengan Noorca M. Masardi dan Anto Baret. Ketiga orang itulah yang sering memberi nasihat mengenai apa yang patut diperbuatnya. Bahkan atas anjuran Anto Baret, Radhar kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Radhar awalnya amat berharap bisa diterima di Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pajajaran. Sayangnya Radhar tidak diterima kuliah di Unpad, namun diterima di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Meski demikian, Radhar berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 2,5 tahun. Setelah berhasil menyabet gelar sarjananya, Radhar kembali menekuni hobinya berteater dan meneruskan karirnya sebagai wartawan.
Kesibukan yang amat menyita waktu membuat Radhar tidak acuh pada tata administrasi di kampusnya. Masalah itu baru diselesaikannya pada saat ia akan pergi ke Perancis untuk menyelesaikan kuliah S2-nya di jurusan Sosiologi di Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales pada tahun 1997 dengan meriset postmodernisme di Indonesia. Di Prancis, Radhar bermukim di Besancon, sebuah kota kecil berjarak 450 km di timur Paris. Tiga bulan kemudian, Evi Apriyanti, istri Radhar menyusul lantaran merasa khawatir akan kondisi suaminya yang seorang diri di negara orang. Sebelum berangkat, Radhar mengingatkan istrinya untuk membawa obat sakit kepala lantaran sering pusing dan muntah. Dalam sehari, ia mengkonsumsi obat tersebut dua sampai tiga kali.
Pada tahun 1998, Radhar sempat memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan membatalkan fasilitas studi yang harusnya mencapai tingkat doktoral. Pasalnya, ia merasa tak kuat menahan diri, hidup enak di Prancis sementara di Indonesia orang-orang hidup dalam teror. Seperti diketahui, ketika itu di Indonesia sedang terjadi kekacauan politik dan ketidakstabilan keamanan akibat tergulingnya Soeharto dari kursi presiden.
Namun kemudian, ia dan istrinya kembali ke Prancis hingga tahun 2000 walau sebenarnya kuliah doktoralnya belum rampung. Awal tahun 2001, atau setahun setelah kembali ke Tanah Air, Radhar divonis menderita gagal ginjal kronis. Penyakit yang dikenal dalam bahasa kedokteran sebagai Acute Renal Failure dan Cjronic Renal Failure merupakan semacam pembunuhan sel-sel ginjal secara perlahan. Dua buah ginjalnya bahkan dinyatakan sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, ia diharuskan menjalani cuci darah seumur hidup. Sejak itu, setelah menjalani cuci darah, tiada hari yang ia lewati tanpa gangguan 2-3 penyakit dari sekitar 15 penyakit baru yang ia dapatkan, di antaranya asam urat, jantung, dan paru-paru. Evi menduga, kebiasaan Radhar mengkonsumsi obat sakit kepalalah yang membuat ginjalnya rusak. Ditambah pola makan suaminya yang buruk. Masih menurut Evi, jika sedang menulis, Radhar suka lupa makan dan minum. Baginya, minum kopi dan sebungkus rokok sudah membuatnya kenyang. Kalaupun disediakan segelas air putih, ia tidak meminumnya.
Karena kondisi kesehatannya yang kian menurun, Radhar pun sempat dirawat di RSCM. Untunglah kondisinya berangsur-angsur membaik, semua itu tak terlepas dari dukungan dan doa sang istri tercinta. Wanita yang telah memberinya seorang putra bernama Cahaya Prima Utama itu tak hentinya memberikan suntikan semangat pada Radhar. Dengan penuh kesabaran, ia memotivasi suaminya untuk kembali berkarya.
Radhar yang awalnya enggan akhirnya kembali menulis, salah satunya sebuah puisi berjudul Tak Ada Siapa Pun di Situ yang bercerita tentang penyakit yang hinggap di tubuhnya. Sejak itu, semangat menulisnya kembali berkobar dan ia semakin rajin menulis artikel dan esai tentang budaya di berbagai media. Prestasinya pun semakin bersinar, cerpennya yang berjudul Sepi Pun Menari di Tepi Hari berhasil terpilih menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas.
Karirnya kian melejit, setelah harian Kompas mempercayakannya untuk mengasuh rubrik “Teroka”, menjadi pengisi tetap cerita komik ‘Mat Jagung’ di Koran Tempo, dan Kolom Perspektif di Majalah Gatra. Ia juga kerap mendapat undangan untuk membaca puisi di beberapa festival sastra di Eropa maupun menjadi pembicara dalam berbagai forum sastra Internasional seperti di Tokyo, Hongkong, Bangkok, Filipina, Jerman, Prancis, Belgia, Brunei, dan Belanda.
Tak hanya itu, Radhar juga menuangkan ide kreatifnya demi mengembangkan dunia teater Indonesia, dengan mendirikan sekaligus memimpin sebuah sanggar bernama Teater Kosong, selain memimpin Federasi Teater Indonesia dan Bale Sastra Kecapi.
Di samping itu, bersama beberapa rekannya, Radhar kembali membangun PEN International Indonesia dan menjadi Sekjennya meski tak lama. Setelah itu ia menyelesaikan studi sosiologinya di Prancis yang dulu sempat tertunda. Dalam kurun waktu itu, Radhar masih menyempatkan diri untuk menekuni hobinya di dunia seni, dari menjadi pemain pantomim bayaran hingga pemain gitar sekaligus perkusi dalam kelompok musik Poci Jakarta. Belakangan kesibukannya kian bertambah dengan aktivitasnya di ranah politik dan akademik dengan menjadi pengajar di Universitas Indonesia.
Selama puluhan tahun berkarir, Radhar telah berhasil menelurkan puluhan karya, mulai dari cerpen, esai, buku, puisi, hingga kumpulan drama. Misalnya, “Menjadi Manusia Indonesia” (esai humaniora, 2002), “Lalu Waktu” (kumpulan sajak, 2003), “Jejak Posmodernisme” (2004), “Cerita-cerita dari Negeri Asap” (kumpulan cerpen, 2005), “Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia” (esai humaniora, 2006), “Dalam Sebotol Coklat Cair” (esai sastra, 2007), “Metamorfosa Kosong” (kumpulan drama, 2007).
Atas pencapaiannya itu, Radhar Panca Dahana beberapa kali mendapatkan penghargaan. Pada 1996, ia terpilih sebagai satu di antara lima seniman muda masa depan Asia versi NHK, tahun 2005 giliran Paramadina Award yang disabet Duta Terbaik Pusaka Bangsa dan Duta Lingkungan Hidup sejak 2004 ini. TV NHK Jepang bahkan pernah membuat dan menyiarkan profilnya. Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 2007, ayah seorang putra ini menerima Medali Frix de le Francophonie dari lima belas negara berbahasa Prancis. Dua tahun berselang, Radhar dianugerahi Kuntowijoyo Award. muli, red