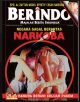Dokter Spesialis di Nias
Kanserina Esthera Dachi
[DIREKTORI] Kanserina Esthera Dachi, dokter spesialis penyakit dalam yang bangga dan bahagia memilih melayani di daerah ‘terisolasi’ Pulau Nias. Tidak banyak dokter yang bahagia mengambil pilihan merelakan kepentingan sendiri, hidup jauh dari keluarga, meski pilihan hidup “lebih baik” di kota bisa digenggamnya.
Sejak tahun 2001 dia menjadi satu-satunya dokter spesialis penyakit dalam di Pulau Nias. Sebelumnya, dokter spesialis penyakit dalam tidak pernah ada di Tano Niha. Meskipun jauh dari gemerlap hidup dokter spesialis, Kanserina mengaku bangga.
Bangga, sebagai orang Nias bisa melayani orang Nias sendiri. Kebahagiaan itu meretas di dalam rumah dinas dari papan kayu 6 meter x 12 meter beratap seng. Pilihan hidup Rina, panggilan akrab perempuan 46 tahun itu, tidak seperti dokter spesialis kebanyakan.
Nias yang terisolasi secara geografis bukanlah medan ringan bagi seorang dokter. Meskipun begitu, tak terdengar keluhan dari penghuni rumah di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gunungsitoli, itu. Tinggal di rumah yang terletak 10 meter dari RSU Gunungsitoli tersebut mengharuskan dia on call (bisa dihubungi) setiap saat jika ada yang membutuhkan.
Kewajiban memberi pelayanan kesehatan tak terbatasi waktu. Apalagi, Nias baru saja dilanda bencana tsunami dan gempa. Kebanyakan orang Nias sakit tuberkulosis (TB) dan anemia. Setiap hari, sedikitnya lima penderita TB yang dia layani.
Kewajiban yang begitu besar memang tidak sebanding dengan pendapatan yang dia terima. Meski penghasilan bersih Rina hanya Rp 3,8 juta per bulan, itu tidak membuat dia merasa kekurangan. Pendapatan itu sudah cukup membahagiakannya.
Dari uang itu, paling tidak Rp 1,2 juta setiap bulan pasti dia belanjakan untuk pergi ke Medan menemui suami dan anaknya. Belum termasuk biaya komunikasi via telepon dengan keluarganya.
Pendapatan Rina jauh lebih kecil dibandingkan dengan insentif seorang dokter magang sebuah universitas terkemuka yang sengaja didatangkan ke Nias untuk mengisi kekurangan dokter. Para dokter muda itu mendapat insentif Rp 15 juta per bulan (separuh dari jumlah itu diperuntukkan bagi almamaternya).
Amanat orangtua
Bertugas di Nias mempunyai arti khusus bagi Rina karena merupakan amanat orangtuanya, Sozanolo Dachi (almarhum). Ayahnya menginginkan Rina mengabdi di Tano Niha (tanah Nias). Maka, sejak 2001 dia menjadi satu-satunya dokter spesialis penyakit dalam di pulau itu.
Tahun 2001, sahabatnya yang juga Wakil Bupati Nias Agus H Mendrofa menemuinya di Medan. Agus mengajak Rina mengabdi di Nias. Dalam sejarah, tak pernah ada dokter spesialis penyakit dalam bertugas di Nias. Para dokter, apalagi dokter spesialis, enggan bertugas di daerah yang terkepung lautan luas dan terpisah dari daratan Sumatera itu.
Apa yang dia lakukan selaras dengan nama pemberian orangtuanya. Kanserina Esthera berarti “ibu harapan pembela keadilan”. Begitulah kira-kira harapan orangtuanya kepada Rina.
Sebelum ke Nias, perempuan yang lahir di Jakarta, 29 Juni 1961, ini belum banyak tahu tentang tanah leluhurnya. Maklum saja, ayahnya seorang pegawai negeri sipil di Departemen Perhubungan. Masa sekolahnya dari SD sampai pendidikan spesialis dia jalani di Medan. Orangtuanya bertugas di Administratur Bandara, Pelabuhan Belawan.
SD sampai SMA dia jalani di Belawan, Medan. Kemudian masuk Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) dan lulus 1987. Rina kemudian melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam, juga di USU.
Pengalaman tugasnya hampir seluruhnya dia jalani di Medan dan sekitarnya sebelum memilih tanah leluhurnya di Nias. Pada awal karier sebagai dokter, dia bertugas di RSU RM Djoelham Binjai (1988-1992). Dia juga pernah menjadi staf Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan (1992). Sebelum mengambil program pendidikan dokter spesialis, Rina bertugas di Puskesmas Pembantu Tanjung Gusta 1992-1995, dan sejak 2001 sampai sekarang dia mengabdi di Nias.
Korban gempa
Meskipun juga menjadi korban gempa pada 28 Maret 2005, bukan berarti dia libur bertugas di Nias. Pada saat gempa, rumahnya terbelah jadi dua, lantainya ambles. Namun, Rina tetap memberikan pelayanan bagi korban gempa. Bahkan, sampai sekarang pun rumahnya belum direhabilitasi.
Dia sempat mengoperasi korban gempa yang kepalanya robek tertimpa reruntuhan bangunan. Saat itu tenaganya sungguh berarti karena pertolongan medis pertama baru sampai 21 jam setelah bencana terjadi.
“Ada 79 orang yang sempat saya tangani. Sebagian besar harus menjalani pembedahan dan pertolongan pertama,” kenangnya. Semua itu dia lakukan dengan peralatan seadanya dan obat-obatan sisa di RSU Gunungsitoli.
Masa sulit itu justru membuat dia berkesan. Itu tidak membuatnya kapok bertugas di Nias. Dukungan dari suami dan dua anaknya merupakan semangat terbesar.
“Suami saya tidak pernah meminta saya kembali ke Medan, begitupun anak-anak,” katanya. Setiap hari, komunikasi dengan suaminya, Faigiziduhu Bu’ulölö, dosen Fakultas Matematika IPA USU, dia lakukan melalui telepon. Di rumah papan kayu, hidup sendiri tak membuat dia kesepian. Di saat senggang, Rina gemar merancang baju dan tas. Kedamaian itu anugerah terindah yang dia terima.
Sebulan sekali Rina pulang untuk bertemu keluarga di Medan. Anak pertamanya Beatrice Angela Bu’ulölö (22) kini bertugas sebagai dokter muda di RSUP Adam Malik, Medan. Adapun anak bungsunya, Roland Lukas Bu’ulölö (19), kuliah di Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Belum terlaksana
Suatu hari, orangtuanya pernah berpesan agar dia nanti bertugas di RS Lukas, Nias Selatan. Rumah sakit yang terletak sekitar 90 kilometer dari Gunungsitoli itu pada tahun 1960-an merupakan rumah sakit termodern di Nias. Bahkan, sebagian peralatan medisnya tercatat paling bagus di seluruh RS di Sumut.
Rumah sakit yang didirikan di atas tanah kakeknya itu merupakan bantuan misionaris Jerman yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Belakangan, RS itu bukannya bertambah maju, malah semakin mundur dan ” turun” status menjadi puskesmas.
Bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias untuk RS itu terkendala persoalan ego sektoral. Para elite pemerintah dan legislatif di Nias Selatan berencana memindahkannya ke tempat lain. Pemindahan itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan tak berujung.
Kanserina sedih. Persoalan itu menghambat pengembangan rumah sakit satu-satunya di Nias Selatan. Baginya, pindah dari Pulau Nias merupakan pilihan yang sulit. Satu sisi, dia ingin dekat dengan keluarganya, satu sisi dia ingin memenuhi amanat orangtuanya yang belum terlaksana. “Saya sulit menjawab, antara ya dan tidak,” katanya saat ditanya soal kemungkinan pindah dari Pulau Nias. (Andy Riza Hidayat, Kompas, 31 Desember 2007) e-ti