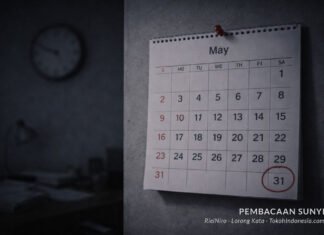Suka Menulis Cerita Tragedi
Tan Hong Boen
[DIREKTORI] Tan Hong Boen (THB) merupakan penulis keturunan Tionghoa serba bisa di era penjajahan. Tulisannya sarat dengan filsafat kehidupan, mistik, kritik sosial dan kepedulian terhadap nasib pribumi. Karena aktivitasnya, ia pernah dipenjara pemerintah kolonial Belanda bersama Bung Karno. Pengetahuannya tentang obat-obatan tradisional Indonesia juga cukup luas. Salah satu obat hasil temuannya yang masih dikenal hingga kini adalah Pil Kita.
Pengarang yang mampu menulis novel, cerpen, biografi, hingga cerita wayang ini gemar menggunakan nama samaran. Orang Tionghoa yang terkemoeka di Java (Who’s who) adalah satu-satunya karya THB yang ditulis dengan nama aslinya. Buku yang selesai ditulis pada tahun 1935 itu hingga kini masih dianggap sebagai dokumen penting mengenai orang Tionghoa Indonesia.
Selebihnya, ia kerap menggunakan nama samaran yang disesuaikan dengan jenis tulisannya. Seperti pemilihan nama Kihadjar Dharmopralojo yang digunakannya ketika menulis biografi singkat tokoh-tokoh sejarah seperti Raden Patah. Nama samaran lain yang pernah digunakannya adalah Madame d’Eden Lovely untuk penulisan sebuah roman berjudul Itoe Bidadari dari Rawa Pening.
Dari sekian banyak nama-nama itu mungkin yang menjadi favoritnya adalah Im Yang Tjoe. Pasalnya nama itu sering dipakai untuk novel-novelnya. Nama pena tersebut digunakan sejak tahun 1925 hingga 1950-an. Saat ia berhenti sebagai novelis dan lebih memutuskan menjadi penulis cerita wayang menjelang akhir usianya, ia menggunakan nama Kihadjar Sukowiyono.
Putra Tan Boen Keng, kelahiran 27 Februari 1905, yang fasih berbahasa Tionghoa, Melayu serta menguasai bahasa Inggris dan Belanda ini mulai merintis karir menulis sebagai seorang wartawan. Ia sering mengumpulkan bahan yang ia dapat dari berkunjung ke berbagai tempat di Jawa dan Bali untuk ceritanya. Hasil karyanya kemudian dikirim ke majalah Liberty dan Penghidoepan.
Pada usia 24 tahun, persisnya pada tahun 1929, ia mendirikan sebuah majalah sastra yang dia beri nama Boelan Poernama di Semarang. Dalam pengantar majalahnya, ia menjelaskan tujuannya mendirikan majalah itu, yaitu untuk memberi bacaan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan majalah itu, ia juga ingin menumbuhkan minat dan bakat menulis kaum perempuan.
Antara tahun 1929 dan 1932, ia juga menjadi pemimpin redaksi Harian Soemanget di Bandung. Di saat yang bersamaan ia diangkat menjadi ketua The Biographical Publishing Centre di Solo. Baru setahun berjalan, tanpa alasan yang jelas, Boelan Poernama pindah ke Bandung. Surat pembaca yang berdatangan dari segala penjuru Tanah Air menunjukkan majalah ini semakin mendapat tempat di hati pembacanya. Meski demikian, majalah itu harus berhenti beredar di tahun 1932, salah satu penyebabnya adalah keterlibatan THB di dunia politik.
Karena kegiatan politiknya juga, ia bersama Bung Karno pernah dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung oleh pemerintah Belanda. Selama di penjara, kedua pria itu sering bertukar pikiran. THB sendiri sangat mengagumi idealisme Bung Karno. Dengan dasar kekaguman itu pulalah timbul keinginannya untuk menulis biografi tokoh idolanya itu pada tahun 1933. Dalam biografi itu, ia bercerita tentang masa kecil Soekarno terutama hubungannya dengan sang ibu, juga kehidupan perkawinan Soekarno namun tidak banyak bercerita tentang perjalanan politik Soekarno kecuali pidato pembelaan dirinya di depan pengadilan.
Biografi lain yang ditulisnya adalah biografi seorang etnis Tionghoa yang menjadi pertapa di lereng Gunung Kawi bernama Embah Eyang Jugo pada tahun 1950-an. Embah dianggap mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang mistik Jawa. Buku ini kini tersimpan di perpustakaan kota Yogyakarta di bagian naskah lama.
Setelah Perang Dunia II usai, ia mencoba membangun karirnya sebagai novelis dengan cerita-ceritanya yang dimuat dalam majalah sastra seperti Goedang Tjerita, Tjilik Roman’s, Tjantik dan majalah terkemuka saat itu, Star Weekly. Di majalah Tjantik, ia sempat menulis cerpen yang bercerita tentang perilaku pejabat yang gemar korupsi berjudul Srigala hitam sakit koening dan Srigala hitam menggigit ekor sendiri. Namun sebelum cerpen itu tamat, majalah itu mengalami masalah keuangan sehingga harus berhenti beroperasi.
Sementara di majalah Tjilik Roman’s, THB menulis cerpen berjudul Melani, Moetiara Djogjakarta. Dalam cerpen tersebut ia tak hanya mengangkat tradisi masyarakat Jawa yang menarik tapi juga kepercayaan terhadap hal-hal berbau mistik yang telah diadaptasi dari kebudayaan kaum Tionghoa di Jawa Tengah. Lewat cerita yang ditulisnya, ia ingin menunjukkan bahwa masyarakat keturuan Tionghoa, paling tidak yang bermukim di Jawa Tengah telah terasimilasi dalam budaya Jawa.
Setelah Perang Dunia II usai, ia mencoba membangun karirnya sebagai novelis dengan cerita-ceritanya yang dimuat dalam majalah sastra seperti Goedang Tjerita, Tjilik Roman’s, Tjantik dan majalah terkemuka saat itu, Star Weekly. Di majalah Tjantik, ia sempat menulis cerpen yang bercerita tentang perilaku pejabat yang gemar korupsi berjudul Srigala hitam sakit koening dan Srigala hitam menggigit ekor sendiri. Namun sebelum cerpen itu tamat, majalah itu mengalami masalah keuangan sehingga harus berhenti beroperasi.
Sedangkan untuk novel, yang pertama ditulisnya berjudul Soepardi dan Soendari. Novel yang dimuat dalam majalah Penghidoepan pada tahun 1925 ini bertema romantisme masyarakat pribumi. Lima tahun kemudian, THB kembali menulis cerita bertema serupa dengan judul Tetesan Air Mata di Padang Lalang. Lewat cerita tersebut ia ingin menarik perhatian pembaca terhadap penderitaan masyakat pribumi, tentang buruh yang bekerja di jalan dan kondisi kerja mereka, serta hubungan mereka dengan orang Belanda. Dalam ceritanya, ia memaparkan kemiskinan dan penderitaan rakyat pribumi dan THB menuding pemerintah kolonial sebagai biang keladinya.
Mulai tahun 1950-an THB mulai menulis cerita wayang. Dalam proses kreatifnya, ia mengumpulkan cerita-cerita tradisi lisan yang diperolehnya dari Pesisir Utara Jawa. Itu sebabnya, cerita karangannya menyimpang dari cerita wayang yang umumnya ditemukan di Jawa Tengah. Cerpen wayangnya yang pertama berjudul Mahabarata yang dimuat di majalah mingguan Pantjawarna. Namun tanpa alasan yang jelas, di tengah jalan cerpen itu tidak dimuat lagi. Tapi fragmen cerita yang sama diterbitkan sebagai buku oleh Sulaksana di Slawi, tempat tinggalnya. THB ingin memperkenalkan cerita itu khususnya pada masyarakat Tionghoa karena ia menilai cerita itu bermanfaat bagi mereka. Tapi pada kenyataannya cerita tersebut lebih disukai orang pribumi. Meskipun begitu, dalam pengantarnya THB menuliskan pesannya agar pembaca tidak hanya sekadar menikmati jalan ceritanya saja namun mengambil pesan moral sebagai bekal di hari tua.
Di masa tuanya, bak seorang dalang, THB sering mengumpulkan orang-orang untuk mengisahkan cerita-cerita wayang karangannya. Meski tanpa wayang dan layar, cerita itu tetap memiliki daya pikat yang kuat.
Menurut Tzu You, yang juga seorang penulis, ciri khas THB adalah tulisannya yang sensasional, melankolis dan terkadang menyeramkan. THB memang lebih banyak menulis tentang tragedi yang lekat dengan kesedihan dan jarang melukiskan kebahagiaan. Sebagai penulis yang baik, ia tak hanya membumbui tulisannya dengan pengetahuan yang luas mengenai sastra tapi juga dengan filsafat, mistik, dan seni bela diri.
Di samping itu, ceritanya juga sarat akan kritik sosial. Pada masa itu, ia kerap menulis cerita untuk menyindir tingkah laku laki-laki maupun perempuan yang tak wajar. Misalnya ceritanya yang berjudul Boenga Rose yang tidak Berdoeri, yang mengisahkan kehidupan seorang janda yang kerap dilecehkan. Cerita yang berjudul Gandaroewo ditujukan untuk mengecam laki-laki yang suka mengganggu istri orang.
Meski demikian, tulisannya tidak bersifat menggurui. Sebaliknya, ia melakukan pendekatan dengan para pembacanya dengan mencontohkan hal-hal baik dalam hidup, misalnya, belajar seni selagi masih muda dan belajar filsafat kala usia mulai senja. Sementara ketika banyak pengarang mengkritik perempuan yang dinilai terlalu modern sehingga lalai mengurus rumah tangganya, THB justru menganjurkan sebaliknya. Ia mengharapkan kaum hawa dapat menunjukkan eksistensi mereka di berbagai bidang.
Melalui goresan penanya, ia juga melontarkan kritik pada dunia jurnalistik yang pada saat itu, surat kabar dipakai untuk mempromosikan pandangan politik dari partai mereka dan para redaktur hanya merupakan domba untuk diadu saja. THB juga prihatin pada para pemuda peranakan Tionghoa berpendidikan Eropa yang menganggap dirinya lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan Melayu dan Tionghoa.
Di awal setiap buku yang ditulisnya, ia sering menyisipkan kata-kata mutiara. Beberapa kata-kata itu dikutipnya dari filsuf dan penyair ternama, seperti Shakespare, Goethe, atau Schoppenhauer.
Untuk karya-karya sastranya, ia tercatat pernah menerima tiga penghargaan. Pertama, cerpen berjudul Boeroeng Pedasih di Moesim Dingin yang dimuat dalam mingguan Sin Po. Yang kedua, cerpen berjudul Boengah Trate di Rawa Peloeng berhasil meraih bintang emas dalam sayembara cerpen yang diadakan oleh mingguan Liberty. Sedangkan penghargaan yang ketiga diperolehnya dari majalah sastra Penghidoepan untuk novelnya yang berjudul Oh, Penghidoepan. Novel yang terpilih sebagai cerita terbaik mengenai makna kehidupan itu juga mendapat penghargaan dari majalah bulanan Hoa Kiao.
Di sisi lain, karya-karya THB juga dihujani kritikan karena diskusi tokoh-tokohnya yang menyinggung agama Islam. Dalam diskusi itu ia memperlihatkan seorang manusia yang mengalami depresi akibat salah mengartikan ajaran Nabi Muhammad.
Semasa hidupnya THB dikenal sebagai sosok bijak yang banyak menghabiskan waktunya dengan bermeditasi. Selain itu, ia juga gemar berolahraga seperti bersepeda dan bermain bulutangkis. Kehidupan pribadinya pun tak banyak menyimpan gejolak. Meskipun ia menikah karena dijodohkan orangtuanya, THB dan istri mengarungi rumah tangga mereka dengan harmonis namun sayangnya mereka tak dikaruniai buah hati.
Kelebihan seorang THB yang lain adalah pengetahuannya tentang obat-obatan tradisional Indonesia. Obat hasil temuannya masih dikenal hingga kini, salah satunya adalah Pil Kita. Untuk memenuhi permintaan pasar, ia kemudian mendirikan pabrik obat dengan nama PT Marguna Tarulata APK Farma yang hingga kini masih berproduksi di Slawi.
Seperti banyak pengarang keturunan Tionghoa lainnya, dimana minat masyarakat pada tulisan mereka mulai memudar, THB berhenti menulis pada 1950-an. Sisa umurnya dihabiskan untuk mengurus pabrik farmasi yang didirikannya.
Meski sudah berhasil sebagai seorang penulis maupun pengusaha, THB selalu memperhatikan nasib orang yang tak beruntung. Maka dari itu, sebelum ia wafat, ia menyampaikan wasiatnya agar kerabat dan teman-temannya mendirikan sebuah yayasan yang akan mengelola beasiswa bagi siswa miskin berprestasi. Satu tahun setelah kepergiannya, tepatnya September 1984 yayasan itu pun berhasil didirikan. eti | muli, red