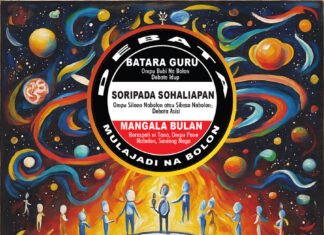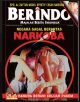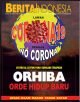Pendekar ‘Sekolah Kampung’ Papua
John Rahail
[WIKI-TOKOH] Melalui “sekolah kampung” yang didirikannya tahun 2007, John Rahail (44) telah mengantarkan 85 anak usia dini di pedalaman Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, duduk di bangku SD. Pendidikan itu dijalankan tanpa biaya dan kurikulum baku. Semua berasal dari warga, oleh warga, dan untuk warga.
Lelaki kelahiran Merauke itu mendirikan sekolah di tiga kampung di Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, yakni Kampung Betaf, Beneraf, dan Yanma. Ia memilih lokasi itu karena kegiatan belajar dan mengajar di daerah pesisir tersebut tak berjalan. Lokasi pantai itu dapat dicapai selama 8 jam perjalanan arah barat Jayapura.
Beberapa gedung SD milik pemerintah kosong karena warga enggan menyekolahkan anak-anak mereka. Rendahnya partisipasi dalam bersekolah disebabkan penerapan waktu belajar yang kaku: dari pagi hingga siang, serta kurikulum yang bernuansa perkotaan. Kondisi itu tidak sesuai dengan karakteristik anak-anak di pedalaman Papua yang umumnya tidak percaya diri bersekolah dengan berbagai aturan formal.
Pendidikan merupakan hal yang asing bagi warga di pesisir Sarmi sehingga perlu metode dan pendekatan berbeda,” tutur pendiri Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (ICDp) ini. Bersama tiga rekannya di ICDp, John memperkenalkan istilah sekolah kampung berbasis masyarakat.
John membuat sekolah ini khusus untuk anak-anak berusia 3-5 tahun agar mereka siap mengenyam pendidikan di bangku SD. Kegiatan belajar-mengajar ini hanya berlangsung dua jam setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Penyusunan kurikulum disesuaikan dengan kondisi warga di pedalaman Sarmi. Metode itu mampu menggugah minat warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Dukungan juga datang dari kepala kampung. Mereka merestui John menyelenggarakan sekolah kampung di balai warga. Ia lantas menamai tiga sekolah kampung dengan Maju Mandiri (Betaf), Maju Bersama (Beneraf), dan Maju Bermartabat (Yanma). Kata “maju” dipilih untuk memotivasi anak-anak di pedalaman agar percaya diri dan mencintai sekolah.
Hal mendasar
Saat didirikan akhir tahun 2007, jumlah siswa di sekolah kampung sebanyak 108 orang, terbagi dalam kelas pemula (usia 3-4 tahun) dan kelas lanjut (5 tahun). John mulanya mengajari mereka hal-hal dasar yang selama ini jarang dilakukan, seperti mencuci tangan sebelum makan, mandi, berdoa, dan sarapan. John meyakini, pembentukan karakter sejak dini akan memudahkan anak-anak menjalani pendidikan formal yang berjenjang lebih tinggi.
Bimbingan terhadap anak- anak dilakukannya sambil membina beberapa warga yang tertarik menjadi guru di sekolah kampung. John sesekali mengajak para calon guru menemaninya mengajar. Dalam waktu sebulan, 10 warga berusia 20-30 tahun telah siap menjadi guru di tiga sekolah kampung tersebut.
Pelibatan mereka perlahan- lahan mengubah paradigma warga terhadap pendidikan. Ibu-ibu mengantarkan anak mereka ke sekolah, bahkan menunggui sang buah hati dari pukul 08.00 hingga sekolah usai dua jam kemudian.
Keberadaan sekolah kampung seperti pepatah sambil menyelam minum air karena orangtua pun bisa mendapat ilmu,” ungkap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih ini.
Pembentukan karakter
Pembentukan karakter agar anak-anak berperilaku sopan dan memerhatikan kesehatan dilakukan John selama sebulan. Setelah itu menjadi kebiasaan anak-anak di pedalaman Sarmi, John mulai mengajari mereka berhitung dan membaca. Dia menggunakan alat peraga dan mengedepankan kearifan lokal.
Pelajaran berhitung, misalnya, dia memanfaatkan permainan tradisional. Anak-anak di pedalaman Sarmi sejatinya telah mengenal cara berhitung dalam beberapa permainan tradisional, seperti tali tangan (twen’kam), gasing (smin’kan), dan jubi lemon (lemon’bran). Ini memudahkan mereka mengenal angka hingga dua digit.
Setelah berjalan tiga tahun, sekolah kampung sudah diikuti 372 anak atau sekitar 90 persen dari jumlah anak usia dini di pedalaman Sarmi. Sebanyak 85 anak kini telah mengenyam pendidikan formal di SD.
“Warga mulai merasakan dampak positif dari konsep pendidikan yang ditawarkan Pak John dan kawan-kawan. Anak-anak juga menjadi lebih percaya diri,” ujar Martinus Wainok (26), salah seorang guru di Kampung Beneraf.
Mulai 2009, biaya operasional sekolah kampung berasal dari dana pemberdayaan kampung dan program pemerintah “Respek” sebesar Rp 25 juta. Meski demikian, John tetap meminta para guru di sekolah kampung untuk mengolah dan menjual minyak kelapa. Hasil penjualan dari sentra minyak kelapa di Distrik Pantai Timur itu untuk membiayai operasional sekolah kampung tahun 2007-2008.
Praktik cerdas
Inisiatifnya membentuk sekolah kampung di pedalaman Sarmi mendapat apresiasi dari Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Kiprah John dalam pemberdayaan warga untuk mengelola sekolah kampung terpilih sebagai salah satu praktik cerdas yang inspiratif di KTI. Ia bersama Martinus Wainok mendapat kesempatan untuk mempresentasikan sekolah kampung pada Forum V KTI yang berlangsung awal November lalu di Ambon, Maluku.
Perhatiannya terhadap dunia pendidikan tidak lepas dari peran serta sang kakek, Ignatius Silibun. Saat pindah dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, ke Merauke, Papua, Ignatius menyebarkan ajaran agama lewat pendidikan. “Kakek menjadi inspirasi saya dalam mengajar, terutama warga di pedalaman Papua yang masih tertinggal untuk urusan pendidikan,” ungkap peraih magister perilaku kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. e-ti
Sumber: Kompas, Senin, 22 November 2010 | Penulis: Aswin Rizal Harahap – Nasrullah Nara