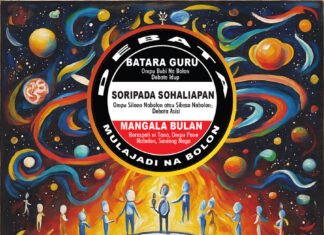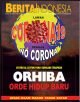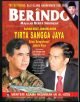Pengarang Roman ‘Atheis’
Achdiat Karta Miharja
[ENSIKLOPEDI] Romannya yang terkenal, Atheis (1948-1949) menjadi roman pertama Indonesia sesudah Perang yang benar-benar menarik dan menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Selain menulis novel, dosen kesusastraan Indonesia pada Australian National University, Canberra, Australia ini juga menulis cerpen, puisi, drama dan esai. Dalam usianya yang sudah lanjut, 94 tahun, ia masih berkarya dengan menerbitkan novel berjudul Manifesto Khalifatullah (MK) pada tahun 2005.
Achdiat Karta Miharja lahir di desa Cibatu, Garut, Jawa Barat, pada 6 Maret 1911. Novelis Angkatan 45 ini besar di tengah keluarga keturunan bangsawan yang sangat feodal. Ayahnya, Kosasih Kartamihardja menjabat sebagai pangreh praja (ambtenaar VB). Kala itu, seorang pangreh praja di zaman kolonial Belanda merupakan orang yang menyandang predikat sebagai priyayi.
Sebagai seorang priyayi, ayah Achdiat dituntut untuk berwawasan luas sehingga ia sering membaca buku terutama sastra dunia. Hobi membaca itu pada akhirnya juga menurun pada Achdiat. Beberapa buku koleksi sang ayah seperti buku karangan Dostojweski, Dumas, Multatuli, buku Quo Vadis karya H. Sinckiwicq, Alleen op de Wereld karya Hector Malot dan Genoveva karya C. von Schimdt, bahkan telah dibacanya ketika duduk di bangku kelas VI SD.
Sebelum diangkat menjadi pangreh praja, Kosasih awalnya bekerja sebagai juru tulis di sebuah kantor pemerintahan Hindia Belanda di kota Garut. Setelah itu, ia menjabat sebagai wakil administratur sebuah bank rakyat. Padahal, jabatan bergengsi semacam itu hanya dipercayakan kepada orang-orang Belanda. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ayah Achdiat mendapat kepercayaan dari orang-orang kolonial. Meski demikian, keluarganya termasuk keluarga bangsawan Muslim yang taat menjalankan beribadah. Mereka merupakan penganut aliran tarekat (sufi) Kadariyah Naksabandiyah dari pondok pesantren Suralaya, pimpinan Kyai Abdullah Mubarok atau Abah Sepuh yang terkenal dengan sebutan Ajengan Gedebag.
Achdiat menempuh pendidikan dasarnya di HIS (sekolah Belanda setingkat SD) di kota Bandung dan tamat tahun 1925. Bagi para bangsawan di zaman kolonial, mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di sekolah Belanda merupakan hal yang lazim dilakukan. Alasannya, mereka menganggap bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum penjajah itu lebih menjanjikan pekerjaan, pangkat, dan bisa segera menjadi ambtenar (kini disebut Pegawai Negeri Sipil atau PNS). Itulah mengapa orang tua Achdiat tidak mengirimkannya belajar ke pondok pesantren.
Tamat dari HIS, Achdiat meneruskan studinya ke MULO, sekolah Belanda setingkat SMP yang selain menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya, juga menekankan para siswanya untuk belajar bahasa asing lain seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Pada tahun 1932, ia masuk sekolah Belanda setingkat SMA atau yang dikenal dengan istilah AMS di Solo. Di AMS, ia mengambil jurusan Sastra dan Kebudayaan Timur (Oosters Letterkundige Afdeling) atau A1.
Memasuki tahun 1940-an, saat kekuasaan atas Indonesia beralih ke tangan Jepang, Achdiat bekerja sebagai penerjemah di bagian siaran radio di Jakarta. Ketika Perang Dunia Kedua mulai memasuki wilayah Asia Timur Raya sekitar tahun 1941, Achdiat menjadi redaktur Balai Pustaka, dan sejak itu minatnya untuk menulis karya sastra bertumbuh. Pada tahun 1946, ia memimpin mingguan Gelombang Zaman dan Kemajuan Rakyat yang terbit di Garut sekaligus menjadi anggota bagian penerangan penyelidik Divisi Siliwangi.
Achdiat meninggalkan kota Solo lalu hijrah ke Jakarta dan mengikuti kuliah-kuliah “non-degree” pada Universiteit van Indonesie atau yang kini lebih dikenal dengan nama Universitas Indonesia (UI). Di UI, Achdiat pernah mengikuti kuliah filsafat dari Prof. Beerling dan Peter Dr. Jacobs S.J., dosen Filsafat Thomisme.
Kemudian pada 1956, dalam rangka Colombo Plan, ia mendapat kesempatan untuk belajar bahasa dan sastra Inggris, serta kursus mengarang selama setahun di University of Sydney dan Australian National University di Canberra. Di Australia, ia memperdalam wawasan dan kesadarannya mengenai masalah-masalah hidup yang dihadapi umat manusia pada umumnya, dan bangsa Indonesia pada khususnya.
Achdiat sempat mengajar di Perguruan Nasional, Taman Siswa setelah menyelesaikan pendidikannya di AMS, tetapi tidak berlangsung lama. Tahun 1934, ia meninggalkan profesi guru dan lebih memilih untuk menekuni bidang jurnalistik dengan menjadi anggota redaksi Bintang Timur dan redaktur mingguan Paninjauan bersama Sanusi Pane, Armijn Pane, PF Dahler, Dr. Amir, dan Dr. Ratulangi.
Memasuki tahun 1940-an, saat kekuasaan atas Indonesia beralih ke tangan Jepang, Achdiat bekerja sebagai penerjemah di bagian siaran radio di Jakarta. Ketika Perang Dunia Kedua mulai memasuki wilayah Asia Timur Raya sekitar tahun 1941, Achdiat menjadi redaktur Balai Pustaka, dan sejak itu minatnya untuk menulis karya sastra bertumbuh. Pada tahun 1946, ia memimpin mingguan Gelombang Zaman dan Kemajuan Rakyat yang terbit di Garut sekaligus menjadi anggota bagian penerangan penyelidik Divisi Siliwangi.
Pada tahun 1949, ia ditunjuk menjadi redaktur kebudayaan di berbagai majalah, seperti Spektra dan Pujangga Baru di samping sebagai pembantu kebudayaan harian Indonesia Raya dan Konfrontasi. Pada tahun itu pula, novelnya yang pertama, Atheis, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Novel ini kemudian mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan dan para kritisi sastra Indonesia. Atheis pulalah yang berhasil mengangkat nama Achdiat Karta Mihardja sebagai sastrawan Angkatan 45 yang tangguh di bidang novel.
Pada tahun 1951, ia mewakili PEN Club Indonesia bersama Sutan Takdir Alisyahbana dan Dr. Ir. Sam Udin untuk menghadiri Konferensi PEN Club International di Lausanne, Switzerland. Ketika itu, ia berkesempatan pula mengunjungi Belanda, Inggris, Perancis, Jerman Barat, dan Roma. Satu tahun kemudian, Achdiat berkesempatan mengunjungi Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai tugas belajar dari Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (DPPK) untuk mempelajari soal-soal pendidikan orang dewasa, termasuk penerbitan bacaan-bacaannya, di University Extention Courses. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Achdiat untuk mempelajari pula seni drama di Amerika Serikat. Sepulang dari Amerika Serikat, Achdiat dipercayai memegang jabatan Kepala Bagian Naskah dan Majalah, Kepala Inspeksi Kebudayaan di Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian PPK.
Tak lama setelah itu, ia bertugas menjadi Ketua Seksi Kesusastraan Badan Penasihat Siaran Radio Republik Indonesia (BPSR) dan menjadi Ketua Pen Club Internasional Sentrum Indonesia. Sebelum diadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1954, Achdiat diangkat kembali menjabat ketua bagian naskah/majalah baru DPKK. Lima tahun berselang, ia menjadi anggota juri Hadiah Berkala BMKN untuk kesusastraan, serta bekerja sebagai dosen Sastra Indonesia Modern di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, selama dua tahun.
Pada tahun 1961, ayah lima anak ini ‘menyingkirkan diri” ke Australia, untuk seterusnya bermukim di Millen St. Hughes, ACT, Canberra. Sebelum meninggalkan Tanah Air, Achdiat sempat menjadi Co-pendiri Paguyuban Sastra-Budaya Sunda, “Kiwari”. Di benua asal suku Aborigin itu, ia menjadi Lektor Kepala (senior lecturer) di Australian National University (ANU) Canberra hingga tahun 1969.
Selain itu, Achdait sempat menjadi anggota Komite Eksekutif Nasional UNESCO, anggota Australian Universities Languages & Literatures Association, Co-pendiri Australia-Indonesia Association; Co-pendiri Himpunan Pengajar dan Peneliti Indonesia di Australia, dan Pelindung Indonesia Cultural & Education Institute, Australia. Ia juga pernah menjadi dosen tamu University of Papua New Gunnea, Posts Moresby, Indonesian Studies Summer Institute di Ohio University, Athens, Amerika Serikat.
Achdiat Karta Mihardja menutup mata untuk selama-lamanya di usia 99 tahun, pada 8 Juli 2010 di Canberra, Australia, karena serangan stroke. Semasa hidup, ia telah menuliskan karyanya di berbagai majalah dan surat kabar, antara lain, Poedjangga Baroe, Prosa, Indonesia, Konfrontasi, Budaya Jaya, dan Varia. Sepanjang karirnya sebagai penulis, ia telah menghasilkan sejumlah karya sastra baik drama, puisi, cerpen hingga esai, yang antara lain berjudul Bentrokan dalam Asrama, Kesan dan Kenangan, Belitan Nasib, Pembunuh dan Anjing Hitam, O, Pudjangga, Keretakan dan Ketegangan, Pengaruh Kebudayaan Feodal, dan masih banyak lagi.
Dua buah novelnya telah mengalami cetak ulang, baik di dalam maupun di luar negeri serta telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Selain Atheis, Achdiat juga mengarang novel Debu Cinta Bertebaran yang diterbitkan di Malaysia oleh penerbit Pena Mas di tahun 1973.
Karya-karya sastra Achdiat umumnya menyoroti tingkah laku manusia dari segi kelemahannya. Plot-plot ceritanya biasanya menarik, dengan penempatan tokoh-tokohnya dalam situasi tidak biasa. Alur cerita dan bahasa pada setiap karyanya sekilas mengalir polos namun menyembunyikan pertanyaan-pertanyaan menghentak. Sehingga banyak pembaca yang rela menghabiskan waktu berhari-hari membaca karyanya.
Karena lahir di zaman revolusi, maka karya-karyanya juga mewakili suasana dan kehidupan revolusi di Tanah Air. Pikiran-pikiran dan pesan yang ingin disampaikan Achdiat dalam karyanya sebenarnya sangat sederhana dan cuma satu yakni: bagaimana cara berpikir dan berbuat sebagaimana layaknya manusia Indonesia, bukan sebagai orang asing.
Sebagai bentuk apresiasi atas karya-karyanya, Achdiat mendapat banyak penghargaan diantaranya Penghargaan Sastra BMKN 1957 untuk cerpen Keretakan dan Ketegangan, dan Penghargaan Tahunan dari Pemerintah RI untuk novel Atheis di tahun 1969. Tahun 1972, R.J. Maguire menerjemahkan novel tersebut ke dalam bahasa Inggris. Dua tahun kemudian, sutradara terkenal Sjumandjaja mengangkatnya ke dalam film layar lebar dengan judul sama, Atheis. Film tersebut dibintangi Christine Hakim and Deddy Sutomo.
Beberapa buku studi mengenai karya Achdiat juga telah diterbitkan, antara lain Roman Atheis: Sebuah Pembicaraan (1962) oleh Boen S. Oemarjati dan artikel “Pendekatan kepada Roman Atheis” dalam Sastra Hindia Belanda dan Kita (1983) oleh Subagio Sastrowardoyo.
Meski ditulis puluhan tahun lalu, novel Atheis juga masih menjadi pembicaraan hangat hingga sekarang. Misalnya, diskusi sastra bertema Atheis dan Seabad Achdiat Karta Mihardja, yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, Maret 2011. Dalam diskusi tersebut diungkapkan bahwa novel Atheis masih relevan dengan kondisi saat ini. Atheis mengisahkan kegelisahan manusia dalam mencari pegangan hidup di tengah zaman yang makin modern, khususnya transisi masyarakat tradisional ke budaya urban.
Menurut Acep Iwan Saidi, salah satu pembicara diskusi yang berasal dari Forum Kajian Budaya Fakultas Seni Rupa Desain Institut Teknologi Bandung (ITB), novel Atheis begitu gereget dan relevan. “Karena terkait dengan krisis keberagamaan yang kita hadapi saat ini,” ujarnya. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh sastrawan Ahda Imran itu, juga hadir pembicara lain seperti dosen sastra Universitas Padjdjaran, Teddi Muhtadin, dan dosen teologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bambang Q Anees.
Acep melanjutkan, novel Atheis berkisah tentang Hasan yang berasal dari kampung dengan latar tradisi Islam yang kental. Tetapi begitu tiba di kota, dia mengalami shock sebagai manusia urban, bersentuhan dengan berbagai paham, pemikiran, dan ideologi. Hasan hidup di tengah dunia yang mempertanyakan peran agama. “Tetapi Achdiat, penulis novel Atheis, akhirnya tak berpihak kepada agama maupun non agama atau atheis, menurutnya manusia akan berarti jika memiliki cinta kasih pada sesama. Saat inilah masyarakat kita saat ini juga krisis cinta kasih,” ujarnya.
Sedangkan Teddi Muhtadin mengatakan, novel Atheis menjadi besar karena mampu menangkap perkembangan jaman. Achdiat mampu memahami masyarakat yang beragam, yakni yang beragama dan yang minoritas yang dalam novel diwakili oleh Hasan yang atheis. “Peran dialog sangat ditekankan dalam novel, misalnya dialog antara Hasan dengan Anwar, Rusli, dan lainnya. Pemikiran memang harus didialogkan, jangan didiamkan,” ujar Teddi.
Sementara Bambang mengatakan bahwa pencarian pegangan hidup dalam novel Atheis merupakan sebuah proses yang tak berakhir dan masih terjadi hingga kini. “Novel ini justru mengugat bagaimana cara kita beragama. Sebuah perjalanan pencarian yang dialami semua orang di semua jaman. Atheisme merupakan perjalanan dan jangan dianggap kejahatan. Agamawan justru harus memberikan ruang supaya perjalanannya itu mencapai tujuan, yakni bisa kembali ke agama maupun yang lain,” papar Bambang seperti dikutip dari situs okezone.com. eti | muli, red